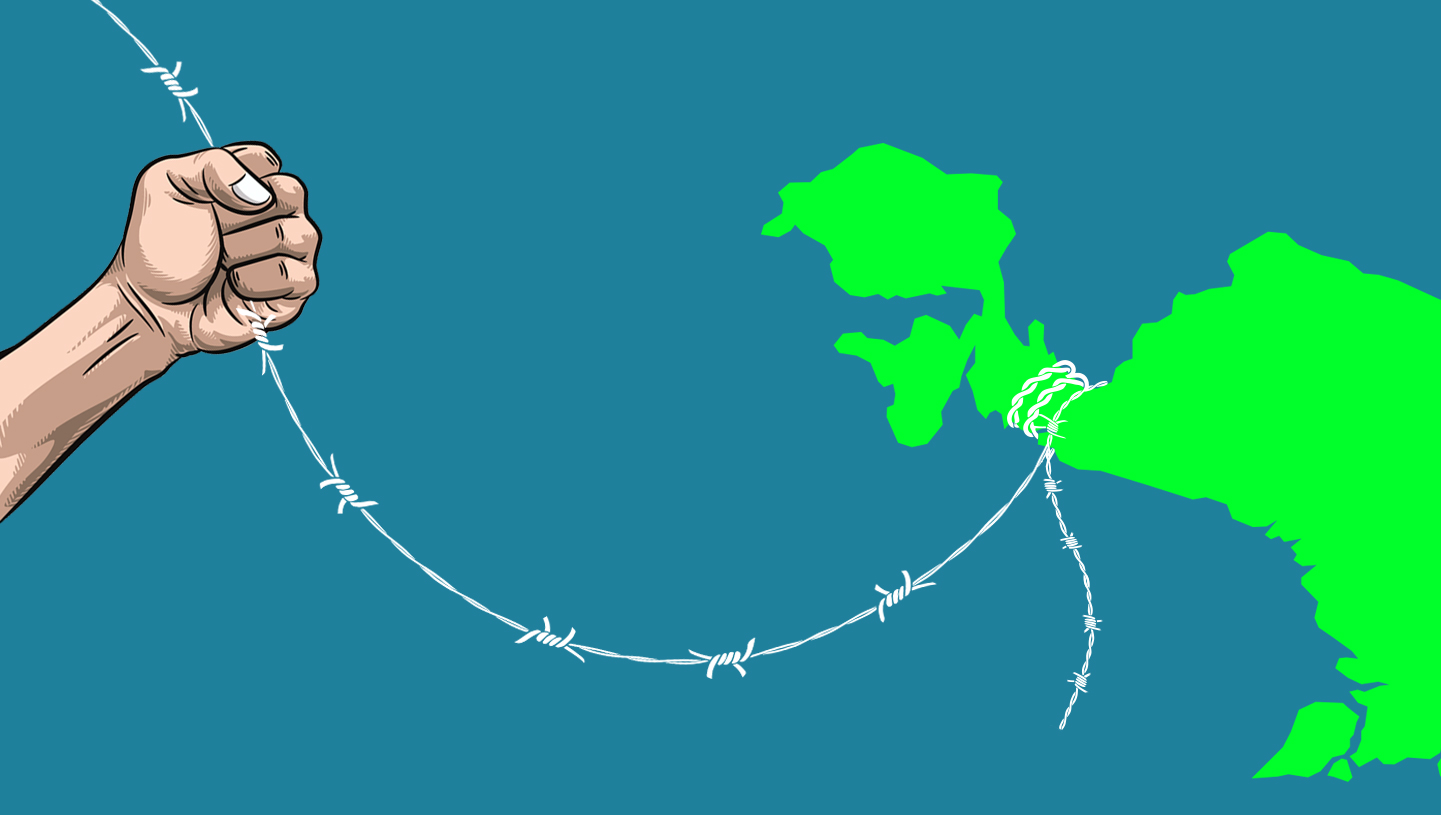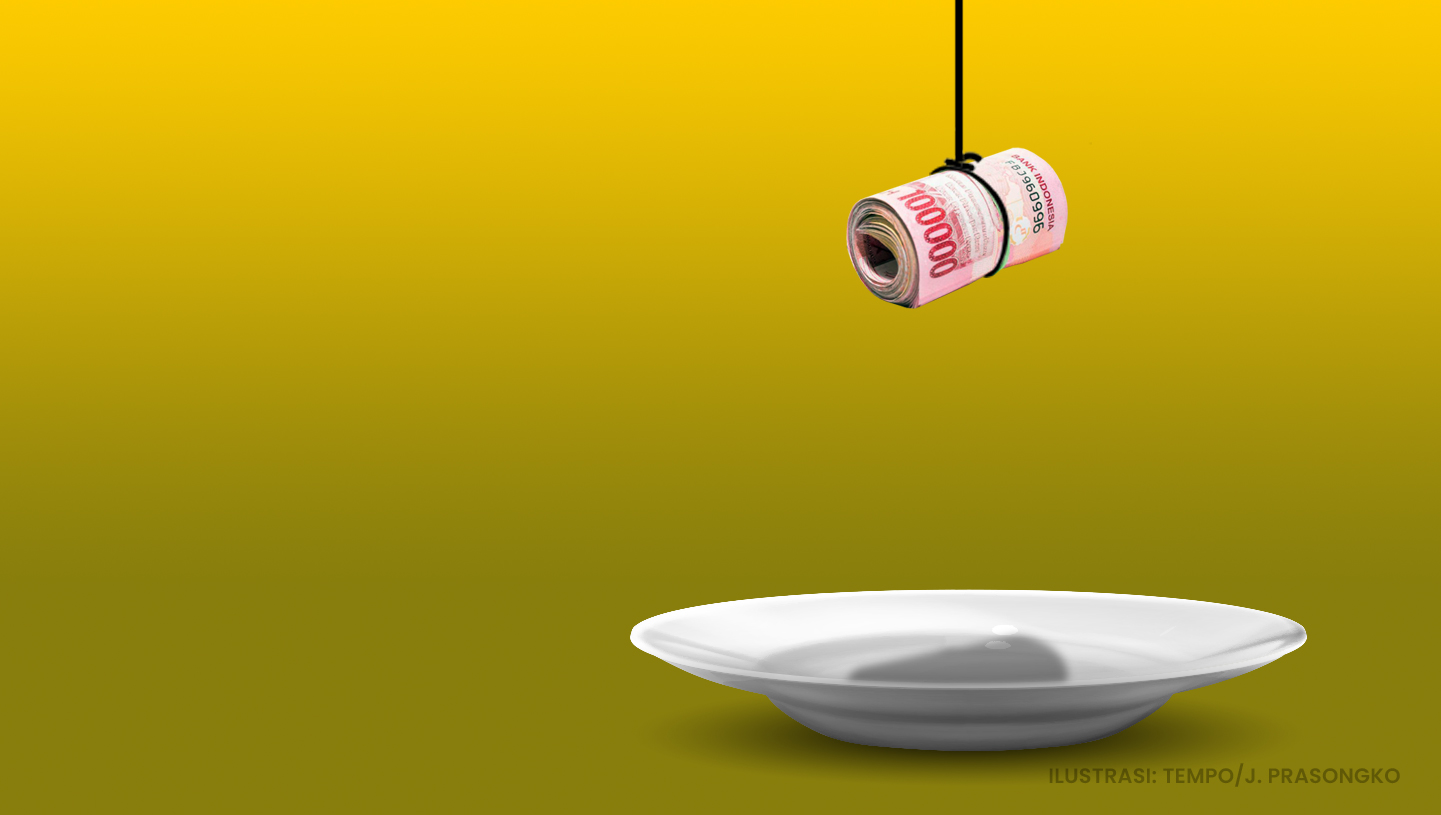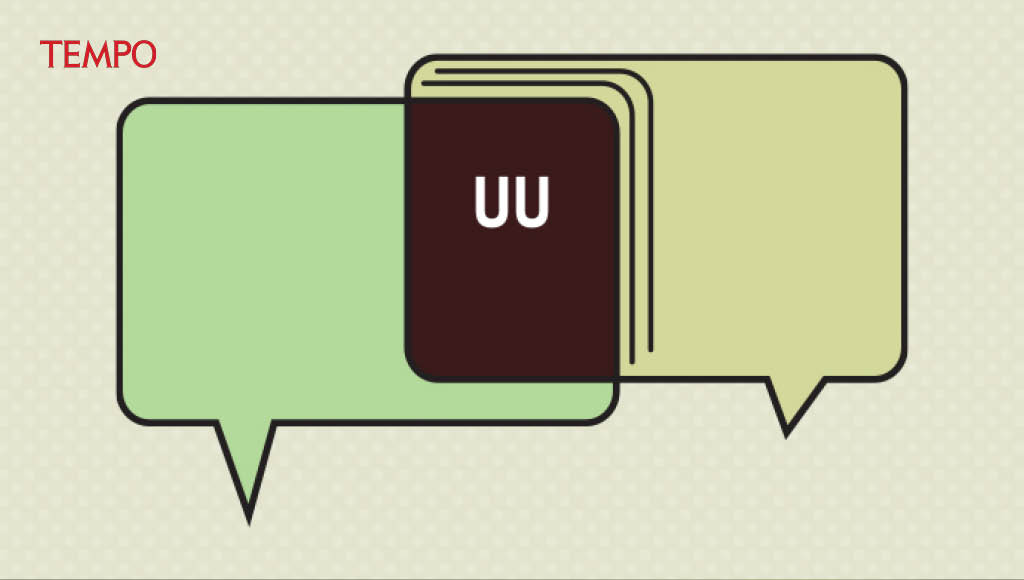Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Ringkasan Berita
Intoleransi politik Indonesia menguat.
Bagaimana cara menyembuhkannya?
MEMBURUKNYA toleransi politik di Indonesia bisa diterangkan secara sederhana melalui polemik Pakta Integritas Universitas Indonesia pada awal September lalu. Polemik berpusat di seputar poin 9 dan poin 10. Poin 9 mewajibkan mahasiswa: Tidak terlibat dalam politik praktis yang mengganggu tatanan akademik dan bernegara. Poin 10 mengharuskan mahasiswa baru: Tidak melaksanakan dan/atau mengikuti kegiatan yang bersifat kaderisasi/orientasi studi/latihan/pertemuan yang dilakukan sekelompok mahasiswa atau organisasi kemahasiswaan yang tidak mendapat izin resmi pimpinan fakultas dan/atau pimpinan UI.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Tak lama setelah pakta ini terbit, muncul suara politikus Partai Keadilan Sejahtera yang menuduh UI mendukung seks bebas karena mengajarkan ide sexual consent kepada mahasiswa baru. Sebagian pihak menilai kritik politikus PKS itu sebagai respons atas Pakta Integritas yang secara langsung akan berimplikasi pada pembatasan ruang gerak politik kader-kader PKS di kampus UI.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Di sini, baik pimpinan UI (yang kemudian membantah mengeluarkan Pakta Integritas) maupun PKS gagal mengambil sikap dengan basis hak dan kebebasan. Sekiranya benar khawatir akan mewabahnya populisme agama di kalangan mahasiswa, UI semestinya menjawab dengan melakukan hal sebaliknya: memperluas kebebasan, memfasilitasi ekspresi kebudayaan anak muda yang lebih liberal, dan mendorong tumbuhnya kelompok-kelompok diskusi untuk membuka pikiran di kalangan mereka.
Di sisi lain, sekiranya benar-benar merasa hak-hak politiknya terancam dibatasi, PKS semestinya menuntut dan mendorong kebebasan berpendapat dan berekspresi secara konsisten di dunia kampus. Tak semata meminta keleluasaan ekspresi politik dan ideologi eksklusif kelompoknya, mereka mesti meminta keleluasaan ekspresi sosial-politik pelbagai aliran di kalangan mahasiswa, termasuk gagasan sexual consent yang harus dilindungi negara.
Kedua pihak mengambil sikap masing-masing dengan alasan ingin melawan intoleransi, tapi argumen dan cara yang mereka pakai justru makin memperkuat represi, segregasi, dan intoleransi politik itu sendiri.
Toleransi politik adalah salah satu tanda dan syarat utama kesehatan demokrasi di suatu negara. Demokrasi, kata Popper, adalah the only system in which citizens can get rid of government without bloodshed (Popper, 1962). Pertanyaan selanjutnya: prosedur dan mekanisme apa yang mesti disediakan supaya pergantian pemerintah berlangsung damai?
Untuk itu, menurut Schumpeter, perlu sistem politik yang mengatur para pengambil keputusan kolektif paling kuat dipilih melalui suatu pemilihan umum yang periodik, dengan ketentuan setiap orang dewasa memiliki hak memilih. Dahl memperkuat argumen ini dengan menambahkan bahwa demokrasi juga adalah a system in which institutionalized respect for the rights of political minorities to try to become a majority must exist. Dengan demikian, sifat-sifat dasar demokrasi pluralistik, selain termanifestasi dalam prosedur reproduksi elite tanpa kekerasan, adalah cermin pengakuan terhadap toleransi politik.
Toleransi politik, secara sederhana, adalah kemauan untuk hidup bersama ide-ide dan kelompok yang tak sepaham. Istilah ini sedikit berbeda dengan pengertian toleransi yang biasa dipakai untuk menjelaskan hubungan harmonis antaragama. Jadi bisa saja seseorang tergolong kelompok “minoritas” secara agama, tapi secara politik (karena dia anggota partai pemenang pemilu) bagian dari mayoritas politik.
Toleransi politik dalam demokrasi mensyaratkan semua hal ideal, termasuk pelbagai kelompok yang mengusungnya mesti mendapat jaminan mendapat akses yang sama dalam pasar ide-ide, dengan pengakuan bahwa ide status quo yang tengah mendominasi sistem memiliki akses yang lebih luas. Dalam konteks tertentu, demokrasi yang kuat dan percaya diri juga secara terbuka menampung dan menyediakan kesempatan yang sama bagi pelbagai ideal politik yang lebih radikal, seperti ide sosialis, komunis, dan agama, untuk bersaing dalam the marketplace of ideas demokrasi (James L. Gibson, 2011).
Batas-batas toleransi politik paling rigid di dalam demokrasi biasanya terkait erat dengan tujuan utamanya sebagai cara mencapai perdamaian dan mencegah pertumpahan darah, yang mengharuskan sistem demokrasi melarang pelbagai bentuk ekspresi dan kelompok kekerasan. Dengan begitu, intoleransi politik adalah ekspresi paling subtil dari penyempitan demokrasi.
Meski demikian, para ahli juga mengingatkan bahwa toleransi politik dengan basis the marketplace of ideas memiliki dua sumber kerentanan. Yang pertama berasal dari rezim atau pemerintah yang memakai hukum dan memaksakan kekuasaan secara sepihak, memberangus pelbagai ide yang mengekspresikan kritik dan menindas suara minoritas politik. Akibatnya, intoleransi politik menguat karena diproduksi suatu politik intoleran yang bersifat sistematis dan dipromosikan negara.
Kerentanan kedua berasal dari dalam kultur masyarakat. Ia bersifat lebih subtil karena telah berakar dalam budaya, nilai-nilai, serta perilaku masyarakat atau suatu kelompok politik yang mendorong mereka mengambil sikap diam yang panjang. Keadaan ini bisa terjadi sebagai akibat sedimen ketakutan yang mengendap dalam memori suatu kelompok politik, perasaan bahwa ide-ide kelompoknya demikian kecil, remeh, atau kritis sehingga memunculkan bahaya dan risiko apabila diekspresikan secara terbuka.
Kondisi ini melahirkan apa yang disebut sebagai spiral of silence, yang apabila membesar akan memadamkan demokrasi. Gibson mengambil contoh sejarah Amerika Serikat pada 1950-an di bawah McCarthyism, ketika teror dan stigma komunis demikian meluas dan mencekam karena dipakai menekan ke segala arah. Akibat tekanan itu, muncul silent generation, kelompok sosial yang tak mau lagi mengekspresikan pandangan-pandangan politiknya karena takut dianggap kontroversial atau tidak disukai masyarakat umum.
Dalam sejarah politik di Indonesia, intoleransi politik yang sistematis setidaknya bisa merujuk pada Demokrasi Terpimpin. Pengukuhan Sukarno sebagai presiden seumur hidup secara praktis mengubur tujuan demokrasi sebagai cara pergantian kekuasaan secara damai, dilanjutkan dengan pembubaran Partai Sosialis Indonesia dan Masyumi pada 1960. Baru di masa Orde Baru ultra-intoleransi politik yang sistematis terjadi dalam pengalaman sejarah Indonesia: kehidupan multipartai yang merupakan basis pluralisme politik dibonsai, stigma komunis ditancapkan kuat di dalam masyarakat, “the marketplace of ideas” yang merupakan sumber bagi oposisi dan ideal-ideal politik alternatif dibatasi secara ketat. Salah satu kerusakan hebat yang dihasilkan intoleransi politik sistematis Orde Baru adalah meresapnya sedimentasi kebencian sosial, budaya, dan ras, serta spiral of silence di alam bawah sadar orang Indonesia.
Pewarisan intoleransi politik yang sistematis masih berlanjut hingga sekarang. Stigma politik lama tentang komunisme, Islamisme, ekstremisme kiri-ekstremisme kanan, sekalipun tidak lagi dipakai sebagai sikap resmi, masih membayang dalam kehidupan politik Indonesia hingga kini. Untungnya, kehidupan multipartai dan riuhnya demokrasi lokal sedikit-banyak membuka peluang pergumulan politik yang ideal karena lebih beragam dan baru sehingga bisa memperluas toleransi politik di Indonesia. Meski begitu, mengencangnya populisme agama dalam sepuluh tahun belakangan dan respons iliberal terhadapnya yang menguat menghasilkan kemunduran besar dalam toleransi politik di Indonesia.
Indonesia memang masih tergolong negara demokratis. Tapi diskursus ideologi politiknya makin sempit dan terbatas: kalau bukan A maka B atau sebaliknya. Orang terus-menerus dipaksa masuk hanya ke dua sistem signifikasi politik yang ada, dan ditekan untuk tidak menyatakan posisi dan ideal yang berbeda.
Akhirnya, penyempitan toleransi politik berkorelasi dengan menguatnya tribalisme politik. Fanatisme dan loyalitas kepada identitas kelompok akhirnya mengalahkan semua akal sehat. Makin merasa terancam suatu kelompok, makin besar intoleransi politik. Akibatnya, kesadaran dan peluang mengoperasikan politik dan demokrasi melalui gagasan dan jalan damai tanpa kekerasan mengecil.
Intoleransi politik hanya bisa diatasi apabila negara mau mengukuhkan suatu etika politik bersama yang diturunkan dalam kebijakan politik-hukum dengan basis demokrasi dan hak asasi. Hanya dengan itu negara akan mendapatkan kepercayaan dari setiap kelompok masyarakat dan memiliki moral standing membangun toleransi politik.
Hal kedua yang juga penting untuk melawan intoleransi politik adalah keberanian kewargaan untuk secara deliberatif mengonfrontasikan hal-hal ideal dalam sosial, politik, dan budaya yang beragam dengan kelompok yang berbeda-beda dalam masyarakat. Yang harus diingat, sekalipun negara penting, toleransi politik yang sejati tidak diturunkan dari proteksi kekuasaan, melainkan berasal dari pengalaman serta perjumpaan kewargaan.
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo