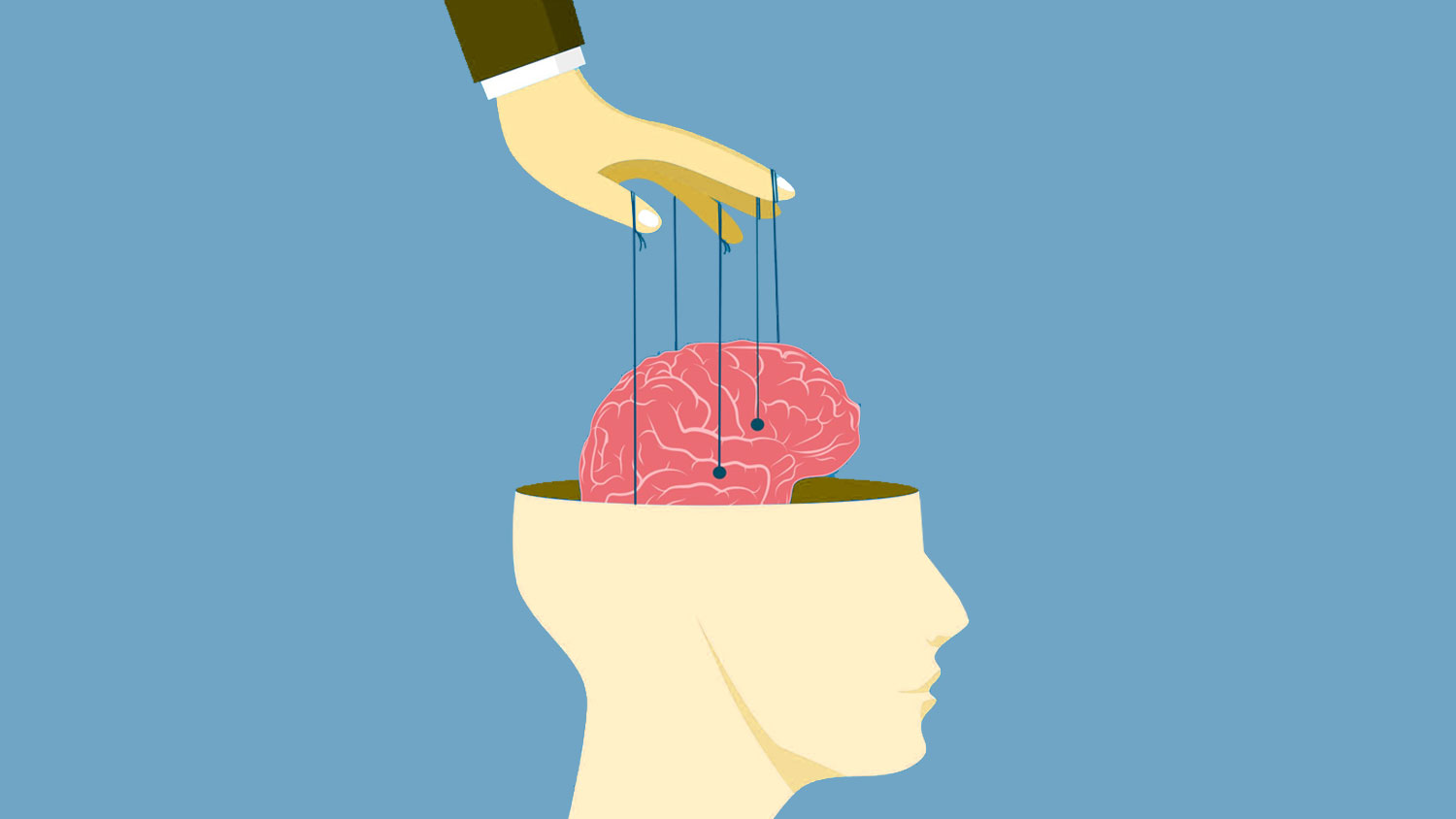Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Ringkasan Berita
Vonis ringan Juliari Batubara menghilangkan vonis bahasa kutukan.
Istilah koruptor kini menjadi terasa basi.
Dalam kosmologi, bahasa kutukan menjadi bagian hukuman bagi penjahat.
DI hadapan bahasa modern, tak bisakah seorang koruptor dikutuk sebagaimana Malin Kundang, Anglingdarma, Parasurama, dan seterusnya seperti zaman dahulu kala? Dalam sejarah Indonesia abad XXI, tampaknya belum ada yang begitu menghebohkan melebihi apa yang menimpa Juliari Batubara secara linguistik.
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo