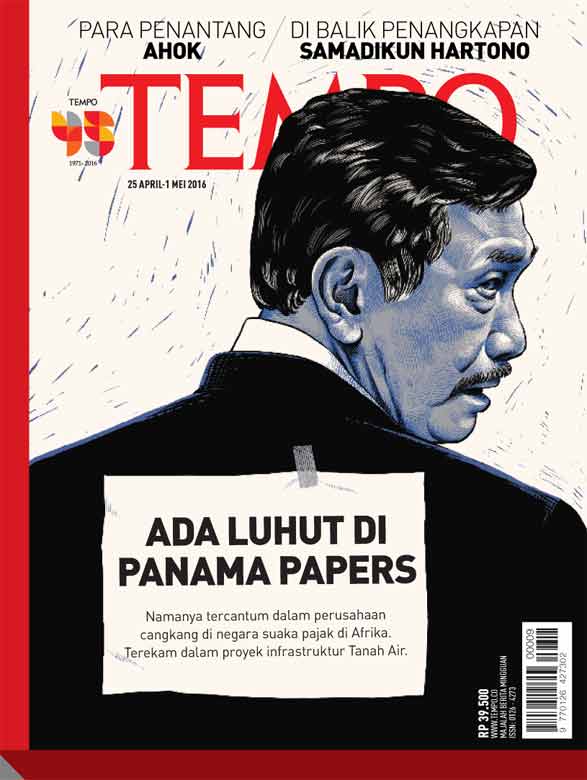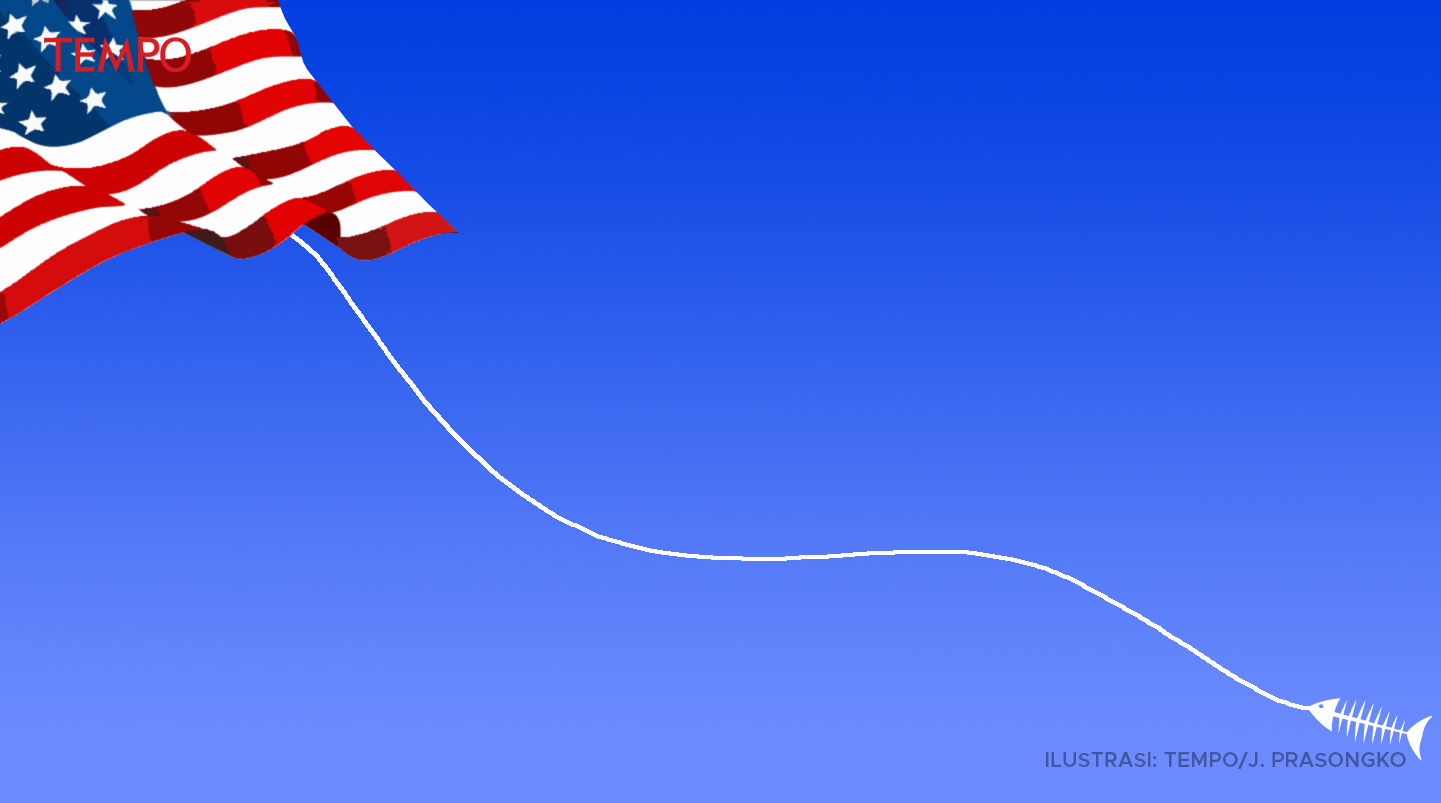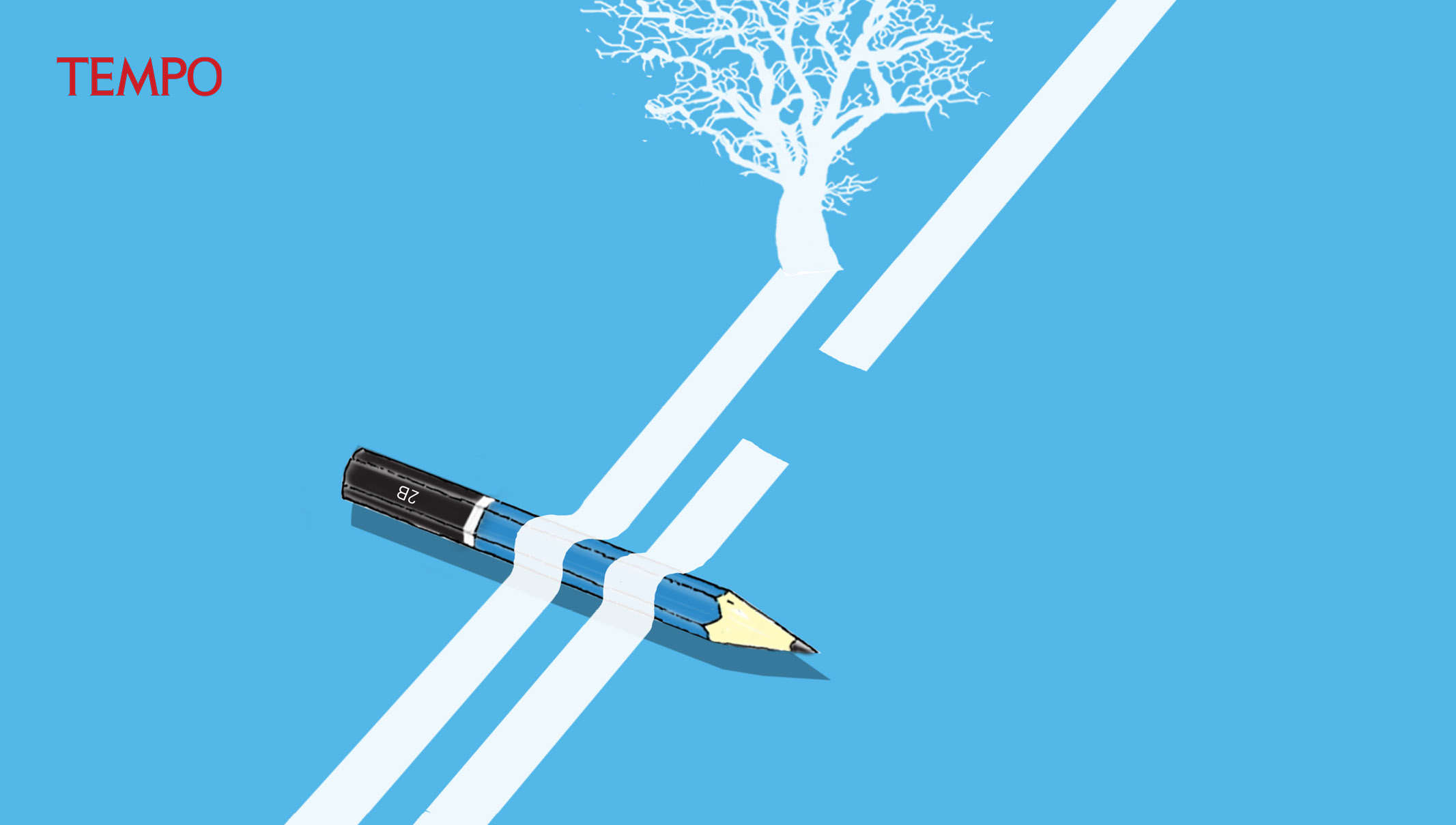Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

ADA satu ungkapan terkait dengan kepemimpinan nonmuslim yang memicu kontroversi belakangan ini: "pemimpin nonmuslim yang adil lebih baik daripada pemimpin muslim yang zalim". Sebagian kalangan Islam menolak ungkapan ini dan menganggapnya sebagai insinuatif, karena melekatkan ajektif "zalim" pada pemimpin muslim dan "adil" pada nonmuslim. Seolah-olah pemimpin muslim identik dengan kezaliman dan pemimpin nonmuslim identik dengan keadilan. Bahkan ada yang menuduh ungkapan tersebut sebagai susupan ide Syiah yang patut diwaspadai. Betulkah demikian?
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo