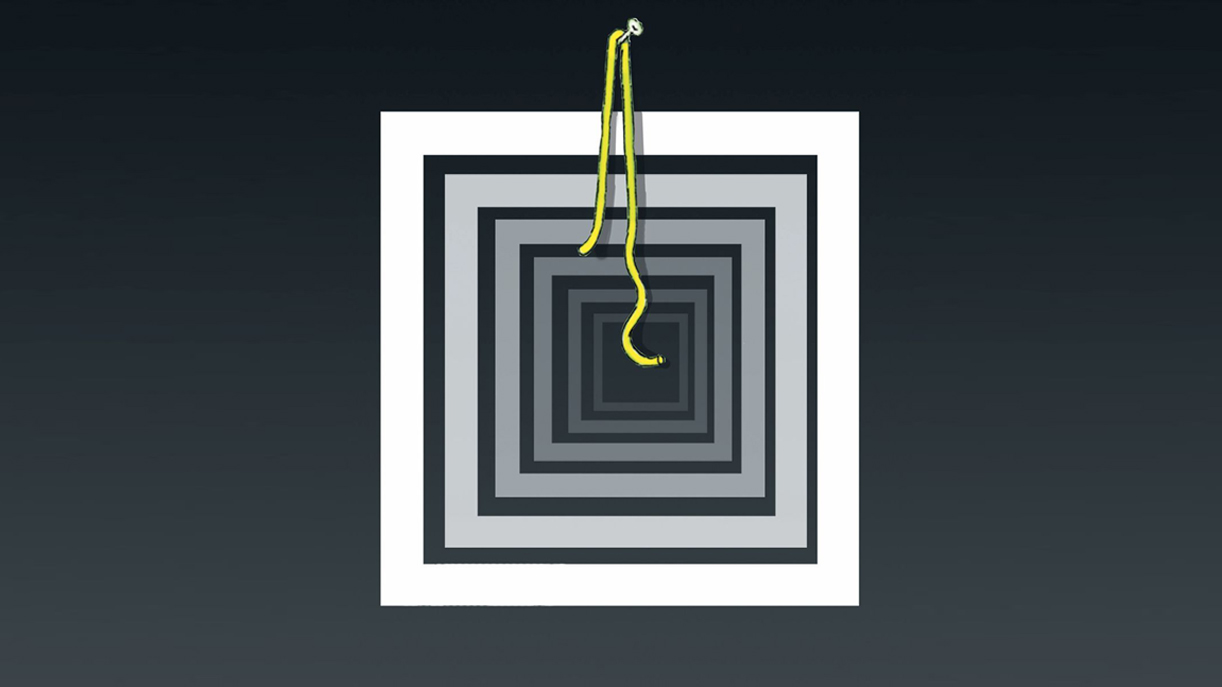Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

PADA 2004, karya klasik Isaiah Berlin, Empat Esai Kebebasan, diterbitkan dalam versi bahasa Indonesia oleh Freedom Institute. Berlin memberi pesan tajam: karut-marut politik membutuhkan “skeptisisme yang tercerahkan”—suatu sikap anti-mesianik atas desain politik dan anti pada janji-janji demokrasi.
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo