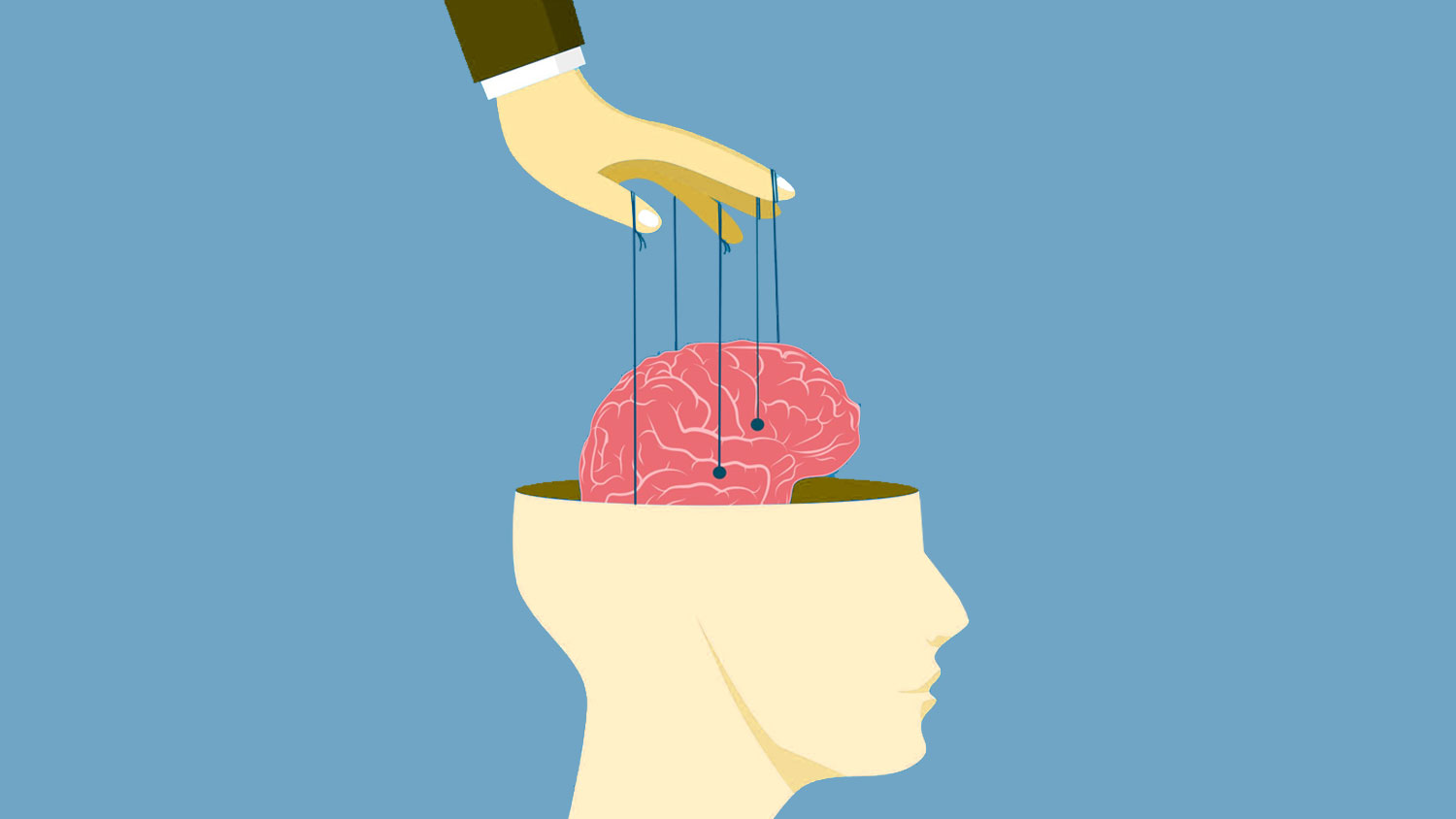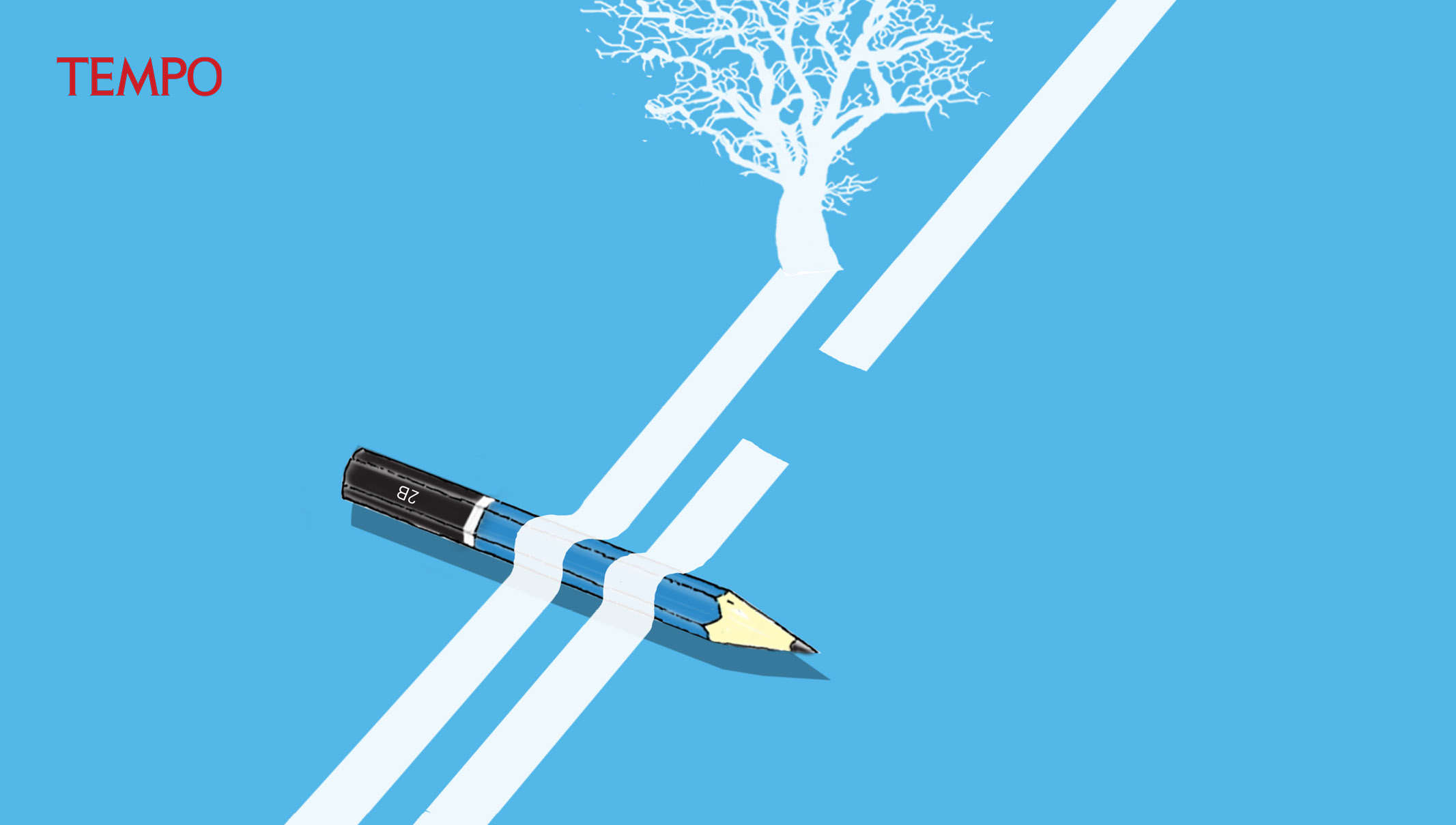Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Muhammad Rasyid Ridha S.
Pengacara Publik LBH Jakarta
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Sepanjang 2018, Kepolisian RI telah mengusut 122 kasus pidana ujaran kebencian, terutama di media sosial. Namun, dari segi substansi aturan, norma ujaran kebencian masih menyimpan problem. Hal tersebut dapat dilihat dari digunakannya istilah "suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)" sebagai indikator identitas masyarakat "yang dilindungi" dalam ketentuan Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Istilah SARA pertama kali dipopulerkan oleh Laksamana Sudomo saat ia menjadi Panglima Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban pada era rezim Soeharto pada 1980-an. Ia menggunakan istilah tersebut sebagai "istilah politis" untuk menyebut penyebab-penyebab konflik yang ditengarai akan mengguncang stabilitas masyarakat dan rezim Orde Baru.
Untuk istilah "suku, agama, dan ras", pendefinisiannya dapat dikatakan cukup jelas karena bisa dibuktikan secara konkret dari segi sains atau akademis. Namun, untuk istilah "antargolongan", batasan dan kriteria yang dicakupnya tidak jelas. Ia bersifat abstrak dan dapat digunakan ke semua hal.
Ini dapat dilihat, misalnya, dalam kasus penangkapan dan kriminalisasi Robertus Robet, pengajar Universitas Negeri Jakarta. Robet dituduh telah melakukan tindak pidana ujaran kebencian di media sosial lewat orasinya dalam Aksi Kamisan yang mengkritik upaya dwifungsi Tentara Nasional Indonesia.
Dalam proses penyidikan, polisi menggunakan ketentuan Pasal 28 ayat 2 UU ITE untuk kasus ini. Artinya, polisi memposisikan TNI sebagai sebuah identitas golongan tertentu. Hal ini menjadi paradoksal karena TNI bukanlah golongan, melainkan institusi pemerintah. Selain itu, pengertian "golongan" dalam pasal tersebut mesti merujuk pada pengertian "golongan yang secara limitatif diatur pada Pasal 156 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana".
Paradoks tafsir frasa "golongan" juga dapat ditemukan dalam beberapa putusan Mahkamah Konstitusi. Misalnya, Putusan MK Nomor 140/PUU-VIII/2009, Putusan MK Nomor 76/PUU-XV/2017, dan Putusan MK Nomor 76/PUU-XVI/2018 tidak memberikan definisi yang jelas dan logis atas frasa "golongan" pada beberapa aturan pidana ujaran kebencian.
Dalam putusan-putusan tersebut, frasa "golongan" dimaknai sejauh ia "bukan golongan agama", yang berarti tafsirnya menjadi sangat luas. Ketidakjelasan definisi akan menimbulkan kerancuan praktik hukum dan sangat mungkin mudah disalahgunakan. Apalagi kasus-kasus ujaran kebencian sendiri biasanya memiliki dimensi politis yang cukup kuat.
Secara historis, istilah "golongan" sebenarnya sudah dipakai dalam sistem hukum dan kedudukan ketatanegaraan Indonesia pada era pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Hal ini dapat dirujuk pada ketentuan Pasal 163 Indische Staatsregeling, yang merupakan peraturan ketatanegaraan pada era kolonial. Pasal tersebut mengatur pembagian tiga golongan di hadapan hukum: golongan Eropa, pribumi, dan Timur Asing (Djojonegoro: 1980).
Golongan Eropa mencakup warga Belanda, Eropa non-Belanda, Jepang, dan warga keturunan Eropa. Golongan pribumi mencakup orang Indonesia asli atau keturunannya yang melebur menjadi warga Indonesia asli. Adapun golongan Timur Asing mencakup orang Tionghoa dan non-Tionghoa, seperti India dan Arab.
Pembagian golongan ini dimaksudkan untuk menentukan sistem hukum apa yang berlaku bagi masing-masing golongan. Untuk golongan Eropa diberlakukan sistem hukum perdata dan pidana Barat. Untuk golongan pribumi diberlakukan sistem hukum adat secara tidak mutlak dan pidana Barat. Sementara itu, untuk golongan Timur Asing dapat diberlakukan sistem hukum perdata dan pidana adatnya sendiri.
Meski ada pembagian golongan, sistem hukum kolonial pada saat itu tetap memungkinkan adanya unifikasi golongan dan sistem hukum dengan cara "penundukan diri", baik secara keseluruhan, sebagian, secara diam-diam, maupun dalam kondisi tertentu. Pembagian golongan ini secara logis didasari kebutuhan, kondisi hukum, dan situasi masing-masing golongan pada saat itu. Jadi, mesti ada situasi hukum khusus yang mengkondisikan keberadaan "golongan" itu menjadi ada.
Golongan berdasarkan kedudukan tata negara hari ini dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan yang membagi golongan warga menjadi dua: warga negara Indonesia dan warga negara asing. Konsekuensinya, kedua golongan tersebut memiliki hak dan kewajiban hukum yang berbeda di hadapan hukum.
Bila tafsir frasa "golongan" dalam istilah SARA hendak diperluas, ia akan lebih baik bila diartikan sebagai golongan warga rentan yang memiliki posisi hukum dan perlindungan yang khusus. Golongan ini mencakup, misalnya, kelompok disabilitas, perempuan, anak, LGBTQ, dan masyarakat adat yang merupakan kelompok rentan dan perlu mendapatkan perhatian khusus, baik dari segi kedudukan, hukum, maupun hak atas akses keadilan. Beberapa di antara kelompok tersebut sudah memiliki aturannya sendiri, seperti kelompok disabilitas dan anak.
Tapi, bila tafsir "golongan yang didasari kedudukan ketatanegaraan dan posisi hukum khusus" diterapkan, bukan berarti kita hendak melakukan praktik diskriminasi atau memberlakukan semacam dualisme hukum. Hal tersebut diupayakan untuk mempercepat hak akses atas keadilan kelompok masyarakat khusus tertentu yang rentan agar kebijakan hukum dan akses atas keadilan dapat berjalan efektif serta tepat sasaran.