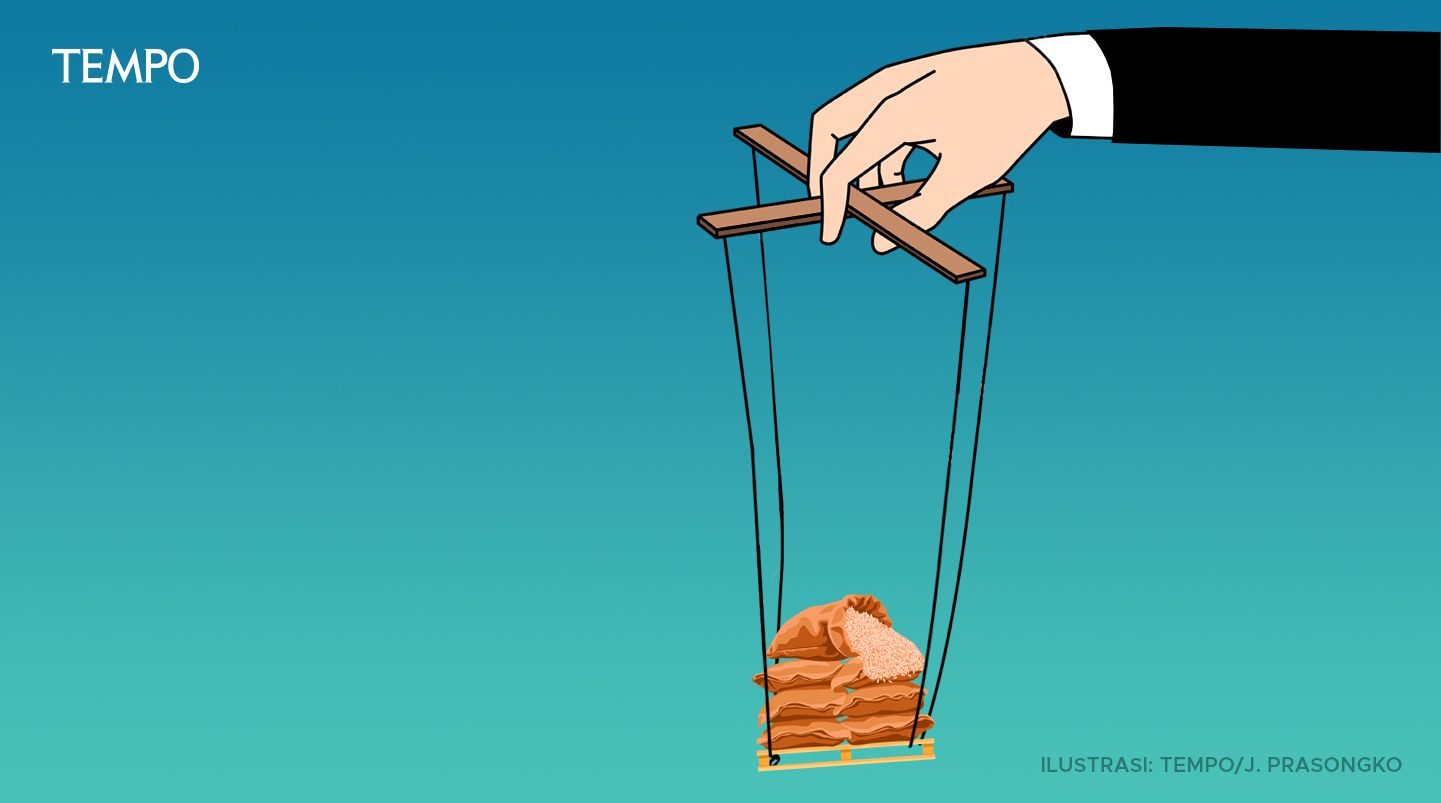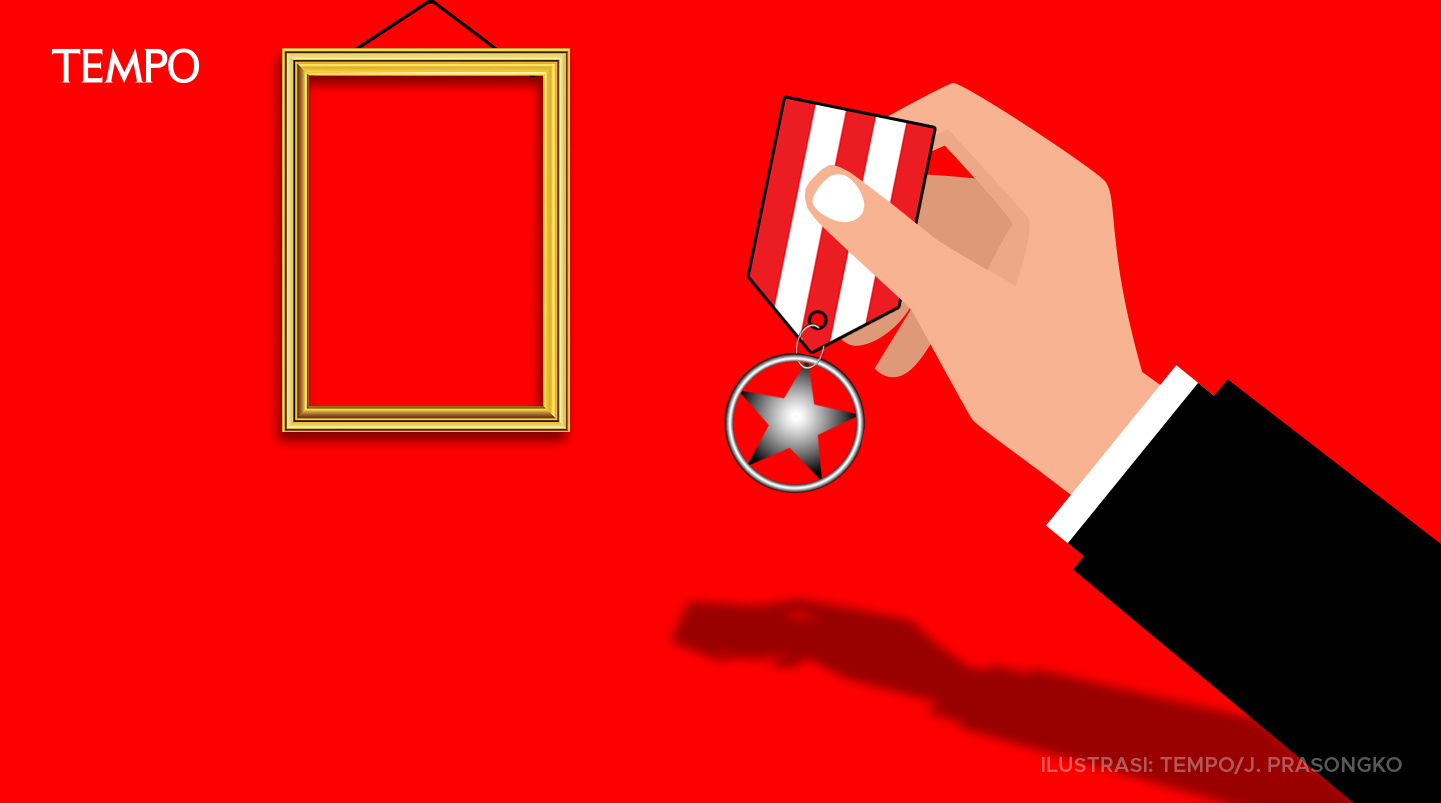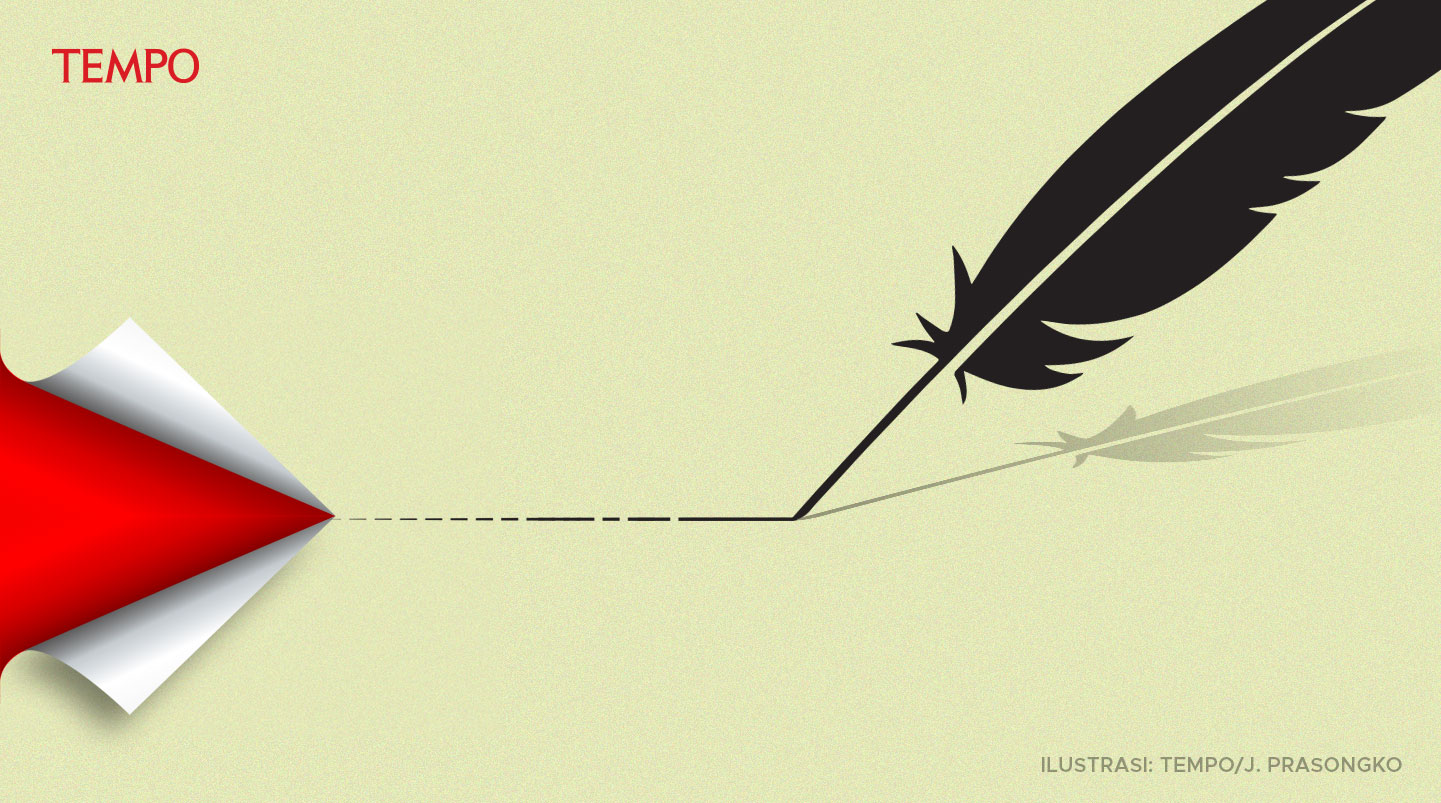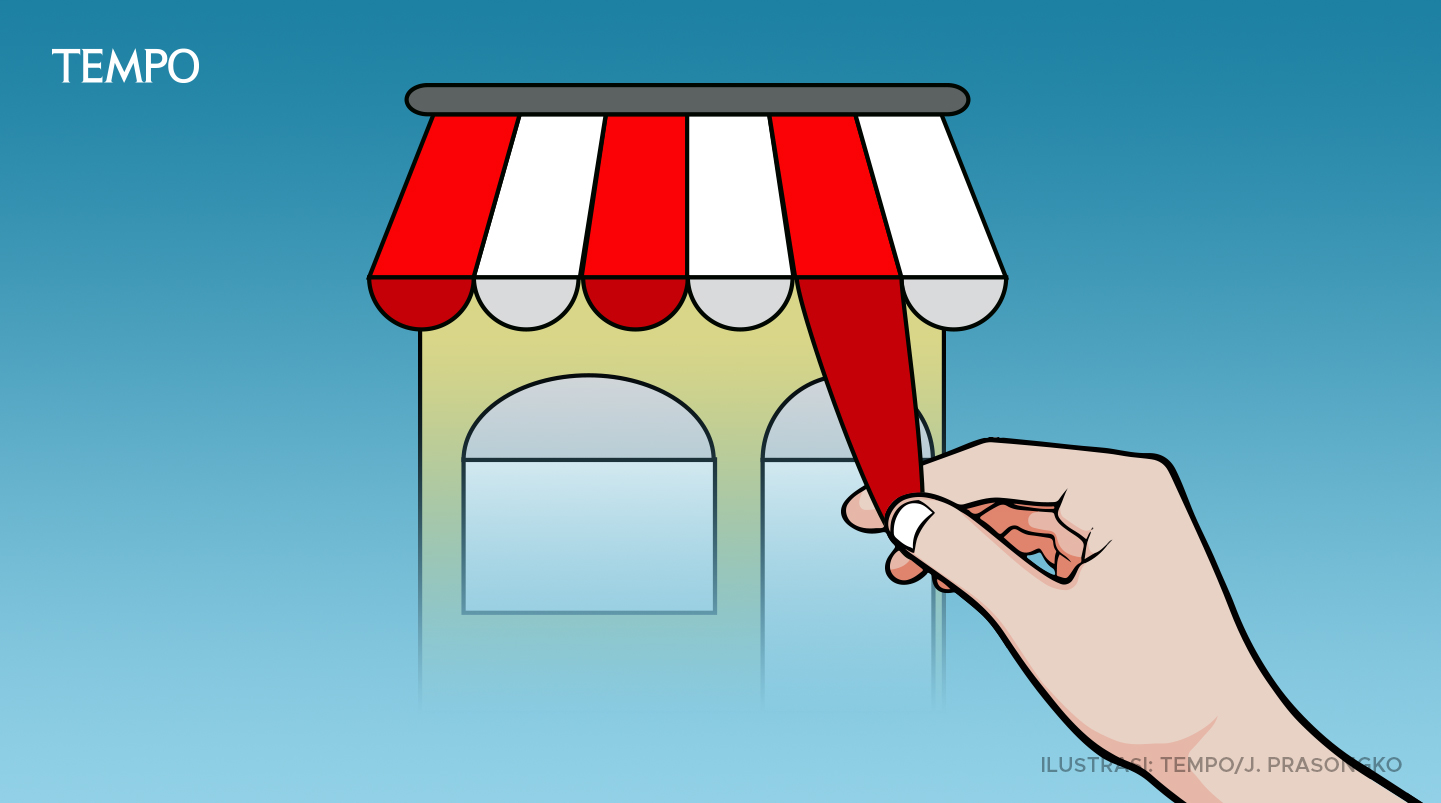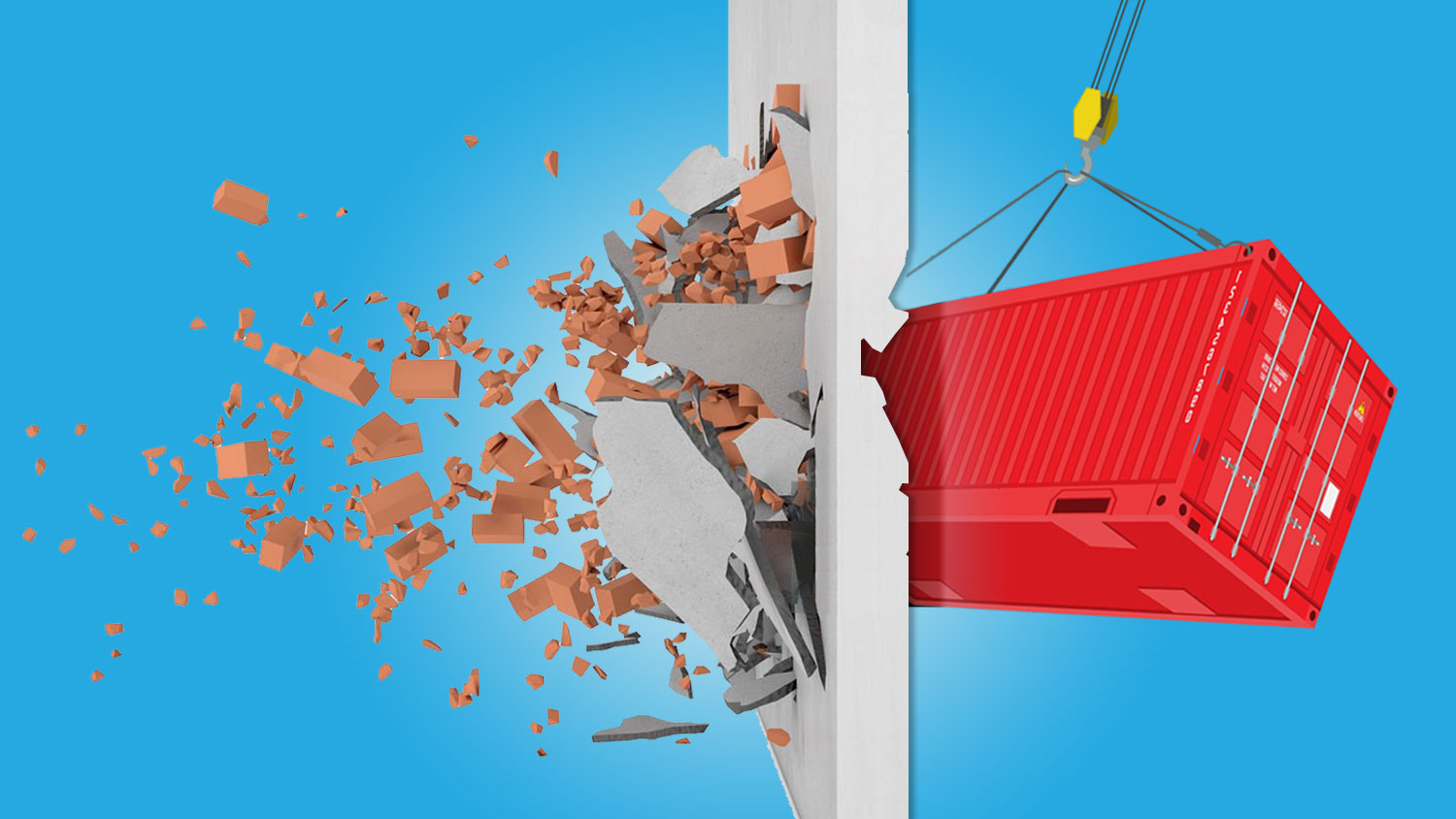Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Slamet adalah sebuah teriakan, ketika ia bunuh diri pada umur 48. Mungkin Kota Pandeglang mendengarnya. Mungkin Banten dan Jakarta mendengarnya. Tapi hanya 10 menit.
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo