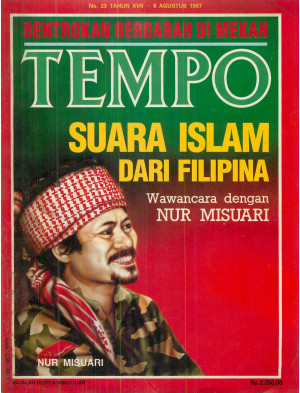KETIKA tepuk sorak penonton Istora Senayan bergema, Minggu malam dua pekan lalu, Ivanna Lie tersenyum. Tapi matanya basah. Satu per satu rekan, pelatih dan kenalannya datang memeluk atau memberi selamat. Bukan hanya untuk gelar juara ganda Kejuaraan Indonesia Terbuka yang baru saja direbutnya bersama Rosiana Tendean. Tapi untuk sebuah keputusan yang sudah bulat diambil: meninggalkan pelatnas Senayan, yang sudah 11 tahun menyatu dengannya. "Saya memang sedih. Tapi, dari sudut lain, saya harus memikirkan masa depan saya juga," kata Ivanna pada TEMPO, Sabtu pekan lalu di rumahnya, di Jalan Terusan Leo, Bandung. Rumah seluas 250 m2 itu tampak sederhana. Tak ada perabot mewah di sana. Di ruang tamu, dalam lemari kaca, dipajang piala kemenangan Ivanna dan foto-foto kenangan Ivanna meniti karier bulu tangkis. "Sebetulnya, masih banyak lagi piala dan medali. Tapi, kapan sempatnya mengurus ini semua? Waktu saya habis buat pelatnas. Dalam seminggu, paling cuma hari Sabtu saja saya pulang dan Minggu balik ke Jakarta. Tapi sekarang saya merasa bebas," katanya sembari tertawa. Omelan-omelan pelatih, dan disiplin keras yang selama ini senantiasa menghantui, tinggal kenangan. Tawanya lepas, tapi wajahnya kelihatan masih memendam rasa letih yang dalam. "Selama sebelas tahun itu, tak pernah saya istirahat total dua bulan penuh, misalnya. Itu membuat saya jenuh. Saya merasa seperti penulis yang kehilangan semangat dan motivasi. Saya harus berlatih terus, teruuus . . . dan rutiiin. Ini yang membuat saya bosan," kata Ivanna seperti mengeluh pada diri sendiri. Ada alasan lain? Sebuah pernikahan misalnya? "Nggak . . . nggak. Itu gosip aja, kok," ujarnya cepat. Ia memang selalu menghindar urusan yang satu ini. Sudah ada calon? Ia cuma tersenyum memamerkan lesung pipinya. Dibalut jeans dan kaus gombrong, Ivanna tampak ceking. Padahal, ukuran tubuhnya tergolong ideal, tinggi 159 cm dan berat 51 kg. Siapa sangka di tangan si ceking ini hampir semua pemain dunia pernah takluk. Sebut saja Lene Koppen dari Denmark, ratu Cina Liu Xia, jago Jepang Hiro Yuki, Tokuda, Yonekura, Kirsten Larsen, dan hampir semua pemain putri Cina lainnya termasuk Li Lingwei dan Han Aiping. "Di Asian Games 1978, saya kalah dari pelatih saya Liang Chiu Shia yang ketika itu masih di RRC," katanya mengenang. Namun, ia tak pernah mencatat prestasi puncak di kejuaraan resmi dunia. Itu sebabnya kalangan bulu tangkis pernah memberinya julukan "juara tak bermakota". "Yang paling berkesan pada final Grand Prix di Kuala Lumpur 1984. Ketika itu, saya menang dari Li Lingwei yang sudah dua tahun tak pernah kalah dari siapa pun. Saya jadi orang pertama yang mengalahkannya," katanya dengan pandangan mata berbinar-binar. Dengan kemenangannya itu, Ivanna menumbangkan mitos bahwa pemain putri Cina tak bisa kalah. Ia juga menumbangkan andalan Cina Han Aiping di Piala Alba, Jakarta, ketika Aiping baru beberapa bulan meraih gelar juara dunia 1985 di Calgary, Kanada. Sederet gelar juara pernah diraihnya, tapi di All England ia hanya mampu mencapai semifinal (1980 dan 1981). Pada 1980, ia menjadi runner-up Kejuaraan Dunia II di Jakarta. Semua itu dimulainya dari raket kayu dan sandal jepit. Di pinggir lapangan kampung, Ivanna kecil sibuk menepok-nepok bulu angsa meniru kakak-kakaknya di dalam lapangan. Rumah mereka di Kiara Condong, memang berhadapan dengan lapangan bulu tangkis. Di rumah itu Ivanna dilahirkan, 7 Maret 1960. Bersaudara 9 orang, Ivanna adalah anak ke-8 keluarga Lie Cung Sin yang pedagang kelontong itu. Toko keluarga itu tak maju, dan banting setir jadi agen Toto, Nalo, dan sejenisnya. "Eh, suatu saat bandarnya kabur dan kami harus membayar pemenang. Terpaksa, rumah Kiara Condong dijual. Saya sering nunggak uang sekolah. Ekonomi keluarga morat-marit," Ivanna mengenang dengan suara lirih. Ini mendorongnya berlatih keras. Lebih lagi, Hanafi, kakaknya yang jago bulu tangkis itu, terserang bronkitis. Ia berhenti main dan menekuni jahit-menjahit. Ivanna bergabung dengan klub Mutiara Bandung pada Februari 1974. Setahun di Mutiara, ia sudah menjadi juara Ja-Bar. "Itu karena pelatih saya Sian Sugiarto, yang juga sering membayari biaya latihan saya. Dia yang paling berjasa," katanya. Akhir 1976 ia sudah masuk Pelatnas. Tapi, pada tahun itu ia sempat kecewa ketika gagal memperoleh paspor untuk mengikuti Kejuaraan Yunior Asia di Hyderabad, India. Pasalnya, ayahnya ketika itu masih berstatus warga negara asing. Ivanna Lie Ing Hoa baru bisa mengubah namanya menjadi Ivanna Lie pada 1982. "Cukup panjang prosesnya, empat tahun," katanya lagi menarik napas panjang. Sejak itu ia praktis terus menghabiskan masa remajanya di Senayan. "Saya ingin punya keahlian lain selain bulu tangkis. Kalau bergaul dengan anak sekolahan, bukannya minder sih, cuma ya . . . kurang sreg aja rasanya," katanya dengan logat Sunda yang kentara. Ia pernah kuliah beberapa bulan di Fakultas Ekonomi Universitas Atma Jaya dan ASMI. Tapi tampaknya bulu tangkis sudah memberikan modal yang cukup. Sebuah Honda Civic Wonder tahun terbaru kini dikendarainya. "Rumah ini juga sebagian saya bangun dengan uang dari badminton," katanya mengedarkan pandang ke rumah di Jalan Leo itu. Dari hasil jual mobil Corona seharga Rp 3 juta, Ivanna memodali usaha konveksi pakaian olah raga dengan merk Elvana yang diurus kakaknya. Mulai dengan sebuah mesin jahit di tahun 1982, Elvana kini sudah memiliki lebih dari 100 mesin jahit dengan 70 orang pegawai. Pabrik seluas 10 X 12 meter itu terletak di Jalan Warung Jambu, sekitar 10 menit berkendaraan dari rumahnya. "Kami sudah mengirim sampai Medan dan Ujungpandang. Sekarang ini kami masih belum mampu memenuhi pesanan," kata Ivanna. Pabriknya memproduksi celana pendek, kaus, dan tas olah raga, sekitar 600 lusin sebulan. Katanya pelan "Kalau saya tetap di pelatnas, saya kuatlr pabrik ini telantar". Pandangan matanya menebar ke arah puluhan penjahitnya yang tekun bekerja. "Inilah harapan saya." Matanya berbinar, seakan memandang masa depannya. Toriq Hadad
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini