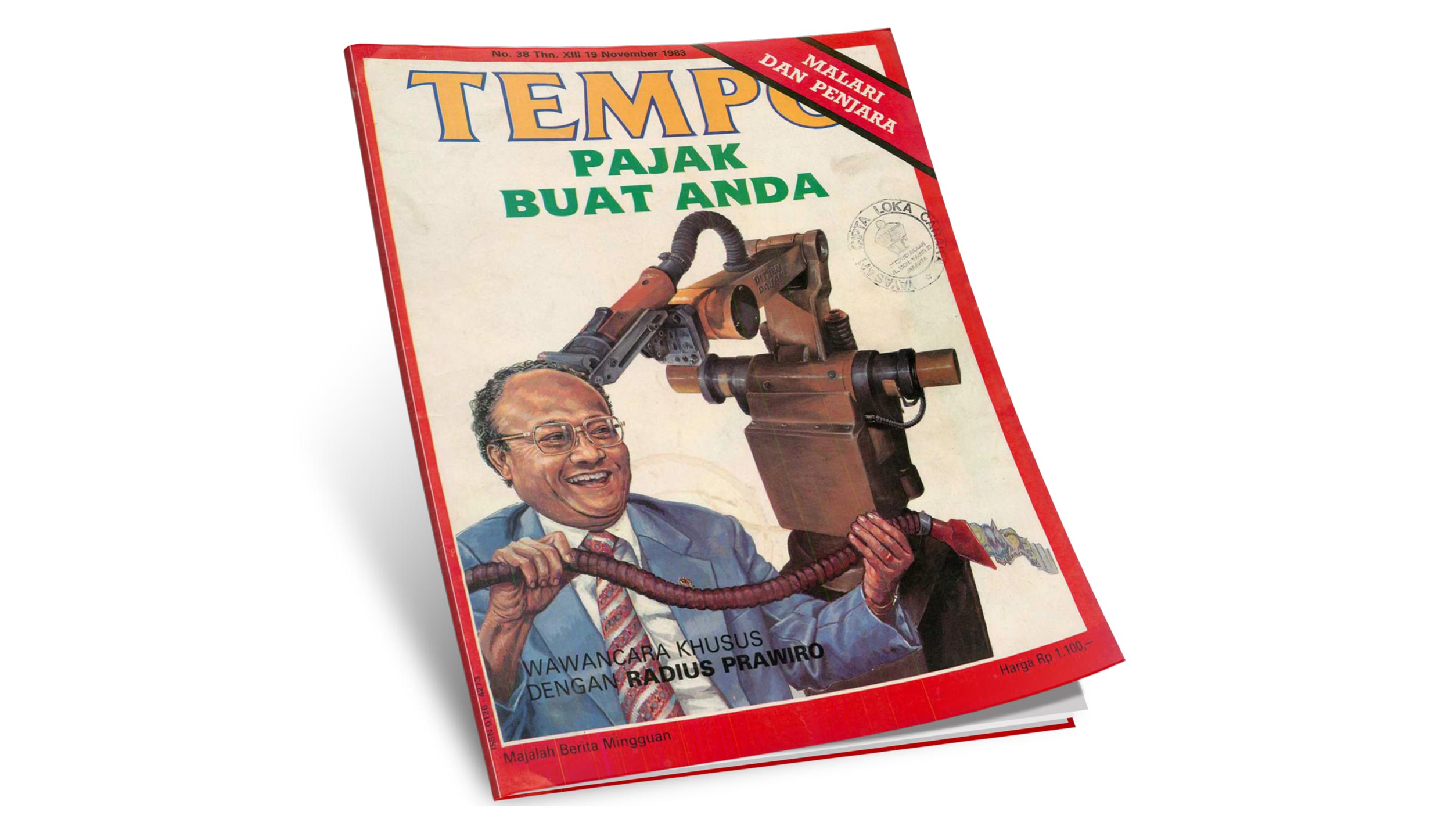Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
PEMERINTAH mencabut subsidi listrik untuk rumah tangga pengguna daya R1/900 volt ampere dengan alasan agar subsidi tepat sasaran. Ketika pencabutan subsidi ini direalisasi, secara otomatis masyarakat pengguna listrik 900 VA bakal membayar tarif listrik jauh lebih mahal dibanding sebelum bantuan pemerintah itu ditiadakan. Selama ini, rumah tangga pengguna listrik 900 VA membayar Rp 568 per kilowatt-jam. Jika subsidi ditiadakan, mereka akan membayar sekitar Rp 1.467 per kWh sesuai dengan perhitungan keekonomian saat ini.
Semula pemerintah akan meniadakan subsidi listrik tersebut per 1 Juli tahun ini. Namun pemerintah urung merealisasinya setelah menuai protes dari berbagai kalangan. Sampai bulan ini, masih terjadi perdebatan yang alot mengenai rencana pencabutan subsidi listrik tersebut.
Majalah Tempo edisi 29 Maret 1986 menulis artikel dengan judul "Menggantol PLN". Dalam tulisan itu, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menggugat kebijakan pemerintah mengenai penetapan tarif listrik. Wakil Ketua Kadin saat itu, Probosutedjo, meminta pemerintah meninjau ulang tarif listrik. Ia beralasan, jika tarif listrik turun, itu bakal menghemat banyak biaya produksi. "Biaya listrik di Indonesia merupakan salah satu yang termahal di dunia," kata Probosutedjo pada Maret 1986.
Benar. Harga listrik di sini, pukul rata, 8,710 sen dolar. Bandingkan dengan harga listrik rata-rata di Singapura--kendati tak punya minyak--yang bisa dijual sebesar 7,723 sen dolar. Listrik murah di Singapura bisa dicapai lantaran, mungkin, perusahaan listrik di sana tidak banyak merentangkan kabel berkilo-kilometer, mengambil tanah orang, dan setiap tahun harus mendepresiasikan harta baru. Penduduknya berdisiplin, sehingga tidak banyak listrik hilang kena gantol di tengah jalan.
Tapi di sini tidak. Tingkat kehilangan listrik PLN dalam transmisi dan distribusi (1982-1983) masih mencapai 18,7 persen. Coba bandingkan dengan Malaysia dan Thailand, yang masing-masing hanya punya angka kehilangan 7,6 persen dan 9,9 persen. Wajar kalau Bank Dunia, sebagai penyedia dana murah terbesar, meminta perhatian. "Kami sudah minta kepada PLN untuk mengurangi tingkat kehilangan listrik dalam pengoperasiannya dan menaikkan kemampuan untuk menyuplai listrik dengan baik," ujar D.C. Rao, Direktur Perwakilan Bank Dunia di Indonesia ketika itu, Maret 1986. Besar-kecilnya tingkat kehilangan listrik ini memang banyak ditentukan letak geografis dan pola penyebaran konsumen. Semakin jauh letak konsumen, dan tempatnya jauh tersebar dari pusat pembangkit listrik, kemungkinan kehilangan daya jadi makin besar. Pola seperti itu ternyata ada di sini. Karena alasan itu, Rao menyatakan, "Tidak terlalu optimistis dalam waktu singkat soal kehilangan listrik bisa ditanggulangi."
Padahal harga listrik banyak dipengaruhi besarnya persentase kehilangan itu. Tapi bukan hanya karena soal itu ketika, pada pertengahan Maret 1986, nama Bank Dunia dan PLN disebut-sebut. Pemberitaan mulai hangat gara-gara sebuah media nasional mengutip Kepala Humas Departemen Pertambangan dan Energi saat itu, Harjoko Seputro, yang menyebut adanya penundaan kredit US$ 350 juta dari Bank Dunia. Jalan buntu terentang gara-gara kedua pihak tidak bisa mencapai kesepakatan mengenai usaha memperbaiki efisiensi PLN.
Menurut Harjoko, kredit lunak sebesar itu seharusnya sudah bisa diterima pada akhir 1985 dan akan digunakan untuk membiayai pembangunan pusat tenaga listrik batu bara di Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Kemudian sebagian lagi akan dipakai untuk membiayai pembangunan transmisi, gardu induk, jaringan tegangan menengah dan rendah, serta trafo distribusi. Tapi kesepakatan belum bisa dicapai karena Bank Dunia meminta PLN mau memperhatikan beberapa hal. "Negosiasi itu tidak gagal, tapi tertunda, sih, memang iya," kata Harjoko, Maret 1986.
Tertundanya pencairan kredit itu mempengaruhi jadwal kerja PLN. Apa boleh buat. Bank Dunia, yang memberikan kredit US$ 2,1 miliar (ditambah dari Bank Pembangunan Asia sekitar US$ 647 juta), jelas ingin melihat pinjamannya memberikan hasil memadai. Mungkin Bank Dunia ingin PLN istirahat berekspansi besar-besaran untuk memberi kesempatan menghitung kembali kewajiban dan prospek usahanya.
Dua kali devaluasi memang menyebabkan PLN menderita rugi akibat perubahan kurs hampir 90 persen. Padahal sebagian besar kewajiban yang harus ditanggungnya berupa valuta asing. Bisa dipahami kalau pada 1985 badan usaha milik negara ini hanya memperoleh laba Rp 500 juta lebih. Untung, pinjaman yang diterimanya itu berbunga rendah dan berjangka panjang. Tapi, "Risiko akibat perubahan kurs itu setahu saya ditanggung Menteri Keuangan (jadi beban APBN), bukan PLN," kata Rao. Toh, dalam situasi serba kekurangan seperti itu, Rao menilai tarif PLN masih sebanding dengan negara lain. Tapi Kadin bilang tarif perlu turun, bagaimana mungkin?
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo