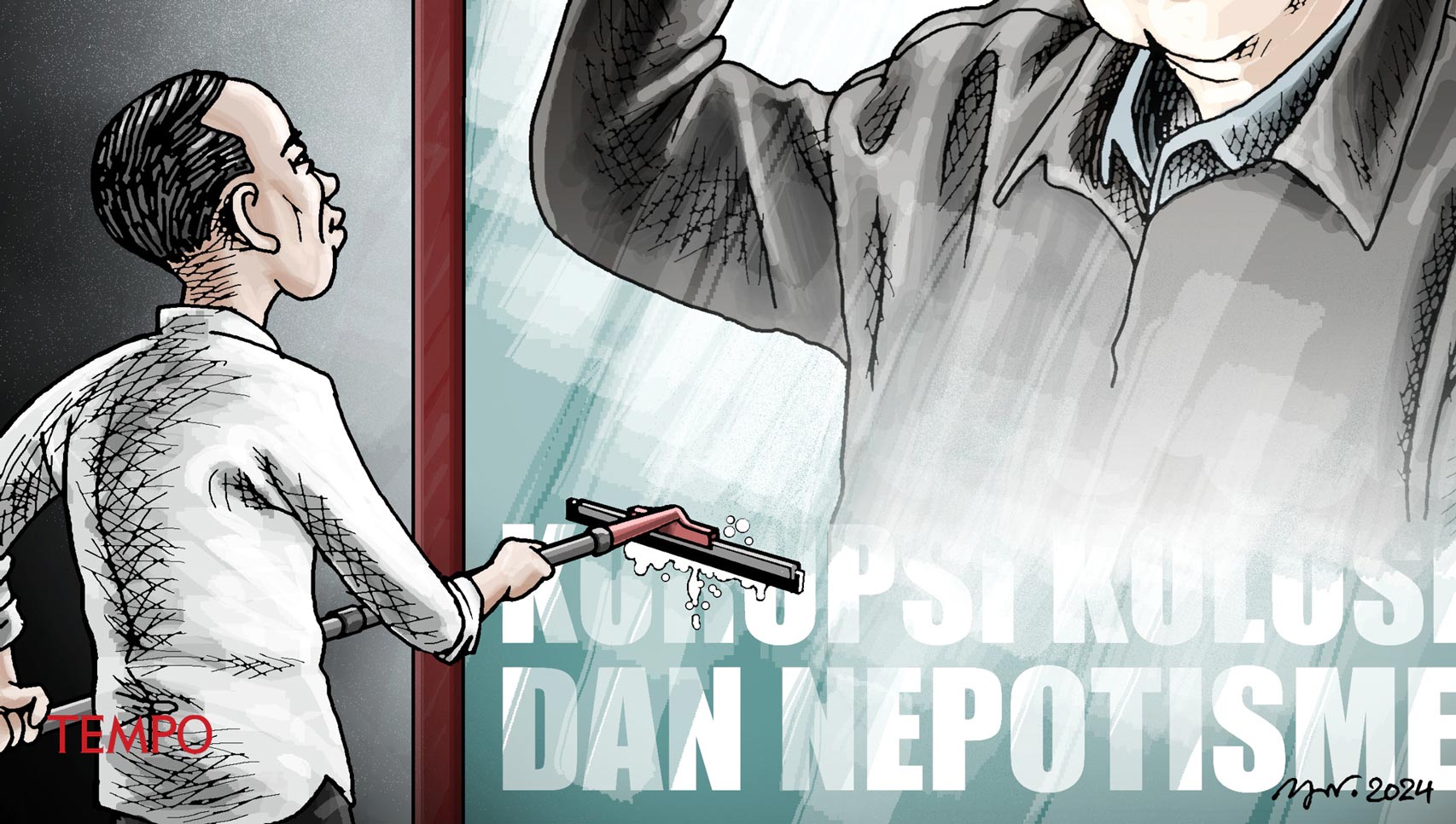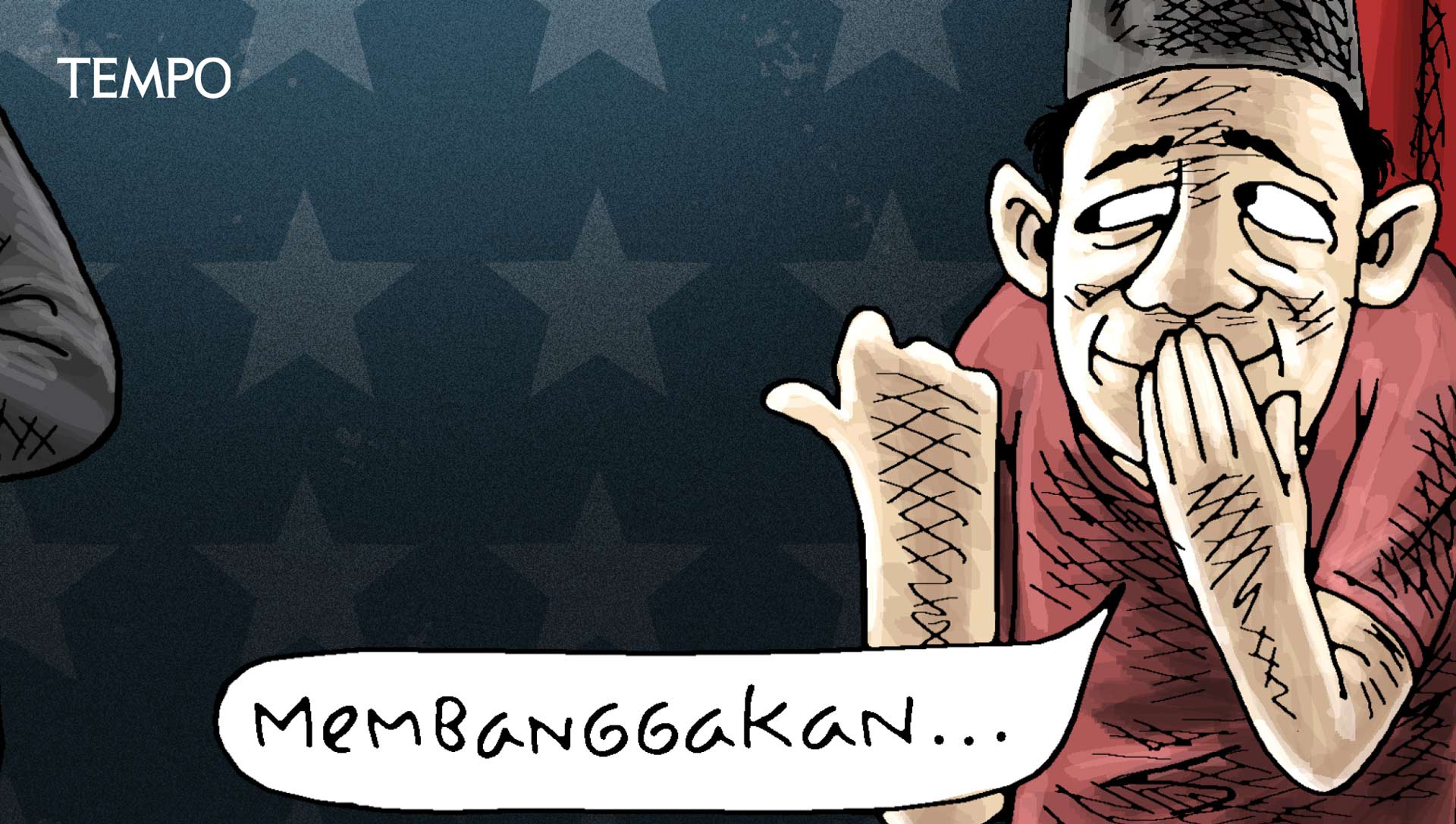Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Pertama, reaksi yang begitu keras dari khalayak ramai, ketika 21 Juni 1994 majalah ini, bersama DeTik dan Editor, dilarang terbit oleh yang berkuasa. Pertama kali dalam sejarah pers Indonesia, para pemuda, aktivis, juga wartawan, turun ke jalan di beberapa kota menentang pembredelan. Protes juga datang dari luar negeri. Bahkan, sebuah pesantren tua di pedalaman Madura mengadakan istigazah, doa prihatin bersama, satu bulan setelah apa yang dilakukan pemerintahan Soeharto bulan Juni itu.
Semua itu tentu tercetus karena rasa marah atas direnggutkannya hak khususnya, hak masyarakat memperoleh informasi. Tapi, bagi kami, aksi itu punya dampak khusus: ia menyisipkan sebuah pesan, sebuah amanat. Kami terharu mengetahui solidaritas begitu luas dari publik ketika pemerintah merampas kemerdekaan kami buat menyatakan pendapat. Tentu saja ini bukan sekadar soal hilangnya kemerdekaan para wartawan yang bekerja di ketiga penerbitan tadi. Tindakan 21 Juni 1994 itu mengisyaratkan kesewenang-wenangan yang mengenai lebih banyak orang. Bagaimanapun, kami sendiri semakin sadar: ada sesuatu yang lebih berharga ketimbang nafkah dan kepuasan profesional--yakni kemerdekaan dan harga diri. Keduanya harus kami pertahankan. Untuk kepentingan umum.
Itu sebabnya kami ikut dalam perlawanan yang lebih luas. Pada 26 Juni 1994 malam, hanya lima hari setelah TEMPO dibredel, direktur utama perusahaan yang menerbitkan majalah itu, Eric Samola, diundang untuk bertemu dengan Hasyim Djojohadikusumo, pengusaha, di Lagoon Tower Hotel Hilton, Jakarta. Hasyim, saudara kandung Prabowo Subianto?menantu Presiden yang kemudian menjadi komandan pasukan khusus yang empat tahun kemudian menculik dan menyiksa sejumlah aktivis (di antaranya kini masih hilang)--memberi tawaran: TEMPO bisa terbit kembali bila ia dan "keluarga" diberi hak mengangkat dan memberhentikan redaksi, dan bila ia dan "keluarga" mendapatkan opsi pertama jika saham TEMPO akan dijual.
Tawaran ini harus segera dijawab sebelum pukul 8.00 esok paginya. Hari itu sudah lewat pukul 22.00. Untuk membicarakan tawaran itu, menjelang tengah malam, direksi TEMPO bertemu di rumah Goenawan Mohamad. Keputusan: tawaran Hasyim Djojohadikusumo--meskipun memberi kans bagi TEMPO untuk hidup lagi--ditolak. Lewat tengah malam keputusan ini kami sampaikan, dengan cara diplomatis, karena kami tentu saja ketakutan. Kami tahu, Prabowo Subianto-lah yang mengutus Hasyim, dan kami menafsirkan kata "keluarga" sebagai "keluarga Cendana".
Kami sadar, dengan penolakan itu, TEMPO tak akan dapat hidup lagi. Terutama, karena sebetulnya bukan pertama kalinya "pembangkangan sopan" itu kami lakukan. Kurang lebih setahun sebelum dibredel, sejumlah orang di pusat kekuasaan dengan pelbagai cara mendesak pimpinan TEMPO agar memberhentikan Fikri Jufri sebagai pemimpin redaksi, setelah Goenawan Mohamad pada 1993 tak lagi duduk dalam jabatan itu. Fikri Jufri rupanya dianggap bagian dari kegiatan "anti-Soeharto". Desakan itu kami tolak. Kami anggap itu awal intervensi kekuasaan ke ruang kerja kami. Penolakan itu mempertajam ketegangan hubungan antara TEMPO dan penguasa--sampai konflik terbuka terjadi ketika majalah ini ditutup.
Itu dimulai ketika kami mengadukan keputusan Menteri Penerangan Harmoko mencabut surat izin usaha penerbitan kami ke PTUN--sebuah langkah yang aneh waktu itu. Sebelumnya tak ada surat kabar atau majalah yang dibredel yang melakukannya. Kami juga tahu, mustahil kami akan menang di pengadilan: kekuasaan "Orde Baru" mencengkeram kepala dan kantong para hakim di mana-mana. Kami tak keliru. Memang mengejutkan Hakim Benjamin Mangkoedilaga di PTUN Jakarta memenangkan TEMPO. Juga pengadilan tinggi mengukuhkan itu. Tapi akhirnya toh Mahkamah Agung seiring sejalan dengan pemerintah. Maka, di tangga Gedung Mahkamah Agung pagi itu Goenawan Mohamad mengatakan di depan ratusan simpatisan yang datang: "jalan hukum" sudah selesai, kini tinggal "jalan politik".
Itu pula sebabnya para wartawan TEMPO ikut mendukung Aliansi Jurnalis Independen (AJI), yang dilahirkkan setelah pembredelan, untuk melawan. AJI pula yang dengan berani menerbitkan majalah berita bawah tanah, yang kemudian disebut Suara Independen. Ketika polisi menggerebek, tiga orang diseret ke pengadilan. Selama sekitar tiga tahun mereka dipenjarakan. Ahmad Taufik, wartawan TEMPO dari Bandung (kini Kepala Biro Jakarta), adalah salah satu di antaranya. Terhukum lain Eko Maryadi, yang pernah bekerja di Pusat Data dan Analisa TEMPO.
Semua itu membuat TEMPO, setelah mati, jadi terasa lebih besar dan berat ketimbang TEMPO sebelum ditutup. Ia bukan lagi cuma "sebuah majalah". Ia bagian dari perlawanan umum terhadap sebuah rezim.
Kami bangga, tentu. Tapi kami, yang bekerja sehari-hari di dalam TEMPO sebagai sekadar "sebuah majalah", tahu bahwa majalah ini bukan makhluk dongeng. Kami pernah salah cetak dan salah foto. Kami juga pernah mengikuti adat "Orde Baru", menyensor diri di sana-sini apabila tekanan begitu keras. Kami memang menganggap jurnalisme waktu itu "perang gerilya"--maju bila penyensor lemah, mundur bila penyensor garang--tetapi tak selamanya "gerilya" itu melahirkan tindakan heroik.
Jurnalisme memang bukan untuk menjadikan wartawan pahlawan. Dalam suasana pers yang bebas, menyiarkan fakta dan pendapat adalah lakon sehari-hari. Keberanian tak sulit. Yang sulit adalah mendapatkan kepercayaan. TEMPO terbit kembali, dan kami tak menganggap majalah ini dengan sendirinya unggul di sana.
Sebab, TEMPO adalah sebuah proses. Di sana pembaca--yang umumnya cerdas dan kritis--ikut menentukan. Bahkan sangat menentukan. Selamat membaca.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo