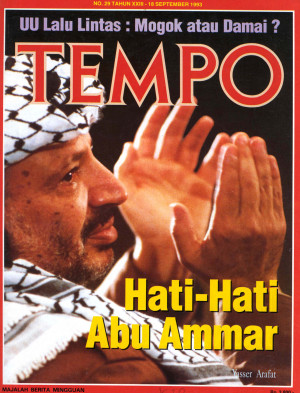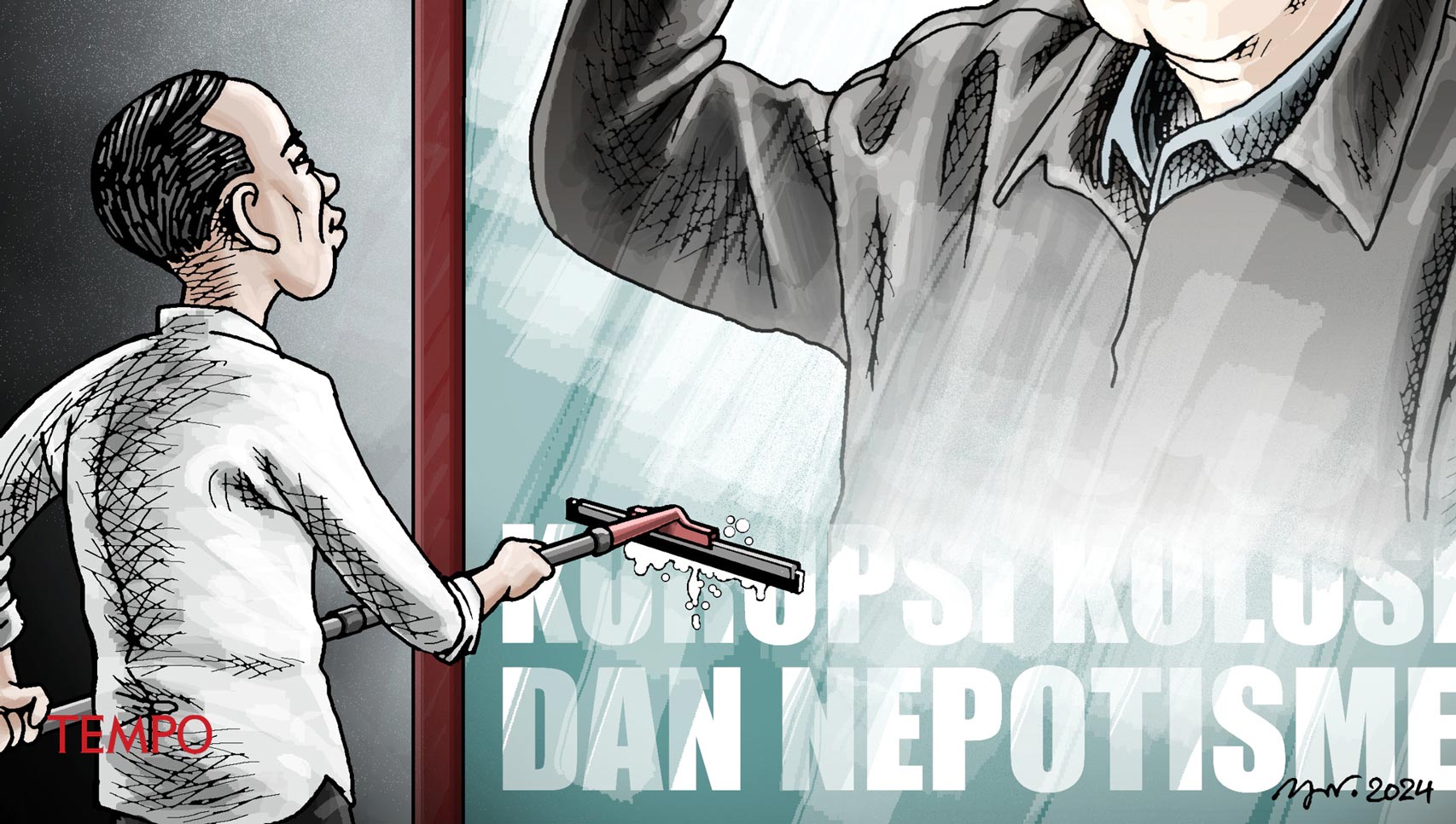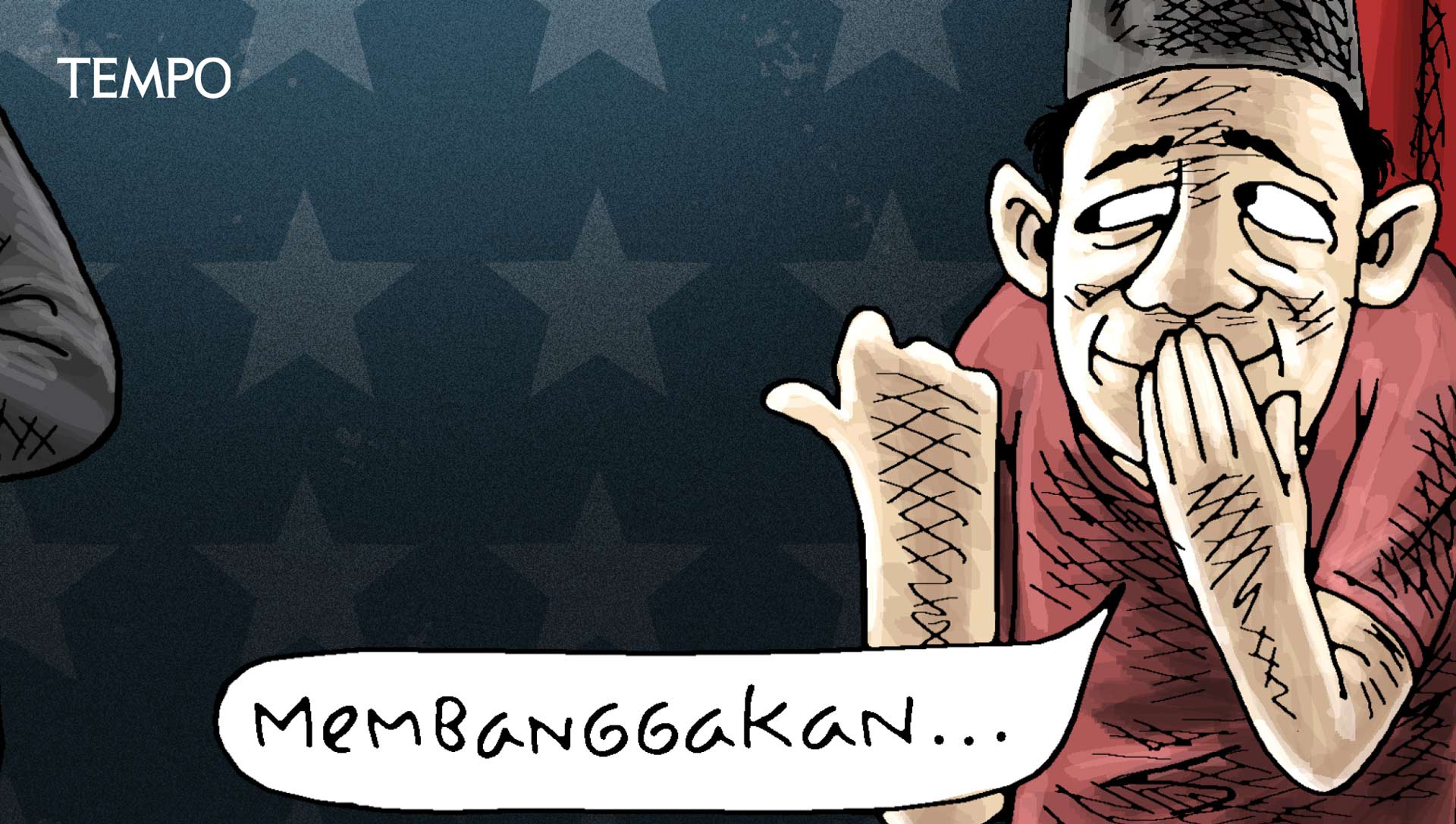Lama saya tercenung membaca komentar tentang buku Minangkabau di TEMPO, 10 Juli, dalam rubrik Buku. Saya sebut tulisan dua halaman dengan foto bergincu itu sebagai komentar, bukan resensi ataupun kritik, karena seluruh isinya bernada cercaan. Sejak awal, komentar tentang buku Minangkabau itu sarat dengan keawaman si penulis tentang topik yang ditulisnya. Simak saja cara ia membuat analogi, ''Buku foto Minangkabau adalah nasi kapau itu.'' Kapau itu Minang, ya, karena merupakan nama sebuah kampung di daerah Bukittinggi. Tapi menamsilkan Minang sebagai Kapau (dengan huruf ''k'' kecil pula), dalam konteks apa pun, sungguh merupakan pemahaman mentah tentang Minangkabau, yang diakui si penulis bahwa potretnya amat padat tersaji di buku tersebut. Adakah buku itu tergolong ensiklopedi, atau buku esai foto, atau mungkin sebagai reportase jurnalistik foto versi Ed Zoelverdi, tampaknya bukan itu inti soal yang harus disorot. Yang perlu dilacak, apakah buku yang bermisi hendak melukiskan profil suatu etnik itu mampu memberikan tambahan pengetahuan atau tidak. Ini yang luput dari penglihatan penulis komentar itu. Dan bila dikaitkan dengan corak budaya Minang yang terkenal dengan budaya kaba atau budaya oral, kehadiran sebuah buku adalah sebuah terobosan. Lalu saya tertawa dan sekaligus prihatin ketika membaca komentar: ''Dengan memotret tiga generasi wanita penghuni rumah gadang dari pantulan cermin kuno, misalnya ....'' Ini komentar hanya sekadar nekat. Kalau betul penulisnya tukang potret dan sedikit rendah hati, tentunya mafhum hasil memotret di cermin. Dalam posisi frontal, pasti tukang fotonya juga terekam. Setahu saya, foto itu dibuat di balik daun pintu yang bolong di sebuah rumah tua di Luhak Tanah Datar. Bolongan itu bentuknya memang oval. Tak ada kaca di situ, apalagi cermin. BUYUNG PALIMO Jalan Diponegoro 19, Padang
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini