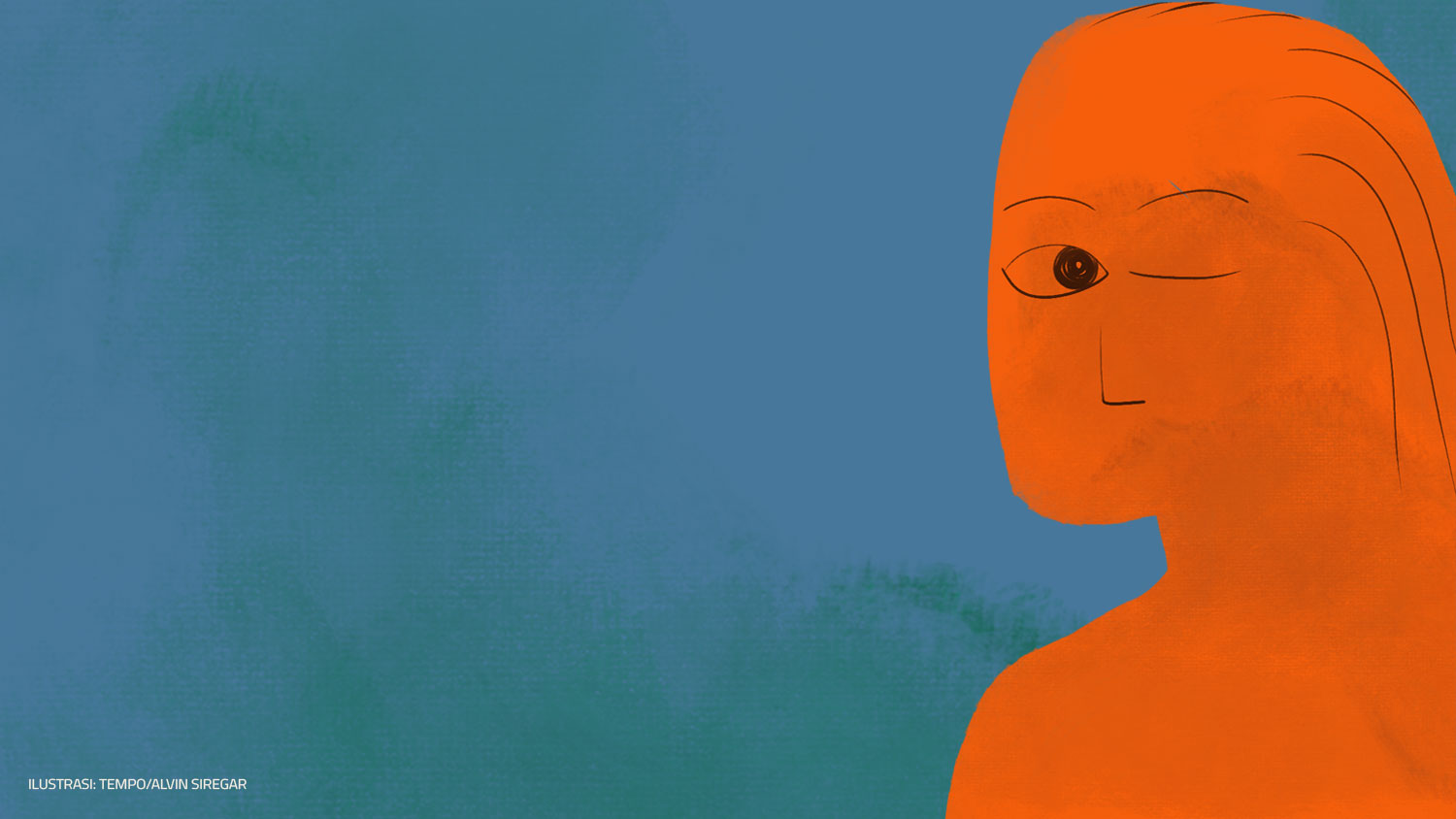Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
DI DALAM warung kopi Salindri terdengar percakapan dua lelaki setengah baya. Kiai Muhaya dan Suro Kolong menjadi pengunjung paling pagi. Mereka berjanji bertemu di warung kopi Salindri sebelum melakukan perjalanan ke pedepokan Ki Gandrung Marsudi. Langkah mereka menjauh dari Lembah Kelelawar yang senyap menuju lereng Jabal Ahad.
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo