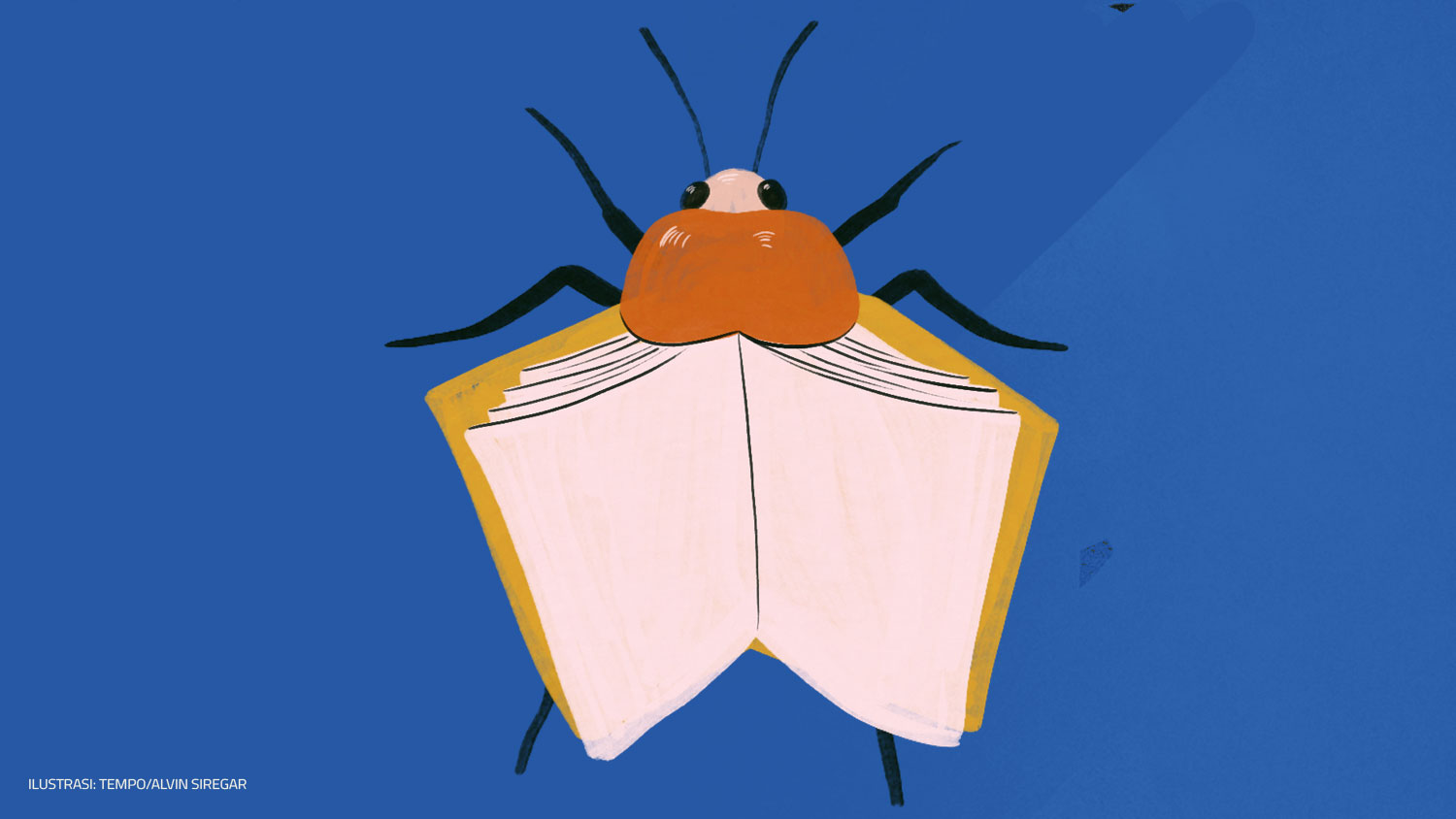Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
PADA Sabtu malam hingga Ahad pagi (1-2 April 2023), klub Arkaoda di Berlin, Jerman, bermandi cahaya kemerahan. Pusat perhatian para pengunjung bertumpu pada dua sosok yang memainkan berbagai peralatan bunyi. Ada yang menghasilkan bunyi secara digital, ada alat tiup yang lebih mirip mainan anak-anak, juga sejumlah alat yang dibuat dari bahan-bahan tak umum seperti pipa paralon dan kantong plastik.
Mereka adalah Ariel William Orah dan Mo’ong Santoso Pribadi. Dalam rangkaian acara CODEX CLUB x Arkaoda tersebut, kedua pemusik asal Indonesia ini mengusung konstelasi duo bernama RANGKA. RANGKA tampil memukau penonton dari pukul satu dinihari. Mereka membawakan komposisi eksperimental dan menawarkan pengalaman bunyi yang sulit dikategorikan dalam satu genre yang kaku.
Duo RANGKA memang baru berusia beberapa bulan, tapi perjalanan berkesenian Ariel dan Mo’ong sudah cukup lama. Ariel tinggal di Berlin, sedangkan Mo’ong berdomisili di Vilnius, ibu kota Lituania. Sejarah Ariel dengan Jerman berawal pada 2007. Ariel saat itu mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Padjadjaran, Bandung, yang terlibat program pertukaran mahasiswa di sebuah universitas di Erfur, kota yang terletak sekitar 300 kilometer barat daya Berlin.
Sesudah program di Erfurt selesai, Ariel pulang ke Indonesia untuk menyelesaikan skripsinya. Lulus dari Universitas Padjadjaran, ia bekerja di Bandung lalu Jakarta.“Tahun 2012 saya ‘kabur’ ke Berlin,” ia berkisah. Ariel mendapat beasiswa di Steinbeis University di bidang sustainability. Pada tahun kedua, Ariel juga memperoleh beasiswa untuk mempelajari human-centered design di Hasso-Plattner Institut di Potsdam sehingga ia menjalani dua program ini secara paralel.
Di samping kuliah, Ariel berkesenian. Meski tidak pernah mengecap pendidikan seni secara formal, Ariel bermusik sejak masih tinggal di Bandung dan Jakarta. Ia pernah bergabung dalam band bernama Vincent Vega yang mengeluarkan album pada 2008. Di Berlin, ia mulai berkenalan dengan komunitas pelajar asal Indonesia yang berkumpul atas kesamaan minat pada seni alternatif.
Pada 2014, salah satu tugas kuliah yang harus ia selesaikan adalah mengorganisasikan sebuah inisiatif nirlaba. Untuk tugas ini, Ariel menggagas gerakan bertajuk Indonesian Initiative atau INN bersama kawan-kawan asal Indonesia yang sedang belajar fashion di Berlin. Pada saat Berlin Fashion Week berlangsung, INN mengadakan event paralel dengan tema slow fashion. “Di situlah saya mulai mengumpulkan teman-teman diaspora Indonesia (di Berlin) untuk membuat event,” Ariel mengenang. “Kami mulai memetakan anak-anak Indonesia di sini sedang belajar apa saja dan melakukan apa saja.”
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo