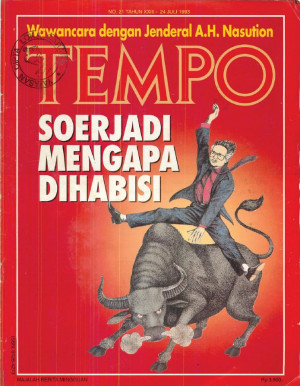Pelukis asal Belanda yang menetap di Bali, Arie Smit, tak cuma melukis dan mencari harta lewat karyanya. Dalam pergaulannya dengan penduduk setempat, ia menyumbangkan sebuah aliran yang sampai kini tetap punya pengikut: Young Artist. Inilah aliran yang lahir dari pergaulan Smit dengan anak-anak desa di sekitar Ubud, yang memberikan warna lain pada lukisan-lukisan tradisional Bali. Pengikutnya kini tak cuma anak-anak. Berkat jasa itu, antara lain, tahun lalu Smit mendapat penghargaan Dharma Kusuma dari Pemda Bali. Dalam usia 77 tahun sat ini, Smit memang tidak aktif berkeliling untuk merekam suasana Bali. Tapi ia tetap melukis di Vila Sanggingan, yang ia sebut pondok, di Desa Peliatan, Ubud. Di situlah ia menuturkan perjalanan hidupnya kepada Putu Wirata dari TEMPO. Aku memang gemar bertualang, tetapi aku tak menyangka akan menyerahkan seluruh hidupku pada Bali. Aku lahir di Zaandam, kota industri di Belanda, 15 April 1916. Ayahku Johanes Smit dan ibuku Elisabeth Ahling mewarisi perusahaan keluarga ''Smit Expeditie'', sebuah perusahaan transpor dan trailer yang sudah berumur 200 tahun lebih. Kami delapan bersaudara, empat lelaki dan empat perempuan. Ketujuh saudaraku bekerja di bidang bisnis dan pendidikan. Hanya aku sendiri yang ditarik oleh pesona dewi kesenian. Memang, sejak di bangku SD aku sudah menyukai pelajaran ilmu bumi dan mengetahui nama beberapa kota, pulau, dan danau di Indonesia. Waktu di kelas enam, aku punya teman baru dari Pulau Sumatera. Keluarga anak Sumatera itu datang ke Belanda untuk belajar ekspor karet. Penampilan anak Indonesia berkulit sawo matang itu sangat berbeda dari kami dan ia merupakan sensasi buat kami. Kami saling bertukar cerita. Dia dengan asyiknya bercerita tentang harimau, pohon raksasa, dan getah karet yang mengalir dari batang. Sungguh sensasional bagiku. Aku tidak mengerti, mengapa ada gejolak emosi begitu hebat ketika berkenalan dengan anak Sumatera itu. Mungkin karena aku memiliki antena kesenimanan yang cukup peka. Maka, ketika remaja aku memilih sekolah seni rupa. Aku mendaftar di Akademi Seni Rupa Rotterdam. Tapi hanya beberapa tahun aku menekuni pendidikan di sekolah itu karena datang tawaran dari ketentaraan Kerajaan Belanda untuk bertugas di Hindia Belanda. Dalam usia 18 tahun, aku sudah masuk wajib militer. Peraturan Kerajaan Belanda menyatakan anak lelaki tertua terkena wajib militer dalam usia 18. Itu terjadi tahun 1934. Pada tahun 1938, ketika usiaku 22 tahun, aku pun meninggalkan Akademi Seni Rupa Rotterdam dan berangkat sebagai wajib militer menuju tanah masa depan dengan penuh khayalan di kepala: Hindia Belanda. Uniknya, sebagai serdadu, aku hanya mendapatkan latihan bahasa Melayu. Tak ada latihan memanggul senjata. Tapi itu bukan ma- salah. Aku berharap mudah-mudahan mendapat pekerjaan yang tak ada hubungan dengan tugas militer. Aku merasa tidak cocok dengan kekerasan. Jiwaku terlalu lembut untuk tugas-tugas militer. Begitulah, aku -- serdadu Arie Smit -- mulai mengarungi ribuan mil yang lebih mirip perjalanan wisata. Aku berangkat dengan kapal Mail en Passagiersdienst Rotterdamse Lloyd, menempuh samudera ganas sepanjang pesisir barat Benua Afrika dan pesisir selatan Benua Asia. Di kepalaku terbayang Gunung Bromo, Gunung Slamet, Gunung Merapi, gunung yang hanya kukenal namanya. Ternyata harapan untuk melihat sendiri gunung itu kesampaian. Aku mendapat tugas di Jawatan Topografi, lembaga yang bertugas menggambar peta-peta pulau atau daerah. Orang Belanda hanya aku seorang, sedangkan orang Melayu ada 40 orang. Pekerjaan yang menyenangkan. Di Jawatan Topografi, aku mempelajari litografi, fotografi sekaligus fotolitografi. Lama-lama, aku juga mengambil pekerjaan yang berhubungan dengan tata letak dan malah pernah bekerja dengan Sutan Takdir Alisjahbana, pendekar Pujangga Baru di Indonesia itu. Kalau malam aku nonton film di Sawah Besar, Alhambra, dan malam minggu ada acara khusus nonton komedi (Stadschouwburg) yang mementaskan opera musik. Pada hari Minggu dan hari libur, aku bersepeda keliling kota Jakarta atau mengerjakan kegemaranku melukis dengan cat air. Aku sering melukis di Kalibesar, di Klenteng, Asemka, atau tempat-tempat lain yang cukup indah dan sunyi. Belum ada sebiji mobil pun waktu itu. Tahun-tahun itu merupakan tahun yang penuh inspirasi. Celakanya, inspirasi yang sedang mekar-mekarnya itu buyar ketika 7 Desember 1941 pecah perang melawan Jepang. Waktu itu Jepang tengah melebarkan sayap ke Asia Tenggara, menebarkan cita-cita Asia Raya dan hendak merangkul ''Saudara Muda'' sambil mendepak kekuasan Belanda. Sebagai seradu Belanda, aku dikirim ke Malang, dan di sanalah aku mendapat latihan militer di daerah Porong Stelling. Kami masih dalam latihan ketika Jepang mendarat di Natuna, Tarakan, dan Manado, Januari 1942. Bulan Februari, giliran Ambon yang direbut. Tanggal berikutnya menyusul tempat-tempat lain seperti Sumatera, Singapura. Akhir Februari, Jenderal Immamura mendarat di Merak dengan 16 orang tentara. Malam itu juga kapal perang Amerika Houston dan kapal perang Australia Perth ditenggelamkan di Selat Sunda. Akhirnya, Belanda menyerah tanggal 8 Maret 1942 di Kalijati. Aku termasuk dalam kumpulan tawanan yang ditangkap Jepang. Aku sempat bertempur, tetapi dengan cerita yang selalu mengundurkan diri. Kami mundur dari Blora ke Kali Brantas terus ke Bojone- goro, mundur lagi ke Surabaya sampai ke pegunungan Tengger. Di lereng gunung itulah aku mendengar berita bahwa Kerajaan Belanda kalah oleh Jepang, dan kami, tentara Belanda, mendapat perintah berkumpul di Probolinggo. Namun, dalam perjalanan ke Probolinggo, 19 Maret 1942, rombongan kami tertangkap. DITAHAN JEPANG Serdadu Belanda yang ditahan Jepang sekitar 4.000 orang. Kami - diangkut dengan kereta api ke Batavia. Di sana aku melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana Jonkheer Mr. Tjarda van Starkenborch Stachouvwer (bos sipil) dan Hern Terpoorten (bos pasukan) dalam keadaan tertawan dan siap dikirim ke Mancuria. Serdadu lainnya, seperti kami, juga siap dikirim ke luar Indonesia. Tanggal 15 Januari 1943, bersama 1.350 orang, aku masuk kapal laut Harikiu Maru. Dalam kapal itu ada tentara milisi, orang sipil seperti pegawai administrasi, pegawai akunting, dan sebagainya. Aku tidak tahu mau dibawa ke mana. Tapi dengar-dengar kami akan diangkut ke Singapura. Tak ada gambaran dalam kepalaku bagaimana nasibku nanti. Mungkin dibunuh atau disuruh kerja paksa, aku tidak tahu. Semuanya penuh misteri. Perjalanan di laut sangat mengerikan, karena ranjau laut sewaktu-waktu bisa merobek lambung kapal. Akhirnya, setelah empat hari empat malam, kami tiba di Singapura. Dengan truk kami diangkut ke kamp Changi, tempat ribuan orang Australia dan orang Inggris ditahan. Kami pun ditahan di sana selama 10 hari. Keadaan sesak, makanan amat terbatas dan tak bergizi. Aku kelaparan. Setelah 10 hari di Changi, aku dan tawanan lain diangkut dengan kereta api ke stasiun Singapura. Satu gerbong berdesakan 39 orang. Begitu sesaknya, banyak yang harus berdiri dan aku termasuk orang yang berdiri. Kereta jalan pelan sekali dan makanan sangat menyedihkan. Tiap gerbong dijatah satu ember bubur dan satu ember sayur encer, yang sebenarnya bukan sayur tapi cuma berbau sayur. Kami tidak bisa beli apa-apa karena dilarang ke luar kereta. Hanya kalau ada yang mau buang air besar pintu kereta dibuka, dan buang air dilakukan sementara kereta jalan terus. Perjalanan kami berlangsung lima hari lima malam. Pada hari yang terakhir, kami hampir berontak karena tidak tahan. Di stasiun Ipoh, ini kira-kira saja karena pada masa perang itu identitas semua tempat dicabut, kami berteriak-teriak ke penjaga, minta agar diizinkan tidur di peron. Setelah bertengkar wawa wowo -- karena penjaga tidak mengerti bahasa kami -- barulah aku bisa tidur untuk pertama kalinya setelah lima hari lima malam terjaga terus. Kemudian kami diangkut terus sampai di Banpong, Thailand, dan diturunkan di sana dan dimasukkan ke kamp. Dari sanalah penderitaan tiga tahunku dimulai. Jepang memberlakukan daftar down country untuk tahanan yang kesehatannya kurang bagus dan out country untuk tawanan yang kesehatannya bagus. Aku masuk daftar out country dan mendapat tugas di Burma, membangun jalan kereta api. Kami harus menebang pohon di hutan, membikin talud untuk mempertinggi tanah, dan memasang rel. Jepang sangat disiplin. Tiap batang rel harus diangkat oleh tim yang terdiri dari 10 orang. Karena dalam timku aku yang paling tinggi, pundakku jadi rusak karena memikul balok-balok besi rel. Panjang jalan yang kami bangun tidak tanggung-tanggung, 200 km. Selama tiga tahun itu, aku pindah kamp sebanyak 15 kali, dan beberapa kali masuk daftar down country untuk mendapatkan perawatan sekadarnya. Seingatku, ada dua kali pemeriksaan Palang Merah dari Swiss, tapi itu hanya pemeriksaan dari jarak lima meter. Pemeriksaan dilakukan secara resmi. Seorang petugas Palang Merah berjalan ditemani seorang perwira Jepang, memperhatikan kami dari jauh. Jepang tidak mengizinkan petugas Palang Merah mendekat karena takut kami berbicara macam-macam, dan petugas Palang Merah itu dilarang melihat kamp. Seingatku, kiriman makanan yang pernah kami terima dari luar hanya dua kali, berupa paket Natal. Paket itu dibagikan untuk ribuan orang, yaitu sepotong biskuit dan sejari mentega. Tapi aku tahu makanan yang dikirim setiap bulannya ditahan oleh Jepang, obat-obatan juga ditahan Jepang. Selama menjadi tawanan, aku mendapat serangan malaria sampai 30 kali. Kalau sudah diserang penyakit, aku tidak bisa bekerja dan artinya aku tidak mendapat upah. Besar upahnya 10 sen sehari. Dengan 10 sen itu aku bisa membeli seekor ikan dan sebutir telur rebus. Kebetulan dalam kelompokku ada dokter yang masih punya bubuk kinine. Setelah menelan kinine aku bisa sembuh dan bekerja lagi. Tapi dua atau tiga minggu kemudian malaria itu kumat lagi. Karena berkali-kali mendapat serangan, tubuhku melemah dan aku menderita penyakit beri-beri yang hebat. Kedua kakiku membesar, kemaluanku juga membengkak tidak keruan. Di antara kami juga ada seorang pastor. Kami membikin gereja sendiri dan pastor memimpin misa dalam keadaan yang sulit itu. Dan itu yang mendorong aku harus bisa bertahan. Aku ingin hidup. Aku harus bertahan. Harapan terus tumbuh karena setiap malam ada saja bisikan dari kawan-kawan bahwa Bali sudah jatuh ke pihak sekutu, atau Manila sudah direbut. Padahal, itu tidak benar, toh bagi kami itu harapan. Harapan yang membuat bisa bertahan. Yang tidak bisa aku lupakan selama masa tawanan itu adalah pemandangan setiap hari ketika tiga atau lima orang tawanan meninggal. Tiap kali ada yang mati, tim penggali lubang siap bekerja. Diiringi tiupan terompet, semua orang di kamp harus berdiri tegak, tidak peduli apakah dia sedang makan atau hanya mengenakan celana dalam. Yang menolong aku dari maut mungkin karena kami berada di sepanjang Sungai Kuwai. Jadi, tiap hari aku bisa mandi dan minum air yang sudah dimasak. Malah, kalau akan berangkat kerja, aku dan semua tawanan membawa bambu panjang berisi teh untuk persiapan sehari penuh. Kami biasa berangkat pukul 6 pagi dan pulang pukul 6 sore, ketika hari sudah gelap. Tiga tahun aku berada di bawah todongan bedil tentara Jepang. Para pengawas Jepang yang kejam mencambuk para pekerja, menyepak, menendang sesuka hati. Memang ada beberapa pengawas yang berhati sabar dan lembut seperti sutera. Tapi pekerjaan dan cuaca buruk yang hiruk-pikuk saja sudah menjadi siksaan. Selama dalam kerja rodi itu, Jepang pernah membolehkan aku - mengirim kartu pos untuk orang tuaku di Holland. Hanya boleh menulis dua kalimat dan itu pun harus dalam omong Melayoe. Orang tuaku menerima kartu pos itu di Holland tanggal 29 Juli 1943, tapi aku tidak pernah menerima balasan. Ambisi Jepang untuk membentuk koloni Asia Raya tak berumur lama. Sekutu menjatuhkan bom di Nagasaki dan Hiroshima pada 6 dan 9 Agustus 1945. Akhirnya, Jepang bertekuk lutut, menyerah tanpa syarat kepada Sekutu. Pada hari Jepang menyerah, seisi kamp merayakan kebebasan. Perayaan yang sangat sensasional. Bayangkan, tiga tahun lebih kami hidup dalam kabut misteri tanpa tahu kapan datang hari pembebasan. Selama tiga tahun kami hanya dikungkung oleh siang dan malam yang tak berujung. Memang, tiga hari sebelum Jepang bertekuk lutut, kami bisa bernapas lega. Tak ada lagi perintah bekerja waktu itu, tak ada teriakan haik, haik, haik dari pengawas yang beringas. Suasana yang tenang itu pun bagi kami merupakan misteri juga. Kami yang biasa bekerja keras justru sakit setelah mendapat istirahat. Perut kami mulas. Selama tiga hari tanpa perintah keras dan perintah apel itu, k- ami jadi bertanya-tanya. Gelisah. Beberapa teman mengintip apa yang diperbuat orang-orang Jepang di dapur. Mengapa mereka hanya bertopang dagu dan tak memberikan perintah kerja. Ternyata, mereka bertangis-tangisan karena pemimpin tertingginya, Kaisar Hirohito, menandatangani penyerahan tanpa syarat terhadap Sekutu. KEMBALINYA KEBEBASAN Jepang resmi menyerah tanggal 1 September 1945 di kapal Missouri. Peristiwa ini dilanjutkan pemulangan tawanan yang sakit ke negara masing-masing. Tapi aku dan kawan-kawan yang sehat ditahan dulu di Bangkok. Kami tak dipulangkan ke Negeri Belanda, tapi malah dikirim ke Indonesia lagi. Di Batavia, aku kembali ke Jawatan Topografi. Di sana aku tinggal di sebuah mes di Gang Pool dekat Istana Negara sekarang. Setelah tiga tahun menekuni pekerjaan ini, aku mendapat kenaikan pangkat menjadi sersan Chromo Lithograaf. Tanggal 27 Desember 1949 Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia dan orang-orang Belanda yang masih di Indonesia dipulangkan. Hanya yang sudah punya pekerjaan diperkenankan tinggal lebih lama di Indonesia. Aku diberhentikan dengan hormat dari tentara dan berganti status menjadi orang sipil. Dan aku termasuk orang yang memenuhi persyaratan untuk tinggal di Indonesia. Datanglah kebebasan. Aku mencopot seragam militerku, kuhirup udara sepenuh paru-paru dan kuterjunkan diriku dalam belantara cat dan kanvas. Untuk menghidupi diri, aku sempat menjadi pen- gajar di Fakultas Ilmu Pengetahuan Teknik Universitas Indonesia Bandung (kini ITB). Tapi pekerjaan itu kuterima sebagai pekerjaan sambilan. Separuh waktuku kugunakan untuk melukis. Tercapailah sudah cita-citaku, menjadi pelukis merdeka. Aku berkenalan dengan Frank Bodmer, seorang Swiss kelahiran Surabaya. Bodmer adalah fotografer Presiden Soekarno. Kami ber- sahabat. Ke mana pun Bomer pergi dengan mobil Austinnya, pasti ada aku. Bodmer memotret dan aku membikin sket. Bodmer yang mengajak aku masuk menjadi warga negara Indonesia pada tahun 1950. Waktu itu memang ada kemudahan bagi orang asing yang sudah tinggal 10 tahun lebih di Indonesia menjadi WNI. Aku mulai produktif menuangkan imajinasi dan kreasiku hingga cukup banyak punya karya untuk pameran. Pameran tunggalku di Plaju, Sumatera (1950) disponsori oleh perusahaan minyak BPM (Bataafsch Petroleum Maatschappij). Sukses! Banyak yang terjual dan aku mengantongi cukup banyak uang. Aku memang tidak pernah berpikir bagaimana agar lukisan- lukisanku terjual dan laris. Aku melukis bukan karena iming- iming pasar. Aku mencipta hanya karena aku ingin mencipta. Maka, ketika aku berpameran kedua kalinya, (di Balikpapan, 1954), dan tak ada yang laku, aku justru senang. Aku bisa mengoleksi karya-karyaku itu. Beberapa yang kecil-kecil malah diboyong ke Belanda oleh teman-teman yang pulang kampung. Aku adalah Arie Smit yang amat mencintai alam dan pemandangan. Kalau aku tinggal di suatu tempat, aku selalu keluyuran ke sana ke sini. Semuanya untuk merekam suasana, merekam kekayaan budaya setempat. Tahun 1951, misalnya, aku melancong ke kota gudek Yogyakarta. Aku naik becak, delman, bersepeda sampai ke pelosok desa. Setahun kemudian aku pindah ke Bandung sebagai lay out man, kemudian bekerja pada Sutan Takdir Alisjahbana di Jakarta, juga menangani hal yang sama. Takdir malah sempat mengajak aku jalan-jalan ke London dan Paris untuk mencari hak cetak beberapa buku yang mereka anggap perlu dibaca oleh masyarakat Indonesia. Tapi, keberangkatan itu atas tanggungan pribadiku. DI TANAH FIRDAUS Tahun 1956 aku meninggalkan Bandung dan menyeberang ke Bali, ke pulau yang konon merupakan firdaus karena keindahan seni budaya. Aku memang sudah sering mendengar nama Bali. Dengan bekal Rp 10.000 sisa berpameran di Plaju dan Balikpapan, aku naik kapal Koninklijke Paketvaart Maatschappij, mendarat di Buleleng, ditemani sahabatku Auke Sonnega, pelukis yang cukup dikenal di Bali. Malam pertama kami menginap di Kintamani. Esoknya, kami meluncur ke Ubud, surga para seniman itu. Di situ berdiam pelukis Jerman, Walter Spies. Juga ada Rudolf Bonnet yang sedang aktif-aktifnya membina perkumpulan pelukis dan pematung. (Kedua pelukis ini sudah tiada). Ketika menjejakkan kaki di Bali, aku masih melihat firdaus itu. Kuil-kuil (pura) Hindu yang eksotis dan anggun, arsitektur yang sangat dalam nilai filsafatnya. Wanita yang mandi telanjang di sungai, atau wanita-wanita tanpa penutup dada. Kami menyaksikan kaum lelaki bersarung, mengenakan destar, yang tua-tua mengunyah sirih. Aku lihat juga seniman-seniman Bali, pematung, pelukis, penari, yang masih sangat alami, belum tersentuh pariwisata. Setiap pagi para petani lewat di jalan, menuntun sapi, memikul bajak dan menyelipkan sabit di pingang. Ketika mentari merambat naik, wanita-wanitanya menjunjung bakul nasi di kepala untuk suami mereka di sawah. Aku mimpi seperti berada di Eropa abad ke-16. Dalam perjalanan selanjutnya, aku berkenalan dengan James Pandy, masih tahun 1956. Ia pecinta kebudayaan Asia yang memiliki pergaulan luas. Ia pernah bekerja sebagai tour leader biro perjalanan Thomas Cook. Sebelum Perang Dunia II, Cook sering memimpin kelompok besar ke Danau Toba, Jakarta, Bandung, Solo, Yogyakarta, dan juga Bali. Ketika Jepang mengebom Pearl Harbour di pantai Barat Amerika tahun 1941, turis yang berkunjung ke Bali macet. Jim kehilangan pekerjaan dan beralih sebagai sekretaris Jack dan Katharane Mershon, pasangan Amerika yang melakukan penelitian di Bali. Pandy kuat dan hebat berdiplomasi. Aku sarankan dia agar membuka sebuah galeri. Pandy setuju. Dengan dana pas-pasan, Pandy membangun sebuah gubuk dari bambu berukuran 3 x 5 meter di Pantai Sanur. Di galeri itulah aku mendapat kesempatan untuk lebih banyak belajar tentang seni lukis. Bagai pucuk dicinta ulam tiba, galeri Pandy mendapat kunjungan orang-orang penting. Presiden Soekarno tak pernah melewatkan ''galeri gubuk itu'' setiap kali berkunjung ke Bali. Ketika Nikita Khrushchev menginap di Sindhu Beach Hotel, tahun 1957, Pandy yang diminta menghias ruang tempat menginap tamu penting dari Uni Soviet itu. Hubunganku dengan masyarakat dan warga banjar adat tidak ada kesulitan walaupun aku penganut Katolik. Aku memang tidak pergi ke pura untuk sembahyang, tapi sebagai pribadi aku tetap menyumbang uang di berbagai tempat suci. Aku merasa berutang budi pada masyarakat Bali karena Bali yang memberiku inspirasi suasana seperti abad ke-16. Apalagi masyarakat Ubud adalah masyarakat yang terbuka terhadap orang asing. Sekarang pun banyak pelukis asing yang tinggal di Ubud. Aku mengenal cukup banyak tokoh adat di Ubud. Beberapa pelukis Young Artist -- nanti akan kuceritakan tentang Young Artist -- sudah jadi pemuka masyrakat, seperti Nyoman Cakra yang menjadi kepala Desa Penestanan, sementara Ketut Soki menjadi pemangku (pendeta di pura). Kedudukan mereka sangat terpandang. Jadi, tidak ada masalah kalau aku menggabungkan diri dengan masyarakat desa, ikut menjadi anggota keluarga besar banjar adat yang kuat memegang adat dan budaya. Aku biasa berjalan kaki keliling desa, ke Penestanan, ke Peliatan, ke Banjar Teges atau ke mana saja. Karena jaraknya kurang dari 5 km. Kalau jaraknya lebih, aku naik kendaraan umum. Aku mampu membeli mobil, tapi aku tak mau. Aku tidak mau direpotkan dengan membeli bensin di pinggir jalan, busi rusak, ban pecah, atau tetek-bengek lainnya. Aku ingin membebaskan kepalaku dari urusan itu, sehingga yang menjadi beban tinggal sket dari objek yang menarik perhatianku. Aku tidak antimodernisasi tapi aku merasa dengan caraku aku mempertahankan perasaan romantis pada karyaku. Dengan cara itu aku bisa mempertahankan goresan misteri alam. Namun kini, setelah usiaku lebih dari 60 tahun, aku membatasi jalan kaki dan naik kendaraan umum. Kalau aku ingin pergi agak jauh, aku naik mobil yang disopiri pegawai Villa Sanggingan. Aku masih mampir di kios pelukis Young Artist, membeli beberapa karya mereka untuk koleksi pribadi, yang akan kuhadiahkan untuk Museum Neka. Apalagi mataku cepat lelah, jadi aku lebih banyak berdiam di studio, melukis, melukis, dan terus melukis. Hanya pada pagi hari aku bangun, aerobik di sekitar pondok, melihat matahari terbit, dan mendengar kokok ayam yang jelas sekali. Aku pernah tinggal di Buleleng (Bali Utara) selama empat tahun. Ini adalah rekor tinggal terlama di satu tempat. Aku tertarik karena daerah itu tidak seturistik Bali Selatan. Kehidupan masyarakatnya masih agraris, penduduknya tidak begitu padat, dan ikatan masyarakat terhadap agamanya masih kuat. Malah, lukisan-lukisanku yang kupamerkan di CSIS (1992) dan Shanti Gallery Jakarta (1993) kebanyakan berasal dari Buleleng. Kenapa aku hidup menyendiri? Pernahkah aku jatuh cinta? Aku sudah biasa membujang. Aku menunda perkawinan, menunda terus, dan menunda terus, ha ha ha. Tapi, waktu muda aku memang pernah ditegur ayah, sebab selalu ditemani pacar-pacarku. Aku mata keranjang waktu muda. Aku tak tahu, apa karena teguran ayah itu aku jadi begini. Aku ambil keputusan, lebih baik jangan kawin. Sampai sekarang. Sebenarnya aku masih punya pacar di Jerman. Tiap tahun dia masih datang ke Bali. Tapi, bagaimana kalau yang satu ini tak usah kuceritakan? Biarlah hubungan kami ini menjadi misteri kami berdua. Hanya Tuhan yang tahu apa di balik misteri itu. Yang jelas, sekarang aku sudah loyo, padahal di masa mudaku, wah, aku ini hebat. Tak ada yang ditakuti hidup menyendiri di Bali, sepanjang bisa bergaul di masyarakat. Aku bisa merasakan kehangatan pribadi orang Timur yang menaruh hormat begitu besar pada orang-orang tua di pulau ini. Di sini kurasakan, semakin tua orang, semakin ia dihormati. Lihat saja jika seniman tua diundang ke Pesta Kesenian Bali. Anak-anak menghormatinya lebih dari orang tua mereka. Aku pun diperlakukan seperti itu. Itu bagus sekali. YOUNG ARTIST Mula pertama di Bali, aku memilih Ubud sebagai tempat tinggal. Pada tahun 1960 aku menetap di lereng Tukad Campuhan yang indah. Aku membikin sebuah studio kecil di sana. Dari tempat itu aku bisa mendengar riak air Tukad Campuhan, atau derai angin yang menggocoh padang ilalang. Sekarang di tebing itu dibangun Hotel Campuhan, dan sebuah kamarnya sampai sekarang diberi nama: Ruang Arie Smit. Mungkin untuk mengenang memori kedatanganku. Dulu, masyarakat jarang yang paham bahasa Indonesia sehingga aku sendiri yang terpaksa belajar bahasa Bali. Komunikasi ini menjadi bagian yang cukup menyenangkan karena aku langsung bisa merasakan keluguan dan kesederhaaan orang Bali. Sebenarnya aku tidak ingat bagaimana secara perlahan-lahan akhirnya aku bisa berbahasa Bali. Ini proses belajar yang terus-menerus. Kalau aku jalan-jalan, orang-orang yang belum kukenal sering teriak ''Hallo-hallo'' karena aku dikira turis biasa. Aku sering ngobrol dengan mereka, tentang apa saja. Kalau omong-omong dengan penduduk desa, aku lebih suka menggunakan bahasa Bali, belajar sekaligus praktek. Orang-orang di pedesaan sering mendekatiku kalau melihatku sedang duduk di bawah pohon besar saat sedang membuat sket. Mereka tidak cuma menyaksikan tapi kadang-kadang protes. ''Pak Arie, ini penempatan puranya salah,'' kata seorang pendeta setelah melihat sketku. Dia mengukurnya dengan bingkai kultur dan filsafat Hindu, sedang aku melihat objek-objek itu dengan kaca mata artistikku. Suatu kali, sewaktu berjalan ke Desa Penestanan, aku melihat anak-anak kecil yang putus sekolah. Mereka berlepotan lumpur karena membantu ayahnya bertani. Ada yang menggembalakan itik, kerbau, atau sekadar mencari belut dan belalang untuk lauk- pauk. Timbul gagasan untuk memberi mereka media berekspresi. Aku tidak mendidik, tapi cuma membimbing. Aku berikan kanvas, cat, dan kuas, lalu kuminta mereka mengekspresikan gayanya yang naif dan kekanak-kanakan. Aku sodorkan kepada mereka tema kehidupan sehari-hari. Ketika gagasan ini kulemparkan, dalam sekejap sudah terkumpul sekitar 40 orang anak-anak. Aku tidak memungut bayaran. Waktu itu lukisan tidak bisa dijual seperti sekarang. Untuk merangsang mereka supaya tetap rajin mengekspresikan gairah seninya, aku biasanya memberi uang 500 kepeng untuk setiap lukisan bagus yang selesai. Ongkos pengganti itu kunaikkan berangsur-angsur, tergantung perkembangan kreativitas mereka. Tujuan utamaku memang untuk membimbing, selain mengoleksi karya mereka. Sampai suatu hari datanglah seorang Jerman, dia kolektor dari Goethe Institut di Jakarta. Aku lupa persisnya tahun berapa waktu itu, tapi orang inilah yang memberi nama gaya lukisan anak-anak Desa Penestanan itu sebagai corak Young Artist. Aku bilang teruskan sajalah corak Young Artist itu. Dan aku bangga pada gaya mereka. Sampai tahun 1980, kalau bicara tentang pemasaran, usahaku belum menunjukkan hasil. Belum ada kolektor lukisan yang memborong lukisan seperti sekarang. Setelah tahun 1980-lah baru terjadi boom. Lukisan gaya Young Artist cukup digemari pembeli. Pengikut corak Young Artist berbiak dari 40 orang yang sudah beranjak dewasa, ditambah ratusan pelukis muda yang mengikuti jejak orang tuanya. Yang sudah tua-tua dan masih aku ingat di antaranya adalah Nyoman Cakra, Ketut Soki, Nyoman Londo, Wayan Pugur, Ketut Tagen, Made Sinte, I Guti Ngurah, Nyoman Gerebig, atau Made Lasir. Seorang pelukis dari Desa Penestanan, Wayan Karma Wijaya, mengatakan hampir 95% penduduk Penestanan menjadi pelukis bergaya Young Artist. Tahun lalu aku menerima penghargaan Dharma Kusuma dari pemerintah Bali. Aku terharu menerima penghargaan yang sangat bergengsi untuk kalangan budayawan itu. Tetapi aku lebih bersyukur lagi terhadap situasi sekarang, saat para pelukis memiliki kebebasan yang lebih besar untuk menuangkan kreativitas. Sekarang infrastruktur sudah lengkap. Dulu, tahun 1970-an, membeli cat dan kanvas saja susah. Sekarang, mau membeli kanvas seharga Rp 1 juta satu rol, atau yang cuma Rp 300.000 juga ada. Galeri-galeri tumbuh seperti jamur. PERSAHABATAN DENGAN SUTEJA NEKA Setelah menerima piagam Dharma Kusuma itulah aku memutuskan berdiam di Villa Sanggingan, milik Suteja Neka. Aku juga menjadi anggota keluarganya, bahkan dengan satu kartu keluarga. Aku merasa hubunganku dengan dia seperti hubungan ayah dengan anaknya, walau aku tidak pernah punya istri. Proses perkenalan kami cukup panjang. Tahun 1973, ketika aku berdiam di Desa Nyuhtebel, Karangasem, Suteja Neka datang bersama istrinya. Dia sudah menjadi kolektor lukisan. Aku juga sudah cukup lama mengenal nama Neka Art Gallery dari Rudolf Bonet. Menurut Bonet, waktu itu Neka sudah mulai mengoleksi dan menjual lukisan yang non-tradisional. Aku tertarik dan lama- lama merasa cocok dengan dia. Dari tahun 1973 sampai sekarang, aku tetap bersama Neka Art Gallery. Aku merasa bebas melukis di mana-mana dan hidup di mana-mana. Neka Art Gallery tetap mempromosikan dan menjual lukisanku. Secara pribadi, aku juga sangat kagum pada Suteja Neka. Dia membangun Museum Neka dengan menyisihkan uang dari menjual lukisan. Museumnya mengoleksi sejumlah lukisan terbaik pelukis Indonesia. Itu sebabnya, aku sumbangkan juga karyaku untuk dia. Sampai sekarang aku sudah menyumbangkan 15 lukisan, 12 di antara lukisan itu adalah karya orang lain. Aku sering menghadiri pameran lukisan. Kalau ada yang cocok, kubeli, kusimpan sekitar tiga bulan, lalu kusumbangkan ke Museum Neka. Aku masuk dalam kartu keluarga Neka karena boleh dikata aku ini ibarat ayah setelah dia kehilangan ayahnya beberapa tahun yang lalu. Tapi kami memang tidak seperti ayah dan anak dalam arti yang sebenarnya. Aku sendiri tidak bisa menjelaskan hubungan ayah-anak itu dalam kalimat yang jelas. Kami punya persamaan apresiasi terhadap seni lukis dan kebudayaan Bali. Di tengah budaya konsumtif yang kuat, ia punya komitmen untuk membangun museum lukisan yang megah dan lengkap. Andai ia jual koleksi lukisan itu, ia bisa menjadi miliuner. Tapi Neka tidak melakukannya. Sementara usiaku terus berjalan ibarat kapal yang mencari tempat berlabuh, aku menemukan ''pelabuhan'' pada Suteja Neka. Aku ingin melabuhkan kapalku setelah berlayar dari Belanda sejak tahun 1938. Aku ingin istirahat setelah perjalanan sepanjang itu. Kasarnya, aku cuma seseorang yang mencari tempat bersandar di hari tua. Barangkali ada orang yang berpikir aku memilih jadi anggota keluarga Suteja Neka sebagai pilihan praktis. Orang mungkin berkata: Arie Smit kan sudah tua, siapa yang nanti mengurus jenazahnya kalau mati karena dia tidak punya siapa-siapa di sini? Tentu saja Suteja Neka yang akan mengurus, ha ha ha. Atau mungkin ada orang lain yang mengatakan: tentu saja Neka mau mengangkat Arie sebagai keluarga karena Arie kan kaya. Aku sendiri tidak mau berkomentar. Aku telah menjawab semuanya itu dengan karya dan Neka juga menjawabnya dengan karya. Enteng saja. KONSEP KARYA ARIE SMIT Yang kutemukan dalam pencarianku di Bali adalah cahaya, puisi, dan misteri. Ini tritunggal. Tentang cahaya, aku teringat epos Ramayana dalam adegan yang menceritakan pemujaan pada Sang Surya Dewa Matahari. Itu adalah tokoh jagat raya yang sudah memberikan kehidupan kepada seluruh umat. Dalam seni lukis juga ada karya-karya yang merupakan wujud ucapan terima kasih pelukis kepada matahari yang sinarnya terus menghidupi bumi ini. Seni lukis itu adalah lukisan-lukisanku. Karyaku berpokok pada usaha melukiskan cahaya. Cahaya penting bagiku karena aku lahir di negeri empat musim yang pencahayaannya jauh berbeda dengan di tanah tropis seperti Indonesia dan Bali khususnya. Di Belanda, pemandangan didominasi warna putih, hitam, dan kelabu. Kelihatan monoton dan membosankan, selain tak merangsang kreasi dan geregetku terhadap nuansa warna yang sebenarnya jauh lebih kaya. Aku mulai merasakan adanya kekurangan itu setelah mengamati apa yang terjadi pada kanvas para pelukis Eropa kurun waktu sebelumnya, seperti lukisan klasik karya-karya Rembrandt van Rijn atau Jan Vermeer. Dari sketsa-sketsa yang kuamati, aku menangkap betapa miskinnya nuansa cahaya. Sebagian besar lukisan itu menyajikan suasana dalam ruang (indoor). Gubahan warnanya amat miskin, hanya ada hitam, kelam, putih, atau kelabu. Tak sekali pun kulihat karya yang menyajikan pemandangan di luar ruangan. Beberapa pelukis modern mencoba menggunakan akalnya. Pelukis seperti Vincent van Gogh dan William Tuner, begitu juga Paul Ceanne dan Claude Monet, mengakali cahaya yang sendu itu dengan melukis di ladang atau di laut lepas dan memilih hari-hari tertentu untuk mendapatkan suasana ketika cahaya tak cuma kelabu, hitam, atau putih. Mereka akhirnya menghasilkan karya impresionis, karya yang dibalur dengan unsur warna putih yang kuat. Melihat pengalaman pelukis-pelukis itu, kurasa aku perlu melakukan sesuatu. Dan itu aku temukan di negeri tropis, tempat cahaya begitu beraneka warna. Dan segera cahaya menjadi dasar untuk mengembangkan obsesi seni lukisku. Ketika bermandikan cahaya matahari Bali, aku merasa berada dalam firdaus yang memabukkan. Tanah Bali begitu subur dan kaya, tanaman tumbuh di mana-mana, sungai mengalir dengan riak air yang membuai, angin lembut menggoyang ranting pepohonan, hujan jatuh dengan rintiknya yang mencekam. Aku kagum pada cahaya matahari Bali yang terus-menerus membalur alam tropis ini, membiaskan aneka warna tanpa hentinya. Aku berkesimpulan, aku harus menggubah karyaku dengan aneka warna. Pada tahun 1956 itu, sesaat setelah menginjakkan kaki di Bali, aku mencoba mengekspresikan perasaanku ini dalam satu lukisan yang kuberi judul Wanita-Wanita Bali Pulang dari Pasar. Karya yang dikoleksi Presiden Soekarno itu menggambarkan dua wanita Bali menjunjung barang-barang untuk dijual di pasar. Tapi, aku tak sedang memotret sesuatu yang vulger. Bukan pada wanita yang bertelanjang dada dengan kulit sawo matang itu letak titik karyaku. Cobalah menengok irama cahaya kuning menyala di latar belakang. Aku menangkap cahaya itu begitu cemerlang memancar di halaman sebuah pura. Pada lukisan Bunga dan Patung, yang juga dikoleksi Presiden Soekarno, aku melukiskan suatu kontras warna benda dalam ruang. Aku tak memulas bentuk, tapi bagaimana warna itu memainkan iramanya hingga menghasilkan efek yang puitis. Ada proses kimiawi warna yang menghasilkan efek puitis di dalamnya. Karya-karyaku pada tahun 1960-an condong pada tempat-tempat yang amat eksotis, tempat yang tentu saja sudah pernah aku jelajahi di seantero Bali. Dengan kuasku, aku ingin menangkap flora, gerak angin menggoyang daunan, wanita di atas pura, pohon kelapa yang membubung ke langit. Aku menangkap semua itu dengan subjektivitas pribadiku. Aku kadang merasa laut itu berona merah, kuil Hindu di Bali gemerlap oleh warna kuning keemasan, pohon menjadi oranye ditimpa cahaya bulan. Aku mengantisipasi stimulasi cahaya dengan perasaanku, dengan mood- ku, dengan impuls-impuls yang bekerja dalam diriku, dan dengan kebebasanku yang sepenuh-penuhnya untuk berkarya. Tahun 1973 aku menciptakan karya Pemandangan Sore Hari dengan membuat mosaik warna yang berkelebat cepat di kanvas, sekaligus membangun komposisi. Citra pemandangan hanya muncul dalam impresi dan bentuk-bentuk yang kugubah dalam abstraksi. Lalu awal 1980-an, dalam karya Pura di Ubud, aku melangkah lebih jauh ke prinsip-prinsip kreasiku. Seperti aku katakan bahwa seribu detail tak lebih bernilai dari sebuah bentuk yang bagus, dalam karya ini aku ingin menggambarkan sebuah kuil Hindu dengan blok warna merah menyala, dengan titik-titik vermilion dan kuning di mana-mana. Di sekelilingnya rimbun pepohonan menaungi dengan nuansa-nuansa biru tembaga. Artinya, bentuk detail benda akan hilang dalam semburan cahaya. Yang tinggal hanya warna belaka. Lalu pertengahan tahun 1980, aku banyak melukis tafril dan pemandangan dengan imbuhan titik-titik. Kucurahkan hasrat ini dengan pulasan kuas pendek. Memang beginilah aku melihat cahaya matahari Bali yang mempesona ketika jatuh ke bumi. Pertama, dia singgah di awan berarak, kemudian memantul ke pucuk pepohonan, lalu daunan yang berayun menaburkannya ke bumi. Hasilnya adalah seribu bayang-bayang, baik kecil maupun besar. Aku mencoba merumuskannya dalam gaya impresif-pointilistik. Dan sampai tahun 1993 ini aku tak berubah dalam caraku mengekspresikan gayaku. Aku mengagumi Roual Dufy, dan orang mungkin akan ingat pada konsepsi artistik Henry Matisse, pelukis Jerman pencetus fauvisme. Dialah orangnya yang meletakkan warna sebagai pokok nilai suatu karya. Tapi, dasar berpikirnya beda. Matisse menatap dan memperbincangkan warna berdasarkan ilmu fisika. Dia menganalisa warna dalam kaidah- kaidah ilmu yang rasional. Dia menangkap warna dengan otaknya. Tapi aku melihat warna dengan perasaan kagum, aku menganggapnya sebagai anugerah, dan aku terpukau oleh pesonanya. Aku suka berpindah-pindah di sekitar Pulau Dewata ini karena mencari getar puisi dalam pemandangan yang menghampar dari gunung ke laut, dari kaja (utara) ke kelod (selatan). Aku mencari sesuatu yang bukan realisme. Aku ingin mencari sesuatu yang tersembunyi, sesuatu yang ada di balik realitas. Aku ingin menyelam sedalam-dalamnya sampai ke hakikat dari realita. Tahun 1990, Garret Kam sudah menulis buku untuk pandangan seni lukisku, judulnya Poetic Realism. Realisme yang puitis, itulah yang ingin kucapai dengan karyaku. Bagiku, lukisan yang cuma menyalin gambar alam sesuai dengan aslinya adalah deskripsi. Mereka yang sanggup membayangkan b- enda sebagai realitas dan melukisnya secara akurat adalah ilustrator. Tapi mereka yang sanggup melihat bentuk tersembunyi dan melihat warna sebagal bentuk, itulah pelukis. Aku membuat karya-karya yang romantik, kugunakan teknik lirikal. Karyaku adalah realisme, tapi aku menghindar dari pemanfaatan aktualitas yang bersifat eksplisit. Aku tak mau menggambar bentuk yang persis sampai ke detail-detailnya. Aku berusaha melakukan suatu realisme puitis, sebuah mimpi, konfrontasi yang lembut. Warna-warnaku tak membentur, tapi berpadu. Garis-garisku tidaklah membagi, tapi menyatukan. Aku tidak suka pada realisme vulger yang menyajikan sesuatu secara telanjang bulat apa adanya. Satu contoh realisme seperti itu adalah iklan sebuah produk obat yang sering disiarkan televisi. Lihatlah iklan obat Konidin, obat antibatuk itu. Dalam iklan itu kita mendengar seseorang batuk dengan hebatnya sampai kita mau menutup mata dan telinga. Itu realisme yang tidak baik. Itu ofensif. Rasanya, Konidin perlu bikin iklan yang artistik dan harmonis. Pakai fantasi. Dan realitas yang vulger, realitas tekanan itu, disajikan pula oleh film di bioskop-bioskop, film di televisi, pada gambar iklan di majalah dan koran-koran. Realitas seperti itu nyaris tak mengandung keindahan. Tidak artistik. Pendapatku, realitas yang vulger seperti itu, the naked truth, yang terlalu tinggi dosisnya bisa menekan jiwa manusia. Tapi, coba bandingkan dengan apa yang ada di film serial Mahabharatha. Perang dilukiskan secara puitis, dengan halus, sama sekali tidak vulger, tidak sadistis. Seniman Bali mencipta tari Baris, sebuah tarian perang yang enak ditonton. Tari itu sangat puitis. Heroisme yang puitis. Alasan lain mengapa aku tidak suka realisme vulger adalah keinginanku untuk memaparkan sesuatu yang gaib, sesuatu yang misterius. Aku mengagumi pelukis interior Belanda abad ke-17, Pieter de Hoogh dan Jan Vermeer. Karya mereka cerah, intim, hangat, superhuman, atmosfernya mengundang hasrat untuk melakukan pendalaman, mengundang kekaguman dan hasrat untuk melakukan penemuan. Komposisinya superior, ada kedalaman dan penuh misteri. Sungguh, karya mereka memiliki daya yang menggoda orang untuk menengok pada apa yang tersembunyi di pintu rumah yang disingkap sebagian. Makanya, aku katakan, seribu detail tidak bisa mengalahkan satu bentuk yang bagus. Misteri hampir lenyap dari muka bumi. Apa yang bisa kita lihat dari tersingkapnya kabut misteri dari kehidupan manusia di Barat? Satu penyebab rusaknya perkawinan Charles-Diana, Andrew- Fergi, adalah karena khalayak ingin agar semuanya diketahui. Pers ingin mengungkap sampai kehidupan ranjang mereka, ingin membuka sampai bagian paling rahasia dari Istana Buckingham itu. Mereka tidak mau ada misteri dalam Istana Buckingham itu. Mereka tidak mau ada rahasia. Ketika terjadi kerusuhan di Thailand, aku lihat di televisi Perdana Menteri Suchinda bersikap keras sekali. Dia mungkin mau menangkap dan menghukum para demonstran. Tapi, Raja Bhumibol Aduljadej memanggilnya untuk menghadap ke istana. Suchinda menghadap, dia duduk dengan hormat di hadapan Raja. Raja bicara sedikit saja, dan urusan selesai. Kerusuhan berhenti. Khalayak di Thailand semua menunggu ucapan Raja. Semua unsur kelihatan menunduk di hadapan yang mulia Raja. Itulah misteri dari kerajaan. Memang, secara global, misteri mulai lenyap dari kehidupan. Seks sudah kehilangan misteri. Itu tidak baik. Aku kira, orang Timur pada umumnya masih memandang seks sebagai suatu misteri dari perkawinan. Bukan sesuatu yang vulger, bukan sesuatu yang harus dipaparkan dari segi biologisnya saja. Biologi itu untuk dokter, bukan untuk khalayak ramai. Aku tidak menulis puisi dalam arti yang sebenar-benarnya. Sekarang ini spesialisasi sudah begitu hebat dan canggihnya. Si A menjadi pelukis, si B penyair, si C jadi pematung, dan seterusnya. Aku melukis karena spesialisasiku memang pelukis. Tapi, spesialisasi yang diarahkan untuk satu tujuan saja bisa merugikan harmoni. Ketika memamerkan karyaku di Shanti Gallery, Jakarta, bulan Mei 1993 lalu, Sulaiman, pemilik galeri itu, mempunyai inisiatif bagus. Dia pilih 77 karyaku untuk dipamerkan. Itu bertepatan dengan usiaku yang 77 tahun. Orang Asia suka bermain dengan an- gka. Sekarang 77 lukisan, jadi tahun depan mungkin 78 lukisan, ha ha ha. Tapi, itulah pameranku yang terakhir. Anda tidak akan pernah melihat pameran lukisanku dalam angka 78. Tidak. Aku sudah tua.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini