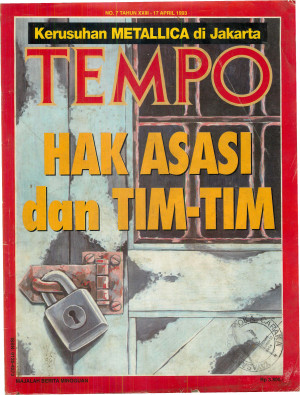Pendiri harian Merdeka ini pekan lalu genap 76 tahun. Dialah salah seorang wartawan tiga zaman yang sukses, satu-satunya wartawan Indonesia yang pernah mewawancarai Presiden Uni Soviet Mikhail Gorbachev. Belakangan ia menjadi bahan berita karena persengketaan dalam keluarga. Burhanudin Muhamad Diah menceritakan perjalanan kariernya kepada wartawan TEMPO Sri Pudyastuti R. HIDUP ternyata tidak semudah yang saya bayangkan. Sejak kecil saya terbiasa dengan pekerjaan-pekerjaan keras dan kasar, seperti membersihkan sepeda, mengambil air, atau mencuci pakaian kotor keponakan-keponakan saya. Pagi-pagi saya naik sepeda ke pasar untuk membeli sarapan buat keluarga. Kalau tidak sekolah, saya berbelanja ke pasar. Seusai bekerja dan pulang sekolah, saya sering tidur-tiduran di lantai dan memandangi dinding rumah. Dinding itu dilapisi kertas koran. Pada salah satu koran, Halilintar namanya, terdapat sebuah sajak yang tidak pernah saya lupakan sampai sekarang. Bunyinya begini: Wahai kaum proletar Hidup sendiri tentu telantar Bersatulah kamu bodoh dan pintar Musuhmu takut, tulangnya gemetar Kalimat itu betul-betul saya baca setiap hari, sehingga saya hafal dengan sendirinya. Saya tidak tahu bahwa ini sajak orang kiri. Entah apa yang berkecamuk dalam pikiran saya waktu itu. Mungkin inilah pengalaman saya yang pertama membaca koran. Tapi sejak itu saya gemar membaca koran, mengamati karikatur, yang tentu saja memihak Belanda, di majalah De Stuw. MOHAMAD YATIM DAN NASIONALISME Saya lahir di Kotaraja, sekarang namanya Banda Aceh, Aceh, tanggal 7 April 1917. Ayah saya, Mohamad Diah, menikah dua kali. Ibu saya, Siti Sa'idah, adalah istri pertama, yang dikaruniai delapan anak, dan saya lahir sebagai anak bungsu. Dari istri kedua, ayah mepunyai dua anak. Ayah mula-mula bekerja sebagai pegawai pabean (klerk boom) di Aceh Barat, kemudian pindah dan menetap di Kotaraja dan menjadi penerjemah. Tak lama sesudah itu ia ganti pekerjaan lagi, jualan sepeda. Menurut cerita saudara-saudara saya, toko milik ayah itu lumayan besar. Selain itu ayah juga mengelola bioskop. Menurut saudara dan sepupu saya, ayah cukup kaya pada waktu itu. Di foto lama, saya lihat kakak-kakak saya memakai gelang emas pada kaki dan lengan, yang besarnya berbongkah-bongkah. Mereka memeluk mainan yang sering dimainkan anak-anak orang kaya kala itu. Pakaian mereka pun dibuat dari kain yang mahal, seperti sutera Cina dan brokat. Rumah kami yang besar di Jalan Merduwati di Banda Aceh itu menunjukkan bahwa ayah orang ternama. Di rumah itu kami dibesarkan sampai beliau wafat. Sayangnya, di zaman dulu orang tidak bisa menyimpan uang, sehingga waktu saya lahir, keluarga saya sudah jatuh miskin. Kami hidup serba kekurangan. Umur saya baru seminggu ketika ayah meninggal. Sejak itu ibu saya, yang selalu memakai kerudung hitam, suka makan sirih, dan gemar memakai wewangian khas Aceh, mengambil alih tugas keluarga. Ia berdagang emas berlian dan pakaian, yang dibawanya ke daerah-daerah, menawarkannya kepada istri-istri hulubalang (orang besar Aceh). Setiap kali pergi, Ibu selalu mengajak saya. Ketika usia saya empat tahun, saya dirawat adik ibu saya di kota kecil, Krungpanjo namanya. Di desa itu saya belajar menunggang kerbau dan membajak. Dalam pergaulan sehari-hari, saya menggunakan bahasa Aceh. Saya tidak bisa berbahasa Melayu. Setelah usia saya enam tahun, abang saya, Awaludin, menyekolahkan saya di HIS (Hollands Inlandse School) di Kotaraja. Ibu meninggal ketika usia saya delapan tahun. Saya pun menjadi yatim piatu. Selanjutnya saya diasuh Awaludin dan istrinya, kemudian berpindah tangan ke kakak perempuan saya yang sudah berkeluarga, Siti Hafsyah. Sejak itulah hidup saya rasakan tidak mudah. Saya senang bisa bersekolah. Sekolah saya ini melewati Sungai Aceh yang besar dan deras airnya. Sepulang dari sembahyang Jumat di Mesjid Raya, saya dan kawan-kawan sekolah sering berenang di situ. Dengan bertelanjang bulat kami melompat dari jembatan. Kami tidak takut, meskipun kadang-kadang di kali itu muncul buaya besar. Jika kakak saya mengetahui saya main di hari Jumat, ia siap menghajar saya dengan kayu bakar sebesar lengan. Menurut dia, pantang bermain seusai sembahyang Jumat, karena bisa disambar setan. Jadi, begitu melihat saya, dia akan memburu saya sampai ke luar gang. Tapi saya selalu bisa lolos dari kejaran. Walau demikian saya sayang kepada saudara perempuan saya ini. Perasaan nasionalisme saya timbul sejak saya sekolah. Saya ingat, ketika itu guru sejarah, Suwadji namanya, bercerita tentang lika-liku kepahlawanan Pangeran Diponegoro. Begitu menyentuh kisah yang diungkapkannya, saya sampai menangis di kelas. Padahal waktu itu saya belum mengenal Pulau Jawa. Hati nurani saya berkata, Pangeran Diponegoro adalah pahlawan kemerdekaan rakyat Indonesia juga. Usia saya masih sembilan tahun, kelas tiga. Tapi di kepala saya sudah tergambar figur seorang hero, pahlawan. Ini saya anggap perasaan nasionalisme. Kalau tidak, kenapa saya mesti menangis. Sejak itu saya merasa, orang Jawa atau bukan, dia adalah bangsa saya. Suwadji ini sayang pada saya karena kebetulan dia kawan baik abang saya, Awaludin. Waktu abang saya meninggal, Suwadji mengeluarkan semua uang dari dompetnya dan diberikan kepada saya. Di Aceh anak yatim piatu disayangi. Tuhan memberi berkah jika kita menyayangi anak yatim. Satu hal lagi yang menunjukkan nasionalisme saya adalah peristiwa ini. Setiap sore, seusai mengaji di Mesjid Raya, saya pergi ke stasiun. Stasiun ini tidak jauh dari mesjid. Di situ ada kereta mayat yang diselubungi kain hitam. Kereta itu membawa mayat serdadu Belanda dari rumah sakit militer di dekat stasiun, ke kuburan Peucut. Saya selalu gembira melihat pemandangan ini. Saya bangga pada patriot-patriot Aceh yang berhasil menewaskan serdadu kolonial. Umur saya waktu itu 13 tahun. Saya sudah mengerti arti penjajahan. Apalagi rumah saya dekat tangsi Belanda. Setamat dari HIS, saya melanjutkan sekolah ke Taman Siswa di Medan. Saya pergi dengan kemauan sendiri. Sebetulnya saya dipesan keluarga ibu saya untuk melanjutkan sekolah ke MULO (Meer Uitgebreid Lager Onderwijs), setingkat dengan sekolah lanjutan pertama. Tetapi saya tidak mau lagi masuk sekolah Belanda. Di Taman Siswa saya bertemu dengan bangsa sendiri. Ada orang Batak, Jawa, Mandailing. Perasaan lebih enak di sini. Saya menjadi pemimpin PMTS (Persatuan Murid Taman Siswa). Lalu saya mendirikan majalah sekolah Mertju Suar dan menjadi pemimpin redaksinya. Di situ pertama kali saya mencantumkan nama saya sebagai: Burhanudin Diah. Tadinya nama saya Burhanudin tok. Waktu di Aceh saya dipanggil Mohammad Yatim, karena saya anak yatim. Jadi, Burhanudin itu nama keren, Mohamad Yatim itu nama rakyat, ha-ha-ha. Lalu seorang teman menanyakan kenapa memakai nama Diah? O, Diah itu nama ayah saya. Saya memakai nama ayah saya supaya orang mengenal siapa Burhanudin. Kan banyak nama Burhanudin. Saya tidak mau orang bertanya-tanya, Burhanudin yang mana? Jadi tanpa saya sadari I want to be different. Padahal ketika itu nama ayah tak lazim dipakai. Jadi cuma saya yang mencantumkan nama orang tua di belakang nama saya. Ada rasa bangga dan angkuh ketika menyandang nama ayah saya itu. Tapi saya tetap dipanggil Bur atau Atim. AL CAPONE DAN DOUWES DEKKER Setamat Taman Siswa di Medan, saya pergi ke Jakarta. Waktu itu namanya masih Batavia. Umur saya kira-kira 17 tahun. Jadi saya lulus HIS usia 13 tahun, lalu tamat Sekolah Taman Siswa 16 tahun. Saya sempat menganggur setahun. Kenapa saya memilih Jakarta? Tahun 193O-an Jakarta sudah jadi impian setiap orang. Banyak orang ingin datang ke kota ini. Saya berangkat dengan kapal laut Op Ten Noort. Di Jakarta sulit mencari tempat indekos. Lalu saya ketemu teman-teman. Kami kemudian membuat asrama di Jalan Kepu, di daerah Senen. Daerahnya sepi. Kenakalan saya waktu kecil ternyata tidak luntur meskipun saya sudah besar. Di asrama saya sering mengganggu teman-teman. Karena saya suka mengganggu, mereka juga usil pada saya. Suatu hari, sepulang dari melancong, saya mendapati sepatu- sepatu saya tergantung di atap tempat tidur. Saya marah sekali. Saya mencari orang yang mencari gara-gara. Saya ajak mereka berkelahi. Hari sudah gelap waktu itu. Setelah puas, saya kembali ke kamar saya. Teman saya, orang Aceh, Abudurachman namanya, mendatangi saya. Dia bilang, ''Tim, kamu jangan begitu. Kalau kamu mengganggu orang, orang tidak marah. Kalau kamu diganggu, kamu marah. Itu tidak baik.'' Saya tidak bilang apa-apa. Hati saya masih panas. Tapi saya membenarkan ucapannya. Sejak itu saya berubah, saya menjadi lebih toleran. Pada perjalanan hidup saya selanjutnya, baik ketika saya jadi wartawan maupun politisi, saya sering dihantam dari mana-mana. Contohnya, waktu masih menjadi pengurus di Persatuan Wartawan Indonesia, nama saya sering disudutkan, tapi saya tidak mempermasalahkannya. Saya tidak marah, apalagi mendendam. Biasa saja. It's a political game. Sampai sekarang, sikap saya sama. Mungkin saya terpengaruh buku tentang Al Capone, itu gengster Amerika legendaris. Menurut buku itu dia mengatakan, biarkan saja orang membicarakan dirimu, baik atau buruk jika itu ditulis di surat kabar, namamu jadi terkenal. Selama di Jakarta saya mulai mencari sekolah yang cocok. Saya masuk ke AMS (Algemeen Middelbare School) Perguruan Rakyat, AMS Muhammadiyah, dan Taman Dewasanya Taman Siswa sekaligus. Namun ketiga sekolah itu tidak cocok buat saya. Saya tidak puas. Sekolahnya lama dan kurikulumnya macam-macam. Saya pikir, saya juga bisa dapatkan semua itu sendiri tanpa harus belajar. Walaupun tidak lama memasuki sekolah itu, saya punya banyak kawan. Misalnya, Latif Hendraningrat, yang mengerek bendera merah putih pada saat proklamasi kemerdekaan RI, dan Soemanang, yang waktu itu sekolah di AMS Perguruan Rakyat. Kemudian Maria Ulfah dari AMS Muhammadiyah, dan Pak Said di Taman Dewasa. Tanpa saya sadari guru-guru saya itu akhirnya menjadi teman pada saat memperjuangkan kemerdekaan Tanah Air. Karena tak cocok dengan sekolah itu, kemudian saya kirim surat kepada Dr. Douwes Dekker di Bandung. Ia memimpin Ksatriaan Instituut. Meski saya tidak mengenal orangnya, saya mengenal namanya. Dia itu wartawan hebat. Tadinya saya di Ksatriaan Instituut ingin masuk sekolah menengah dagang (Middelbare Handels School), tapi karena ada sekolah menengah jurnalistik (Midelbare Journalisten School), saya masuk ke situ. Sekolah yang dikelola Douwes Dekker itu mahal, tapi guru- gurunya sangat bermutu. Meskipun ada yang berbangsa Belanda, Austria, Jerman, Jepang, dan sebagian masih mempunyai sifat- sifat kolonial, semangat yang dibawakan oleh sekolah itu adalah semangat Indonesia dan nasionalisme. Sehingga keinginan untuk menjadi manusia merdeka tertanam di dalam diri kami masing- masing. Di tahun pertama sekolah itu mengajari kami membuat karangan dalam bahasa Perancis, Jerman, Inggris, dan Indonesia. Tahun kedua kami bergumul dengan pengetahuan bahasa dan sejarah bangsa Indonesia. Sebetulnya tidak mudah menyerap pelajaran di sekolah tersebut. Namun ada hal yang saya sukai, dalam setiap pelajaran guru menanamkan pengertian politik dalam jiwa kami, agar kami menyadari pentingnya memiliki tanah air. Saya merasa cocok dengan sekolah ini. Selain jurnalistik, kami juga diberi pengetahuan perdagangan agar kami sadar bahwa dalam segala hal, berpikir sebagai pedagang itu sangat penting. Untuk sekolah, saya membutuhkan sedikitnya 4O gulden sebulan: 25 gulden untuk bayar sekolah, 12,5 gulden untuk pondokan, dan seringgit lagi untuk jajan. Saya dibiayai kakak yang mempunyai tiga anak. Gaji kakak mungkin sekitar 2OO gulden. Suatu hari saya minta izin kepada Douwes Dekker untuk mengunjungi kakak saya yang bekerja sebagai duane di Surabaya. Saya belum membayar uang sekolah, tapi saya katakan padanya bahwa uang itu akan saya kirim dari Surabaya. Dari Surabaya saya agak terlambat mengirim uang itu. Akibatnya Douwes Dekker mengirim surat yang bernada marah. Saya dituduh menipunya. Tapi sebetulnya, waktu dia mengirim surat itu, saya sudah mengirimkan uang itu ke Bandung. Jadi surat dan kiriman uang berselisih jalan. Mungkin dia terkejut ketika selang beberapa hari menerima uang itu. Hari itu juga ia mengirim surat kepada saya dan mengungkapkan penyesalannya karena telah menuduh saya. Dalam suratnya, Douwes Dekker mengatakan bahwa saya memiliki ingeboren beschaving (kejujuran yang dibawa sejak lahir). Ia juga menyuruh saya segera kembali ke Bandung. Padahal dalam surat saya, saya mengatakan akan berhenti karena tak sanggup membayar uang sekolah. Rupanya dia terharu pada kejujuran saya. Saya kemudian diberi pekerjaan sebagai sekretaris di sekretariat sekolah dagang tinggi. Dengan demikian saya mendapat semacam ''beasiswa'' untuk menyelesaikan sekolah jurnalistik. Di sela-sela kesibukan mengerjakan pekerjaan sekolah, sebagai seorang anak muda berusia 18 tahun, saya pernah bertanya kepada Douwes Dekker, kapan saya bisa menjadi wartawan hebat. Ia menatap saya, lalu berkata dengan tenang, ''Jika umurmu sudah 4O tahun.'' Bagi saya, jawaban itu berarti sekali, karena saya akan menjadi penulis hebat dalam usia 4O tahun! Dalam bayangan saya, kalau saya menjadi wartawan, saya bisa menjadi pribadi yang independen. Bisa mengkritik, bisa menulis. Douwes Dekker, yang kemudian mengubah namanya menjadi Setiabudi, memberi banyak pelajaran berharga pada saya. Misalnya, dia bilang, ''Kalau kau mau menjadi wartawan, kau bisa mengkritik, tapi dirimu harus bersih lebih dulu.'' Kemudian dia bilang lagi, ''Kalau kau mau melawan orang-orang Barat, kau harus mempelajari ilmu dan pengetahuan mereka.'' Petuah itu diberikannya di dalam kelas. Padahal Douwes Dekker orang Barat. Kata-katanya itu menaikkan kebanggaan saya pada bangsa sendiri. Dengan sendirinya nasionalisme saya semakin mengental. Saya tidak tahu bagaimana saya bisa begitu akrab dengan Douwes Dekker. Saya senang kepadanya, dan dia baik sekali pada saya. Ini bukan karena dia punya istri yang masih muda dan cantik. Mungkin saya waktu itu menjadi figur anak muda yang dia sukai. Saya memang menonjol dalam hal bahasa, sejarah, dan aktif bertanya di dalam kelas. Di sekolah ada grup diskusi -- di sana saya menjadi wakil ketuanya. Barangkali saya dianggap sebagai harapannya di kemudian hari. Di masa perjuangan, nasib saya juga tidak terlalu jauh dengan Douwes Dekker. Pada tahun 1948 dia dipenjarakan oleh pemerintah Belanda di Penjara Wirogunan, Yogyakarta. Saya pun dipenjarakan di tempat yang sama, persis di sebelah selnya. WARTAWAN SINAR DELI Setelah tamat dari sekolah jurnalistik, saya kembali ke Medan. Di Jakarta juga banyak surat kabar, tapi rupanya lamaran saya tidak diterima. Di Medanlah saya merintis karier sebagai wartawan. Saya diterima langsung sebagai redaktur pertama di harian Sinar Deli. Saya adalah wartawan pertama keluaran sekolah. Usia saya waktu itu sekitar 2O tahun. Menurut saya, orang-orang itu bodoh --karena mau menempatkan saya di posisi itu. Saya kan belum berpengalaman. Tapi proses belajar saya memang cepat. Meskipun oplah Sinar Deli tidak besar dan tidak begitu maju dibandingkan dengan Pewarta Deli yang dipimpin wartawan keluaran sekolah tinggi Jerman, Djamaluddin Adinegoro (namanya diabadikan untuk hadiah jurnalistik, Hadiah Adinegoro), harian tempat saya bekerja ini cukup terkenal sebagai harian nomor dua di Medan. Kedua harian itu merupakan alat perjuangan yang baik dalam menentang penjajahan. Selain meliput berita, saya juga menjadi penerjemah dan membuat karangan. Hampir setiap hari kami memuat berita tentang hal-hal yang berkaitan dengan pengadilan negeri. Pengadilan Belanda ini menyidangkan rakyat Indonesia yang ketahuan masuk ke perkebunan karet milik Belanda. Padahal mereka hanya memungut ranting yang jatuh untuk kayu bakar. Pengadilan model begini saya anggap keterlaluan. Perkebunan menjadi sebuah simbol kekuasaan dan kapitalisme kolonial. Pengadilan saya kritik habis-habisan. Akibatnya, hampir saban minggu saya dipanggil polisi rahasia Belanda (Politieke Inlichtingen Dienst). Saya diinterogasi, kenapa mengkritik dan menjelek-jelekkan Pemerintah? Saya capek dan bosan. Mereka saya anggap rewel dan keterlaluan. Tapi, herannya, saya tidak pernah diperkarakan. Penyelidikan itu memang lebih bersifat teror pikiran terhadap wartawan Indonesia. Tapi saya, demi Allah, tidak pernah merasa takut. Padahal pada tahun 193O-an itu kolonialis sedang galak- galaknya. Mungkin karena saya belum tahu bagaimana rasanya disiksa. Pada masa itu saya juga melihat besarnya pengaruh Cina terhadap kehidupan bangsa Indonesia. Saat Jepang menyerang Shanghai, Cina, Sinar Deli mengkritik sikap tentara Cina yang lari tunggang-langgang. Akibatnya, orang Cina di Medan memboikot Sinar Deli. Mereka ramai-ramai menarik iklan di surat kabar itu. Ternyata soal ini berbuntut panjang. Gaji saya dipotong tanpa alasan jelas. Saya protes. Saya menyewa pengacara Belanda, Romme namanya, dan memperkarakan Sinar Deli ke pengadilan. Untuk membayar pengacara, saya terpaksa merelakan simpanan yang diberikan kakak saya, yang rencananya untuk melanjutkan sekolah ke Universitas Santo Thomas di Manila, Filipina. Karena proses pengadilan itu berlarut-larut, saya ke Jakarta. Belakangan pengacara mengabarkan bahwa saya memenangkan perkara itu. Sinar Deli harus membayar kerugian. Tapi pemimpin surat kabar itu, Mangaradja Ihutan, membujuk agar saya tidak menuntut ganti rugi, karena Sinar Deli tidak kaya. Saya jadi iba. Tuntutan itu akhirnya saya abaikan. Satu setengah tahun saya menjadi wartawan di harian itu. Di Batavia saya diterima di sebuah harian Melayu-Cina, Sinpo namanya. Saya boleh menulis berita apa saja. Setiap akhir bulan, sehabis menulis berita, saya mengukur baris yang saya tulis itu per sentimeter, disebut centimeter-vreter, untuk menentukan honorarium. Bekerja sebagai wartawan honorarium ini saya lakukan selama beberapa bulan, sampai saya diminta menjadi wartawan di koran Warta Harian. Koran ini didirikan atas permintaan orang Jepang, namanya Kubo. Saya masuk ke situ. Selama saya di situ koran itu sering diobrak-abrik polisi kolonial. Waktu itu sudah ada gosip bahwa Jepang akan menyerang Asia. Waktu itu bala tentara Jepang sudah sampai di Tiongkok Selatan, akan menuju Singapura. Belanda sudah menangkap bahaya itu. Tidak lama kemudian surat kabar itu ditutup. Kubo dianggap membahayakan keamanan. Saya pun kembali mengganggur, setelah bekerja di situ tujuh bulan. Akhirnya saya mendirikan surat kabar sendiri, majalah bulanan Percaturan Dunia, majalah tentang masalah-masalah luar negeri dan film. Oplahnya lumayan, sekitar 5.OOO eksemplar. Pembelinya kebanyakan anggota volksraad (dewan perwakilan rakyat). Waktu itu mendirikan surat kabar mudah sekali. Tidak perlu izin apa-apa. Kalau laku, Anda untung, kalau tak laku, ya buntung. Usaha saya lumayan. Banyak langganan dan banyak iklan. Jadi cukuplah buat hidup. Metode wawancara ketika itu berbeda dengan sekarang. Dulu orang tidak terlalu peduli dari media apa kami ini. Juga belum ada metode cek dan recek. Jadi interview saja. Pada zaman Belanda ada kantor berita semacam Antara, namanya Aneta. Dari situ kami mengambil berita-berita luar negeri. Pernah, suatu hari saya diundang perusahaan penerbangan Belanda KNILM ke Medan. Saya hanya disuruh membayar 1O% dari harga tiket. Jadi, saya adalah wartawan Indonesia pertama yang naik kapal terbang untuk melakukan sebuah reportase. Bayangkan, di zaman susah itu ada wartawan Indonesia yang membuat tulisan tentang perjalanan ke luar Jakarta dengan kapal terbang kolonial Belanda...ha-ha-ha. LAHIRNYA B.M. DIAH Suatu ketika saya ditawari oleh seorang Indonesia keturunan Arab, Al Junid namanya, menjadi asisten kepala penerangan untuk pers Indonesia di Konsulat Jenderal Inggris di Jakarta. Dan saya boleh tetap mengelola majalah saya. Wah, ini kesempatan baik, saya pikir. Apalagi gajinya bagus. Besoknya saya langsung datang ke kantornya di Harmoni. Saya ditugasi memilih berita perang yang dimuat dalam majalah Inggris. Ada dua staf yang membantu saya. Satu penerjemah dan satu tukang ketik. Atasan saya orang Inggris, Collins namanya, baik sekali orangnya. Karena saya juga punya majalah, maka berita yang saya dapatkan itu sebagian saya pakai untuk majalah saya. Sejak bekerja di situ, karier saya sebagai wartawan meningkat terus. Di situ saya punya kesempatan belajar bahasa Inggris dan politik Inggris. Kenapa Al Junid memilih saya, itu juga pertanyaan buat saya. Dalam buku otobiografi saya, hal itu juga saya pertanyakan. Dulu ketika sering bertemu, hal itu tidak sempat saya tanyakan: malu. Ada hal menarik ketika saya bekerja di situ. Yakni, saya melengkapi nama saya menjadi Burhanudin Mohamad Diah, disingkat B.M. Diah. Ini gara-gara saya gemar membaca buku-buku cerita Inggris. Saya lihat di situ banyak nama yang disingkat. Saya lalu berpikir, wah, aksi juga ya? Nama B.M. Diah itulah yang saya pakai sampai sekarang. Tiga tahun saya bekerja di konsulat (1939-1942) Inggris itu. Setelah Jepang masuk, saya melanjutkan karier sebagai wartawan radio milik balatentara Jepang, Hosokyoku. Saya diterima sebagai penyiar untuk siaran bahasa Inggris. Saya membuat karangan propaganda Jepang untuk menjatuhkan mental Sekutu. Sebelum disiarkan, berita itu diperiksa dulu oleh orang Jepang yang mahir berbahasa Inggris. Pada saat yang bersamaan, saya juga ditawari menduduki posisi wakil pemimpin redaksi, bersama Anwar Tjokroaminoto, di surat kabar Asia Raya. Ini koran berbahasa Indonesia yang juga milik balatentara Jepang. Saya terima tawaran ini, tanpa menyadari adanya larangan bekerja di dua tempat meskipun kedua tempat itu milik Jepang. Saya dipersalahkan. Saya diharuskan menghadap seorang perwira Jepang di bagian dinas rahasia. Waktu saya mau ditempeleng, saya memanandang matanya. Saya bilang saya tidak tahu ada larangan itu. Apalagi dua pekerjaan itu serupa, sama-sama jurnalistik. Akhirnya saya tidak jadi ditempeleng, cuma masuk penjara empat hari. Meski berat, akhirnya saya memilih Asia Raya. Dan saya tetap dihukum, tidak boleh menggunakan nama asli. Saya memakai nama Bahrun (kebalikan dari Burhanudin) Oedaja. Oedaja adalah kependekan nama sahabat saya, Hoedojo Hoeksamadiman, sesama alumni Ksatriaan Instituut. Anak wedana Sidoardjo ini, seorang karikaturis paling bagus. Sebelum Jepang masuk, ia pergi ke Jerman dan meninggal ketika Nazi berkuasa. Entah diapakan dia. Enam bulan saya tidak memakai nama asli saya. Asia Raya dipimpin Soekardjo Wirjopranoto, anggota volksraad. Meski media ini milik Jepang, semua anggota redaksinya orang Indonesia. Ini yang membuat kami berani membuat media itu sebagai alat perjuangan. Selain menulis tentang perjalanan peperangan Asia Timur Raya, saya juga mempersoalkan masalah yang menjadi pikiran masyarakat pada waktu itu, seperti soal beras yang semakin sulit didapat. Atau tulisan yang sifatnya mengobarkan semangat perjuangan pemuda Indonesia untuk Indonesia merdeka. ''Jika peperangan mau berhasil, berilah senjata dan kebebasan berpikir kepada anak negeri.'' Jadi ada pukulan-pukulan di balik perkataan-perkataan indah (propaganda Jepang) itu. Pemimpin redaksi kami adalah Raden Mas Winarno. Ia seorang wartawan perlente, senang berdandan, selalu memakai parfum, dan bahkan memupuri wajahnya. Maklumlah, ia bangsawan Yogya. Sebagai wartawan, sentilan Winarno di ''pojok'' surat kabar itu tajam dan menyakitkan. Rekan-rekan dan politisi yang dianggapnya lawan disentil melalui pojok. Kekuatan wartawan Indonesia di masa lalu memang ada di ''tulisan pojok'' itu. Anwar Tjokroaminoto memakai nama samaran Bang Bejat untuk pojok yang ditulisnya. MEREBUT DJAWA SHIMBUN Saya ketemu Herawati di Radio Jepang itu. Dia senang sama saya karena saya pandai berbahasa Inggris, muda dan, kata orang, handsome. Menurut cerita orang, saya memang gagah dan ganteng waktu muda, ha-ha-ha. Pacar saya banyak .... Herawati juga penyiar. Dia baru beberapa bulan di Jakarta. Baru selesai sekolah jurnalistik dan sosiologi di Amerika Serikat. Mula-mula kami dekat karena sesama profesi. Lalu love comes through it. Kami menikah 18 Agustus 1942. Bung Karno dan Bung Hatta hadir pada pernikahan kami. Kami mengadakan resepsi siang di Jalan Prapatan, Jakarta, yang sekarang jadi hotel Aryaduta. Itu rumah orang tua Herawati, dr. R. Latip. Saya sudah lama mengenal nama Bung Karno. Tetapi ya kenal begitu-begitu saja. Sebagai wartawan saya kerap bertemu dengan dia, tapi saya kan orang kecil, sedangkan dia negarawan. Ketika saya menikah, Mr. Soebardjo, adik ibu mertua saya, mengundang Bung Karno. Pada saat itulah Bung Karno betul-betul mengenal saya. Ketika saya bekerja di Asia Raya, Herawati hanya seorang ibu rumah tangga. Waktu itu, mencari pekerjaan susah. Ia bersama teman-temannya menjual makanan dan pakaian. Kami tinggal di Jalan Yogya (sekarang Jalan Mangunsarkoro). Itu rumah rampasan dari Belanda, ada pianonya segala. Kami tinggal di situ sampai perang berakhir. Lalu kami tinggal di Jalan Perapatan, rumah mertua. Mertua saya memang orang terpandang. Mertua perempuan, Ibu Halimah, adalah tipe perempuan modern yang berpikiran maju. Dari Herawati, saya mempunyai tiga anak, Adianiwati (sekarang 50 tahun), Nurdianiwati, 48 tahun, dan Aditya Tedja Nurman, 45 tahun. Ketika bom atom jatuh di Hiroshima dan Nagasaki, Sekutu menetapkan jajahan Barat yang dikuasai Jepang dalam keadaan status quo. Ketika itulah saya bersama kawan-kawan seperjuangan, antara lain Soekarni dan Chairul Saleh, mendirikan gerakan Angkatan Baru, untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Inilah saat yang tepat untuk memberitahukan kepada dunia bahwa Indonesia sudah merdeka. Kami tidak ambil pusing soal status quo antara Jepang dan Sekutu. Ketika itu Bung Karno dan Bung Hatta pergi ke Saigon. Di sana Jepang seolah-olah akan menghadiahkan kemerdekaan pada Indonesia. Padahal di Jakarta, Jepang sudah menyerah. Kaisar Jepang pun sudah mengumumkan bahwa perang sudah selesai, seperti diminta oleh Sekutu. Pemimpin-pemimpin Indonesia harus mempunyai inisiatif sendiri untuk memproklamasikan kemerdekaan. Tapi, melihat gerakan pemuda ini, Bung Karno dan Bung Hatta tak setuju. Mereka menganggap kami gegabah dan tidak bertanggung jawab. Kedua pemimpin ini tampaknya enggan mengambil risiko. Mereka khawatir jika melawan Jepang akan dihancurkan, dan jika Belanda bersama Sekutu datang lagi ke Indonesia, pemuda Indonesia secara militer tidak terampil. Apalagi kami tak memiliki senjata yang memadai. Situasi memang sedang genting. Tapi pemuda tak takut berkorban. Tanggal 15 Agustus 1945 malam pemuda berkumpul dan menghadap Bung Karno, mendesak agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Lalu Bung karno menjawab, ''Walaupun kamu potong leher saya, saya tidak akan memproklamasikan kemerdekaan.'' Meski Bung Karno menolak, kami tetap memaksa. Perhitungan kami, sekaranglah waktunya. Bung Karno bertahan karena Jepang berjanji akan memerdekakan Indonesia. Setelah rapat selesai, kami pulang. Lewat tengah malam Soekarni dan Chairul Saleh menculik Bung Karno dan Bung Hatta ke Rengasdengklok. Di situ Bung Karno didesak lagi. Esok harinya Jakarta heboh karena kedua pemimpin lenyap. Baru pada malam harinya, tanggal 16 Agustus 1945, mereka berdua muncul diikuti oleh Sukarni di Jalan Imam Bonjol. Chairul Saleh belum datang. Saya sudah menunggu di gedung itu. Saya tahu Bung Karno dan Bung Hatta akan ke tempat itu. Di sanalah disiapkan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Chairul datang kemudian. Pimpinan Angkatan Baru memang berada di sana, sehingga dapat dikatakan bahwa proklamasi kemerdekaan lahir karena dorongan mereka. Proklamasi itu tidak dapat diumumkan di Lapangan Ikada seperti direncanakan semula. Bung Karno akhirnya menetapkan proklamasi diucapkan di kediamannya, di Pegangsaan Timur 56. Langit cerah pada waktu itu. Dan pengorbanan pemuda Indonesia membawa hasil juga dalam tahap pertama kemerdekaan Indonesia. Akhir Agustus Asia Raya ditutup. Bangsa Indonesia kehilangan alat penerangan dan penyebaran berita mengenai Republik yang baru berdiri itu. Maka satu-satunya jalan adalah merebut Djawa Shimbun yang menerbitkan surat kabar Asia Raya itu. Akhir September, tanpa memberi tahu maksud saya, saya mengajak teman-teman ke percetakan Djawa Shimbun. Saya membawa revolver untuk berjaga-jaga saja. Begitu tiba saya terheran-heran, Jepang langsung menyerahkan percetakan itu tanpa perlawanan. Semua pemimpin dan pegawai bangsa Jepang pergi begitu saja. Dalam sekejap percetakan berpindah tangan. Jika di surat kabar asing disebutkan presiden Indonesia selfstyled, atau mengangkat diri sendiri, saya pun selfstyled, mengangkat diri sendiri sebagai pemimpin percetakan Djawa Shimbun. Saya menempelkan secarik kertas di dinding di luar percetakan dengan tulisan: ''Milik Republik Indonesia'.' WARTAWAN, PEJABAT, PENGUSAHA Tanggal 1 Oktober 1945 kami menerbitkan surat kabar Merdeka. Sebelumnya ada yang mengusulkan nama Suara Merdeka. Tapi saya pikir tidak perlu nama sepanjang itu. ''Merdeka'' adalah kata salam sesama kaum Republik di masa itu. Inilah pekik yang ditunggu-tunggu. Saya menganggap Merdeka adalah nama yang cocok untuk bangsa yang sudah merdeka. Tapi mencari dan menyajikan berita pada saat itu berbahaya sekali. Kami harus memuat berita yang menggembirakan pejuang- pejuang kita. Hal yang menggembirakan itu tentu tidak menyenangkan Inggris dan Belanda. Jadi kami berada di antara dua kekuatan. Bagaimana aturan mainnya, ya pintar-pintar berdiplomasi dan bijak. Inilah "gerilya" kota pertama yang kami lakukan. Perjalanan hidup saya tampaknya memang bervariasi. Dari wartawan kemudian menjadi duta besar, menteri, lalu sekarang pengusaha. Bukan, ini bukan semata-mata hoki. Saya ini sebetulnya seorang wartawan. Ini profesi saya. Tapi ada kalanya saya menjadi ''politikus.'' Ini pekerjaan tambahan. Begitu Indonesia merdeka, saya diangkat sebagai anggota Komite Nasional Indonesia Pusat, dianggap mewakili Angkatan Baru atau kaum muda Indonesia, bersama kawan-kawan seperjuangan lain. KNIP, demikian disingkatkan, adalah sebagai parlemen Indonesia merdeka dalam masa peralihan. Kemudian, di tahun 1953, saya menggantikan Ki Hadjar Dewantoro sebagai anggota parlemen sementara. Sesudah pemilihan umum, saya mewakili Gerakan Pembela Pantja Sila mengadakan satu stembus accoord dengan PNI. Saya tidak masuk DPR walaupun kami dapat dua kursi. Kedua kursi itu jatuh pada Pak Gatot Mangkupradja dan Mohamad Yamin. Tahun 1957 saya diangkat oleh Bung Karno sebagai anggota Dewan Nasional, suatu badan serupa DPA sekarang, yang dipimpin langsung oleh Presiden Soekarno. Wakil ketuanya adalah Cak Ruslan Abdul Gani. Lalu pada tahun 1959 saya diminta menjadi duta besar. Ini bukan semata-mata hoki, tapi karena saya tangkas bermain politik. Namun saya tetap wartawan. Sekali lagi, profesi saya wartawan, yang punya pekerjaan sebagai anggota parlemen. Pada waktu itu DPR tidak melempem. Betul-betul menyuarakan suara hati rakyat. Pada tahun 1959 itu saya ditugasi sebagai duta besar di Cekoslovakia, sekaligus duta besar di Hungaria -- istilah diplomatiknya: ''diakkreditir.'' Dan ditambah satu jabatan lagi sebagai gubernur pada International Atomic Energy Agency di Wina, Austria, untuk Indonesia. Saya sengaja memilih Ceko karena negeri itu kecil dan indah. Tidak sesemrawut dua negara lain yang ditawarkan kepada saya, Uni Soviet dan Polandia. Tiga tahun saya bertugas di situ. Tahun 1962 saya dipindah ke Inggris. Saya tidak menyangka akan mengalami kondisi berat ketika bertugas di negeri monarki itu. Ketika itu tahun 1963. Kedutaan Inggris di Jakarta dibakar massa. Saya dipanggil menteri luar negeri Inggris Lord Hume. Saya belum bisa menjelaskan apa-apa, karena memang belum mendapat kabar dari Jakarta. Pemerintah Inggris ingin mengetahui apakah ada warganya di Jakarta yang cedera. Apakah saya bisa menghubungi Jakarta, tanya pihak Inggris ketika memberitahukan tentang kebakaran itu. Saja janjikan pasti bisa. Jangan dibayangkan telekomunikasi ke Indonesia saat itu semudah sekarang. Sulit, sangat sulit. Tapi tentu saja saya malu untuk mengatakan hal itu. Begitu sampai di KBRI, saya menelepon Haji Ir. Djuanda, waktu itu perdana menteri. Astaga, ternyata tersambung. Pembantunya yang terima. Dia bilang, Pak Djuanda sedang di kamar mandi. Waduh, saya bilang, ini mendesak. Kalau menelepon lagi belum tentu bisa masuk. Akhirnya Pak Djuanda dipanggil, dan dia tegopoh-gopoh menerima telepon saya. ''Saya ditanya Pemerintah Inggris tentang kebakaran di kantor Kedubes Inggris,'' kata saya. Lalu jawab Pak Djuanda dengan logat Sunda yang kental: ''O ... nggak apa-apa. Temboknya kan dari beton. Tidak akan terbakar habis.'' Masya Allah, saya ini panik bukan main, ternyata dari Jakarta jawabannya enteng. Saya tidak menanyakan kondisi gedungnya, tapi insidennya. Pak Djuanda tertawa. Lalu dia ceritakan juga tentang kebakaran yang dilakukan orang-orang yang pro-Partai Komunis Indonesia itu. Meskipun hubungan Indonesia-Inggris tidak bagus pada waktu itu, saya disegani oleh pemerintah Inggris. Suatu ketika, dalam sebuah karikatur, Indonesia digambarkan sebagai anjing. Saya protes. Lalu saya mengirim tulisan ke majalah Diplomat. Saya gasak pemerintah Inggris. Saya bilang, mereka tidak tahu persoalan-persoalan Indonesia. Indonesia baru beberapa tahun merdeka. Kami masih mempunyai trauma atas penjajahan Belanda. Bagi masyarakat Inggris, artikel saya itu keras. Lebih dari dua tahun saya bertugas di Inggris. Saya kemudian dikirim ke Bangkok, Thailand, untuk jabatan yang sama. Ketika itu Indonesia masih konfrontasi dengan Malaysia. Sehingga orang Indonesia yang mau ke luar negeri harus melewati Bangkok, bukan Singapura. Saya bertugas di Bangkok sampai tahun 1966. Sepulang dari Bangkok, saya diangkat menjadi menteri penerangan oleh Presiden Sukarno. Pak Harto sudah menjadi pejabat presiden pada waktu itu. Kenapa saya diangkat menjadi menteri? Karena saya antikomunis dan mendukung perjuangan Orde Baru. Saya tahu, karena saya pengagum Bung Karno dan cukup dekat dengan Beliau, ada orang yang menafsirkan saya sebagai komunis. Tapi dengan kenyataan bahwa saya terang-terangan menentang PKI, orang tahu saya mendukung Pancasila. Pernah, tahun 1964-1965, Merdeka ditutup pemerintah. Bung Karno bertanya kepada Mahbub Djunaidi, kenapa Merdeka ditutup. Dia tidak tahu. Menurut sumber-sumber penting, karena Merdeka dianggap menyebarkan paham Sukarnoisme dan menentang PKI. Padahal, jika yang dimaksud paham Sukarnoisme itu Barisan Pendukung Sukarno (BPS) yang dibentuk oleh saya, Adam Malik (waktu itu pemimpin redaksi Kantor Berita Antara), dan Soemarsono (pemimpin redaksi harian Berita Indonesia), adalah supaya Bung Karno jangan seratus persen dipengaruhi PKI. Ini rupanya yang tidak disukai PKI. PKI juga menuduh bahwa BPS bertujuan membunuh Sukarno. Jadi, meski kemudian para pemuda Angkatan '66 menghukum Bung Karno sebagai komunis, saya tidak sependapat. Bung Karno tidak pernah menjadi komunis. Dia betul-betul seorang nasionalis. Cuma dia terpengaruh dinamika anak-anak muda, seperti Aidit, yang komunis itu. Bung Karno tidak melihat bahaya yang ada dalam PKI. Dia hanya melihat kegairahan anak-anak muda itu berpolitik, karena itulah cita-citanya untuk menghidupkan partai politik. Ketika Merdeka ditutup, saya masih bertugas di Bangkok. Banyak wartawan kami yang pindah ke harian Angkatan Bersenjata. Tak lama sesudah itu surat kabar Kompas dan Sinar Harapan terbit. Bagus juga ada koran baru, untuk mengimbangi koran komunis, seperti Harian Rakyat, Warta Berita, dan Bintang Timur. Organisasi wartawan, PWI (Persatuan Wartawan Indonesia), tidak berfungsi karena sudah diperalat PKI. PWI sudah menjadi mantel organisasi PKI. Sejak ''pensiun'' dari menteri penerangan, tahun 1967, saya kembali lagi ke Merdeka. Tapi saya tidak aktif lagi di redaksi. Saya memberi kesempatan anak-anak muda untuk mandiri. Harus ada regenerasi. Saya tidak ikut campur lagi dalam pembuatan berita. Saya sendiri lebih banyak berpikir how to catch the biggest attention. Jadi lebih ditujukan pada psychological approach. Saya lebih banyak melontarkan ide, kemudian ditulis oleh editor saya. Kalau kemudian tajuk di Merdeka terkesan keras, itu seperti saya katakan tadi, kita tidak menghantam manusianya, tapi sistemnya. WARTAWAN AMPLOP DAN PERAN PERS Di zaman konsumtif seperti sekarang sulit menemukan wartawan idealis. Sebab kebutuhan seseorang jadi tak berbatas. Sekalipun digaji Rp 1 juta, tak ada artinya. Untuk beli satu set stereo saja, habis. Akibatnya dia mesti mendapatkan lebih dari itu. Tapi, ketika dia mendapatkan lebih, dia beli barang seharga itu pula. Habis juga. Karena tekanan itu muncullah istilah wartawan amplop. Tapi kondisi ini juga bukan semata kesalahan wartawan, melainkan menjadi dosa masyarakat juga. Jika Anda seorang direktur perusahaan baru, kemudian mau memperkenalkan diri, maka promosi yang murah adalah dengan mengundang wartawan. Lalu wartawan diberi amplop sebagai uang jalan. Di sini perlunya kesadaran wartawan. Mau terima sogokan atau tidak. Jika amplop diterima, dia akan susah melepaskan diri dari ikatan. Wartawan akan membeo terhadap apa yang diucapkan si direktur tadi. Dia tidak lagi independen. Dia tidak bisa melihat lagi hal-hal yang mungkin bisa menjadi bahan kritik. Kondisi seperti ini sulit diberantas karena menyangkut mental masyarakat. Coba saja, setiap hari ada saja berita penggelapan, korupsi, penyelundupan, tapi tersangka dibebaskan. Secara tidak disadari, apa yang dilakukan pimpinan menjadi anutan bagi yang di bawahnya. Padahal, kalau dia merasa gaji tidak cukup, keluar saja. Cari pekerjaan lain. Oplah Merdeka sekarang sekitar 3O.OOO eksemplar. Salah satu problem kami adalah karena kami tidak ikut-ikutan konsumtif. Kami tetap berpikir secara politis. Kami, terus terang, tidak bisa melawan surat kabar lain yang tampil dengan full colour. Menurut perhitungan saya, secara bisnis, mereka tidak bisa untung. Merdeka walaupun oplahnya kecil, tidak punya utang sesen pun. Jurnalisme dulu dan sekarang berbeda. Dulu tidak dipersoalkan siapa yang akan dihantam. Pokoknya, tujuannya menjatuhkan pemerintah kolonial. Sekarang tidak bisa begitu. Yang diperlukan sekarang, bagaimana membuat surat kabar itu acceptable to the society (pas dengan masyarakatnya) dan bagaimana society itu bisa mempergunakan surat kabar itu sebaik-baiknya sebagai landasan untuk menghindari social problems. Dalam hal kontrol terhadap pers, Pemerintah kerap mendengung- dengungkan pasal: ''pers yang bebas dan bertanggung jawab.'' Bertanggung jawab terhadap siapa? Biarkan masyarakat yang menilai. Seyogyanya yang berhak menilai memang masyarakat, atau pengadilan. Bukan Pemerintah. Dalam UU Pokok Pers juga tidak disebutkan kepada siapa pers harus bertanggung jawab. Maka pengertiannya, pers harus bertanggung jawab pada diri sendiri. Dan jika ada yang tidak bisa menerima pemberitaannya, silakan mempersoalkannya pada media yang bersangkutan. Tidak adil jika hanya sebuah lembaga yang menentukan hal itu. Apalagi kalau disertai ancaman pencabutan SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers). Sebab SIUPP itu berkaitan dengan periuk nasi karyawan perusahaan. Periksa dulu siapa yang salah, lalu tuntut ke pengadilan. SIUPP sebagai lembaga jangan dicabut hanya karena seseorang menulis salah, atau karena mengkritik Pemerintah. Itu tidak adil. Dalam UU Pokok Pers jelas disebut bahwa pers tidak boleh disensor dan dibredel. Ancaman itu akhirnya membuat pers ketakutan. Sehingga, demi keamanan perusahaan, pers tidak kritis dan tidak peka lagi terhadap persoalan yang ada di sekitarnya. Yang dilakukan Surya Paloh (salah satu pemilik harian Media Indonesia) untuk membuat judicial review atas Peraturan Menteri Penerangan tentang SIUPP beberapa waktu lalu itu bagus. Pers itu harus ''hidup'' karena menjadi jembatan antara masyarakat dan Pemerintah. Pemerintah boleh saja menjaga agar pers tidak terlalu bebas dan tidak bermutu. Misalnya, jangan seenaknya menghantam orang. Cuma, perkataan tanggung jawab sedemikian samarnya, sehingga dapat membuat tindakan orang yang tidak bertanggung jawab, yang barangkali luput dari perhatian pemimpin redaksinya, bisa mengakibatkan perusahaan ditutup. Sebetulnya tidak ada alasan bagi Pemerintah untuk membuat SIUPP sebagai pentungan. SIUPP sebagai lembaga bagus sekali, tapi menggunakannya untuk mementung surat kabar agar perusahaan itu mati, itu berbahaya. Sebab pers mempunyai sifat yang baik. Apalagi secara harfiah dapat dikatakan pers Indonesia itu kental kewajibannya. Kritiknya juga sopan. Hanya, sekarang ini jangan lupa, orang yang melakukan pelanggaran-pelanggaran pada negara juga kasar dan jahat. Jadi seyogyanya Pemerintah tidak usah takut pada pers. Jika ada hal yang dilanggar, ada kode etik jurnalistik. Ada Dewan Kehormatan PWI yang bisa menghukum wartawan, atau lebih jauh lagi, mengajukan wartawan yang bersalah ke pengadilan. Menutup perusahaan, seperti terhadap surat kabar Sinar Harapan dan tabloid mingguan Monitor, itu tidak mendidik. Pemimpin redaksinya boleh masuk penjara, tapi korannya boleh terbit lagi. Kalau pelanggaran terjadi lagi, ciduk lagi wartawannya, habiskan saja wartawannya. Penjarakan semuanya. Bisa saja toh? Sulitnya sekarang, Dewan Pers itu diketuai Menteri Penerangan. Dan orang Indonesia zaman sekarang terbiasa nggih ...nggih (ya- ya). Apa pun kata yang di atas, diiyakan tanpa debat. Itulah sifat kita dalam politik sekarang, akomodatif! Jadi kalau menteri mengatakan begini, ya begini jadinya. Tidak ada perlawanan. Sebab kalau dia berbuat seperti itu akan dituding sebagai dissident atau oposisi. Sudah begitu, solidaritas pers juga meluntur. Dulu, ketika Harian Kami dibredel, pers bersatu membelanya. Sekarang, kalau sebuah penerbitan ditutup, lalu yang lain apatis. Tidak berbuat apa-apa. Zaman sekarang orang terbiasa tidak ambil pusing, karena kepentingan bisnis yang utama. Jadi ada wabah individualisme, masa bodohisme. Pada kenyataannya, Pemerintah sekarang tidak menginginkan adanya kontrol sosial. Maka kita harus pandai-pandai menulis. Jangan dibaca yang tersurat, tetapi yang tersirat. Contohnya, begini: si A ini orang baik, tapi .... Benar, Merdeka pun tidak berperan lagi seperti dulu -- apa gunanya. Coba saja, memilih presiden dan wakilnya mengikuti arus saja, tidak ada yang berani menentang. Soalnya bukan ekonomi yang mapan. Ini soal watak bangsa kita yang penurut. Dan kritik dari pers sekarang ini, meski begitu hebat, saya lihat tidak ada gaungnya. Tidak ada perubahan. Dulu, bila pers mengritik, orang atau lembaga yang dikritik itu goyang, karena dia malu. Sebab politikus di parlemen memperhatikan kritik itu, kemudian melemparnya ke forum parlemen. Pers kemudian menulis kembali hasil pembahasan di forum itu. Jadi berputar terus. Sampai lembaga atau orang yang dikritik itu kewalahan. Jadi pers sebagai lembaga kontrol sosial betul-betul berfungsi. Dulu setiap orang merasa dirinya bertanggung jawab, merasa dirinya menjadi bagian dari masyarakat yang bergerak dinamis. Sekarang orang tidak ambil pusing. Orang hanya pusing pada dirinya sendiri. Lurah dibela camat, camat dibela bupati. Bupati dibela gubernur. Begitu seterusnya. MIKHAIL GORBACHEV Hal yang berkesan dalam hidup saya adalah ketika tahun 1987 mewawancarai Sekretaris Jendral Partai Komunis Uni Soviet Mikhail Gorbachev. Keinginan itu bermula dari keprihatinan saya karena perundingan antara Presiden AS Ronald Reagan dan Gorbachev mengenai pembatasan senjata nuklir mengalami jalan buntu. Sebagai wartawan, intuisi saya seperti sedang diuji. Apa yang terjadi jika perundingan itu gagal terus? Apakah Perang Dunia III akan meletus? Lalu saya bertemu dengan Duta Besar Soviet di Jakarta, Mr. Semenov. Saya ajukan permintaan saya untuk mewawancarai pemimpin negaranya. Saya berani mengatakan itu karena saya tahu Gorbachev juga menerima wartawan dari negara asing lainnya. Permintaan saya itu ditanggapi. Saya langsung diminta membuat surat permohonan resmi. Tak lama sesudah itu saya mendapat kabar bahwa permohonan itu dikabulkan. Udara agak dingin ketika saya tiba di Moskow bulan Juli 1987. Saya memakai mantel berlapis-lapis. Rombongan kami diterima di ruang kerja Gorbachev di Kremlin. Ruangan itu sangat besar. Begitu besarnya ruangan itu, sehingga kalau ada orang jalan, derap sepatunya bergema ke mana-mana. Pokoknya, di sini semua serba besar. Kursi, meja, lukisan, pintu, dan jendela, semuanya besar-besar. Sekitar setengah jam kami menunggu, Gorbachev muncul bersama stafnya. Ia langsung menjabat tangan saya. Wajahnya tampak ramah. Sebelum saya memulai wawancara, dia lebih dulu menanyakan kabar saya dan kabar Presiden dan negara Indonesia. Pertanyaan saya ajukan dalam bahasa Inggris, yang kemudian diterjemahkan dalam bahasa Rusia. Antara lain saya katakan, demi keamanan dunia, kekuatan nuklir harus dikurangi. Bukan hanya di Soviet tetapi juga di pangkalan senjata Soviet di Asia. Sebab kalau hanya di Soviet saja, percuma. Gorbachev setuju. Pembicaraan berlangsung selama lebih kurang satu jam. Menurut saya, Gorbachev itu seorang pemikir. Bicaranya tangkas dan pemikirannya jernih. Sayangnya, pelaksanaan strateginya kurang mantap. Ini yang menyebabkan gagasan glasnost dan perestroika yang diciptakannya jadi gagal. Wawancara dengan Gorbachev adalah wawancara saya yang terakhir sebagai wartawan. Kala itu usia saya persis 7O tahun. Itu sebabnya wawancara ini sangat berkesan. Namun demikian, sebagai wartawan saya tidak berhenti sampai di situ. Sampai sekarang saya tetap aktif mengikuti perkembangan dunia dan menerima diplomat asing. Dunia usaha saya masuki bersamaan dengan kembalinya saya ke Merdeka. Waktu itu istri saya, Herawati, mempunyai ide mendirikan hotel. Dia ingin membangun hotel dengan 75 kamar. Saya bilang, kenapa tanggung amat. Terlalu kecil. Ini kan bukan mendirikan losmen. Saya usul 250 kamar. Ia setuju. Kebetulan, ketika hotel itu dibangun, Konperensi PATA akan berlangsung di Jakarta. PT Hotel Prapatan, yang menjadi pemilik Hotel Hyatt Aryaduta itu, diresmikan Presiden Soeharto tahun 1974. Tidak ada pertentangan batin untuk memadukan profesi wartawan dengan dunia usaha. Sebab yang dihadapi sama, manusia. Surat kabar memberikan makanan buat otak, sedang hotel menawarkan makanan buat perut. Jadi prinsipnya tidak ada perbedaan. Satu hal lagi yang juga penting, jika tidak mampu menjual kamar hotel akan sama akibatnya jika tidak berhasil menjual koran. Kalau surat kabar dengan oplah 1O.OOO mesti habis, hotel dengan 25O kamar juga mesti habis. DRAMA KELUARGA DAN PELIPUR LARA Saya kenal dengan Julia binti Abdul Manaff, ketika saya bertugas di Bangkok. Dia adalah istri keponakan Bung Karno, Gandi, yang waktu itu bertugas sebagai Kepala Pariwisata di KBRI Bangkok. Julia itu cantik, sudah mempunyai tiga anak. Dia kawin muda. Sayangnya, entah oleh sebab apa, Julia sering ditinggal suami. Sebaliknya, saya pun kerap ditinggal istri, karena Herawati waktu itu sering pergi ke Jakarta. Jakarta-Bangkok kan dekat. Akhirnya dua orang yang senasib itu bertemu. Dan tanpa diduga kami kemudian saling mencintai. Belakangan saya tahu perkawinan Ibu Julia dengan suaminya rupanya sudah tidak bisa dipertahankan lagi. Mereka bercerai tahun 1966. Kami menikah setahun kemudian. Herawati, yang waktu itu berada di Bangkok, tidak tahu. Julia tinggal di Jakarta. Tahun 1968 tugas saya sebagai duta besar di Bangkok selesai. Saya kembali ke Jakarta. Meski saya menikah lagi, saya tetap tinggal bersama Herawati di Kuningan, Jakarta Selatan. Pada waktu-waktu tertentu, ketika saya main golf, misalnya, saya menengok Julia. Julia tidak menuntut. Dia orang baik kok. Dari Julia saya dikaruniai dua anak, Asmarawan, 24 tahun, dan Asmarani, 14 tahun. Seorang lagi, di antara keduanya, meninggal dalam usia 3 tahun. Herawati baru tahu bahwa saya beristri lagi, dua belas tahun kemudian. Nurman, putra saya dari Herawati, yang membuka rahasia ini. Ceritanya begini. Ketika Nurman masih bekerja di Merdeka, saya memergoki stafnya mencuri uang. Lalu saya peringatkan supaya stafnya diperkarakan ke pengadilan. Rupanya Nurman ini tidak suka dikritik ayahnya. Lalu rahasia yang sudah diketahuinya tentang istri kedua ayahnya itu disampaikan kepada ibunya. Nurman tahu ini dari teman-teman. Saya ingat kejadian itu, tanggal 27 Desember 1979. Seperti sudah diduga, Herawati tidak terima. Kami ribut besar. Saya tidak bisa menceraikan Herawati, karena tidak ada alasan. Tapi lama-kelamaan Herawati bisa menerima juga. Oktober tahun silam saya pindah ke rumah Julia. Ini gara-gara Nurman juga. Bersama ibunya dan kakak-kakaknya, dan menarik juga orang luar, yaitu Dewan Komisaris PT Hotel Prapatan (yang mngelola Hotel Aryaduta Hyatt), Nurman berhasil menyingkirkan saya sebagai direktur perusahaan itu. Saya tidak mengerti. Nurman tidak henti-hentinya mencoba menyusahkan saya. Dia berkali-kali menuntut saya pribadi, yayasan atas nama saya, dan perseroan surat kabar Merdeka di pengadilan. Mengenai perkara terhadap Yayasan ini gagal. Hakim menolak tuntutannya. Yang dua lagi sedang berlanjut. Semua itu menjadi alasan sah kepindahan saya ke rumah Julia. Saya yakin, mereka berbuat begitu bukan karena saya beristri lagi. Persoalan istri bisa nomer sepuluh. Pernah, sebelum kejadian bulan Oktober itu, saya merenung. Saya bicara dengan Herawati, saya ini sebetulnya gagal dalam hidup. Saya tidak tahu kenapa saya katakan ini. Mungkin ini hanya firasat. Lalu istri saya bilang, tidak, kamu sama sekali tidak gagal. Sudah banyak yang kamu capai. Ternyata betul. Kejadian yang saya alami menunjukkan hal itu. Keluarga saya tidak sempurna. Yang dilakukan Nurman pada saya sekarang pernah dilakukannya pada kawan-kawannya ketika ia masih bergelut dalam jurnalistik. Ia berkelahi dengan Goenawan Mohamad (kini pemimpin redaksi TEMPO), Christianto Wibisono (direktur Pusat Data Bisnis Indonesia), dan kawan-kawan muda lainnya yang bekerja dalam majalah mingguan Ekspres. Saya menjadi korban karena lawan- lawan Nurman mengira saya ikut-ikutan. Akhirnya Goenawan, pemimpin redaksi Ekspres, dan kawan-kawan mendirikan TEMPO. Baiklah saya katakan sekarang, saya tak mencampuri urusan anak- anak muda. Akibat kasus Ekspres, dalam Kongres PWI tahun 1970 terjadilah pertentangan hebat untuk menentukan pengurus baru. Ada dua ketua, saya dan Rosihan Anwar. Saya disokong oleh Ali Moertopo, bekas menteri penerangan. Dan kepengurusan saya diakui oleh menteri penerangan waktu itu, Budiardjo. Wartawan- wartawan muda, antara lain Zoelharmans (kelak menjadi ketua PWI, dan 28 Maret lalu meninggal), dan Harmoko (menteri penerangan sejak 1982) menentang kepengurusan saya. Tapi saya tak ingin pecah dengan kawan-kawan wartawan. Saya tidak mendendam mereka yang melawan saya. Wartawan-wartawan muda yang dulu melawan saya kini menjadi sahabat baik. Bahkan termasuk Rosihan Anwar, yang menjadi musuh saya dalam ''pengurus PWI kembar'' dulu itu. Saya gembira hidup sebagai wartawan. Karena percaya pada diri sendiri, saya tak punya jalouise de metier, kecemburuan profesional. Inilah pelipur lara dalam hidup saya. Usia saya 76 tahun sekarang (7 April 1993). Saya sadar fisik akan berkurang banyak. Tapi saya tidak punya penyakit. Juga tidak ada pantangan makanan. Saya berenang di rumah, kalau pegal ada alat massage, dan alat-alat menjaga kebugaran. Saya betul-betul menjaga berat badan saya. Kalau malam mau makan enak, sore saya tidak makan. Begitu saja.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini