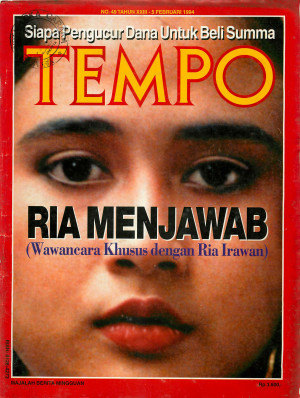Ketika Ali Sadikin dan kawan-kawannya dari kelompok Petisi 50 diundang Menristek B.J. Habibie untuk mengunjungi PT PAL dan IPTN, banyak orang kaget. Kunjungan itu agaknya dilihat sebagai perubahan sikap Pemerintah terhadap kelompok Petisi 50. Bagaimana sebenarnya kelompok Petisi 50 itu saat ini, dan bagaimana latar belakang keberadaannya? Akhir tahun 1993 lalu, Ali Sadikin bercerita panjang tentang hal itu -- juga tentang sisi-sisi kehidupannya yang lain -- kepada wartawan TEMPO Gabriel Sugrahetty dan Wahyu Muryadi. "Supaya generasi muda mengetahui fakta sejarah yang sebenarnya," katanya. Menjadi Menteri pada Usia 36 Tahun Menurut ibu saya, saya lahir pada hari Rabu tanggal 7 Juli 1927. Tapi ketika saya coba menghitung tanggal, ternyata tanggal 7 Juli 1927 bukan hari Rabu. Hari Rabu justru jatuh pada tanggal 7 Juli tahun 1926, bukan tahun 1927. Maka, saya selalu mengatakan lahir tahun 1926 meskipun dalam KTP ditulis lahir tahun 1927. Saya masuk ke Sekolah Pelayaran Tinggi pada waktu zaman Jepang. Sejak dulu saya memang sudah bercita-cita ingin menjadi perwira Angkatan Laut. Kelihatannya gagah. Setamat dari Sekolah Pelayaran Tinggi, saya sempat menjadi guru di Sekolah Pelayaran Tinggi di Jakarta. Tahun 1945-1949 saya menjadi anggota Badan Keamanan Rakyat, yang ditempatkan di Karesidenan Pekalongan. Saya termasuk salah satu yang ikut membentuk Pangkalan IV Angkatan Laut. Sejarah membuktikan bahwa Pangkalan IV itu adalah satu-satunya kesatuan Angkatan Laut yang ditugasi oleh pusat untuk tugas teritorial selain Angkatan Darat. Pada waktu perang gerilya, Pak Nasution adalah panglima komando untuk Jawa sambil merangkap wakil Panglima Besar Jenderal Sudirman. Saya anggap Pak Nas sebagai Bapak Angkatan Darat karena saya kenal betul dengan dia. Saya tidak pernah tahu Panglima Besar Jenderal Sudirman. Saya pernah dilatih oleh Pak Nas ketika zaman Jepang, sebelum saya belajar ke Pelayaran Tinggi. Ketika itu Pak Nas sudah ikut dalam gerakan bawah tanah bersama almarhum T.B. Simatupang. Sewaktu Clash Kedua, kami kembali lagi ke Korps Armada IV. Kemudian kami diberangkatkan ke Surabaya dan di sana menjadi Korps Komando Angkatan Laut (KKO-AL). Pangkat saya waktu itu masih kapten. Tahun 1953-1954 saya dikirim ke korps marinir di Amerika Serikat selama sembilan bulan. Pulangnya mampir ke Negeri Belanda melihat korps marinir di sana selama dua bulan. Saya menikah bulan Desember 1954, sepulang dari Amerika, karena juga kebetulan Ibu Nani sudah selesai kuliahnya di Universitas Airlangga bulan Desember 1954 itu. Saya sudah pacaran dengan Ibu Nani sejak tahun 1952. Saya dan kawan-kawan kemudian mengadakan reorganisasi KKO. Markas Besar KKO yang di Surabaya dipindahkan ke Jakarta. Saya tetap di Surabaya sebagai Komandan Pusat Pendidikan merangkap Komandan Pasukan KKO-AL. Kemudian saya serahkan Komandan Pasukan KKO-AL, supaya saya berkonsentrasi hanya pada Komandan Pusat Pendidikan dan sebagai guru di Akademi Angkatan Laut. Tahun 1960 saya sudah brigadir jenderal, padahal waktu itu saya baru berumur 34 tahun. September 1963 saya menjadi Menteri Perhubungan Laut dan tahun 1964 menjadi menteri koordinator maritim. Pada umur 36 tahun, saya sudah mayor jenderal dan menteri perhubungan laut. Jadi, pada umumnya sekarang menteri umurnya 50-an sampai 60-an, sedangkan saya dulu umur 36 sudah jadi menteri. Ketika saya menjadi menteri, saya menguasai PAL. Dulu PAL itu adalah bagian dari Angkatan Laut, sebagai detasemen untuk melayani kapal-kapal perang dan juga melayani seluruh instalasi Angkatan Laut di darat. Sekarang PAL sudah dikeluarkan dari Angkatan Laut. Angkatan Laut itu mempunyai sejarah "bodoh politik". Lain dengan Angkatan Darat, yang menguasai teritorial di darat. Mungkin itu tradisi dari pemerintah Hindia Belanda dulu dengan KNIL-nya, yang menguasai angkatan darat dan udara. Ketika itu, kalau keadaan darurat perang, yang berkuasa adalah tentara, KNIL. Sedangkan gubernur, residen, dan bupati di bawah komandan angkatan darat. Jadi, di darat yang berkuasa adalah angkatan darat. Saya Berdiri di Atas Semua Golongan Waktu saya menjadi Gubernur DKI Jakarta, partai-partai ingin supaya floating mass dihapuskan. Kalau tidak dihapuskan, mereka hanya bisa sampai kabupaten, sedangkan di kecamatan hanya ada komisaris partai. Tapi Golkar tidak begitu. Jalur pembinaan masyarakatnya melalui gubernur, bupati, camat, dan lurah. Dan pembinaan floating mass dalam kenyataan praktisnya dikerjakan oleh Korpri sampai pada tingkat lurah. Tapi PDI dan PPP tidak boleh sampai bawah. Mereka hanya diizinkan sampai tingkat komisaris atau tingkat kecamatan. Bagaimana akan ada pembinaan politik? Bagaimana Golkar sampai kalah (di Jakarta) sewaktu kepemimpinan saya? Yang jelas, saya tidak mau main curang. Waktu itu pemalsuan hasil pemilu banyak terjadi. Teromol yang sampai ke pusat apakah teromol yang asli atau tidak, kita tidak tahu. Selama dua kali pemilu, saya menggunakan komputer dan pada saat Golkar dan partai berkumpul, orang-orang partai sudah punya angka dari setiap tempat pemungutan suara. Jadi, dia tinggal mengecek saja, berapa angka dari tiap-tiap kelurahan atau TPS, kita akan tahu. Yang paling lucu, saya belum lagi selesai menghitung dan melaporkan ke masyarakat mengenai hasil pemilu untuk Jakarta, sekonyong-konyong Gubernur Sulawesi Selatan, Ahmad Lamo, melaporkan bahwa perhitungan di sana sudah selesai. Golkar menang sekian persen, katanya. Padahal, lurah di sana itu jaraknya sekian ratus kilo di pedalaman. Telepon juga tidak ada. Bagaimana mungkin? Padahal, di Jakarta ada telepon dan komputer, perhitungan suara belum selesai. Kalahnya Golkar di Jakarta tetap saja membuat saya tenang. Menteri Dalam Negeri, waktu itu Amirmachmud, tidak meminta saya bertanggung jawab. Dia sudah tahu sifat saya. Memang, semua gubernur diminta memenangkan Golkar. Ambillah misalnya 70%, itu targetnya. Lalu gubernur akan bilang ke bupati bahwa targetnya 75%. Lantas bupati bilang ke orang kecamatan supaya menang 80%. Camat akan bilang sama lurahnya 90%, dengan ancaman "Awas, lo, kalau kalah!" Belum lagi bantuan ABRI pada Pemilu 1971 dan 1977. Tapi, waktu itu khusus untuk saya tidak dikenakan target. Mereka tahu sifat saya. Saya menempatkan diri sebagai seorang ABRI yang berdiri di atas semua golongan. Komitmen saya dengan Golkar saat itu memang tak begitu kuat, karena saya menganggap gubernur dipilih oleh rakyat. Dan sebagai perwira, yang berarti berjiwa kesatria, saya harus berani jujur, benar, dan adil. Dalam Saptamarga butir ketiga, semuanya itu jelas. Orang lain mungkin lupa pada hal ini, tapi saya tidak. Ini masalah keyakinan, saya tidak ingin diperalat. Mungkin mereka mengatakan saya tidak loyal. Itu terserah. Loyalitas? Menurut saya, loyalitas hanya kepada UUD 1945 dengan berusaha menjalankan keimanan yang sebenarnya. Jangan menempatkan Saptamarga dan Sumpah Prajurit di atas UUD 1945. Saya tidak setuju dengan Persatuan Purnawirawan ABRI (Pepabri) kalau doktrinnya tidak bebas berpolitik. Artinya, saya tidak setuju Pepabri yang orientasinya ke Golkar. Menurut saya, Pepabri hanyalah ikatan kesejahteraan. Sedangkan mengenai soal politik, masing-masing mempunyai kebebasan. Selama Pepabri tidak bebas sikap politiknya, saya tidak akan menjadi anggota Pepabri. Tidak Tahu Kenapa Mahasiswa Percaya Saya Waktu peristiwa Malari (Januari 1974), keadaan mahasiswa genting dan sudah dikelilingi oleh kekuatan pemerintah. Karena itu, Pangdam Jaya G.H. Mantik bilang pada saya supaya kami berbuat sesuatu. Kami harus bertemu dengan mahasiswa. Saya yang menemui Hariman Siregar dan kawan-kawannya di UI Salemba. Tapi saya tidak masuk langsung ke dalam, dan hanya berdiri di depan. Waktu itu UI sudah dikelilingi orang. Saya masuk dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Saya tanyakan kepada mereka, apa benar Hariman yang membakar Pusat Perdagangan Senen, dan mereka bilang tidak. Tapi GUPPI dan Operasi Khusus (Opsus) menyudutkan mahasiswa. Begitu mereka melihat saya, mereka baik-baik saja. Saya tidak tahu kenapa mahasiswa percaya pada saya. Mungkin karena waktu adanya operasi Komisi Antikorupsi yang dipimpin Arief Budiman, saya juga yang menyelesaikannya. Waktu itu Pak Mitro (Jenderal Soemitro) sudah bingung, tapi saya menemui Arief dan mengajak dia bicara baik-baik. Saya sampaikan ide saya sama dia: yaitu menggelapkan kota, membunyikan sirene, dan mengheningkan cipta, sambil masing-masing berdoa pada Allah. Kemudian betul Jakarta kami gelapkan, sirene dibunyikan. Persoalan selesai, tidak ada apa-apa. Kembali ke soal Malari, setelah bertemu dengan Hariman, saya dipanggil Pak Mitro. Saya ditanya, "Ada apa Pak Ali pergi ke UI?" Saya sampaikan saja bahwa saya pergi untuk melihat anak- anak dan itu merupakan permintaan Kodam. Soemitro kemudian menyuruh saya agar membawa mereka ke TVRI, dan di TVRI nanti Hariman supaya menyampaikan pernyataan bahwa persoalan sudah selesai. Malamnya saya kembali ke UI dengan Land Rover, dan mengajak empat orang mahasiswa -- termasuk Hariman -- ke TVRI. Saya suruh dia ngomong, dan setalah itu kami kembali ke Pak Mitro. Selesai. Kalau saya tidak cepat bertindak, mungkin mahasiswa itu bisa diserbu. Keadaan mereka sudah lemah. Mereka sudah diisolasi. Waktu itu saya bilang pada Hariman bahwa keadaan sudah sulit, dan kalau ada sesuatu, dia yang akan payah sendiri. Hanya itu yang saya bilang. Dan mereka memang berhenti karena mereka sudah gelisah. Kecewa terhadap Pelaksanaan Orba Orang tidak bisa menuduh saya mengalami post-power syndrome. Kalau nasib saya begini, itu semua karena Gusti Allah yang menentukan. Tahun 1977, saya bertemu Amirmachmud yang waktu itu menjabat menteri dalam negeri. Dia bertanya, "Bade ka mana, Pak Ali?" Saya jawab, "Saya kembali ke masyarakat." Dia malah bengong. Begitu selesai menjabat Gubernur DKI, saya minta agar pensiun dipercepat. Permintaan itu saya tulis kepada Pangab Jenderal Maraden Panggabean secara terbuka, tidak diam- diam. Kalau kemudian ada petisi Dipo Alam (ketika itu Dipo Alam mahasiswa UI) yang mencalonkan saya sebagai presiden, saya anggap itu permainan anak-anak saja. Itu lambang kejengkelan mereka terhadap keadaan yang mereka lampiaskan dengan cara begitu. Waktu itu Sudomo lantas datang ke saya dan bertanya, "Kenapa Pak Ali tidak menolak?" Saya jawab, "Untuk apa menolak, toh saya tidak ada kemauan untuk menjadi presiden?" Toh ada juga yang mengatakan, "Pak Ali itu masuk barisan sakit hati." Itu tidak benar. Kepada Amirmachmud, saya sudah bilang bahwa saya memang tak mau lagi aktif dalam birokrasi. Kalau kemudian saya aktif di Fosko Angkatan Darat, Lembaga Kesadaran Berkonstitusi (LKB), dan Petisi 50, itu karena saya ingin mengingatkan Orde Baru. Itulah dasar pikiran yang ada pada diri saya. Saya ingin mengatakan bahwa perjuangan di Fosko AD, LKB, dan Petisi 50 itu dimulai sejak di tubuh Orde Baru tumbuh permasalahan-permasalahan. Kalau tidak ada masalah, mengapa lahir Petisi 50, kenapa ada LKB, kenapa ada Fosko AD maupun Gerakan Mahasiswa di Bandung tahun 1977-1978, kenapa ada Malari, dan ada Komisi Antikorupsi. Itu sebabnya saya tak bisa ngomong soal Petisi 50 kalau sama sekali tidak mempersoalkan apa yang terjadi di sidang-sidang MPRS sekitar tahun 1966. Petisi 50 itu tidak tiba-tiba dan berdiri sendiri, tapi saling mengait dengan sejumlah peristiwa sebelumnya. Bermula pada pernyataan Lembaga Kesadaran Berkonstitusi 1 Juni 1978. Isinya tentang pelaksanaan pemilu, pembentukan anggota DPRD I dan II, serta adanya kesenjangan anggota MPR dengan yang lain, yang memperlihatkan keadaan UUD 1945 belum dilaksanakan secara murni dan konsekuen. Adapun tujuan lembaga itu antara lain: 1. Penelitian, diskusi, simposium, dan pendidikan untuk belajar hidup berkonstitusi. 2. Menyumbangkan pendapat ke lembaga, perorangan, orpol, ormas pusat maupun daerah. 3. Memberikan tuntunan kesadaran hidup berkonstitusi di kalangan masyarakat dengan cara melaksanakan Pancasila & UUD 45. Jadi, kembali ke tekad Orde Baru yang dipidatokan Pak Harto pada tanggal 16 Agustus 1967 dan dipadukan dengan hasil seminar Angkatan Darat tahun 1966. Di antara anggota Lembaga Kesadaran Berkonstitusi, terdapat Bung Hatta, Panggih Soeroso. Bisa Anda bayangkan, Bung Hatta adalah proklamator, pendiri Republik. Anggota lainnya Soetardjo, Prof. Soenario, I.G. Kasimo, Frans Seda, Slamet Bratanata, Mohammad Natsir, Hoegeng, Suyitno Sukirno, Azis Saleh, A.Y. Mokoginta, Soehardiman, Koesbandono, H.M. Sanusi, Nyonya Walandouw, Sabam Sirait, Arif Mawardi, Rima Sofyan, Anwar Musadat, Anwar Haryono, M. Noer, Marsilam Simandjuntak, Chris Siner Key Timu, Nurbani Jusuf, dan lain-lain. Semuanya ada 66 anggota. Boleh dikatakan bahwa saya tertarik masuk LKB karena saya kecewa terhadap pelaksanaan Orba. Saya tidak bisa mengerti kalau dikatakan "politik no dan ekonomi yes". Kenapa? Ini kan lucu, orang merdeka tidak boleh berpolitik. Merdeka itu pengertiannya mencapai kebebasan berpolitik. Kalau tidak ada kebebasan berpolitik, berarti kita tidak merdeka. Lahirnya Petisi 50 Sekarang kita bicara tentang pidato Presiden Soeharto di Pekanbaru, tanggal 27 Maret 1980, waktu Rapim ABRI. Di Pekanbaru itu ada pidato yang tidak tertulis. Ceritanya, setelah membaca pidato yang tertulis dan turun dari podium, Pak Harto naik lagi dan berpidato yang tidak tertulis. Kemudian Pak Harto berpidato lagi di Cijantung, pada HUT Kopassus tanggal 16 April. Waktu itu kami menunggu-nunggu reaksi DPR tentang pidato Presiden itu, tapi ternyata tidak ada. Malah yang memberi reaksi justru Fosko AD. Seperti yang saya ketahui, yang bereaksi adalah Jenderal Mokoginta dan tanggal 26 April ia bikin surat. Pidato Pak Harto di Cijantung rupanya masih belum sampai ke Pak Mokoginta sehingga suratnya belum terarah pada pidato itu. Baru pada tanggal 2 Mei 1980 ada lagi surat dari Jenderal Sudirman, dan Pak Dharsono ikut menandatangani sebagai sekjen. Surat itu sebagai reaksi terhadap pidato di Cijantung. Sampai di situ masalahnya masih tetap jadi masalah intern karena surat tidak keluar. Lantas kami diundang oleh Fosko AD di Gedung Veteran. Saya datang memenuhi undangan tersebut. Rapat pertama dipimpin Pak Sukendro, sedangkan rapat kedua dipimpin oleh Yahya, keduanya sudah almarhum. Peserta rapat pertama hanya sekitar 20 orang. Dari situlah akhirnya keluar Pernyataan Keprihatinan yang ditandatangani tanggal 5 Mei secara berturut-turut oleh 50 orang. Belakangan Pernyataan Keprihatinan ini dikenal dengan Petisi 50. Kenapa hanya ditandatangani 50 orang karena tangan Gusti Allah saja. Mungkin juga kalau terlalu banyak akan susah mengajukannya ke DPR. Saya tidak tahu. Tidak pernah ada target supaya sampai berjumlah 50. Mungkin yang tugas mutar-mutar mengira bahwa jumlah 50 itu sudah cukup untuk dibawa ke DPR. Jadi, lahirnya Petisi 50 itu sebenarnya di sana (Gedung Veteran), bukan di rumah saya. Dan itu pun tidak semuanya ikut berkumpul di Gedung Veteran. Surat itu dibawa berkeliling dari rumah ke rumah. Waktu saya terima surat, sudah ditandatangani beberapa orang. Waktu disodori surat itu dan menandatanganinya, saya tidak mempunyai penafsiran yang tidak-tidak. Saya juga tidak berpikir bahwa hal itu akan menimbulkan kepekaan. Kami anggap kondisinya sama-sama berjuang. Republik ini adalah milik kita semua. Secara pribadi saya tidak tahu siapa yang membuat konsep Surat Keprihatinan itu. Tapi saya membantah kata-kata Sudomo bahwa yang menyusun konsep itu Pak Anwar Haryono dan A.M. Fatwa. Meskipun saya tahunya sudah jadi, saya yakin apa yang dibilang Sudomo itu tidak betul. Sebab, sebelum Surat Keprihatinan itu ditandatangani, sudah ada dua kali pertemuan dan pada waktu itu konsep surat sudah jadi. Konsep itu juga bukan konsep Masyumi. Hanya kebetulan di Petisi 50 ada beberapa orang eks-Masyumi. Setelah surat Pernyataan Keprihatinan diajukan ke DPR, ternyata hal itu menghebohkan dan berakibat panjang. Terbukti kemudian pada tahun 1980 media massa dilarang memuat berita-berita Petisi 50. Padahal, selama itu banyak kegiatan Petisi 50 yang berlangsung. Tanggal 23 Juli 1980, misalnya, Kelompok Kerja Petisi 50 menulis surat ke Pimpinan DPR, yang berpendapat bahwa tanggapan Pemerintah terhadap Pernyataan Keprihatinan tidak tepat. Kemudian tanggal 5 Juli 1980, ada 19 anggota DPR yang mengajukan pertanyaan kepada Presiden Soeharto tentang Petisi 50. Mereka menanyakan apakah Presiden sependapat bahwa Pernyataan Keprihatinan mengandung hal-hal yang sangat penting dan selayaknya mendapat perhatian umum. Mereka juga menanyakan apakah tidak sebaiknya rakyat Indonesia mendapat keterangan dan penjelasan mengenai duduk persoalan sebenarnya. Ada jawaban dari Presiden yang meminta agar anggota DPR yang menanyakan itu bisa membaca kembali pidato Presiden di Pekanbaru dan Cijantung. Presiden juga menugasi Menhankam/Pangab memberikan penjelasan yang diperlukan. Setelah itu, Sudomo mengatakan sudah selesai. Tapi menurut saya itu belum selesai. Tanggal 21 Mei 1991 juga berlangsung peristiwa menarik karena ada dialog antara kelompok Petisi 50 dan Pemerintah, yang diwakili Sudomo. Dialog terjadi setelah Petisi 50 berusia 11 tahun. Dua hari setelah dialog itu, saya menulis surat ke Pimpinan DPR dengan mengajukan kemungkinan agar dilangsungkan dengar pendapat dengan DPR, seperti awal tahun 1980. Saya perlu menegaskan bahwa kelompok kerja Petisi 50 bukan merupakan satu organisasi. Ada delapan orang yang diberi tugas menjadi kelompok kerja Petisi 50. Yang menugaskan kami adalah LKB. Jadi, kami tidak berdiri sendiri, tapi dibentuk oleh LKB. Tugas kelompok kerja ini adalah terus mengamati keadaan negara dan bangsa dalam segala persoalan. Delapan orang terdiri dari saya, Hoegeng, Chris Siner Key Timu, Anwar Haryono, H.M. Sanusi. Pak Mokoginta juga masuk Kelompok Kerja, dan setelah meninggal digantikan Sanusi. Meski kelompok kerjanya hanya delapan orang, kalau Petisi 50 berkumpul, ada sekitar 20 orang yang hadir. Kumpul-kumpul ini diadakan dua kali seminggu, tiap Selasa dan Kamis. Segala permasalahan kami bicarakan: politik, ekonomi, dan sosial. Kalau kami anggap serius, diusulkan ke DPR dan semua pejabat mendapat tembusan, termasuk media massa. Hubungan kami dengan Pak Nas sampai kini masih cukup erat. Beliau di antara kita kan menjadi sesepuh. Juga Pak Nasir dan Pak Sanusi. Dari 50 orang anggota Petisi, yang meninggal sudah ada 11 orang. Berbagai Larangan Sebelumnya kami tidak tahu sikap Pemerintah terhadap kami. Setelah beberapa lama kami baru tahu. Saya tahu waktu anak saya mau meminjam uang di bank. Anak saya ditanya identitas orang tuanya, "Ini Sadikin yang mana?" Anak saya bilang, "Ya, Pak Ali Sadikin." Anak saya tak boleh mendapat kredit. Saya lalu menemui Rachmat Saleh yang waktu itu Gubernur Bank Indonesia. Masuk ke kantornya nyelonong saja. Saya tanya, "Ini bagaimana, anak saya mau minta kredit kok tidak boleh." Dia bilang, ini ada perintah. Bagusnya Rachmat Saleh, dia tidak berbohong. Dia menjawab, "Itu sebetulnya berlaku untuk Pak Ali, bukan untuk putra Pak Ali." Kemudian saya tahu dari kantor berita Reuters bahwa kedutaan- kedutaan asing supaya mencoret nama anggota Petisi 50 yang biasa diundangnya. Saya baca itu, kemudian saya menemui Menteri Luar Negeri Mochtar Kusuma-Atmadja. Saya perlihatkan, apa betul berita itu. Ternyata benar ada perintah dari atas. Sekuriti Istana juga diperintahkan supaya nanti kalau ada undangan- undangan kepada Presiden Soeharto supaya diteliti apakah orang- orang Petisi 50 juga diundang. Saya pernah mengalami hal itu. Orang yang sudah mengundang saya memohon agar undangan yang pernah diberikan dianggap tidak ada saja dan karena itu ia mohon maaf. Belakangan ada juga yang mengatakan tetap mengharapkan kehadiran saya, tetapi jamnya ditentukan. Yang paling nyata waktu Pak Mitro (Sumitro Djojohadikusumo) mengawinkan putranya, Prabowo. Pak Mitro datang sendiri ke rumah Pak Hoegeng dan ke rumah saya. Padahal, dia orang tua, sedangkan saya ini apalah artinya. Rupanya, ia ingin menghargai saya dan ingin menyatakan sikap sayang. Pak Mitro datang untuk minta maaf karena tidak bisa mengundang saya. Sebab, katanya, ia sudah berusaha, tapi tetap dilarang sekuriti. Larangan mengundang juga datang dari TNI AL, termasuk Korps Marinir. Begitu pula Pemda DKI. Merayakan pembukaan Pekan Raya Jakarta saya pun tak boleh diundang, padahal saya yang mendirikan PRJ. Ketika saya akan mengawinkan anak saya nomor dua, di hari akad nikah ada yang meminta supaya Anwar Haryono tidak memberikan khotbah nikah karena takut ada unsur politiknya. Ributlah saya. Tapi karena saya kasihan sama besan, saya terima, akhirnya yang memberikan khotbah nikah adalah pak penghulu. Yang paling menyedihkan waktu istri saya meninggal, ada upaya supaya orang-orang TNI AL tidak memberikan bela sungkawa dan tidak usah datang. Lucunya, Presiden Soeharto dan Wapres Umar Wirahadikusumah mengirim bunga. Banyak menteri yang datang ketika itu, seperti M. Jusuf, Radius, dan Sumarlin. Sudomo pun datang karena kami bertetangga. Kasad, Kasau, dan Kapolri mengirim bunga. Yang tidak mengirim bunga justru Kasal. Itu anehnya. Jadi, selama ini siapa yang melarang? Nasib penanda tangan petisi yang lain juga kurang lebih sama. Tapi tidak betul kalau dikatakan Pak Jasin minta maaf karena tidak tahan terhadap perlakuan-perlakuan itu. Ia tidak minta maaf yang berhubungan dengan Petisi 50. Pak Jasin minta maaf dalam masalah dia pribadi dengan Pak Harto. Masalah pribadi itu bermula ketika di DPR, Pak Jasin mempersoalkan masalah Tapos. Bahwa peternakan itu jalannya dibikin oleh PU, alat-alatnya dari Krakatau Steel. Itu dilemparkan oleh Pak Jasin. Waktu itu ia dituntut. Jadi, tidak ada hubungannya dengan Petisi 50. Begitu pula dengan berita Pak Mokoginta minta maaf. Itu tidak betul. Soal permintaan maaf anggota Petisi 50 lainnya kepada Pemerintah memang ada. Itu dari dua orang anak muda, bukan yang tua-tua. Satu dari Surabaya, dan satunya lagi dari HMI. Perjuangan sebagai Ibadah Kegiatan Petisi 50 inilah yang sekarang sepenuhnya memberikan isi kekuatan kehidupan bagi saya. Mau dagang nggak bisa, dan percuma, nggak bakalan dapat proyek. Kegiatan sosial lain masih ada. Rumah Sakit Mata Aini itu kan didirikan istri saya. Saya diminta menjadi anggota dewan penyantun. Kegiatan saya yang lain menghadiri undangan. Begitu banyak undangan yang saya terima. Nah, ini anehnya. Hampir tiap malam saya dapat undangan, terutama perkawinan. Jadi, perhatian masyarakat terhadap saya rupanya masih cukup besar. Saya diterima baik, ditempatkan di VIP. Sekarang agaknya memang ada kesan sikap Pemerintah terhadap Petisi 50 melunak. Tapi apa benar? Itu bisa disebut sebagai suatu keadaan yang di luar perhitungan. Kalau memang benar, itu saya lihat sebagai rekayasa Gusti Allah. Tapi dalam upacara Hari ABRI tanggal 5 Oktober lalu saya tak diundang, padahal saya kan pernah di eselon tinggi Angkatan Laut, dan pernah jadi gubernur. Lucunya, sebelumnya saya dengar dari orang dalam bahwa Feisal Tanjung mau mengundang saya. Saya tak tahu. Tapi kenapa waktu Habibie yang ngundang, kok, tidak ada larangan? Tentang cekal saya yang dihapus? Saya betul-betul tersinggung, kenapa saya mendengarnya ketika Kapuspen Mabes ABRI Syarwan Hamid ditanya oleh wartawan. Jadi, kalau wartawan tidak tanya, kami tidak tahu. Tersinggungnya di situ, kenapa kami tidak diberi tahu secara resmi. Bagi saya, soal cekal tidak ada masalah, walaupun menurut saya hal itu tetap merupakan tindakan tidak beradab karena melanggar hak asasi manusia. Pengaruh bagi saya tidak ada artinya. Apa artinya itu buat saya? Saya ini kan sudah kenyang ke luar negeri. Dan kalau ada wawancara dengan orang asing, mereka datang ke rumah minta wawancara, atau wawancara langsung via telepon. Saya tidak pernah bicara di luar negeri. Waktu saya ada di Negeri Belanda dengan istri pada tahun 1985, saya maunya diwawancarai wartawan asing tapi saya tolak. Saya katakan, kalau Anda mau bicara soal politik, datang saja ke Indonesia. Saya ke Belanda karena mendapat telegram keadaan istri saya genting dan saya harus ada di tempat. Waktu menyelesaikan paspor sudah berjalan lancar, tiba-tiba Kepala Imigrasi Jakarta Pusat mengatakan, "Pak, sebaiknya ini diselesaikan di kantor pusat Imigrasi." Rupa-rupanya, saya akan diganggu. Saya marah. Kenapa? Apakah saya dilarang? Apakah Bakin yang melarang? Kalau begitu, akan saya temui dia. Rupanya, pejabat itu tidak tahu bahwa saya bakal berani menemui Bakin. Kemudian dia mengatakan, "Sudah, Pak, anggap saja ini tidak ada. Silakan Bapak berangkat, tapi ada persyaratan. Selama di luar negeri, Bapak tidak boleh berpolitik." Saya bilang tidak bisa. Hak politik itu milik saya sejak lahir, saya ini insan politik. Larangan tidak boleh bicara di luar negeri juga saya tolak. Apakah saya mau ngomong atau tidak, tidak ada yang ngatur. Sedangkan tentang permintaan supaya saya melapor ke kedutaan besar, ya, tentu saja saya tidak keberatan. Saya juga diminta tidak lebih dari dua bulan di luar negeri. Saya pikir untuk apa dua bulan? Urusan istri saya tiga minggu sudah selesai. Jadi, tuduhan Sudomo bahwa saya mau bicara di luar negeri dan gara- gara itu bantuan luar negeri bisa menurun jelas tidak benar. Nyatanya, bantuan luar negeri tiap tahun juga naik terus. Alasan itu kan dicari-cari. Setelah itu, saya tidak pernah ke luar negeri lagi. Saya ke Mekah pada tahun 1975 dan 1978. Jadi, pengaruh cekal ke luar negeri saya anggap enteng. Walau demikian, kita harus berusaha untuk menghapuskan cekal. Hanya saja, jangan dikira bahwa kita berjuang untuk cekal. Kita berjuang masalah sistem politik, yang kita anggap Orba ini sudah menyimpang dari tekadnya yang semula. Itu masalahnya. Selama itu belum tercapai, masalah-masalah ini masih akan terus kami perjuangkan. Jadi, kalau sekarang ini orang sudah banyak mempersoalkan demokrasi dan sistem politik, itu sebenarnya sudah kami lemparkan bertahun-tahun lalu. Ini juga merupakan kepuasan bahwa apa yang dulu kami perjuangkan akhirnya diikuti oleh yang lain. Bagusnya, mereka tidak dicekal, dan masih dimuat di surat kabar. Dan kami anggap yang berjuang itu bukan kami saja. Itulah sejarah perjuangan kita, seperti yang saya bilang sudah mulai sejak tahun 1965. Dan lama-lama saya menganggap perjuangan ini sebagai ibadah, untuk membela dan menegakkan kejujuran. Untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Apa yang nanti terjadi, terserah Allah. Kebenaran Tidak Bisa Dikalahkan Saya diundang Habibie ke PAL dan IPTN. Ajakan Habibie ke PAL itu spontan. Karena terjadi dalam hari mulia, yaitu hari Lebaran. Dan saya mengenal Habibie sejak tahun 1973-1974, waktu dia kembali dari Jerman. Habibie itu teman Wardiman Djojonegoro, kini Menteri P dan K. Ketika saya Gubernur DKI, Wardiman adalah kepala biro. Beberapa kali saya melihat Habibie bertemu Wardiman. Mereka ngobrol sebagai teman lama sejak sama- sama kuliah di Jerman. Kedua, adik Habibie, Fanny Habibie, yang bekas dirjen perhubungan laut itu, adalah anak buah saya. Dia dipecat dari TNI AL dengan teman-temannya. Saya sebagai menko maritim ditugaskan oleh Bung Karno untuk menampungnya. Tentu Habibie tahu bahwa saya bersikap baik terhadap adiknya. Mau tidak mau dia menghargai saya. Lagi pula, saya ini orang maritim, jadi tahu masalah maritim. Dan dia rupanya menganggap saya tokoh maritim juga, karena itu Habibie mengundang saya. Gambaran saya waktu Habibie ketemu Pak Harto, dia tentunya melapor bahwa dia mengundang saya. Adapun apa yang ada pada pikiran Pak Harto, saya tentu tidak tahu. Tahu-tahu setelah kunjungan ke PAL itu, respons masyarakat bukan main. Itu sama sekali tidak terduga. Berarti masyarakat membaca seolah-olah akan ada pendekatan Pemerintah kepada kami. Saya tidak punya pikiran macam-macam, apalagi sampai mikir rekonsiliasi. Tapi yang paling tersentuh adalah bahwa masyarakat ingin ada kemajuan proses demokratisasi. Itu jelas. Terus berlanjut ke IPTN. Terus terang saya tidak menduga kalau IPTN sudah begitu pesat kemajuannya. Jelas jauh lebih baik daripada PAL. Waktu saya disuruh pidato, tadinya saya mau pidato soal umum dan apa itu Petisi 50. Tapi kemudian saya pidato soal cekal. Saya langsung teringat pada Pak Nasution karena sebelumnya saya pamit Pak Nas dan melihat keadaan Pak Nas yang sudah payah. Kalau Pak Nas seandainya dipanggil Allah, dan dia masih dihukum, apa itu tidak dihinakan namanya? Dan waktu itu saya juga teringat pada Pak Natsir, Pak Burhanuddin, Syafruddin, Bratanata, maupun Pak Mokoginta, yang sudah meninggal dan masih dalam status dicekal. Saya tidak ikhlas dan tidak rela kalau nasib Pak Nasution, sebagai Bapak Angkatan Darat, bisa jadi demikian. Jasa Pak Nas itu bukan main. Nasution sempat menjadi wakil Panglima Besar, membantu Jenderal Sudirman. Waktu perang gerilya di Jawa, Pak Nas itu panglima Jawa. Konseptor teritorial, konseptor dwifungsi, konseptor sistem pendidikan Angkatan Darat, melawan pemberontak-pemberontak. Waktu PKI Madiun, kalau tidak ada Siliwangi, payah kita, karena tentara semua kan di front Semarang. Karena teringat itu semua, saya meledak menangis. Jadi, bukan tangisan politik seperti yang dituduhkan orang. Untuk apa saya nangis-nangisan? Itu spontan saja. Saya tidak tahu apakah perlakuan Pemerintah pada saya sekarang ini melunak setelah peristiwa-peristiwa itu. Saya baru sekali saja berceramah di Masjid Al Azhar. Adapun untuk ceramah di ITB, UGM, dan Unhas, saya tetap tidak diizinkan. Saya sempat ikut hadir dalam suatu ceramah di Cides -- sebuah lembaga di bawah Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia -- sewaktu Jenderal Soemitro memberikan makalahnya dan saya ikut dalam dialognya. Ternyata mereka kemudian didatangi polisi. Padahal, 17 kali ceramah sebelumnya tidak pernah diapa-apakan. Jadi, kalau begitu saya masih ada cekal plusnya. Yang perubahannya terasa baru Pak Nas. Kenyataannya memang masalah Pak Nasution sudah dianggap selesai walau Pak Nas dalam perjuangannya masih tetap dengan kami. Hikmahnya jelas, sekarang Pak Nasution diakui kembali oleh TNI AD. Kebenaran bisa disalahkan, tapi tidak bisa dikalahkan. Nasution dianggap salah, tapi nyatanya jasanya dibenarkan. Buktinya, sekarang dia dihormati lagi oleh negara. Betul nggak? Itu adalah jalan yang sudah diberikan Allah kepada kami.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini