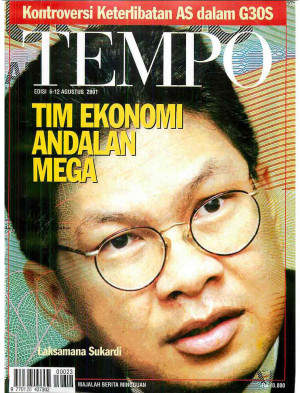Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Secara formal, rezim militer di Indonesia memang tak pernah ada. Tetapi dalam praktek sehari-hari, masa-masa ketika militer begitu berkuasa, dan bahkan merebut hampir semua pimpinan puncak birokrat sipil, pernah terjadi. Itulah era pemerintahan Soeharto, atau yang lebih dikenal sebagai pemerintahan Orde Baru. Apalagi pada awal-awal kekuasaannya, militer memang seolah segalanya. Mereka menguasai hampir segenap aspek kehidupan, dari presiden, wakil presiden, menteri, gubernur, bupati, hingga ketua RT. Juga, dari direktur sampai petugas satpam, tentara selalu muncul di sana.
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo