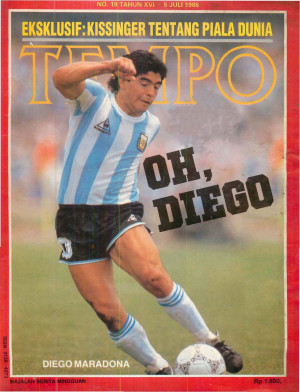SHANGHAI di hari Idulfitri, 9 Juni 1986. Pagi hari, matahari muncul dengan latar langit yang bersih, sinarnya membersit di antara daun-daun pohon ya dan liu, dan sela-sela bangunan tua sisa-sisa kolonial Eropa. Satu suasana yang tak akan ditemukan di RRC di luar Shanghai. Kota ini memang punya sejarah yang lain. Di masa lalu, Shanghai sempat terpilah-pilah menjadi daerah konsesi Prancis, Inggris, Jerman, Rusia .... Keremangan perlahan jadi benderang. Pukul 7 sudah. Jalanan mulai ramai oleh sepeda, pejalan kaki, dan bis kota. Namun, taksi belum satu pun ada yang bergerak. Bila ada, tentu itu sudah dipesan oleh turis asing di hari sebelumnya. Memang, ini bukan taksi swasta, tapi milik negara. Sopir, bergaji 120 yuan (sekitar Rp 40.000), baru mulai bertugas pukul 8 demikianlah jam kerja diatur. Taksi di kota ini semuanya bikinan Jepang keluaran tahun terakhir. Hanya di Beijing ada Mercedes, Volvo, dan Citroen buatan tahun 1983, 1984, dan 1985. Dan tanpa kecuali, semuanya milik pemerintah. Tapi benarkah ini hari Lebaran? Tiba-tiba saya ragu. Suasana tak jauh berbeda dengan hari kemarin. Bahkan semalam tidak ada suara takbiran. Di malam sebelumnya juga tak terdengar atau tampak sedikit pun aba-aba datangnya hari Idulfitri ini. Sampai tengah malam, kota bandar, yang dahulu tersohor dengan berbagai hiburan dan kehidupan malam hanya sepi. Seperti kota-kota besar, di negeri sosialis, kehidupan malam, juga untuk pendatang, ada batasnya. Diskotek yang ada di hotel, misalnya, hanya buka sampai pukul 11 malam. Saya tak tahu, di RRC ini ada jugakah acara sembahyang led di tanah terbuka. Bila cuma soal masjid, tak perlu khawatir. Di Shanghai ada sembilan masjid, atau dalam bahasa Cina disebut qingzhengsi. Tapi itu dahulu, sebelum masa Revolusi Kebudayaan. Sebab, di masa Partai melakukan pembersihan terhadap segala yang berbau asing, tiga masjid remuk oleh barisan Pengawal Merah. Tiga yang lain kini sedang dalam persiapan untuk dibuka kembali. Jadi, tinggal tiga masjid, dan yang paling besar di antaranya adalah Xiao Tao Yuan Qingzhengsi atau Masjid Xiao Tao Yuan. Nama masjid itu diambil dari nama jalan di depannya rupanya, Jalan Xiao Tao Yuan -- satu daerah yang termasuk tidak gemerlapan, jalanannya pun termasuk bukan jalan besar, hanya selebar empat meter. Lalu saya ingat, masjid itu bisa ditelepon. Maka, yakinlah saya, hari ini memang Lebaran, dan sembahyang Ied berlangsung pukul 9 pagi (atawa pukul 7 pagi WIB, mengingat mulai musim panas tahun ini perbedaan waktu di seluruh RRC dengan Waktu Indonesia Bagian Barat telah menjadi dua jam). Kurang jelas mengapa sembahyang Ied diatur mulai pukul 9. Mungkin disesuaikan dengan beredarnya taksi yang mulai pukul 8? Siapa tahu. Dari Huaqiao Fandian (Overseas Chinese Hotel) menuju Xiao Tao Yuan memerlukan waktu sekitar 10 menit. Sebenarnya tidak terlalu jauh. Tapi karena taksi harus sering berkelit di antara para pengendara sepeda dan trem listrik beroda karet, perjalanan menjadi agak pelan. Ini salah satu gambaran kota-kota di RRC, yang rata-rata dipadati manusia dan pengendara sepeda. Hanya di Beijing, meski berpenduduk hampir 10 juta dan ada sekitar 6 juta sepeda yang tercatat, terasa longgar. Di ibu kota RRC ini jalan-jalan banyak -- lebar, cukup untuk enam jalur mobil. Menjelang masuk ke daerah Xiao Tao Yuan, baru suasana Lebaran sedikit tercium. Tampak beberapa kelompok lelaki berkopiah putih bergegas mempercepat langkah. Dari kulit mereka yang kecokelatan dan roman muka yang sekeras alam, mereka tampaknya termasuk suku bangsa Uighur, atau suku yang berasal dari Provinsi Xinjiang yang mayoritas warganya beragama Islam. Di antara mereka ada juga rombongan berkopiah putih yang bertampang khas keturunan Han (baca: Tionghoa), dengan kulit yang lebih kuning dan mata yang jelas sipitnya. Sejauh ini, bahkan sampai di tikungan terakhir menjelang ke masjid, tak terdengar suara takbiran. Bahkan hingga di gerbang dan halaman Masjid Xiao Tao Yuan, tetap sepi dari "Allahu akbar, Allahu akbar . . . " -- orang hanya ramai, beriringan masuk, serta bersalam-salaman. Assalamualaikum, saya ucapkan kepada seseorang yang di dadanya tertempel tanda panitia penyelenggara (seperti di tanah air, di sini Lebaran juga ada panitianya, rupanya). Waalaikumussalam, jawab lebih dari satu orang dengan serentak dan ramah. Maka, hilanglah rasa canggung yang saya derita sejak melangkahi gerbang masjid. Terasa sekarang, perasaan seagama ternyata bisa menembus batas politis dan ras. Di Shanghai, kota bandar dengan penduduk hampir 12 juta jiwa, menurut Al Haji Mahmud Ahad, "Ada 40-an ribu umat Islam." Al Haji Mahmud Ahad, Tionghoa asli, mengaku tidak memiliki nama Cina. Dia sekretaris dewan pengurus Masjid Xiao Tao Yuan. Kegembiraan beribadat kini tampaknya tak terlepas dari suasana dan kebijaksanaan baru yang dilancarkan Deng Xiaoping. Seiring dengan dibukanya pintu RRC untuk masuknya modal asing, tempat-tempat peribadatan Katolik, Protestan, Budha, dan Islam dihidupkan kembali, dipugar. Di masa sebelumnya, terutama sepanjang Wenhua Geming atau Revolusi Kebudayaan -- 1966-1976 -- tak ada ampun bagi umat beragama yang sering mendapatkan tuduhan sebagai antek imperialisme dan mata-mata musuh (entah siapa). Dalam buku A Documentary History, Religious Policy and Practice in Communist China, misalnya, bisa dilihat kembali poster-poster yang tersebar di Beijin pada musim uur 1966. Poster yang menyerukan pengganyangan terhadap kebiasaan dan segala tata upacara Islam. Misalnya, sebuah poster berbunyi: "Tutup semua masjid, kacaubalaukan segala asosiasi keagamaan, jegal penelaahan Quran, hilangkan tuntunan perkawinan berdasarkan kepercayaan, dan lenyapkan tradisi bersunat." Lebih dari itu, ada program yang lebih terencana untuk: "Dengan segera menghapuskan semua jenis organisasi Islam dan mengharuskan para ustad dikirim ke barak-barak kerja paksa .... " Waktu itu, di Xiao Tao Yuan -- seperti juga di masjid-masjid atau pusat pertemuan umat Islam lainnya -- jangan lagi kegembiraan Idulfitri, "Salat berjamaah saja tidak pernah ada," kata Jiang, seorang umat di situ yang pada 9 Juni lalu ikut menjadi makmum. "Selama Revolusi Kebudayaan, kami secara sembunyi-sembunyi bersembahyang sendiri di rumah." Atau, seperti kata Zhang Chiceng, pejabat hubungan masyarakat Asosiasi Islam Shanghai, kepada wartawan TEMPO Seiichi Okawa yang tahun lalu juga ke RRC. "Sepanjang Revolusi Kebudayaan adalah masa yang celaka bagi kami. Hongweibing atau barisan Pengawal Merah membakari ratusan kitab suci Quran ...." Di masa itu hanya satu masjid, yaitu Dongsi di Beijing, yang boleh dibuka -- terutama karena untuk memenuhi kebutuhan para diplomat asing. Masjid tempat saya salat Ied dibangun pada 1343. Di pelataran dalam, di balik bangunan lama ini, pada 1917 didirikan masjid baru. Dan inilah yang sampai sekarang menjadi pusat peribadatan dan sembahyang berjamaah, di kawasan Xiao Tao Yuan. Sebuah bangunan yang ugahari, pada tanah seluas kurang dari seribu meter persegi, yang polos. Tak ada ornamen atau hiasan di dinding-dindingnya. Bahkan kaligrafi huruf Arab -- yang bisa dilihat di Masjid Niujie, Beijing, misalnya -- di sini pun tak ada. Di sisi kanan bangunan ada tempat berwudu yang menyambung ke ruang sekretariat. Halaman yang memisahkan bangunan lama dan yang baru kurang lebih berukuran 4 x 12 meter. Orang berkerumun di bagian dalam dan pelataran, tanpa melantunkan takbiran, seperti laiknya menjelang salat Ied -- juga tak ada suara beduk. Yang agak mengherankan, mayoritas kerumunan ini terdiri dari orang-orang berusia di atas 30 tahun. Anak muda dan remaja, serta wanita dan anak-anak, sedikit jumlahnya. Sosialisme dan kocokan peradaban di masa Revolusi Kebudayaan rupanya telah mengubah selera para generasi muda kepada agama. Waktu berjalan, dan kerumunan pun menjadi makin berdesakan. Terselip di antaranya tiga orang pelaut Indonesia yang bekerja pada kapal Hong Kong, yang hari itu kebetulan tengah bersandar di Shanghai. Tampak pula beberapa pria hitam berjubah panjang ini rombongan pemuda Nigeria. Selebihnya warga lokal. Dan pukul 9 lewat dua menit, Al Haji Mahmud Ahad mengisyaratkan kepada seorang panitia untuk mengumumkan bahwa salat Ied segera dimulai. Sebagian besar lelaki sudah berada di dalam masjid, membentuk saf-saf. Karena penuh, sebagiannya lagi naik ke lantai dua. Para wanita di sudut yang lain. Remaja dan anak-anak, lelaki dan perempuan -- tidak semuanya ikut bersembahyang, cuma berjejer menonton di sisi bangunan lama. Orang-orang Islam Shanghai ini mengaku mengikuti mazhab Hanafiah. Namun, bagi mereka masuk Islam, tak berarti harus menghilangkan segala akar tradisi. Menjelang salat Ied mulai, delapan kiai berjejer di pelataran menghadap ke arah masjid. Al Haji Mahmud Ahad, sebagai pengurus masjid, mendampingi mereka. Di tangan kiai yang berjejer itu masing-masing terselip tiga batang hio (dupa) warna hijau. Secara serempak mereka mengangguk-anggukkan hio sembari melantunkan takbiran "Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La illahailallahhu Allahhu akbar. Allahhu akbar walillahil hamd" dengan suara dan nada biasa. Para hadirin hanya menonton dan tidak harus menirukan bertakbiran. Sekitar lima menit kemudian, para kiai bergerak maju ke arah dalam masjid. Masing-masing meletakkan hio ke atas guci-guci yang terletak di beberapa sudut. Mereka lantas bergerak ke saf terdepan dan diam di situ. Menyusul kemudian seorang petugas panitia berkeliling ke semua ruangan dalam masjid, menyemprotkan wangi-wangian. Khotbah, seperti lazimnya, dilakukan sesudah salat. Dikumandangkan dalam bahasa, mau bahasa apalagi kalau bukan, Cina. Terselip dalam khotbah anjuran-anjuran untuk hidup dalam heping (kedamaian), duanjie (persatuan), dan huxiang bangzu (saling membantu) antara sesama Muslim, dan juga dengan kerabat senegeri yang non-Muslim. Kita ini sedang membangun, menuju ke kehidupan yang lebih baik, kata khatib -- eh, lalu saya teringat khotbah-khotbah di tanah air. Meskipun bau hio tersebar, ucapan dan lafal khatib dalam mengutip dan menyitir ayat-ayat Quran sangat fasih. Juga sewaktu imam membaca surat Ad Dhuha dan Al Ahad, sesudah Al Fatihah dalam dua rakaat salat, terdengar melantun dengan enak. Buat saya yang selalu membayangkan kelenteng bila tercium bau hio, pengalaman ini terasa aneh. Hidup di bawah pengawasan Zhonggong (singkatan Zhongguo Gongchandang alias Partai Komunis Cina) tak membuat para pemeluk ajaran Nabi Muhammad saw. tersebut jera untuk tetap menegakkan iman dan terus mengkaji Quran. Ada rupanya anak-anak muda yang, meskipun jumlahnya tak seberapa, sanggup melepaskan diri dari trauma politik dan cengkeraman sosialisme, lantas menekuni agama. Di Masjid Xiao Tao Yuan tujuh orang berusia antara 17 dan 24 tahun tekun menyerap ajaran-ajaran Islam dan belajar bahasa Arab. Pihak masjid membuka kursus ini tiga kali (dua jam) dalam seminggu. Satu di antaranya adalah Jin Hongwi, 24 tahun. Pemuda yang memiliki nama Islam Moosa ini selepas SMA tak masuk universitas. Ia malah mencemplungkan diri ke kehidupan prihatin, belajar banyak menahan diri di lingkungan keagamaan. Ia memang bercita-cita menjadi seorang imam. Dan wajahnya, menurut kesan saya, sungguh cerah. "Islam merupakan agama yang penuh kegembiraan," kata Moosa dengan lugas. Sering ia menyendiri di menara masjid, duduk berjam-jam membaca Quran. Kegembiraan, barangkali juga perasaan merdeka, telah merasuki orang-orang di Xiao Tao Yuan. Usai salat Ied, orang-orang berhamburan ke pelataran lagi. Bersalam-salaman, sebagian berpelukan dan berangkulan dan menyebar tawa -- sebuah adegan yang mirip dengan di lapangan bola, ketika seorang anggota kesebelasan baru saja mencetak gol ke gawang lawan. Tertawa-tawa, bicara-bicara, bla . . bla ... bla .... Tapi memang tak terdengar ada yang mengucapkan minal aidin wal faizin. Ucapan itu tampaknya memang khas Islam Indonesia. Toh, sejenak keramaian ini menghapuskan bau komunisme dan sosialisme. Patokan-patokan nilai yang telah menyelaputi tampang (terutama) generasi tua Cina, sehingga mereka nyaris kehilangan senyum dan selalu tampak waswas menghadapi orang asing, sejenak terlupakan. Ikhlas adalah suasana hati yang tercermin di wajah-wajah orang yang habis salat Ied ini. Semua tampak senang. Bagaimana di Beijing? Dua hari menjelang Lebaran tahun ini, saya ke Niujie (Jalan Lembu) -- daerah enclave kaum Muslimin di ibu kota RRC. Dari Tiananmen (Gerbang Kedamaian Abadi) di pusat kota menuju ke Niujie diperlukan waktu tak kurang dari enam menit dengan mobil. Niujie, jalan selebar enam meter memang yang kurang dari lima kilometer, kanan-kirinya adalah hunian pemeluk Islam. Para Muslimin dan Muslimat di sini mencapai 80% dari seluruh warga kampung. Seorang petugas masjid di situ tak bisa menyebutkan jumlah yang tepat berapa umat Islam di wilayahnya. Kira-kira 120 ribu orang, katanya. Qingzhengsi Niujie, begitu nama masjidnya, dari luar tak menampakkan atau tidak kelihatan sebagai masjid. Seluruh kompleks yang terletak di tanah sekitar 6.000 meter persegi ini berarsitektur Cina kuno. Dibangun pada 996, masjid Niujie diperbaiki pada 1442 dan 1696. Atapnya yang meliuk-liuk, dengan goresan warna-warna kuning dan hijau, serta pintunya yang merah menjadikan masjid ini bak sebuah kuil. Baru, setelah memasuki bangunan utama, tempat sembahyang berjamaah seluas 600 meter persegi, barulah tampak bahwa ini masjid yang sebenarnya mengagumkan. Warna merah memang masih mendominasi pilar-pilar, jeruji kayu yang menempel ke langit-langit, dan hiasan di atas pintu-pintunya. Tapi warna ini mengesankan bau Islam karena diperkaya dengan ornamen tradisional Cina yang didampingi stiliran-stiliran khas Arab. Ada kaligrafi huruf Arab berwarna kuning emas, lalu sentuhan-sentuhan biru dan putih, dengan gambar-gambar kitab dan rehal -- mengingatkan hiasan pada keramik-keramik di kawasan Timur Tengah. Sebuah perpaduan yang enak dipandang. Sejarah seni rupa Cina dan Timur Tengah timbal-balik. Seni rupa tradisi Persia, umpamanya, sangat dipengaruhi seni rupa tradisi Cina. Di masjid ini tampaknya terjadi arus balik dari Timur Tengah. Dua hari menjelang Lebaran, tak banyak kegiatan di Niujie. Selain Ustad Khalid, yang sudah lewat dari 70 tahun dan tak mengakui lagi punya nama Cina, beberapa staf membaca-baca di ruang sekretariat. Ada satu dua orang memintas, menuju tempat wudu di sisi kiri bangunan utama, menjelang salat lohor. Seorang wanita datang menyerahkan zakat berupa uang, diterima oleh Ustad Khalid. "Alhamdulillah," gumamnya, setelah menerima zakat yang memang dikumpulkan di masjid. "Orang-orang sudah sibuk di rumah masing-masing menyiapkan hari Idulfitri lusa." Karena mustahil saya di hari yang sama ada di dua tempat, Shanghai dan Beijing, baiklah kita tengok catatan wartawan TEMPO Seiichi Okawa, yang pada Idulfitri 1984 berada di Niujie. "Hari itu," tulis Okawa-san, yang bukan Muslim, "Orang menyemut di sepanjang Niujie. Suasana meriah, solah-olah mereka hendak ke pesta, bukan ke tempat peribadatan. Sambil berjalan, banyak yang ngobrol satu dengan lainnya. Sekelompok orang merubung sebuah kedai khusus yang menjual makanan-makanan yang halal -- bagi Muslimin. "Para lelaki masuk ke bangunan induk, sedangkan kaum wanita yang hari itu berpakaian rapat, lengkap dengan kerudung, dengan warna abu-abu dan hitam -- berada di bangunan belakang. Di antara bangunan induk dan tempat berkumpulnya umat wanita adalah halaman. Ribuan orang berdesakan di situ. "Upacara sembahyang Ied dimulai setelah Ma Shouting, 90 tahun wakil presiden Asosiasi Islam RRC, tiba. Haji Shi Kunbin, pejabat tertinggi di Qingzhengsi Niujie, mendampingi Ma Shouting. Delapan puluh orang siswa peserta pendidikan Quran -- bagian yang tak terpisahkan dari kegiatan sehari-hari Niujie -- berdiri berjajar menyambut kedua pemimpin tersebut. Dan, secara hampir berbareng, 80 pemuda itu mengucapkan, Assalamualaikum .... "Eh, ada kejadian menggelikan di kelompok wanita, yang kebanyakan tua-tua itu. Beberapa nenek serentak memarahi seorang gadis cantik, Yang Fengqing namanya, 20 tahun usianya. Gadis itu tidak bermukena atau berkerudung, tapi hanya mengenakan celana jin, blus merah, dan bertopi putih. Ia memang tidak ikut salat, dan karena itulah gadis yang sehari-hari bekerja sebagai buruh sebuah pabrik tersebut kena marah. Mengapa? Yang Fengqing, satu dari sekitar 2.500 orang keturunan Huizhu. Suku bangsa ini, terutama tersebar di belahan barat, sedikit di tengah dan utara RRC, sudah lama dikenal sebagai pemeluk Islam yang taat. Para orangtua biasanya mengharuskan anak-anak mereka memeluk Islam. Maka, Fengqing pun kena marah." Jadi, mengapa nona manis itu tak bermukena? "Ya, bagaimana, ya? Saya ke sini memang karena hanya ingin ikut bergabung dengan keramaian. Itu saja." Islamkah Nona? "Orangtua saya Islam, saya sendiri saya tidak tahu," jawabnya. Ya, mau bagaimana lagi. Orangtua boleh marah. Tapi dalam Undang-Undang Dasar RRC ada pasal yang menyebutkan bahwa "Rakyat tidak dipaksa mempercayai agama apa pun, serta tidak dipaksa tidak percaya kepada agama." Lantas ada tulisan, "Agama dan organisasi agama tidak menerima pengontrolan asing." Itulah pasalnya, sehingga orang semacam Yang Fengqing dan generasi muda lainnya yang acuh tak acuh pada kegiatan keagamaan mendapatkan perlindungan undang-undang. Tak ada guru atau bahkan orangtua sekalipun yang berhak menentukan kepercayaan anaknya. Dan Anda pasti sudah tahu sebabnya. Pemerintah Komunis tentu lebih suka jika generasi muda lebih beriman pada garis kebijaksanaan partai daripada agama. Tahun-tahun pertama sesudah Pembebasan (baca: Kemenangan Partai Komunis Cina atas Guomindang alias Partai Nasionalis yang kini bercokol di Taiwan) 1949 adalah masa bulan madu para pemimpin agama dan pemerintah. Tapi tak berlangsung lama. Para pemimpin agama kemudian kecewa terhadap sepak terjang pemerintah. Kritik itu muncul di pers. Ini terjadi sebelum periode Seratus Bunga Berkembang 1957, ketika Mao Zedong masih memberikan kesempatan kelompok kanan dan para intelektual menyuarakan kritik terhadap pemerintah. Kemudian, Mao mengubah sikapnya. Atau, kebijaksanaan Mao sebelumnya memang sebenarnya sebuah perangkap. Para pengkritik ia babat habis. Para intelektual dan pemimpin agama yang dianggap penganut garis kanan dikirim ke barak-barak kerja paksa. Klimaks terjadi pada 1966, dengan dicanangkannya Revolusi Kebudayaan. Para pengkritik akhirnya diam total, mati kutu. Pada Mei 1958, misalnya, setahun sesudah "Biarkan Seratus Bunga Berkembang" dicanangkan, organisasi Islam di Provinsi Honan bangkit. Sebab, para pemimpin mereka dipojokkan sebagai penganut garis kanan. Tekanan ini menyebabkan kaum Muslimin di situ merasa sah untuk mematahkan garis Partai. Di Honan, pemimpin-pemimpin Islam, yang rata-rata terdiri dari keturunan suku bangsa Hui atau Huizhu, mengorganisasikan sebuah pemberontakan dengan membangkitkan semangat kesukuan. Slogannya: "Bangsa Hui di seluruh pelosok bumi, bentuklah satu ikatan keluarga," dan, "Agama ada lebih dulu dibandingkan negara..." Tapi pemberontakan kaum agama ini memang kecil. Di negeri berpenduduk lebih dari 1 milyar jiwa ini, upaya itu hanya tampak berupa percikan kecil. Karenanya, kelompok agama mudah dilindas oleh kekuatan Partai. Dan kemudian tangan Partai pula yang akhirnya mengatur kelompok agama: ketua dan dewan pengurus dipilihkan dari tokoh yang bersedia meletakkan garis partai di atas ajaran agama. Adalah Burhan Shahidi. Ia, pada periode sebelum Revolusi Kebudayaan, menjabat presiden Asosiasi Islam RRC. Lembaga ini resmi berdiri pada 1953. Pada Kongres Nasional Ketiga Asosiasi Islam RRC, 1965, Burhan Shahidi dengan bersemangat berpidato panjang lebar mengenai posisi Islam di dalam negeri. "Partai Komunis Cina dan Pemerintahan Rakyat telah secara konsisten mendukung kebebasan beragama," demikian antara lain ia berkata. Lalu diuraikannya keberhasilan Institut Teologi Keislaman yang berdiri pada 1955, yang telah berhasil melahirkan imam-imam baru dan para ahli Islam. "Institut telah memberikan perhatian khusus dalam melahirkan penelaahan agama. Hingga para siswa dari seluruh negeri bisa menekuni Quran, hadis, fiqih, sejarah Islam, dan bahasa Qrab," katanya lagi. Akhirnya, ketua tertinggi umat Islam RRC ini menutup pidatonya dengan: "Umat Islam RRC akan seiring sejalan dengan Partai Komunis Cina dan Ketua Mao Zedong, ketua agung semua suku bangsa di Cina. Mereka akan ikut aktif membangun negara sesuai dengan garis sosialis." Dan setelah itu orang tak lagi tahu nasib Burhan Shahidi. Kebijaksanaan pemerintah RRC terhadap agama mirip orang bermain layang-layang: diulur, ditarik, diulur lagi, direngkuh. Juga terhadap kepercayaan-kepercayaan tradisional leluhur sendiri, seperti Taoisme, Konfusianisme, dan Budhisme. Pekan lalu, misalnya, pemerintah sudah mengeluarkan tuduhan bahwa anak-anak muda di Cina Selatan, terutama di Guangzhou, telah kena pengaruh orang Hong Kong. Akhirnya mereka mulai mempercayai takhayul, pergi ke kelenteng-kelenteng dan membakar pedupaan, tuduh pemerintah. Provokasi seperti itu, bagi sebagian orang, membuat politik pemerintah RRC kini (yang lebih memberi kebebasan buat kaum agama) menjadi tak berarti. Muhammad Rashid Yang Tang, wakil ketua Asosiasi Islam Guangzhou, umpamanya, sangat pesimistis. Kata lelaki yang sempat menunaikan haji pada 1982 ini, "Kaum muda kami sekarang sudah kurang berminat pada agama, meski orangtua mereka adalah pemeluk Islam yang baik." Di Guangzhou -- ibu kota Provinsi Guandong sendiri hanya tercatat sekitar lima ribu pemeluk Islam. Padahal, jumlah penduduknya hampir enam juta jiwa. Para Muslimin dan Muslimat di situ kebanyakan keturunan suku bangsa Hui (atau Huizhu), atau pedagang-pedagang yang datang dari daerah otonomi Provinsi Xinjiang -- kawasan hunian pemeluk Islam terbesar di Daratan Cina. Tapi, sebagaimana kaum minoritas di mana pun, selama masih ada kesempatan, mereka masih akan terus berupaya. "Kami sedang berusaha meningkatkan ekonomi organisasi, hingga cukup dana untuk melakukan dakwah di kalangan generasi muda," kata Haji Yang Tang itu. Sebuah rancangan telah siap: sebuah Islamic Service Center. Di situ segera dibangun masjid, hotel, dan restoran. Tentunya, bila kelonggaran di RRC tak dipersempit lagi, hari Idulfitri di sana akan lebih semarak. Dan karena tradisi sebagian masih melekat juga, Islam di Cina akan tampil dengan unik. Bau hio bersemarak, ketika iqamat diserukan, ini sekadar contoh. Dan siapa tahu, umpamanya, arak-arakan malam takbiran diiringi oleh liong yang berjoget meliuk-liuk -- liong yang Islam sudah tentu. Memang tak mudah, bagi sebuah bangsa yang telah mengenal peradaban tinggi pada 2.000 sebelum Masehi, untuk melupakan begitu saja adat istiadat lama. Dan begitulah misalnya para petani suku bangsa Uygur di Provinsi Xinjiang, yang mulai memeluk Islam pada akhir abad ke-10. Sebelumnya suku ini mengenal berbagai agama, Zoroaster dan Budha antaranya. Tapi kini boleh dikata suku ini hanya mengenal hari raya Kurban dan Idulfitri sebagai hari besar keagamaan mereka. Kurang jelas bagaimana akhirnya suku yang hidup di pegunungan ini akhirnya sama sekali Islam. Tapi sentuhan kebudayaan yang mereka alami, tampaknya, telah mempersiapkannya. Misalnya, pernah suatu kali dalam sejarah suku ini menggunakan bahasa Turki dan Arab sebagai bahasa pengantar sehari-hari, demikian disebutkan dalam majalah China Pictorial, nomor April tahun lalu. Orang Uygur adalah seniman tari dan nyanyi yang piawai. Lihat saja bila orang-orang muda Uygur berpesta. Dengan jubah oranye dan topi cokelat, dengan sekuntum bunga merah di telinga, seorang gadis dengan luwes mengikuti gerak-gerik si pemuda yang mengenakan celana hitam, jubah kuning muda, dan pici hitam. Dua penari itu tak saling menyentuh (dilarang bersentuhan lelaki dan wanita yang bukan muhrim). Dan penonton, lelaki mengenakan kopiah mirip yang dipakai orang-orang Timur Tengah, yang perempuan hampir semuanya memakai kerudung, siapa menyangsikan ini bukan masyarakat Islam?
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini