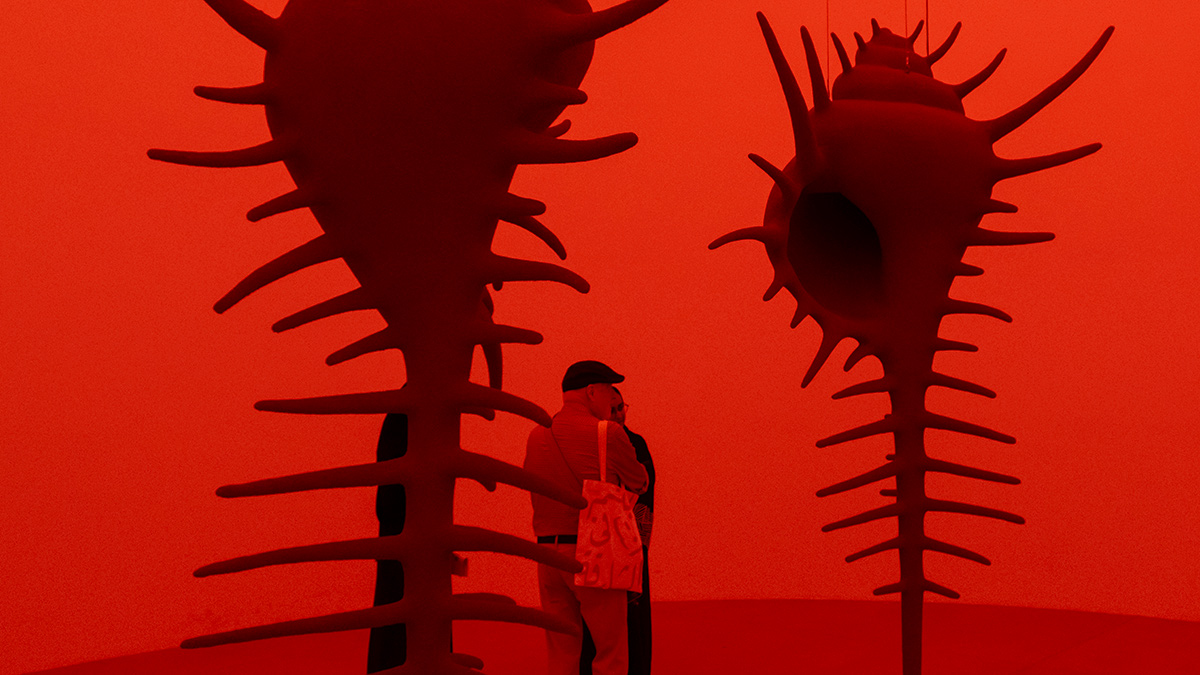Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Pahlawan bermula dengan menolak. Ia berangkat dari nilai. Karena itu, tak mudah sebenarnya memadankan kata "hero" dalam bahasa Inggris dengan "pahlawan" dalam bahasa Indonesia. Kini orang sering menyebut "hero" dengan sikap seringan membaca iklan film. Ketika John Wayne berkata "Orang sebaiknya jangan menonton bioskop jika ia tak percaya kepada hero", ia mencampuradukkan "pahlawan" dengan "jagoan".
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo