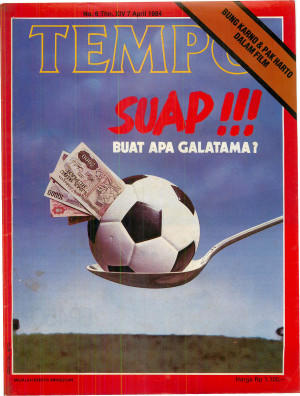ADA desa yang bernama Cacao (baca: Kakao). Ada pula Javouhey. Di mana? Nun jauh di sana, di lembah hutan rimba Amazon, wilayah Guyana, Amerika Selatan. Kedua desa itu baru lahir ke dunia enam tahun lalu, dan dibangun oleh 1.200 pelarian dari Suku Hmong. Hmong - juga disebut Hmung, Hmoong, Hmu, Miao, Meo - adalah sebuah kelompok etnis khas berasal dari Cina, dan di sana pula sebagian besar mereka tinggal. Sejumlah kecil berada di Vietnam Utara, Laos, dan Muangthai. Oleh orang luar mereka sering juga dianggap Cina, meski diketahui perbedaannya. Tahun 1977, Prancis, bekas tuan Indocina, memutuskan menempatkan kelompok yang terjepit perang itu di Guyana - dari Laos. Caranya hampir diam-diam, mengingat sikap permusuhan pribumi Guyana yang dikenal dengan xenophobie-nya alias kebencian kepada orang asing. Memang layak bila ada kekhawatiran pada penduduk setempat yang mungkin bakal menghadapi daya kerja luar biasa dari para pendatang yang akan mendesak berbagai kebiasaan lokal. Wartawan khusus Paris Match, Jean Francis Held, mengunjungi Desa Cacao itu November lalu. Dan ia menyatakan kagum akan banyaknya kerja membuka hutan liar oleh orang-orang gunung dari Asia itu. Di tanah berhektar-hektar hasil penaklukan hutan lebat, mereka menanam sayuran, beras, dan selada. Berkat merekalah pasar Kota Cayenne berlimpah dengan hasil bumi yang masih segar. Dihitung-hitung, tindakan Prancis itu merupakan percobaan yang berani dalam hal menempatkan penduduk di tanah asing yang bukan main jauh. * * * Orang "metro" (kota) di Guyana adalah orang Prancis. Seorang gadis putih sambil lalu mengelus anak kecil bermata sipit, manis sekali. Anak itu lari menyelinap di antara tiang-tiang rumah kayu, memandang ke arah rimbunan daun pisang. T-shirt-nya jatuh sampai ke pangkal paha. Di bawahnya ia tak mengenakan apa-apa lagi selain celana dalam berwarna hitam. Dua perempuan tua Hmong, yang berhari Minggu dengan tunik warna gelap dan kerpus berjambul besar merah ungu di kepala, lewat tanpa memperhatikan. Tetapi sebenarnya mereka melihat .... Pada hari Minggu yang lain, orang-orang Hmong menangkap seorang Prancis yang sedang merayu pacarnya sendiri. Dalam kebiasaan orang-orang gunung dari Laos itu, laki-laki dan wanita memang tidak dibolehkan bahkan bergandengan di muka umum .... Seorang Hmong dipotret terus-menerus tanpa sapaan. Dengan lagak tak peduli, ia pun pergi mengambil Minolta-nya sendiri. Lalu membalas si pemotret dengan jepretan demi jepretan. * * * Sepekan penuh Cacao bekerja. Hari Minggu adalah kesemrawutan. Pejabat dan pegawai Cayenne, militer yang lagi prei, singkatnya orang-orang putih dari pantai yang pada merasa bosan, naik ke Cacao bersama keluarga, menghirup udara. Dan orang Hmong tahu apa yang mesti dilakukan. Di tanah yang lapang, di keteduhan pohon-pohonan, para wanita dan gadis kecil berdagang baju-baju yang sama dengan yang mereka jahit di Laos dulu. Bayi-bayi berpipi gembil tidur di tengah tumpukan terong, pisang-pisang, kaleng-kaleng gula, mangkuk-mangkuk sup. "Saya merasa seolah berada kembali di Muangthai, bukan di salah satu perkemahan besar yang menakutkan di dekat perbatasan, tetapi di Fakh-Ta misalnya. Di sana para pengungsi dengan cerdik membangun kembali desa mereka, tempat bunga-bungaan tropis berkembang di depan rumah-rumah kayu jati," demikian Jean mengenang. Dari Cayenne ke Cacao, 70 km jalur indah di tengah hutan lebat. Dari atas bukit-bukit, orang bisa melihat kehijauan sampai ke ufuk. Papan-papan lebar berwarna biru berkilau mengerjap di senja hari. Ada bekas sebuah tambang emas. Cacao, tempat terkutuk seabad yang lalu: budak-budak, para penderita penyakit lepra, para kanibal, sebuah penjara kuno. Di depan pasar di Kota Cayenne ada sebuah bukit, dan di atasnya sebuah restoran milik orang Prancis, Pierrot, dan istrinya, Lao. Gila sibuknya. Begitu pula di restoran Lau Phai Neng, yang terasnya menghadap ke "teluk". Juga di "Chez Daniel et By". Kalau tidak datang awal tak akan kebagian meja. Lebih dari seratus mobil terpanggang matahari di jalan besar. Bayi-bayi putih, bayi-bayi kuning, merangkak dengan enak di antara anjing-anjing di teras yang kotor. Dan tepat di belakang restoran adalah 3.000 km hutan rimba. Sampai ke Rio! * * * Beberapa gadis Hmong dari Cacao sudah menikah dengan orang "metro" - dan beruntung mempunyai majikan baru yang kurang kejam dan kurang mekanis dibanding majikan di negeri mereka yang dulu. Sebaliknya, orang-orang putih ini merasa senang oleh ketekunan kerja dan kepatuhan istri-istri Asia ini. Mulanya, kata Daniel, ia mempunyai masalah dalam kerja sama dengan Hmong itu dalam mengurus restoran. "Orang Hmong individualis keluarga. Ada pertengkaran ...." Tapi itu hanya mulanya. Daniel sendiri dulunya ahli perkebunan di Nantua. Ia mengajarkan bahasa Prancis di Cacao, lalu jadi agen pos, lalu ... ia berbahasa Hmong. "Di sini," kata Daniel, "orang Hmong sering meneruskan kebiasaan mempunyai beberapa istri. Hal ini tak mengganggu di Guyana, karena orang Creol sendiri bukan bangsa monogam. Dengan segala cara mereka memikat wanita. Orang-orang tua mula-mula tidak menyukai perkawinan antarbangsa. Sebabnya, di Laos dulu tentara Prancis kawin hanya untuk sementara! Ya, ada masalah kecil. Saya, misalnya, ketika melihat istri saya, By, mengisi kantung-kantung besar dengan beras, saya cenderung membantunya. Tapi yang seperti itu tak pantas dilihat, katanya." Tak jauh dari "Chez Daniel et By", sebuah jalan mendaki bukit kecil yang lain. Ia menyusur ke kedai rempah-rempah dan ke gereja yang indah. Stop! Sebuah rantai berpemberat pada panil menunjukkan tanda larangan. Di atas bukit, mendominasi Desa Cacao dengan keagungan yang menekan, berdiri pasturan Pater Charrier, bapak orang Hmong, lebih besar dan lebih bagus dari rumah-rumah yang lain. Orang Hmong membangunnya dengan tangan mereka sejak awal kedatangan. Kemewahan pasturan ini bukan kebetulan. Di sini orang bicara tentang "puri" itu dengan suatu ironi yang kadang-kadang pemaaf, kadang-kadang putus asa. * * * Memang sebuah pengalaman yang menakjubkan, perpindahan orang-orang Hmong itu - 700 di Cacao dan 600 di Javouhey. Nasib yang berbeda dari nasib orang-orang kuning kecil yang meninggalkan Negeri Cina pada abad XIX. Migrasi yang panjang telah membawa mereka ke Vietnam Utara, lalu ke Muangthai, lalu ke pegunungan di Laos. Di Laos, orang-orang gunung seminomad itu membantu Prancis melawan Cina asli, Jepang, dan Viet-Minh. Tangan pendendam Hanoi itu berat: yang paling "membekas", orang Hmong dipaksanya menyeberangi pegunungan dan Sungai Mekong. Mereka dibombardir, dimitraliur, dibom napalm, dan - seperti dikatakan Pendeta Charrier yang mahakuasa itu - sumber-sumber air mereka diracuni. Tak terhitung lagi gas beracun yang digunakan melawan para pelarian ini. Sekarang mereka itu tersebar: tiga juta di Cina sendiri, 400.000 di Vietnam, 300.000 di Laos, 100.000 di Muangthai, 85.000 di antaranya hidup di tenda-tenda, dan akhirnya yang 1.300 di Guyana ini. Tapi rupanya orang Prancis Indocina tak melupakan teman-teman atau "kaki tangan" mereka itu. Hanya niat baik yang sering bertentangan membalik bumi dan langit - dan menggerakkan pengembaraan ke Guyana. Pengembaraan, akhirnya. Toh di Guyana mereka bukan satu-satunya orang asing. Bagi beberapa juta orang Indian bercawat merah di desa-desa sepanjang Sungai Maroni, semua orang Guyana adalah pendatang: orang-orang Creol keturunan budak, suku-suku bangsa budak lainnya, sisa zaman dulu yang sampai sekarang hidup lebih jauh di dalam hutan, para pelarian dari penjara, gelombang imigran lain yang datang dengan persetujuan, paksaan atau janji muluk yang kosong, orang-orang Cina yang mengendalikan perekonomian, orang-orang Jawa, orang Brazil, orang Libanon, orang Antilles, orang Haiti .... Daftarnya masih panjang. Sesudah perang, juga datang orang Eropa Timur yang melakukan desersi. Hanya, mereka semua kembali pulang, kecuali dua orang. Yang pertama menjadi pilot pesawat kecil, dan lainnya mengusahakan sebuah restoran khas Creol. Orang Hmong masuk ke sana seperti rambut nyemplung ke dalam adukan sup manusia yang terburuk, dengan kemauan luar biasa untuk tinggal. Di tanah milik Prancis yang mustahil ini, yang lebih besar dari Belgia dan 90% tertutup rimba raya tak tertembus, 700 penduduk baru di Cacao dan 560 di Javouhey tinggal jauh masuk ke dalam hutan. Sedangkan 70.000 "orang Guyana" hanya sudi menempati daerah sepanjang pantai. Kehadiran yang sangat menyehatkan, sebenarnya. Tetapi orang tropis "asli", yang malas tanpa guna, memancing rasa putus asa dan kebencian. Penyuntikan orang-orang Asia ke Amazon ini sebenarnya sebuah ide lama. Pierre Dupon-Gonin, pejabat tinggi pencinta Laos dan Guyana, mewujudkannya dengan meyakinkan pejabat lain yang bernama Sainteny, lalu Giscard d'Estaing. Tetapi Guyana bukan tanah kosong, di samping penuh dengan celah-celah dan kemungkinan. Mula-mula orang-orang Hmong yang malang diusir orang Guyana, dituduh sebagai paranoiak yang kejam: "Mereka itu penyerbu, pemadat, yang dikirim untuk merusakkan anak-anak muda kita, merusakkan identitas (sic) Creol!" Guy Lamaze, pemikir independen yang sangat baik dan seorang Creol campuran, pun merasa terganggu: "Saya bukan seorang rasialis, pasti. Identitas kami adalah campuran. Ayah saya Cina, istri saya metro. Jadi anak saya hitam, kuning, dan putih. Tetapi akar kami adalah Creol! Jika saya mencemplungkan tangan dalam kekusutan...." Lamaze tak pernah menjejakkan kakinya di Cacao. Ia takut ada yang memotretnya sedang bersama orang Hmong. Ini merugikan! Golongan independen hanya merupakan 9% penduduk. George Othily, Ketua Dewan Penasihat Daerah dan pemimpin Partai Sosialis, bahkan lebih serius: "Oke, saya juga campuran. Tetapi lebih dari 20.000 orang "asing" (sic) di sini sudah terlalu banyak! Guyana harus mengontrol migrasinya. Orang-orang Hmong itu dibantu, dimanja. Dan kami, kami tidak terbelakang, barangkali?" 7 September 1977, rombongan pertama orang Hmong turun di lapangan udara ochambeau setelah perjalanan sejauh 20.000 km yang melelahkan, dengan pengawalan. Orang-orang fanatik mengayun-ayunkan papan bertuliskan: Meos dero, "Meo keluar", dalam bahasa Creol. Orang Vietnam dulu memang menamakan orang gunung itu "Meo". Dan esok harinya televisi menyiarkan liputan yang menyayat hati. Diiringi musik Albinoni, pemirsa melihat para pengungsi yang ketakutan, mati karena letih, menuruni titian menggandeng anak-anak mereka, membawa buntalan lusuh. Lalu keluarga-keluarga itu akhirnya menemukan Cacao. Di sana, selama berminggu-minggu, bisa dilihat pemandangan yang pilu. Laki-laki menebang pohon. Istri mereka memotong-motong. Anak-anak membabat semak. Gadis-gadis kecil sekali menggendong bayi-bayi ke tempat mereka yang sedang bekerja, agar ibu-ibu bisa menyusui. Mereka mengumpulkan besi tua. Membuat peniup tungku dari bambu yang ditempa buku-bukunya. Gereja, candi, balai pengobatan, sekolah, rumah panggung seperti di Laos - dan, tentu saja, "puri" Pendeta Charrier yang tegak di tanah bekas hutan. Puluhan hektar digarap. Orang gunung itu masing-masing menerima 40 franc sehari selama dua tahun, kemudian naik menjadi 50 franc. Tetapi, ternyata, tiap orang cuma membelanjakan 3 franc. Sisanya diinvestasikan dalam bentuk bahan bangunan, alat-alat menebang pohon atau alat pertanian. Ada saat-saat bahagia, misalnya pada hari Arhmong, ketika orang Creol datang berbondong-bondong ke Cacao. Dan orang-orang gunung itu, dengan tunik berwarna mereka, mencoba menari. * * * "Beberapa jam saya lewatkan bersama Ly-Foung di Javouhey. Ia tampak bersih. Tampang lucu dengan celana pendek dan sepeda, bekas buruh di Paris yang meninggalkan tujuh anaknya sebelum dikirim ke Cacao sebagai instruktur pertanian." Ly-Foung berwatak keras. Dengan Pendeta Bertrais akan bisa bentrok. Rasa kesal terbesar Ly-Foung, agak bertentangan, adalah karena sang pendeta ingin orang Hmong tetap menjadi orang Hmong. Integrasi dan asimilasi "yang merusakkan" itu mesti dibatasi. Bukan dihilangkan. "Kami ini orang-orang yang bangga, dan bukan orang gampangan," kata Ly-Foung. "Di Laos, pendeta bermain yoyo dengan 300 muridnya. Itu ramah, dan murah hati. Murid-murid belajar bahasa Prancis. Tiga ratus ribu orang tanpa masalah! Tetapi di sini, mereka ingin kami hidup di bawah lonceng, jadi harus menyesuaikan diri di bawah hukuman mati. Prancis bisa mengerti, tapi pendeta-pendeta itu tidak." Suster-suster di sekolah-sekolah Cacao menyuruh murid-murid menggunakan nama Kristen. Pater Charrier ingin membuka sekolah tinggi di Cacao, agar anak-anak muda tidak berlompatan ke kota, ke Cayenne. Charrier menentang penggunaan buldozer - ia memilih alat-alat kuno. Ia juga memberi penalaran kepada orang-orang tua yang melarang anak-anak berbicara Prancis di rumah. Dan anak-anak Cacao suatu kali gagal membuat keributan, yang disebabkan oleh Pendeta Charrier yang tak mau segera menjalankan sebuah alat bermotor. Anak-anak lain menyewa alat penangkap kupu, menangkapi kupu-kupu yang indah lalu menjualnya kepada turis. Uangnya untuk membeli sepeda balap. Di samping itu sudah banyak gadis-ibu di Cacao, yang hamil tanpa suami. Ada perkawinan campuran. Orang-orang minum kopi susu untuk sarapan. Singkatnya, sebuah dunia lenyap - dan yang baru muncul berada dalam kekhawatiran dan guncangan. Toh sifat-sifat turun-temurun orang Hmong, keras hati dan tahan menderita, tampak juga dalam tindakan. Walau daerah di Cacao sulit, para imigran ini membuka 600 hektar dengan bersemangat, dan belajar cara-cara bertanam-tanaman jenis baru, jauh berbeda dari opium dan padi gunung di negeri mereka. Tahun berikutnya ulat-ulat yang rakus menyerbu perkampungan. Semua orang memberantasnya, juga anak-anak sekolah. Tiga puluhan ribu parasit itu dipunguti hanya dengan tangan. Terpisah, terasing pada hari Minggu, orang metro mana pun akan merasa rugi. Tapi Hmong tidak. Seluruh keluarga bekerja, masing-masing pada tugasnya. Nenek-nenek mengasuh cucu. Orang muda pagi-pagi sekali berangkat ke pasar Cayenne dan Saint-Lourent Maroni, dengan Toyota mereka atau dengan sepeda motor yang ditumpangi peti besar kayu. Mereka menjualnya dalam jumlah besar ataupun kecil. Dan dibayar kontan. Inilah yang mereka maui, yang mereka pahami: uang, dengan cepat. Sistem koperasi, yang dipimpin Pater Bertrais dengan gaya tiran, membuat mereka khawatir - teringat "zone baru ekonomi" gaya Vietnam. Susah. Petani selalu curiga, di mana-mana. Orang-orang Hmong adalah nomad. Mereka seperti di rumah sendiri di mana pun berada, asal masih tetap di tengah sesama Hmong, asal masih cukup banyak orang Hmong, asal sistem klan mereka yang kaku itu masih bisa diusut. Di negeri mereka yang lama, untuk sebuah ya atau sebuah tidak satu keluarga yang kehilangan muka akan berpindah rumah, berpindah gunung. Atau kembali bergabung dengan orang-orang kuat dari klannya, yaitu mereka yang sukses. "Lihat orang Klan Yan dan Klan Ly membangun pasar di dekat pasar yang pertama karena ada perselisihan dengan klan-klan lain," kata Ly-Foung. "Di sini tidak ada cukup banyak klan. Anda bisa saja memberi kami Istana Versailles yang terbuat dari emas, tetapi akan segera ditinggalkan jika tak ada orang Hmong lain. Begitu kami hidup." Mereka datang, mereka pergi, menyusup ke Amerika Serikat, Australia, ke semua wilayah tempat orang Hmong telah melabuhkan jangkar fatamorgananya. Tetapi fatamorgana yang paling jelas adalah Prancis metro. "Wah, lutut saya sakit, saya tak bisa lagi bekerja disini ...." Atau: "Ada paman istri saya di Dreux, di Mont-de-Marsan, di Cachan ...." Dan keluarga itu pun terbang, tanpa menoleh sedikit pun ke Cacao. Sekali saja rapuh, orang Hmong cepat menjadi kecil hati akibat kegagalan, dan angin migrasi tiba-tiba mengangkat mereka seperti bulu. Marakuja, buah yang sangat diharapkan dan yang ditanam tiap orang, susah dijual tahun ini? Nah, orang pun pergi. Kekhawatiran kehilangan muka memperkuat fatamorgana ini. Di kota metropolitan, hidup keras. Sebuah keluarga besar berjubel di dalam tiga kamar yang tak patut. Dingin menggigil. Potongan daging ayam untuk pesta. Mengerikan. Tetapi bila orang Hmong dalam perjalanan, ia akan mengirim kartu bergambar taman Luxemburg yang indah, atau kaset yang didengarkan di tempat umum, mandi dalam minyak pada hari peringatan yang paling sok, "mengejek: saya punya mobil dan sepatu bersemir hitam... saya tak lagi berbaring mandi matahari .... " Sudah ada empat puluhan anak muda Hmong belajar sampai ke sekolah menengah, yang merupakan kunci segalanya. Dua pemuda berumur 18 tahun, Ly Pao dan Pierre Van Toua, adalah murid kelas dua di SLA Cayenne. "Saya ingin berwiraswasta," kata Ly Pao. Pierre akan jadi dokter. "Akan ada pekerjaan untuk kami di Cacao, mengobati orang, mengurus perusahaan. Anda tahu, peternakan udang air tawar sudah digalakkan? Kami akan menetap masa depan kami ada di sini." Kolam-kolam udang yang dikatakannya itu memang luas, dan sebagian sudah diusahakan. Kerja besar-besaran: pompa-pompa, galangan-galangan yang membelokkan aliran air sungai. Semua itu dibiayai dengan pinjaman yang merupakan bantuan untuk pembangunan. Orang Hmong membayar bunga dengan beban batin. Di samping itu ada sawah-sawah yang segera siap berproduksi. Orang Hmong ini hebat tak tertanggungkan. Yang disukai adalah kerja keras, asal mereka tahu untuk apa dan untuk siapa mengadakan pesta menyembelih kerbau - dengan teman-teman satu klan pergi menempuh perjalanan jauh. Tetapi teman-teman terbaik mereka mengeluh: orang Hmong penuh curiga. Mereka sedikit bicara. Untuk mereka, uang yang masuk selalu baik, yang keluar buruk. Aneh. Mereka cepat belajar main sulap dengan uang subsidi masa percobaan minta dibayar penuh, ditambah keuntungan. Mereka berbudaya, dalam beberapa hal. "Orang-orang bakhil!" kata Dokter Ho A Chuck, pura-pura marah. "Tetapi punya keberanian hebat!" Jarang ada rumah yang tak punya kulkas modern magnetophone untuk kaset televisi berwarna, dan magneccope. Seorang Hmong bisa punya simpanan di bank, juga celengan tradisional sebagai cadangan masa sulit. Toh mereka perlu tampak seakan-akan tak punya uang, walaupun perniagaan lagi baik. Bawang putih, misalnya, di pasar harganya 40 franc per kilo, dan selada 30 franc. Seorang petani yang baik dengan mudah bisa menghsilkan 100 kilo dalam seminggu. Tapi dalam kertas laporan penghasilan, orang Hmong menuliskan: nol. Dan jika seorang penduduk desa tiba-tiba berimigrasi bersama keluarga, ia merasa berhak menjual rumahnya seharga 20.000 franc - rumah yang secara legal bukan pemiliknya. "Toh," kata seorang ibu guru, "cukup dengan sikap yang tepat, dengan munjukkan perhatian yang sungguh-sungguh, seorang Hmong yang tertutup seperti tiram pun akan membukakan hatinya kepada Anda dengan caranya sendiri." * * * Semua yang dikonsumsikan di Guyana diimpor dari negeri lain, kecuali 10%. Tanpa orang Hmong, Cayenne tak akan makan selada. Negeri orang miskin ini kekurangan tenaga kerja. Sebuah tempat pengawetan buah tanaman sebangsa palm baru saja ditutup - tak ada pekerja. Ada penggergajian ultramodern yang dibeli dengan uang subsidi, dijual kembali ke luar negeri. Ada nanas yang ditanam dan segera dicabut kembali. Ada mesin berkarat yang dicat lagi sebagai ganti rugi. Baik, itu keterbelakangan dan akibat buruk kolonialisme, yang lama menggenggam Guyana untuk kemudian mencampakkannya. Begitu besar iri hati pada orang-orang Hmong yang hidup dengan tangannya sendiri. Di sana mungkin titik lemahnya. Walaupun kejutan indah di Guyana bisa ditimbulkan oleh orang Hmong, orang Guyana tak bisa mengerti - demi kepentingan politik - adanya usaha pendirian desa ketiga di suatu tempat di hutan itu. "Harus meminta izin kepada kami dengan berlutut," kata Dokter Ho A Chuck. "Masalah Hmong" sendiri merupakan hal tabu dalam Dewan Daerah, walau getarnya tetap hidup. Padahal, jika orang Hmong tidak segera berjumlah lima atau enam juta, ada risiko mereka akan kabur. Padahal, Prancis mengharapkan mereka berhasil. Cacao dan Javouhey, paling tidak, akan merupakan catatan yang jelas dalam sebuah dunia yang lain.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini