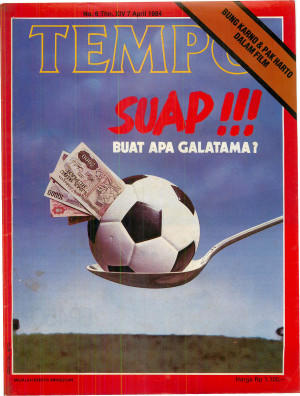SAYA menonton Gandhi di sebuah gedung bioskop mewah di kawasan Shibuya, Tokyo, sesudah makan siang dengan baby steak, french fries dan milk shake. Seperti pada pertunjukan matinee di mana-mana, juga siang itu gedung itu dipadati oleh muda-mudi. Hal yang mencolok pada penampilan muda-mudi Jepang masa kini adalah kesan mewah dan chic pakaian mereka. Hampir-hampir tidak ada yang tampak kumal, kedodoran dan seenaknya berpakaian - suatu pemandangan yang biasa kita lihat pada muda-mudi di kota-kota metropolis Amerika Serikat atau Eropa Barat. Melihat Gandhi dalam suasana dan latar begitu jadinya terasa aneh betul. Dicekam oleh keberanian, kegigihan, dan kekepalabatuan Gandhi menghayati dan menjalani kesederhanaan dan keprihatinan selama hidupnya, sepanjang film yang indah itu saya bertanya dalam hati akan relevansi film semacam ini buat penonton film di dalam gedung di Shibuya. Penonton yang hidup di tengah kelimpahruahan kemewahan, dan kenyamanan ada dalam jangkauan tangan serta dompet! Richard Attenborough, sutradara film itu, menggambarkan Gandhi sebagai seorang yang penuh kepercayaan, bahkan nyaris fanatik, akan harga diri manusia sebagai pilihan yang paling utama dan mendasar dalam hdup. Kegusaran Gandhi terhadap diskriminasi ras di Afrika Selatan penjajahan Inggris di India, bahkan purbasangka kasta serta sentimen agama dalam masyarakat yang dicintainya, digambarkan dengan jelas dalam Gandhi sebagai benang merah. Tapi kegusaran itu bukanlah kegusaran seorang panglima perang yang mengayun-ayunkan pedangnya siap membabat musuh-musuhnya. Ia gusar dan muak melihat berbagai distorsi wajah kemanusiaan yang diciptakan oleh manusia sendiri, tapi ia sekaligus percaya bahwa distorsi itu hanya bisa dihilangkan lewat perjuangan tanpa kekerasan, perlawanan damai dari satyagraha, yang secara harfiah berarti kekuatan kesetiaan atau kekuatan cinta. Kekerdilan manusia untuk mampu dan tega membuat distorsi yang demikian mengerikan dilawannya dengan mengajak bangsanya untuk mau menggali dalam-dalam esensi yang paling dasar dari budaya dan budi daya manusia lewat berbagai metafora. Menenun baju sendiri, menambang garam sendiri, berpuasa, naik kereta api di gerbong kelas III, berjalan kaki, sayang dan akrab dengan pemeluk agama lain, hidup dengan kenyamanan yang paling minim. Maka, alangkah tampak asing metafora pilihan Gandhi itu muncul dalam gedung bioskop Shibuya indikator dari masyarakat industri maju yang sukses yang disebut Jepang itu. Bagaimana tidak. Di deretan kursi penonton itu anak-anak muda, yang dengan bangga pada memakai baju newah dan chic, dengan merk-merk impor dari Italia dan Prancis - tidak lagi berkimono. Mereka dihadapkan pada dhoti dari khadi, baju tenunan sendiri dari lawon putih. Di depan itu anak-anak muda Tokyo yang baru mulai suka bertualang dengan makanan asing (lebih dari orangtua mereka yang hanya suka ikan) seperti hamburger, spaghetti bahkan juga chicken tandoori a la India Utara. Mereka disuguhi keprihatinan puasa yang nyaris tanpa istirahat. Dan akhirnya di depan itu anak-anak muda yang sudah biasa naik kereta-api peluru yang mewah dan nyaris tak terasa bergerak karena kecepatannya melebihi suara. Mereka dihadapkan pada kereta api gaya kuno yang berjalan alon-alon dengan wagon kelas III yang terdiri dari bangku-bangku kayu yang keras. Tentu saya, baju chic, hamburger dan kereta api peluru adalah metafora juga. Lambang pernyataan kreatif dari suatu masyarakat "hewan ekonomi" modern. Bagi mereka, lambang itu adalah pernyataan kemenangan yang mereka capai lewat berbagai pertempuran seru. Pertempuran antara berbagai vested interests para shogun, kemenangan mutlak dari shogun Ieyasu Tokugawa, Restorasi Meiji dan akhirnya modernisasi Jepang. Juga pertempuran mereka yang lebih berat sesudah Perang Pasifik, yakni mengalahkan kepahitan kekalahan mereka oleh Sekutu. Barangkali keanehan atau keasingan metafora Gandhi adalah kehadirannya pada perspektif waktu yang berlainan dengan khalayak Jepang. Metafora Gandhi adalah metafora suatu masyarakat yang penuh dengan kesenjangan sosial dan budaya, dan berada pula dalam suatu kesenjangan kurun masa. Maka, "metode" perjuangan Gandhi yang satyagraha dan dilaksanakan dengan penuh keprihatinan adalah metode suatu mula perjuangan. Strategi yang dipilihnya bukan strategi kasta ksatria, bahkan bukan kastanya sendiri, vaisya, melainkan, agaknya, gabungan antara unsur kasta brahman dan kasta harijan. Yakni strategi kasta yang mengagungkan keprihatinan sebagai ideal keindahan dan sekaligus strategi kasta yang tak terjamah, harijan, yang melihat keprihatinan sebagai kenyataan nasib yang mesti dijalani. Dengan demikian, lambang-lambang pilihan Gandhi adalah penanaman benih, investasi, bagi suatu ladang yang mahaluas yang pada satu waktu, kelak, dapat menghasilkan panen besar. Sedangkan metafora Jepang kini adalah metafora suatu tahap akhir perjuangan. Metafora suatu panenan besar dari suatu perjuangan yang dilaksanakan dengan strategi bushido, jalannya para prajurit, the way of the warrior, kasta ksatria yang melihat keprihatinan sebagai keindahan peperangan. Keduanya memang menerima keprihatinan sebagai unsur utama dalam perjuangan. Tetapi cara Gandhi dan orang Jepang meletakkan makna kualitas keprihatinan agaknya memang berlainan. Keduanya melihat keprihatinan sebagai suatu keindahan, tetapi keduanya meletakkan kaitan keindahan itu dalam tempat yang berbeda pula. Pada Gandhi agaknya keindahan penderitaan keprihatinan itu dikaitkan dengan kasih sayang, sedangkan pada orang Jepang pada kepuasan kemenangan. Maka, apabila pada tahap akhir perjuangan keprihatinan bushidoitu sekarang (sudah) menghasilkan suatu "kemenangan kebendaan," mungkin sekali kemenangan tahap akhir yang dibayangkan Gandhi akan tercapai kelak adalah "kemenangan spiritual". Yang menjadi pertanyaan ialah: apakah muda-mudi Jepang yang serba berlimpah milik kebendaannya itu masih memahami makna keprihatinan bushido dari nenek moyang mereka. Dan dalam menyaksikan Gandhi, suatu perjalanan mental apa yang berkecamuk dalam dirinya .... Di New Garden Hall, Jakarta, saya sekali lagi menonton Gandhi rame-rame bersama anak istri serta sanak keluarga lain. Perjalanan menonton Gandhi itu jelas merupakan suatu perjalanan kemewahan, bila diingat akan harga karcis yang Rp 4.000 sehelainya itu. Juga di sini pertanyaan tentang arti Gandhi bagi khalayak menjadi relevan. Sepintas apa yang terlihat dalam New Garden Hall tidak banyak berbeda dengan gedung bioskop di Shibuya. Muda-mudi yang keren dengan baju kaus Elesee dan Lacoste, serta kawasan tempat gedung bioskop itu berada, adalah salah satu pusat pameran barang mewah impor yang populer di Jakarta. Tentu saja, dibanding dengan kawasan Shibuya atau Shinjuku, kawasan Blok M, Kebayoran Baru, dan Aldiron Plaza bukan apa-apa. Tetapi bila kita berbicara dalam konteks proporsi, dalam konteks gross national product, pendapatan per capita, dan garis kemiskinan, kiranya tidak berlebihan kalau suasana gedung bioskop New Garden Hall itu suasana mewah, suasana gaya hidup elit metropolis. Jelas, hanya lapisan bagian atas dari masyarakat Jakarta yang akan berkesempatan menikmati Gandhi dalam latar seperti itu. (Meskipun itu tidak usah berarti bahwa semua penonton dalam gedung itu adalah orang-orang yang selalu berduit banyak. Sebagian, termasuk penulis karangan ini, memaksakan diri untuk menonton di gedung itu). Sedang mereka yang pada menonton di gedung bioskop Shibuya itu adalah warga dari suatu masyarakat industri maju dengan pendapatan per capita yang tinggi tanpa mengenal suatu garis kemiskinan. Kemewahan suasana dan penampilan di Shibuya itu adalah ciri merata dl negerl itu. Maka ironis juga, menonton Gandhi dengan motivasi "pedagogis" untuk memahami makna keprihatinan dan kesederhanaan di suatu negara belum kaya atau masih melarat seperti negeri kita ternyata menjadi suatu perjalanan kemewahan. Kok kita nggak punya pemimpin kayak begitu, ya Kalau punya 'kan asyik! Itu adalah komentar anak-anak saya (dan agaknya dari banyak muda-mudi lain) sehabis menonton Gandhi. Saya agak tertegun mendengar reaksi begitu. Hampir otomatis saya menjelaskan bahwa di negara seperti apa pun kepribadian seperti Gandhi adalah langka. Belum tentu satu kali dalam satu abad tokoh sebesar itu akan hadir dalam sejarah. Akan tetapi, saya jadi terkesima mendengar nada yang tuntas dari anak-anak yang memutuskan "kok kita nggak punya plmpinan kayak begitu." "Sudah begitu jauhkah citra keprihatinan dan kesederhanaan lepas dari penampilan kita? Di satu negeri di mana kata-kata scperti prihatin, tirakat, sederhana, puasa, puasa senen-kemis, bertapa, dan nglakoni, adalah kosa-kota sehari-hari? Dulu waktu masih kecil saya menyaksikan bagaimana kakek dan nenek saya adalah aktor dan aktris yang aktif dalam dunia keprihatinan itu. Puasa senen-kemis, ngrowot dan nganyep, yakni makan ubi-ubian saja untuk waktu tertentu dan tanpa garam, jalan-jalan pada setiap malam Jumat Kliwon yang dimulai pada menjelang tengah malam hingga subuh dan macam-macam "olah keprihatinan" lainnya. Dan karena latihan semacam itu dikerjakan oleh banyak orang yang sebaya dan setaraf dengan mereka, kelihatannya mereka gembira betul mengerjakan itu. Untuk apa sesungguhnya mereka mengerjakan itu semua? Kakek dan nenek akan dengan tersenyum mengatakan "untuk kalian, anak cucuku, agar kehidupan kalian lebih baik dari kami." Dahulu saya cenderung melihat latihan keprihatinan semacam itu sebagai semacam "olah raga" untuk menggarap kondisi tubuh dan batin sebagai suatu keseimbangan yang ideal. Semacam cerminan harmoni yang indah dari "jagat kecil" menurut konsep orang Jawa. Tetapi "target-target" yang kemudian sering saya dengar dari banyak orang yang nglakoni membuat saya jadi skeptis dan ragu akan keseriusan "olah keprihatinan" itu. Target-target seperti ingin "melihat anaknya bisa menduduki jabatan tinggi pemerintahan," bisa "naik mobil yang gede dan mewah", bisa "menjadi orang yang terkenal pandai" dan sebagainya pernah membuat saya berkesimpulan bahwa "olah keprihatinan" di negeri kita sudah degenerated betul menjadi "olah batin" yang berpamrih kebendaan dengan selera murah. Di balik kesederhanaan, kerendahan hati, serta kehendak kuat untuk menekan keinginan keduniawian, bercokol keserakahan tersembunyi yang akan disembul bersama sukses anak-cucunya. Maka, saya jadi melihat rangkaian "olah keprihatinan" yang dilakukan dengan kegembiraan oleh kakek-nenek saya sebagai rangkaian metafora, lambang-lambang, investasi, penanaman modal diri satu keluarga petani-kecil untuk mengulur kemampuan keluarga dan keturunannya dan jaringan keluarganya. Berpuasa senen-kemis ngrowot dan nganyep, berjalan kaki hingga fajar merekah pada setiap malam Jumat Kliwon adalah metafora dari penerimaan secara ikhlas akan keterbatasan miliknya dan keberatan kewajibannya. Tapi sekaligus juga semacam optimisme akan kemampuan meneruskan dan menyerahkan "tongkat estafet" kepada keturunannya. la adalah strategi pertahanan petani kecil dalam menghadapi jagat yang begitu besar, rumit, dan mahakuasa. Ia adalah juga strategi pemahaman akan tempatnya dalam jagat semesta itu. Maka, ajaran Pakubuwana IV dalam Wulangreh untuk ". . . mengurangi makan dan tidur, jangan bersuka-suka, berpakaianlah sekadarnya, karena orang yang suka berfoya-foya cenderung untuk tidak waspada batinnya . . . " adalah semacam tarikan ke atas, hogere optrekking, dari strategi sang petani kecil ini. Dari sudut pemahaman keprihatinan yang demikian mestinya ia lebih dekat pada keprihatinan Gandhi ketimbang keprihatinan busido. Seharusnya ia adalah konsep perjalanan jangka jauh yang akan mengharapkan kemenangan bukan-sekarang, tetapi kelak. Tetapi dari sudut pemahaman yang sama juga komentar anak-anak tentang Gandhi itu juga jadi menarik. Keinginan mereka untuk melihat seorang Gandhi hadir di tengah masyarakat mereka menandakan tidak hadirnya citra keprihatinan itu di dekat mereka. Menandakan juga tidak cukup banyak metafora keprihatinan tampil sebagai "contoh soal" di depan mata mereka. Sehingga, penampilan Gandhi dan para pengikutnya yang penuh dengan kesederhanaan itu seketika tampak memesonakan. Memang harus diakui, keprihatinan dan kesederhanaan sebagai suatu gaya hidup, suatu life style, agak terlalu cepat menghilang dari permukaan kehidupan kita. Di India, pengaruh keprihatinan dan kesederhanaan seperti itu masih tampak betul pada penampilan para pemimpinnya pada resepsi-resepsi, misalnya, sangat susah membedakan pakaian pemimpin dan bukan-pemimpin, pakaian pejabat dan bukan-pejabat. Hampir semua laki-laki yang hadir mengenakan "jas Nehru dengan kerah tutup" sedang para wanitanya dengan sari. Dan bahannya pun adalah bahan bikinan dalam negeri, dan sutra mentah, raw silk, nyaris merupakan satu-satunya tanda kemewahan yang tampak. Mengapa citra kesederhanaan dan keprihatinan begitu sebentar bertahan di negeri kita sebagai suatu life style Apakah para "petani kecil" kita yang sekarang sudah mengalami mobilitas vertikal dalam masyarakat sudah meninggalkan strategi mereka yang lama, sehingga tidak dibutuhkan lagi metafora-metafora keprihatinan seperti puasa senen-kemis, ngrowot dan nganyep, jalan kaki hingga fajar merekah? Dan menggantinya dengan metafora baru yang dianggapnya lebih sesuai dengan strategi mereka yang kontemporer? Metafora seperri Mercedes Benz, BMW, sepatu Bally, segala accessones dari Pierre Cardin dan rumah-rumah berarsitekturkan Spanyol dan Romawi itu? Tetapi, bila ini benar, apakah ini bukan metafora keprihatinan dari mazhab yang lain? Metafora dari satu tahap akhir perjuangan seperti telah ditunjukkan pada contoh Jepang? Barangkali para "petani kecil" kita memang sudah mengubah strategi hidup mereka. Barangkali hikmah revolusi kita yang memungkinkan banyak dari "petani kecil" itu bergerak ke atas, menikmati satu mobilitas vertikal, menjadi priyayi bahkan priyagung, membuat mereka banting setir dalam melepaskan lambang-lambang. Barangkali lambang-lambang yang ditunjukkan oleh orangtua mereka telah dianggap terlalu kuno, lamban, dan tidak menjawab lagi pertanyaan besar mereka. (Sementara roda alat tenun Gandhi diambil oleh rakyat India sebagai metafora kesederhanaan dan keprihatinan abadi dengan menempelkannya pada bendera mereka). Tentu saja tidak ada yang melarang untuk banting setir. Bahkan mungkin sah saja. Asal tahu bahwa lambang-lambang baru mereka itu berasal dari mazhab "peperangan", mazhab yang haus kemenangan kongkret dan mazhab yang menuntut macam keprihatinan dan kesederhanaan yang keras dan lama. Saya khawatir, para "petani kecil" yang sekarang menjadi priyayi dan priyagung agak kesusu menangkap metafora, lambang-lambangnya. Dan bukan menangkap proses keprihatinannya terlebih dahulu. Sehingga metafora yang tergesa ditangkap itu mancala, mengubah diri, dari esensi keprihatinan menjadi esensi konsumsi kenikmatan. Dambaan para muda-mudi akan hadirnya seorang Gandhi di tengah-tengah kita, siapa tahu, mungkin sekali berhubungan erat dengan fenomena itu.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini