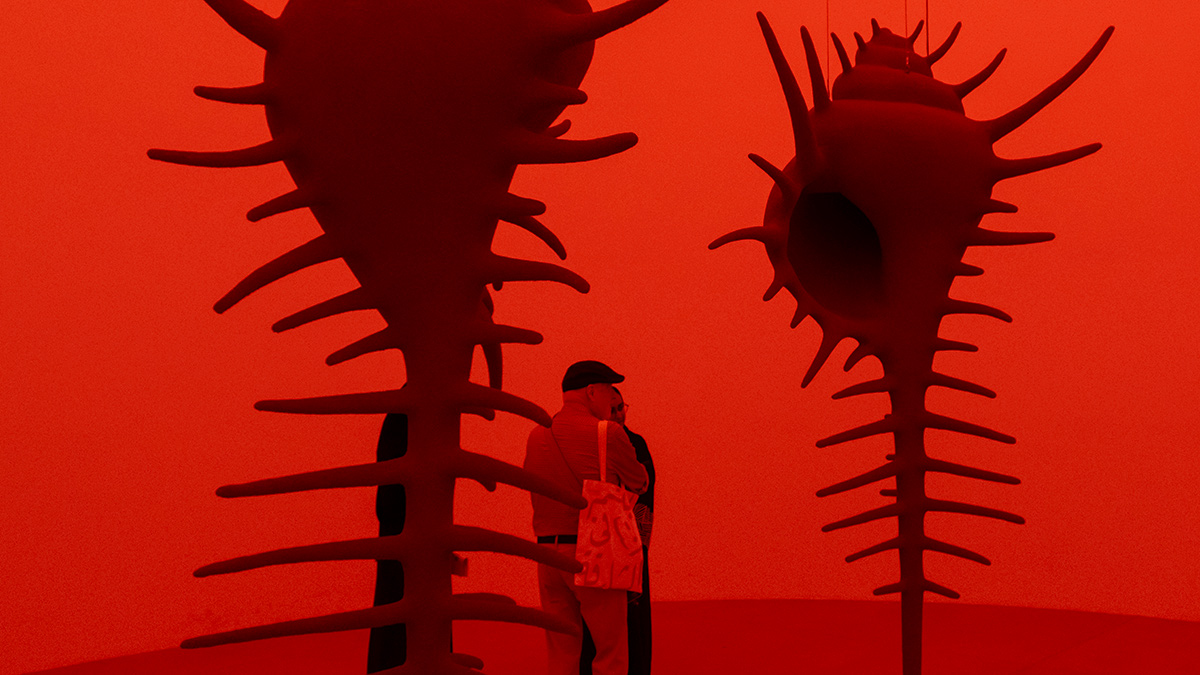Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Ringkasan Berita
Keterlibatan Gerwani dalam Gerakan 30 September masih samar.
Orde Baru membuat stigma Gerwani menghambat gerakan perempuan.
Bagaimana memulihkan luka sejarah ini?
PEMENJARAAN tanpa pengadilan dan kekerasan fisik yang dialami para aktivis Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani) ataupun mereka yang dituduh berafiliasi dengan organisasi ini berlangsung serentak. Kekerasan itu diikuti serangan kekerasan verbal terhadap perempuan, berupa label seksual seperti “lonte”, “penyilet penis jenderal”, atau “penari telanjang pembunuh jenderal”.
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo