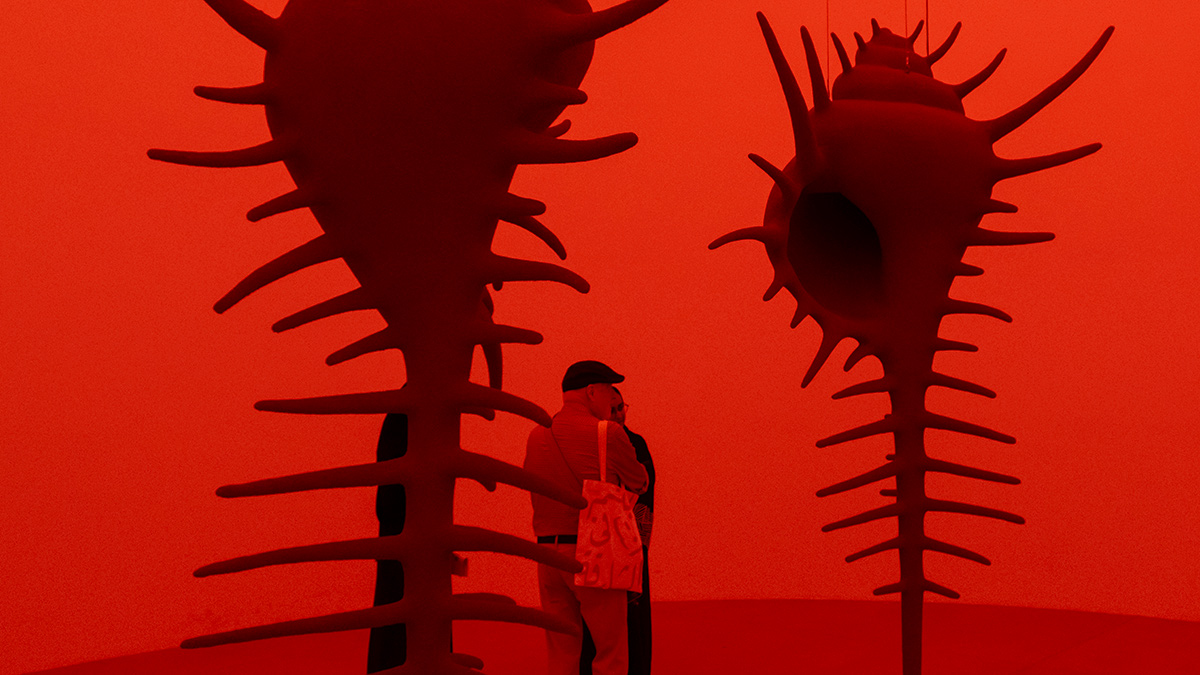Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

SEKILAS pemandangan itu seperti papan permainan ludo. Setiap pedagang menempati satu lingkaran putih di tanah beraspal yang digoreskan dengan abu dapur. Mereka duduk di atas batu yang sudah ditata. Jarak antarlingkaran itu sekitar 1,5 meter, mengindahkan protokol kesehatan Covid-19. Beragam bahan makanan terbentang di hadapan pedagang. Mereka menggelar lapak berisi sayur-mayur, bertandan-tandan pisang, juga ikan terbang. Di deret lingkaran lain, ada pedagang yang menjejerkan daging paus potong dan gerabah tanah liat.
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo