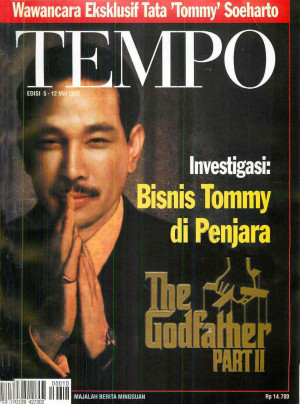Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
SELALU saya terkenang akan pasangan setengah teler itu: duduk bermalas-malasan di sofa, mereka berselisih ringan apakah bulan di langit New York itu berwarna ungu atau kuning keemasan. Mereka mencoba berlaku mesra satu sama lain, tapi sia-sia agaknya: keduanya terseret oleh kenangan masing-masing. Si perempuan, Jane, teringat akan suaminya, yang kini dibayangkannya ada di Alaska; si pacar, Marno, merasa tiba-tiba istrinya berada di dekatnya. Lelampuan di barisan pencakar langit di Manhattan itu mengingatkan Marno pada ratusan kunang-kunang di sawah embahnya di desa nun di Jawa. Sedangkan Jane teringat bagaimana ia meninggalkan boneka kesayangannya ketika bertemu dengan si calon suami di high school.
Cerpen di atas memukau lantaran si pengarang hampir tak mengatakan apa-apa tentang raut dan riwayat tokoh, juga latar dan alasan kejadian. Begitu saja ”terdampar” menyaksikan keduanya, kita mereka-reka apa yang terjadi sebelum dan setelah ”adegan” pada malam itu. Bahkan mungkin kita hanya meng-intip mereka melalui lubang kunci atau mendengar mereka dari balik dinding: namun, ah, sungguh tak ada laku berahi di antara mereka, kecuali sikap ragu, enggan, nyaris dingin, salah tingkah. Di akhir kisah si Jawa hanya mencium dahi si bule, pamit pulang. Seperti Marno yang menolak untuk bermalam di apartemen Jane itu, si pengarang Seribu Kunang-kunang di Manhattan itu juga begitu menahan diri: ia tak memasuki kedalaman psikologi dan biografi tokohnya. Marno dan Jane adalah sosok konkret yang tak memerlukan campur tangan pengarang.
Menghargai cerpen-cerpennya awalnya yang berlatar New York lebih tinggi ketimbang prosanya yang belakangan yang menelusuri kedalaman dunia kaum priayi Jawa, saya pernah dikatakan Umar Kayam, sang pengarang, sebagai pecinta ”eksotika luar negeri” dan pengacuh ihwal di tanah leluhur sendiri. Tapi percayalah, pengarang yang piawai adalah seorang pengabar yang tahu diri sekaligus perajin kata yang cekatan, sebagaimana Kayam pada cerpen-cerpen New York-nya. Empati yang berlebihan terhadap tokoh dan tempat kejadian akan membuat ceritanya tak lincah bergerak, memberat oleh pandangan dunia yang didesakkannya, sebagaimana terjadi pada novelnya Para Priyayi dan sejumlah cerpen terakhirnya.
Pengabar yang tahu diri: ia mengerti bahwa ceritanya hanya sejenis berita kecil. (Dalam wawancara terakhirnya di jurnal Prosa yang baru terbit, Kayam mengaku memungut cerita dari koran bekas, koran kuning, yang dibuang tetangganya.) Pem-baca akan memutar sendiri gambar-hidup jika si pengarang mengatakan serba sedikit. Seakan-akan ia selalu penasaran tapi gagal atau urung menangkap keseluruhan hidup tokoh-tokohnya. Maka kependekan sebuah cerpen bukanlah peringkasan dari peristiwa besar, melainkan tangkapan atas momen peristiwa kecil. Peristiwa di apartemen Jane itu kiranya hanya berlangsung satu-dua jam, bahkan mungkin jauh lebih singkat. Panjang waktu cerita itu tak dinyatakan, tapi kita merasakannya melalui percakapan si pasangan.
Ketika pertama kali membaca cerpen itu 25 tahun yang lalu, saya merasa ada yang hilang atau tak lengkap di sana. Kemudian, ketika membacanya berulang-ulang, bahkan sampai kini, saya tahu bahwa ketaklengkapan itulah yang membuat kita merangkai sendiri suasana, rinci tempat dan peristiwa di antara laku dan tuturan para tokohnya. Seperti dalam puisi lirik, kata-kata hanya digunakan seperlunya: seakan pengarang tahu, dunia ini akan kian bermakna jika ia menyediakan makin banyak celah kosong-sunyi bagi pembaca dan membebaskan tokohnya dari pesan moral. Namun, jika puisi sering terlalu ekstrem menyuling pengalaman dan memisahkan kita dari dunia orang ramai, puitika Kayam justru bergerak dalam wicara sehari-hari, sebagaimana juga kita temukan pada cerpen Ernest Hemingway dan J.D. Salinger, dua pengarang yang agaknya memengaruhinya. Di sinilah penulis kelahiran Ngawi, Jawa Timur, ini adalah seorang perajin kata yang piawai: ia berhasil menghindarkan ceritanya dari kemubaziran, sesuatu yang sering menghantui realisme.
Maka Jane tak menangis ketika Marno menolak ha-diah piyama darinya dan meninggalkannya malam itu, kecuali bahwa si perempuan ”merasa bantalnya basah”. Dan Peggy si waitress, bertengkar kecil dengan si pacar, Bung Kakatua, dalam diam—melalui tukar-menukar ”surat” kertas tisu—di antara keramaian orang memesan kopi dan donat. Dan ketika di akhir cerita, Peggy berlari ke arah Dilbert Supermarket, tempat si pemuda bekerja, kita pun tahu ia hendak minta maaf dan melampiaskan kangen. Pun tak ada yang dramatis pula dalam There Goes Tatum ketika si pemuda kulit hitam yang mula-mula hanya mengemis lima puluh sen itu perlahan-lahan merampok halus dengan pisau lipatnya jam tangan Titoni si aku. Dan Sybil, si gadis kecil tak berayah dalam cerpen berjudul sama, hanya mengatakan ”Tuan akan tidur siang, kali ini?” kepada lelaki yang hendak menzinai ibunya.
Atau jika waktu cerita terentang panjang, sang pengarang tak tergoda menampilkan semuanya. Dalam Isteriku, Madame Schlitz, dan Sang Raksasa, sekian bulan terentang sejak si aku dan istrinya menempati apartemen mereka, hingga Madame Schlitz, tetangga yang misterius itu, menghilang tanpa jejak. Tapi di sini pun Kayam berhasil menangkap sejumlah momen kecil: narator menceritakan kembali kisah istrinya ber-temu, beberapa kali, dengan sang bule pemilik anjing Chihuahua itu. Melalui cerita berbingkai ini kita mendapat gambaran yang centang-perenang, tak pernah utuh, bahkan bertentangan, tentang Madame Schlitz: misalnya, apakah sesungguhnya dia beraksen Austria atau Manhattan biasa saja; adakah suaminya sudah mati ataukah masih hidup; dan kenapa dia memanggil anjingnya dengan nama suaminya. Kita menikmati cerita sebagaimana si aku dan istrinya tak tahu mana yang benar dan yang bohong.
Saya ingin mengatakan bahwa tokoh-tokoh New York itu menjadi kental dan tak terlupakan lantaran si pengarang hanya melukiskan sketsa tentang watak luaran mereka, bukan biografi. Sang pengisah, baik sebagai orang pertama maupun ketiga, tak hendak menembus kedalaman jiwa mereka, namun sekadar merekam laku dan wicara mereka. Bahkan mereka hadir sebagai hanya tilas tipis dari suatu masa dan suatu tempat, katakanlah belantara Manhattan 1960-an, tapi dengan demikianlah mereka bukan model atau eksemplar untuk hukum atau etika sosial. Tapi sampai kapankah sang pengarang bisa bertahan sebagai pencatat yang tak berpamrih dalam menghadirkan sepotong momen kehidupan yang unik dan bukan secara diam-diam menyelenggarakan sosiologi dan mungkin antropologi?
Dalam Musim Gugur Kembali di Connecticut kita ter-bawa oleh lompatan pikiran Tono, seorang penulis Lekra, ke masa lampaunya: sel tempat ia baru ditahan, pertengkarannya dengan teman sesama Lekra di sana. Semua itu mengonkretkan masa kini Tono: masa pembebasannya yang sebentar, kemesraannya dengan istrinya. Sosoknya menjadi begitu kuat justru lantaran ia dilukiskan sebagai komunis yang ragu-ragu. Dan kita pun membayangkan kematian Tono—tanpa si pengarang mengatakannya—ketika ia dijemput sejumlah tentara. Menjelang pergi, Tono mencium bau mani pada lengan jaketnya sendiri. Tilas persetubuhan itu begitu wajar dan elok pada bayangan mautnya.
Tono adalah orang Jawa. Mulailah sang juru cerita menemukan—atau menciptakan—kembali dunia asal-muasalnya, Jawa. Bila latar cerita begitu dikenalnya, dan bila empatinya terhadap tokoh terlalu dalam, kita pun tahu Kayam tak bisa menghindar dari laku serba menjelaskan. Seperti Mustari, Kayam melihat ”kepingan kaleidoskop masa silam sekilas-sekilas”, bukan hanya untuk memperkuat psikologi tokohnya, tapi juga untuk melukiskan bagaimana sang individu harus bertarung dengan model yang disediakan kelompoknya. Tono dan Mustari masih bisa mengesankan karena mereka alah atau terpinggir di akhir kisah yang tak teramalkan itu.
Dua cerita Kayam yang kemudian, Sri Sumarah dan Bawuk, adalah novelet: cerita panjang yang tak lagi mendedahkan sketsa tentang tokoh dan peristiwa. Ditampilkannya riwayat hidup tokoh sebagai bagian dari sejarah yang lebih besar. Seakan pengarang ingin mencoba: adakah karakter yang mampu keluar dari kemelut badai, katakan saja peristiwa ”Gestapu”, dan tetap tegak sebagai pribadi. Dan sang pengisah menyurukkan kita lebih jauh ke dunia Jawa: dunia kaum priayi. Seakan ia ingin menguji pula apakah lapisan sosial ini mampu menjelmakan diri ke dunia modern. Tapi mampukah Bawuk dan Sri Sumarah meloloskan diri dari kerangka yang disediakan sang pengarang?
Jalan hidup Sri Sumarah sudah ditentukan sejak ia dinamai: sumarah, yang berarti pasrah, menyerah, tabah. Janda Pak Guru Martokusumo ini menjadi penjahit dan pembuat kue ketika suaminya meninggal karena wabah eltor. Ketika ia harus menggadaikan sawah dan rumahnya kepada Pak Mohammad, dan ketika ia terpaksa mengawinkan putri tunggalnya, Tun, dengan seorang aktivis CGMI, kita pun tahu bahwa sang pengarang sedang menghadapkan Sri Sumarah, yang priayi rendah itu, dengan sang santri dan sang abangan. Namun kepasrahan pun menjadi kesaktian: ketika sang menantu tertembak mati dan sang putri ditahan, Sri bertahan hidup dengan mengasuh cucunya dengan menjadi juru pijit atas wisik (bisik gaib) almarhum suaminya.
Memijit adalah mengelus-elus, ”melemaskan urat-urat yang semula tegang.” Dan jika pelanggan Sri adalah kaum lelaki, tak begitu sulit kita berpendapat bahwa sosoknya dalam novel dibentuk oleh mata lelaki. Sejenis erotisisme halus membayang sepanjang kisah, tetapi Sri tetap tinggal dalam kesuciannya: seperti Kunti, ibu Pandawa, dan seperti Sembadra, salah satu istri Arjuna, ia tetap setia kepada almarhum suami dan keluarga. Ia suri tauladan yang sakti. Ketika ia tergoda oleh seorang pemuda Jakarta yang dipijatnya, sehingga mereka berpeluk sepanjang malam—alangkah luar biasa—ia berhasil mengelakkan persetubuhan. Sungguh, sang pengarang tak mengizinkan Sri menjadi manusia darah dan daging yang bisa berdosa.
Demikianlah sang protagonis harus menjunjung etika priayi. Tapi Bawuk, perempuan anak bungsu sang onder setenan Karangrandu itu, mencoba mengelakkannya, bahkan melawannya, meskipun gagal kiranya. Mengawini Hassan, abangan yang aktivis PKI itu, Bawuk harus hidup dalam buron bersama keluarganya tak lama setelah ”Gestapu”. Malam itu Bawuk kembali ke rumah ibunya, Nyonya Suryo, untuk menitipkan dua anaknya. Di sana sang ibu mengumpulkan kembali anak-anaknya yang telah berpencaran di pelbagai kota, untuk membicarakan nasib Bawuk. Tapi ia menolak uluran tangan mereka, dan memilih ”dunia abangan yang bukan priayi, dunia yang selalu resah dan gelisah”: ia memilih bergabung dengan suaminya dalam pelarian.
Mungkin kisah Bawuk mencekam karena sang pengisah menampilkannya sebagai pelawan tradisi. Namun jelaslah, sekian fragmen hidup Bawuk pada masa kanaknya, yang menyusup sebentar-sebentar ke masa kininya sebagai orang kiri buron tentara, membuat tokoh ini begitu penuh teka-teki—dan karena itu kita jatuh hati kepadanya. Meski terkadang sang pengarang mengembalikannya kepada model Sembadra lagi, seperti Sri Sumarah: dia menjadi orang PKI bukan atas pilihannya sendiri, tapi karena cintanya pada Hassan. Ketika Hassan mati tertembak, kita tak tahu bagaimana Bawuk di akhir kisah itu: tapi di rumah eyangnya, dua anak Bawuk belajar mengaji.
Novelis cemerlang suka berkelahi dengan gambaran dunia yang sudah mapan. Namun dalam novelnya Para Priyayi sang pengisah sepenuhnya berdamai dengan gambaran Jawa yang tak terbantahkan itu. Ketika membaca novel itu mula-mula, saya menduga sang pengarang ingin memberi alternatif bagi tipologi Jawa yang selama ini sudah begitu dimamah biak oleh traktat sosiologi, antropologi, bahkan ilmu politik. Membaca lagi kisah tiga generasi trah Sastrodarsono, guru abdi gupermen yang berumah induk di Wanagalih, Jawa Timur itu, saya menemukan sang juru kisah perlahan berubah menjadi sang pembela dunia priayi. Tapi ia tahu diri: ia bukan yang mahatahu tentang bagaimana trah yang berasal dari kaum tani itu memantapkan dan melestarikan diri sebagai kelas priayi sejak zaman Belanda sampai awal Orde Baru. Ia menyilakan tiap-tiap tokoh bicara sendiri—menjadi ”saya”—kepada kita. Setiap bab pada dasarnya adalah otobiografi.
Namun, dalam bentuk otobiografi itu pun, sang pengarang terlalu berkuasa. Setiap ”saya” hanya wadah yang berbeda untuk suara yang sama. Kita pun tahu, Sastrodarsono dan anak-anaknya hanya varian dari model baku dari sang priayi. Guncangan sosial yang sungguh besar—misalnya pendudukan Jepang, pemberontakan PKI di Madiun, dan peristiwa ”Gestapu”—tak mampu mengubah keyakinan mereka akan hakikat kapriyayen, bahkan memperkuatnya. Baru pada generasi ke-tiga kita menemukan penyimpangan atau perlawanan terhadapnya, tapi ini pun hanya untuk membuktikan kesaktian etika priayi. Marie yang bebas dan ”kebarat-baratan” itu harus terhukum: ia hamil oleh seorang pemuda desa, dan demikianlah ia menjadi pribadi yang lemah dan keliru lantaran menyimpang dari keluarga besarnya. Adapun Harimurti si seniman Lekra mengakui kesalahan pilihannya akan perjuangan kelas selepas masa penahanannya: ia meyakini kembali kebenaran trahnya, ”priayisme” yang hakikatnya juga ”pengabdian kepada orang kecil”. Adalah Lantip, anak jadah seorang keponakan jauh Sastrodarsono dengan seorang gadis dusun, yang tampil sebagai juru selamat setiap kali keluarga besar itu mengalami celaka: seperti sang embah kakung, ia berhasil mengangkat dirinya ke dalam trah itu dengan menyesuaikan diri kepada etika priayi.
Dengan rasa sabar dan ingin tahu yang berlebihan kita mengikuti kisah sepanjang 308 halaman ini. Jika sang pengisah menjalani juga peran sebagai antropolog atau sosiolog sekaligus pelaku yang terlalu banyak tahu perihal latar ceritanya, mungkinkah ceritanya masih bisa memukau? Saya cenderung menjawab tidak. Ia bukan hanya menjelas-jelaskan, tapi juga mendedahkan apologia. Sebuah novel yang cemerlang, bagi saya, mestinya mencari retak-retak ketimbang mengulangi kesempurnaan semu sebuah kelas sosial: novel yang memihak ”tidak” yang penuh risiko ketimbang ”ya” yang layu.
Lalu kita membaca cerpen-cerpen Kayam yang bertema lebaran, yang ditulisnya hampir setiap tahun sepanjang 1991-1999: tentang pembantu yang gagal pulang kampung karena kalah berebut tempat dalam bus; tentang duda yang tak kunjung berani menyampaikan niatnya untuk kawin lagi kepada si mertua; tentang suami-istri yang menyingkir ke hotel demi menghindari sungkeman dengan keluarga besar mereka; tentang suami yang dipecat di akhir bulan Ramadan; tentang bekas pembantu tua renta yang mengunjungi keluarga induk semangnya setiap lebaran dan sekatenan; tentang pembantu yang berniat pensiun dan pulang kampung setelah mengabdi selama 15 tahun. Pengalaman mereka, bagi saya, urung menjadi cerita karena ia terlalu mirip dengan rutin berita di sekitar kita. Terkadang terasa bahwa si pengarang hendak menyajikan alternatif terhadap sudut pandang yang terlalu sering kita gunakan, tapi kata-katanya tak lagi lincah karena diberati amanat tentang ke-rukunan dan keselarasan sang keluarga besar, tinggalan nilai priayi.
Cerpen-cerpen Kayam yang terakhir juga menyajikan satir tentang birokrasi. Dilukiskannya para pejabat sebagai Sphinx (mitologi Mesir Kuno), Raja Midas (Yunani), Arjuna (si tengah Pandawa), dan Citraksi-Citraksi (kembaran Kurawa), tetapi sang pengisah terlalu mementingkan komentar ketimbang suasana, dan keterangan ketimbang fantasi. Sebagian cerita, saya kira, bisa menjadi alegori yang kuat jika saja Kayam mempunyai kelincahan verbal seperti dalam cerita New York-nya. Namun cerita itu hanya menjadi rancangan pikiran lantaran potensinya sebagai cerita yang sadar-diri—seperti ludruk, lenong, atau teater Brechtian—tak tergali benar, mungkin juga karena ”moralisme” pengarangnya.
Namun saya segera tersadar, kelincahan Kayam tetap terjaga dalam ”cerpen”-nya yang lain, yang terbit hampir tiap minggu di harian Kedaulatan Rakyat Yogyakarta sejak 1987. Terbit kemudian sebagai seri buku Mangan Ora Mangan Kumpul, ini adalah metamorfosis dari adegan goro-goro dalam pentas wayang kulit: di sana sang saya, Pak Ageng, adalah Arjuna atau Yudhistiraa, dan Mister Rigen, sang pembantu berikut keluarganya, adalah Semar dan para panakawan lainnya. Dengan bahasa campuran Jawa dan Indonesia, sang priayi dan sang batur saling mengejek melalui pelbagai soal sejak makanan hingga politik. Demikianlah ”pertentangan kelas” dilunakkan dalam humor dan ironi dalam rumah sang juru kisah maupun di luarnya—agar keselarasan terjaga, dan kita mengalami perubahan dalam damai.
Perjalanan Umar Kayam dari kumpulan cerpen Seribu Kunang-kunang di Manhattan (1972) ke dua novelet Sri Sumarah dan Bawuk (1975) ke novel Para Priyayi (1992) adalah perubahan perlahan sang juru kisah menjadi sang apologis. Tapi bila saya hanya seorang nyaris-Jawa yang tak pernah memercayai keadiluhungan kultur priayi, saya bertanya apa pentingnya apologia pro vita Java yang demikian bersemangat itu? Maka baiklah saya mengingat Bawuk yang dari sudut pandang priayi adalah tokoh yang gagal dan karena itu ia mengesankan buat saya. Bawuk, yang surat-suratnya mengandung cerita-cerita yang tak ”ada manfaatnya yang langsung” bagi pembacanya: ia mempergunjingkan orang-orang yang ”tidak dikenal” dan ”tidak akan ditemui selama hidupnya” oleh si pembaca, namun ”justru omong kosong itulah yang membuat surat-surat Bawuk menarik dan banyak mem-buat kangen.”
Seperti Bawuk, Kayam selalu terkenang bila ia menceritakan pribadi-pribadi yang berbuat iseng atau berdusta. Marno dan Jane merasa sebagai pemilik Manhattan padahal mereka cuma pasangan yang gagal; Sybil membekap anak tetangganya mungkin lantaran rasa muaknya ke sang ibu yang kerap membawa lelaki ke rumahnya; Madame Schlitz mengaku suaminya almarhum se-orang chef restoran yang jempolan meski di akhir cerita kita mendapatkan si lelaki masih hidup; Peggy bertukaran pesan cinta di kertas serbet dengan Bung Kakatua di kedai yang riuh itu; Charlie si kakek berbohong ia barusan berdiskusi politik kepada menantunya padahal ia hanya bermain komidi putar. Tapi sang juru kisah sungguh kehilangan pesonanya ketika ia mendesakkan kebenaran kepada kita melalui tokoh-tokoh priayinya.
Ketika mendedahkan momen-momen kecil pada senjakala kehidupan tokoh-tokoh Jawanya, Umar Kayam memberikan kesan yang sangat membekas. Tono mencium bau maninya sendiri, tilas percumbuan dengan istrinya, pada lengan jaketnya ketika ia dijemput sejumlah serdadu; ia juga, menjelang eksekusinya, tidak melihat tembok penjara maupun hutan karet, melainkan pepohonan mapel pada musim gugur di Connecticut, tempat studinya dulu. Dan Bawuk mengenang keriangan masa kecilnya di setenan ketika ia hendak kembali ke pelarian mencari suaminya; sungguh, ia lebih memilih risiko maut di luar sana ketimbang lindungan aman ibu dan kakak-kakaknya di antara ketuaan meja marmer bundar, jam Westminster, dan patung-patung kepala kijang itu. Seperti Tono dan Bawuk, sang juru kisah begitu tak terlupakan ketika ia menyangkal model yang disediakan sang kelompok, keluarga besar, atau masyarakat.
Nirwan Dewanto
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo