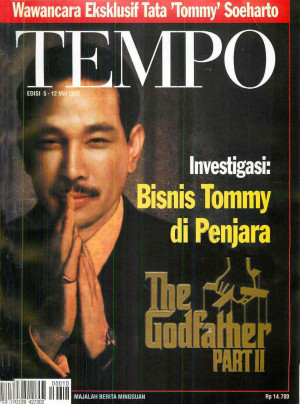Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

HIDUP mesti dihadapi dengan common sense. Dan teater adalah refleksi kehidupan dengan akal sehat itu dalam berbagai kewajaran dan sikap yang rileks. Rileksasi itulah suasana hidup Umar Kayam.
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo