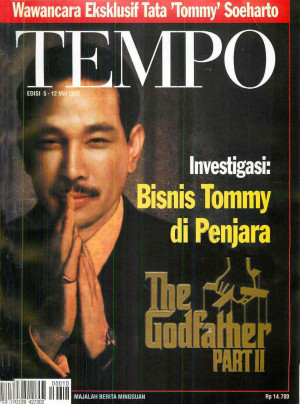Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Dia tiduran telentang, kakinya yang baru di operasi masih terlalu nyeri untuk digerakkan. Saya dan seorang kawan dari Yogya berdiri di kedua samping tempat tidurnya. Dengan suara pelan, kami berbicara tentang hal yang enteng-enteng. Tiba-tiba, seakan-akan teringat sesuatu, ia berkata dengan suara yang lemah.
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo