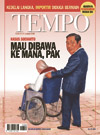Bhairawa, arca berbentuk raksasa menyeramkan, sampai sekarang tetap menjadi maskot dan primadona Museum Nasional Jakarta. Arca itu disebut-sebut sebagai simbol rohani Raja Adityawarman, penguasa Kerajaan Dharmasraya di Sumatera dari abad ke-14.
Tak banyak yang kita ketahui mengenai Kerajaan Dharmasraya, karena perihal kerajaan itu hanya disebut di prasasti Amoghapasa dan Negarakertagama. Diduga Dharmasraya dahulu adalah kerajaan yang kuat sehingga Singasari memintanya menjadi mitra untuk menahan pelaut-pelaut Kubilai Khan.
Wartawan Tempo Febriyanti melakukan perjalanan ke Padang Roco, tepian Sungai Batanghari. Padang Roco adalah lokasi yang diduga sebagai pusat Kerajaan Dharmasraya dahulu dan tempat ditemukannya arca Bhairawa. Reportasenya dilengkapi dengan tulisan mengenai Uli Kozok, ahli aksara-aksara kuno Sumatera asal Jerman yang menemukan naskah tua di Kerinci yang bisa sedikit membuka tabir Kerajaan Dharmasraya.