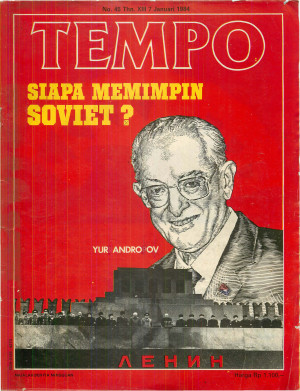HARAMSHALA. Artinya: persing-gahan terakhir para pengelana suci. Julukan yang pas untuk dusun yang bertengger di. Iereng pertama Himalaya ini. Di sinilah Dalai Lama -raja yang didewakan- dari Tibet, bersama pengikutnya, mendirikan pemerintahan dalam pengasingan. Dalai Lama menempati suatu kawasan yang disebut McCleod ganj. Tak pelak lagi, kawasan ini suasananya benar-benar Tibet. Tampang orang-orang yang berseliweran, sebagian besar, tampang Tibet. Panji-panji persembahyangan berjumbai ke sana kemari, seperti sarang laba-laba raksasa, menghiasi pohonan oak. Bebatuan dan karang di sepanjang jalan setapak, dipenuhi berbagai kalimat doa para pengungsi Tibet itu. Bagi Gurmeet Thukral -wartawan freelance dengan spesialisasi India dan Himalaya, yang menulis laporan ini dalam majalah Journey- daya pikat Dharamshala bukan pada keriuhan suasana akibat kedatangan orang Tibet. Tapi, nyatanya, di antara para pengungsi itu menyusup pula kaum imigran lain, dari Eropa, Amerika, dan Australia. Mereka berdatangan ke pojok utara India itu untuk mencari kehidupan yang bersahaja, ketenangan rohani, dan kebutuhan batin lainnya yang rupanya sangat mereka dambakan. Dan dalam Budhisme Tibet, kelompok orang putih yang berasal dari kawasan dunia hingar bingar dan rusuh itu rupanya memperoleh apa yang mereka buru. Bagi yang tak tertarik ke masalah religi, Dharamshala boleh memberikan pesona yang lain. Diselimuti rimba, noktah ini terletak di antara lereng bersalju Dhauladar -sisi utara- dan lembah menghijau di sisi selatannya, yaitu Lembah Kangra. Sebuah lokasi pelarian yang pas bagi generasi abad ke-2 yang tumbuh di dunia materialistis yang hiruk. ' Di McCleod ganj, orang-orang kulit putih yang terdiri dan kaum-hipis, turis, atau yang benar-benar berkelana untuk kerohanian, bergerombol dengan pakaian ekstis. Ada yang berjubah warna oker sebagai pendeta :Budha, berpakaian gaya harem, ada pula yang bertudung kepala seperti laiknya kaum bohemian . Dalam gaya hidup gado-gado itu, bau asam asap mariyuana dan bau tengik asap lampu minyak menyeruak. Mengatasi suara perdebatan, bisik-bisik, atau pembicaraan tentang jemaah kelompok kaum tanggung, pengungsi, petualang, dan tokoh-tokoh suci. Inilah potret kaum muda negeri-negeri Barat yang makmur, kelanjutan "generasi bunga" tahun 1960-an. Termasuk kelompok musik TheBeatlesdulu sempat ketularan wabah ini, dan berguru pada tokoh spiritual di India. Sebuah pasar kecil di McCleod ganj di jejali warung-warung makan, menyediakan masakan Barat dan Tibet. Meja-mejanya, di bawah atap sementara yang menjadikan tempat itu layak disebut warung kaget, tampak sudah reyot. Bule-bule mengelompok dalam bayang-bayangnya, dalam ayunan asap hasyisy. Pembicaraan mereka berkisar pada soal paspor, visa, tiket pesawat. Hanya saja, kelihatan ada kejenuhan. "Seolah mereka sendiri bingung, tak tahu arti sebenarnya datang ke pojok Dharamshala," kata Thukral. Ketika Thukral mencoba menanyakan sesuatu, ia disambut dengan cemoohan dan cibiran. Mereka memang tidak memiliki masa lalu, kata seseorang. Juga masa depan. Menjejali dunia saja, ujar yang lain. Dan, sewaktu Thukral mencoba menyinggung soal kepercayaan mereka dan ajaran Budhisme, mereka menggeleng. Lalu menganjurkan si wartawan menemui Thupten Tharthu saja. "Itu nama Tibetnya. Tapi ia orang Kanada, sudah menetap di sini beberapa tahun. Saban orang tahu dia. Kamu bisa menemuinya di kuil," kata beberapa di antara mereka. Tak perlu repot Thukral mencari kuil yang dimaksudkan. Begitu keluar dari kedai, suara bel kuningan, terompet, dan genderang menggema, seperti memberl tahu di mana sumber suara itu. Kurang dari satu kilometer, di sisi bawah terminal bis dan pasar, kuil itu ia temukan. Ternyata, sebuah bangunan modern. Dihiasi juluran tali untuk menggantungkan panji-panji persembahyangan. Di luar gedung, berjejer para biksu di tikar alang-alang. Mereka membuat kitab-kitab pemujaan. "Suasana yang kuhadapi berubah secara dramatis dari kejanggalan dan kepengapan di warung tadi. Di sini lebih ada keceriaan, sekaligus ketekunan: para biksu itu, dengan cermat, merapikan setiap halaman, setelah menyelesaikan pencetakan hurufnya." Thupten Tharthu, sesuai dengan petun juk mereka, tinggal di biara pada sisi bawah kuil. Ia mendiami sebuah bilik kecil, dengan dipan berkaki rendah dan tikar yang terawat. Wajahnya yang bersahabat merupakan isyarat bagi sang wartawan bahwa Thupten tak akan menolak diinterviu. Ia dengan lancar berbicara dalam bahasa Tibet dengan para biksu lainnya. Dan dengan kepalanya yang juga mulus, Thupten agak sulit dibedakan dari mereka. Hanya tubuhnya yang lebih jangkung dan tampangnya yang bule menyebabkannya punya kelainan. Nama aslinya: Gareth Spooham. "Tapi tak seorang pun disini mengenal saya dengan nama itu," tutur yang empunya nama. "Nama Thupten Tharthu saya peroleh dari guru rohani saya. Thup berarti Budha, ten sama dengan ajaran. Dan tharthu mengandung makna pembebasan," kata Gareth, eh, Tharthu. Biksu kulit putih ini lahir di Inggris. Orangtuanya memboyongnya ke Kanada sewaktu ia berusia enam tahun. Di universitas ia mempelajari art- tak ada waktu untuk mengenal Budhisme atau agama-agama yang lain. Ketika itu, katanya, "saya tak pernah menyukai Budhisme. Sebab, saya pikir, orang-orang gundul itu mengerikan. Dalam masyarakat saya rambut botak begini memang selalu menjijikkan." la mengusap rambutnya, eh kepalanya yang botak itu, sembari terkekeh-kekeh. Lalu kapan mulai tertarik kepada Budhisme? "Saya membaca beberapa buku. Di antaranya Tibetan Book of Liberation". Disusul kemudian, pada 1972, mencari-cari tempat untuk mempelajari Budhisme. Berangkatlah ia ke Sri Lanka. "Saya pikir, itu karena tidak ada Budhisme di India, meski dulu bermula dari situ. Secara untung-untungan saja saya ke Kathmandu, dan menetap di Boginath selama sekitar satu tahun. Di situlah saya bergabung dalam sebuah kursus. "Mereka memberi penjelasan tentang dasar-dasar Budhisme dan meditasi. Lalu saya memutuskan menekuninya, supaya memperoleh basis yang kukuh. Saya pun menjadi rahib di Nepal, datang ke Dharamshala, dan sejak itu saya di sini. Hampir sembilan tahun sudah." Setelah ngobrol, acara selanjutnya bagi Thukral adalah menerima ajakan Thupten untuk mengunjuni Tushita. Ini pusat meditasi dan khalwat yang dibangun khusus untuk para kawula dari Barat. Mereka berdua berjalan balik ke bukit, menembus pasar, lalu sampai pada puncak sebuah punggung bukit. Apa sebenarnya yang memikat Gareth, waktu itu, untuk menekuni Budhisme? "Saya dan teman-teman di bangku kuliah terbiasa bersenang-senang. Tidak canggung menenggelamkan diri dalam hasyisy dan mariyuana. Saya hidup dalam kelimpahan materi. Tapi, jika dilihat dari pemikiran kaum Budhis, itu kenestapaan. Meski saya bukan tak bahagia, rasanya ada sesuatu yang luput. Ada yang kurang. Saya tak pernah berpikir untuk melarikan diri. Dan, bagaimanapun, saya tidak berpendapat bahwa saya telah terbebaskan." Perjalanan diteruskan, menyusuri jalan setapak, menyusup di antara pohon-pohon pinus dan pohonan cedar Himalaya. "Ada sesuatu yang saya temukan dalam Budhisme, yang begitu membahagiakan. Khususnya ide ini: jika Anda menghadapi sesuatu dengan sikap welas asih, maka yang tampak hanyalah kekosongan. Selebihnya tak ada apa-apa. Hanya itu. Ia tak sanggup membeberkannya lebih jauh lagi, dan memang tak perlu. Ia seorang biksuni kini. Ia telah menghayati Budhisme, dan itulah segalanya. Tapi satu hal masih bisa dikorek: bagaimana ia kok betah berlama-lama di Dharamshala. Begini keterangannya: "Kebaikan orangtua saya sungguh tak bisa dipercaya. Mereka selalu saja mengirimi saya segala sesuatu. Yah, sesekali saya kirimkan karpet Tibet, yang dibuat di sini, ke ibu saya. Ia rupanya menjual barang itu, dan uangnya dikirim ke sini. Urusan begitu kini menjadi lebih sulit. "Toh saya juga tak memerlukan banyak uang. Saya tak perlu bayar kamar. Hanya makanan, yang tak lebih dari 150 rupee. Sering pula seseorang, yang mengerti Budhisme, memberi saya 100 atau 150 dolar. Ini cukup untuk hidup selama setahun. Yah, begitulah. Kalau dipikir-pikir, sulit dipercaya, ya." Thartu dan Thukral hampir tiba di Tushita -sebuah bangunan cukup besar, di pinggir bukit- ketika sang biksuni menunjuk ke arah sebuah rumah lain, sedikit di bawahnya. "Itulah Anand Bhawan, Tempat Kebahagiaan. Para hipis tinggal di situ. Sewanya murah, dan mereka mendapatkan kelimpahan musik dan grass." Barang yang disebutnya terakhir ini di kalangan kita berarti ganja. Di sebuah celah, di sisi bukit, mariyuana tampak tumbuh dengan merdeka. Begitu sampai di Tushita, Thukral diperkenalkan kepada seorang biksuni yang lain, gadis dari Auckland, Selandia Baru. Ia juga mencukur klimis kepalanya. "Anda boleh memanggil saya Anne saja," katanya. Di Tushita tinggal enam biksu dan sepuluh biksuni, semuanya kulit putih. Ada juga beberapa bule lainnya yang datang ke situ menekuni Budhisme - dan kelihatan begitu serius dalam studi. Guru para penghuni, Gashe Ketchong, hari itu tidak ada di tempat, dan tugasnya digantikan Anne. Sang biksuni segera mengambil dua cawan teh untuk Thartu dan Thukral. Lalu bertanya, "Apa yang ingin Anda ketahui dari saya?" "Orangtua Anda, juga yang lainnya, tentu sulit menerima kenyataan bahwa Anda menjadi seorang bia rawati Budha. Iya, 'kan?" Yeah, yeah," jawab Anne. "Orang-orang tua keluarga Barat sangat repot untuk memahami. Bahkan menjadi biarawati Kristen masih merupakan hal aneh." "Saya kini bekerja di bidang yang sama sekali lain," katanya. "Sewaktu masih hijau dulu, saya menjadi peragawati untuk beberapa tahun. Lantas terlibat dalam gerakan kebebasan wanita. Kesudahannya, saya malah merana di dunia. Tunggang-langgang saya menghadapi kenyataan itu. Saya mendambakan jawaban rohaniah. "Beberapa biksu datang ke negeri saya. Dan saya mengikuti kursus-kursus meditasi. Ajaran mereka begitu sangat berarti buat saya. Yah, semacam bisikan kebenaran, yang tak mungkin terlupakan. Kemudian saya terus menjalankan meditasi, dan studi tentang itu, sedikit-sedikit." Kebanyakan biksu atau biksuni bule mendapatkan Budhisme di Timur. "Tapi saya sudah menjadi biksuni sebelum datang ke India. Ada sebuah institut kaum Budhis di Selandia Baru. Cuma, saya pikir, akan lebih cepat dan mudah kalau datang langsung ke Timur. Dan di sinilah guru saya," kata Anne. Seorang biksuni lain menyeruak masuk. Ia begitu gelisah. Sewaktu ia berkali-kali mencoba duduk di arena obrolan itu, Anne dan beberapa biksuni lainnya malah mengusirnya. Anne menjelaskan, yang bersangkutan mesti melakukan retreat, khalwat, dan ini berarti larangan berbicara. Perlu didengar komentar Anne terhadap kaum hipis yang bermarkas di Anand Bhawan. "Oh, ya. Orang-orang yang sepanjang hari mengulum pipa itu. Apa, ya. Mereka 'kan tidak menyadari diri sendiri," katanya. "Mereka tidak tahu kenapa mereka ke sini. Sepanjang hari mabuk dan melayang-layang: mereka kotor dan sakit. Yang sebenarnya ditawarkan India tak mereka alami. Bagi saya, kalau datang ke India hanya untuk menjalani cara hidup begitu, yah, percuma. " Agak lama wartawan kita kemudian terpaku di ruang meditasi-suatu aula yang panjang, tertib, temboknya mulus-kecuali beberapa gambar suci untuk dijadikan pusat konsentrasi. Setiap pojok dan ruang di situ masing-masing memberi kesan angker. Sewaktu Thukral melintasi sekat-sekat ruang, sembari menikmati panorama salju yang bergelantungan di bukit di kejauhan, mendadak terdengar bisikan halus, seperti lenguhan minta tolong. Di balik pintu yang sedikit membuka, gadis itu rupanya biksuni yang mesti menjalani khalwat tadi-memberi kode kepada Thurkal supaya menyelinap ke dalam biliknya. "Rupanya, ia ingin menumpahkan segala unek-uneknya," tutur si wartawan. Namanya Yangchen Dolkar. Ia datang dari Argentina. "Saya telah menamatkan universitas, fakultas psikologi, dan tesis saya mengenai gelombang otak berdasarkan yoga," kata Dolkar dengan tergopoh-gopoh. Suaranya masih pelan, hampir berbisik. "Saya mengajar di sebuah sekolah di Argentina, dan saya bekerja di sebuah rumah sakit di New York sebagai psikolog." 'Lho, terus, ngapain Anda di sini?" "Mencari kebenaran hakiki," jawabnya. "Dan menyelidiki yoga lebih jauh. Saya sudah menulis surat kepada Kalo Rimpoche, orang yang sudah menguasai meditasi. Saya dengar ia melakukan retreat selama tiga tahun. "Dalai Lama pernah bilang, reinkarnasi ke badan wadag lain bisa dilakukan dengan sadar. Saya ingin mengungkapkannya, dan berniat melakukan reinkarnasi dengan kesadaran penuh." Tiba-tiba pintu bilik terbuka. Seorang biksu muncul, dan segera mengusir Thukral dengan kasar sembari memarahi biksuni yang gundah itu. Thukral jadi salah tingkah. Lalu angkat kaki dari situ, menuju pasar. Ia dibikin bingung oleh perangai wanita aneh itu. Tampaknya, ia tenggelam dalam sebuah masalah, meskipun mengaku menemukan kedamaian dalam Budhisme. Di pasar, Thukral ketemu lagi dengan para hipis. Ada yang sedang. main band di sebuah restoran. Nama band itu: The Subterranean Vajra Hammer, dan musik rock menghentak menggoyangkan atap warung kaget itu. Suasana lebih hiruk-pikuk sewaktu Thukral memasuki ruangan. "He, he, inilah wartawan kita! Datang lagi pekik mereka. Thukral menyodorkan cokelat sebagai suap, baru dibolehkan memotret. Jengah di situ, wartawan kita ngeloyor ke lembah lagi, menuju perpustakaan di balik kuil. Di sana ia bertemu dengan seorang biksu yang, seperti biasa, tampil dengan tampang bersahabat. Bule berjubah itu rupanya dari Swiss. "Tapi saya sudah menetap di sini 11 tahun. Ingin melihat-lihat perpustakaan? Mari, mari, saya antar." Namanya George- nama Kristennya. Sederet buku hampir memenuhi ruangan, dan tampak bule-bule duduk di bangku menekuni teks. "Koleksi komplet karya Tibet ada di sini," kata George alias Sangye Sandurp. "Ketika saya datang ke sini, dulu, kondisinya masih sulit. Sekarang sudah ada perpustakaan, para guru, dan tempat bagi orangorang Barat." Sandurp lalu mengajak Thukral ke biliknya, yang terpisah dari biara. Di tengah jalan ia bertutur lebih banyak mengenai dirinya. "Saya datang ke India hanya untung-untungan. Waktu itu saya di Turki, Istambul, dan setiap orang kok selalu berniat ke India. LaJu saya berkemas, dan pergi juga. Eh, di India saya malah kecewa. Sebab, orang-orang sangat membosankan. Apalagi, kalau kita tak bisa berlaku sebagaimana yang mereka kehendaki... Bah! Dan makanannya...,"ia tak melanjutkan, hanya nyengir. "Atau barangkali karena saya berharap terlalu banyak." Hampir saja ia mudik ke Swiss, digenjot kondisi seperti itu, katanya. Kemudian di Benares (Varanasi), George bertemu dengan seseorang yang baru saja dari Dharamshala. Orang itu menuturkan kepadanya segala kemolekan kawasan pemerintahan Dalai Lama di pengasingan itu. Termasuk promosi iklim dan makanannya yang bakal cocok bagi George. "Sebelum sampai ke sini, saya agak tertarik juga pada Hinduisme, dan membaca sedikit tentangnya. Tapi lantaran atmosfer India yang begitu, Hinduisme menjadi tak ada apa-apanya buat saya." Di tembok, di atas dipannya, tergantung potret Dalai Lama. Thukral menunjuk gambar itu, dan menanyakan sikap biksu Swiss ini. "Saya takzim kepadanya. Jelas, beliau patut kita junjung tinggi .... Seorang yang begitu bijaksana dan welas asih. Saya bertemu dengan beliau, yah sekali setahun. Ini pertemuan pribadi. Kalau ketemu ramai-ramai dengan orang lain, sih, biasa. Bukankah beliau sering mengadakan pengajaran umum? Beliau sangat sibuk. Kalau tidak menemukan persoalan yang sangat mendesak, saya tak berani mengganggu." Apakah para biksu kulit putih itu akan menetap di Dharamshala untuk selamanya? Atau sekadar beberapa tahun? Jawabannya antara lain dikemukakan George. "Tinggal selamanya di sini?" katanya, balik bertanya. "Oh, tidak. Barangkali sekitar tiga tahun lagi. Saya ingin belajar menjadi gashay. Kalau di universitas, semacam dokter. Lantas akan mudik dan mengajar di Vevey, Swiss. Ini pusat pengajaran untuk orang kulit putih. Saya bisa menerjemahkan atau melakukan hal lainnya di sana. Tapi, bagaimana takdir saja ...." Seperti semua penghuni McCleodganj, George tak memiliki gambaran yang jelas tentang masa depan. Dicekam rindu ke kampung halaman, dan tentu bisa pulang kapan saja, toh kepastian selalu tak muncul. Begitulah adanya. Sebab, masa depan apalah artinya
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini