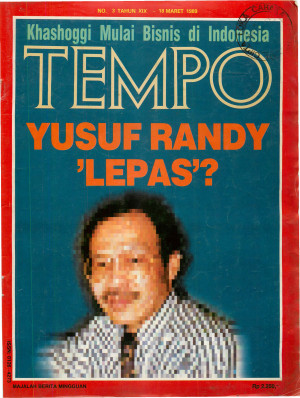Indusri tidak hanya mencetak uang, tetapi juga maut. Bencana kebocoran gas di Bhopal merengut 3.323 nyawa, 100 ribu masuk rumah sakit, ribuan jadi buta. Reaktor nuklir di Chernobyl bocor, seluruh Eropa panik. Teluk Minamata dicemari methyl mercuty, 2.062 menjadi korban -- sepertiganya meninggal. Jutaan ikan di Sungai Rhine mati dibunuh limbah pabrik obat Sandoz. Dunia sudah ternoda, Indonesia pun cemar. Negara maju membuang limbah beracun ke Dunia Ketiga -- celakanya, disambut menggebu, karena haus doku. PETAKA kematian masal merayap diam-diam. Berserak ke seluruh pelosok dunia, beringsut-ingsut dari neara maju ke Dunia Ketia. Ia melemparkan senyumnya yang menggiurkan: uang. Tapi dibalik topengnya yang mempesona, terlempit rapi targetnya sebagai pembunuh kejam yang berdarah dingin. Siapa lagi dia kalau bukan apa yang kita sebut: industri. Tengah malam di bulan Desember 1984 itu, misalnya. Rani Chabra yang sedang hamil delapan bulan, pedagang rokok Raj Kumar Sahu, dan ratusan ribu warga Bhopal, India, lainnya terlelap tidur dalam gubuk mereka. Tiba-tiba gas methyl isocyanate melayang pelan-pelan meninggalkan tangkinya yang bocor, lalu membalut seluruh kota dengan selimut maut. Bencana pun pecah. Tak tersangka, dalam sekejap, Bhopal berubah menjadi kamar gas raksasa. Dengan amat keji, kabut gas mencekik pernapasan, membakar penglihatan, dan memuntahkan nahas pada penduduk. Mayat bergelimpangan di jalan dan rumah-rumah. Penduduk terkejut, bangun, terhuyung, muntah-muntah, sambil menahan rasa sakit yang bukan alang-kepalang. "Saya sulit bernapas," kata Rani mengenang. Raj Kumar pun terus terteror oleh "neraka" itu sampai sekarang. Saban terbangun pagi, ia masih merasa ada kabut yang melayang membakar matanya. Orang boleh saja cuek: tragedi Bhopal toh sudah berlalu. Lima tahun sudah lewat. Tapi bisakah 1.600 korban jiwa saat itu -- menjadi 3.323 orang hingga November tahun lalu -- dihapuskan, untuk kemudian dilupakan sama sekali? Bisakah malapetaka terburuk dalam sejarah industri itu dianggap tak pernah ada? Sedang sampai sekarang, masih 100 ribu jiwa yang harus terus dirawat. Ribuan di antaranya telah menjadi buta. Memang, tak semua industri berbakat sebagai pembunuh raksasa seperti yang terjadi di Bhopal. Namun, sebagian besar punya kesalahan awal yang sama: mengabaikan risiko yang mungkin datang. Union Carbide, misalnya. Waktu baru menapakkan kaki di India di tahun 1977, mereka nampak mulia, bagai pahlawan yang akan memberi penghidupan pada penduduk. Niat luhur itu pun memang nyata dilakukan. Karena itu, mereka disambut baik oleh pemerintah dan masyarakat. Tapi niat yang penuh kemanusiaan tersebut sebenarnya bungkus. Alasan sesungguhnya mereka memilih Bhopal, karena upah buruh rendah dan risiko kecil. Di India, seperti juga di Indonesia dan negara Dunia Ketiga lainnya, tenaga manusia murah. Sekaligus pasar empuk untuk menjual DDT -- pestisida yang sulit terurai secara bebas. Plus tidak perlu sungkan-sungkan untuk ceroboh hal yang sulit dilakukan di Amerika Serikat dan negara maju lain, karena mereka cerewet terhadap urusan pestisida dan pengamanan industri. India tak peduli dengan racun dan kecerobohan, sebelum itu kemudian berkembang menjadi malapetaka. Kecerobohan industri yang melahirkan bencana bukan hanya monopoli Union Carbide dan Dunia Ketiga. Di wilayah Eropa juga, tiba-tiba saja awan radioaktif membubung, menyerang Swedia dari arah Uni Soviet. Para pejabat Swedia sempat kebingungan, tak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tak ada penjelasan resmi sampai kemudian ada berita kecil dari TASS (kantor berita Uni Soviet) bahwa telah "terjadi kebocoran di reaktor nukiir di Chemobyl utara Kiev, ibu kota Ukraina, pada 26 April (1986)". Sepotong berita itu langsung menjadi "ledakan dahsyat". Seluruh penduduk Chemobyl diungsikan. Berapa jumlah korban langsung tak diungkapkan. Namun, yang kemudian membikin teror justru debunya. Debu radioaktif itu membubung tinggi, membentuk awan yang melebar hingga 1.600 km, mencapai Skandinavia. Debu itu juga dibawa angin sampai di Alaska, Pegunungan Alpen di pusat Eropa, bahkan melintasi Siberia menyerbu Jepang. Ancaman radiasi lewat debu itu membikin panik Eropa. Industri dan perdagangan susu macet, lantaran susu dianggap mudah tercemari radiasi itu. Stok susu yang ada di gudang-gudang negara Barat hanus dibuang. Swedia melarang penduduk di wilayah timur meminum air hujan. Warga Denmark antre di apotek-apotek untuk membeli pil yodium, buat mencegah unsur radioaktif terserap ke kelenjar thyroid. India mengembuskan gas beracun, Soviet melontarkan radiasi, dan Jepang mengotori lautnya dengan racun yang mematikan. Sebutlah misal, nasib yang menimpa keluarga Hammamoto. Juga derita nelayan-nelayan lain yang menggantungkan hidup pada ikan di Teluk Minamata yang tenang. Sebagai orang Jepang, keluarga Hamamoto penyantap ikan. Malah -- karena penghidupannya -- mereka makan lebih dari kelaziman orang Jepang yang rata-rata 200 gram sehari, setiap orang. "Sehari-hari kami makan ikan olahan dan shasimi," kata Tsuginori Hamamoto. Shasimi adalah ikan mentah yang dicelupkan ke dalam bumbu-bumbu. Shasimi itulah yang mengundang petaka. Tahun 1951, ayah Tsuginori meninggal dengan cara mengenaskan. Berhari-hari ayahnya kejang, terkena serangan saraf, sampai "dia diikat kuat-kuat di atas tempat tidur". Sepuluh tahun kemudian, ibunya pun menyusul, dengan mengalami penderitaan serupa. Tapi Tsuginori terus juga makan shasimi. Serangan misterius itu berkelanjutan menyergap semua pemakan ikan Minamata. Termasuk Tsuginori. Pada usia 17 tahun, ia mulai merasa sakit. Mula-mula tangannya terasa kebal, kemudian makin parah, sehingga ia tak merasakan lagi apa yang dipegangnya. Sesudah itu, tremor pun menyerang. Ia menjadi gemetar, sampai air minum dalam gelas pun tumpah-tumpah saat ia sedang minum. Penderitaan itu bukan hanya ditanggungkan keluarga Hamamoto. Setidak-tidaknya sudah 2.062 orang terdera -- sepertiganya meninggal. Setelah heboh, semuanya baru sadar: ikanlah perantara petaka tersebut. Ternyata, seluruh Teluk Minamata telah tercemari air raksa dalam bentuk methyl mercury. Yakni bahan buangan yang berasal dari pabrik Chisso Corp., yang memproduksi acetaldehyde. Methyl mercury mampu menembus tubuh janin, hanya karena sang ibu yang mengandungnya memakan ikan yang tercemari oleh air raksa itu. Perkara limbah juga pernah menggemparkan Eropa. Sungai Rhine, yang melintasi beberapa negara, mengalir tenang. Airnya yang jernih seolah mengisyaratkan kedamaian. Tapi, di tahun 1986, sungai itu mempersembahkan kengerian. Mendadak jutaan ikan di Sungai Rhine menggelepar dan mati. Pemerintah Prancis -- negara yang paling panjang dilalui Rhine -- juga Belanda serta Swiss, tempat sungai itu berpangkal, menjadi kelabakan. Biangnya ternyata Sandoz. Sebuah perusahaan obat-obatan ternama yang berpusat di Basle, Swiss, yang membuang limbah pabrik ke aliran sungai. Demikian juga agaknya industri kimia lainnya, di kawasan itu. Menurut angka yang disebut The Sunday Times Magazine, setiap tahun Rhine menumpahkan 100 ton racun logam berat, ke Laut Utara. Tidak cukupkah semua itu menjadi bukti bahwa industri telah membunuh manusia. Di Indonesia sendiri, selain memang berhasil memberi keuntungan finansial, atribut negeri maju itu mulai menjadi momok bagi kehidupan sekitar. Kasus PT Inti Indorayon Utama (IIU), misalnya. Pabrik pulp di Porsea, Sumatera Utara, ini bikin heboh. Masyarakat mengeluh: IIU membuang limbah hitam kecokelatan ke Sungai Asahan. "Aku tidak tahu ke mana harus mengadu," kata A. Panjaitan, pencari ikan di sungai itu. Katanya, jumlah ikan susut (TEMPO, 24 September 1988). Keluhan Panjaitan belum apa-apa. Nery Sitorus harus menanggung derita yang lebih getir. "Air sungai itu lengket kental, dan gatalnya bukan main," kata Sitorus, 65 tahun, yang bertahun-tahun mandi di sungai itu. Lalu, setelah sungai tercemar limbah, kulit Sitorus gatal. Kulit itu berair dan berdarah bila digaruk. Seminggu kemudian, bintik merah hitam muncul di tengkuk. Lalu berubah menjadi bisul kecil bernanah. Hal serupa juga menimpa seorang bayi. Dedy, nama orok yang baru berumur 3 bulan itu, menjadi rajin merengek setelah dimandikan oleh ibunya, Minta boru Malau, dengan air sungai. Beberapa hari sesudahnya, sekujur tubuh Dedy dipenuhi bisul-bisul sejenis yang terdapat pada tengkuk Nery. "Padahal, sebelum saya memandikan dia," kata Minta, "air itu saya masak dahulu." Minta tak tahu: limbah industri bukan bakteri yang kehilangan daya ganggunya -- lantaran mati -- setelah direbus. Ada adonan -- natrium karbonat, natrium sulfat, dan soda api, buat mengolah kayu pinus untuk dijadikan pulp -- telah dimuntahkan begitu saja ke aliran sungai dalam bentuk limbah. Maka, keasaman air Asahan pun melonjak. Dalam pemeriksaan laboratorium, derajat keasaman di hilir pabrik mencapai angka 9,4. Padahal, sebelumnya hanya 7,9. Industri yang hanya menguntungkan sepihak itu tidak hanya mengancam kehidupan ikan Asahan dan penduduk sekitarnya. Ia juga menghantam investasi lain yang lebih strategis dan leih berharga: turbin PLTA Sigura-gura dan Tangga yang dibangun dengan dana 2 milyar dolar AS -- sepuluh kali lipat harga IIU. Seorang pejabat Otorita Asahan yang menolak disebut namanya menyatakan, "Jika limbah itu terus mengucuri Sungai Asahan, turbin PLTA Sigura-gura dan Tangga akan segera hancur dimakan karat." IIU kini digugat oleh Walhi -- Wahana Lingkungan Hidup. Perkaranya disidangkan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Perkara ini bukan satu-satunya kasus limbah yang mengotori Indonesia. Para pencinta lingkungan ingat apa yang terjadi di Teluk Jakarta beberapa tahun lalu. Bayang-bayang Minamata (lihat Kebusukan Bisnis Pembuangan Limbah) tiba-tiba saja muncul. Merkuri, kabarnya, mulai mencemari kerang dan ikan yang kemudian dikonsumsi warga Ibu Kota ini. Rasa cemas pun menyergap, ketika diketemukan sosok anak-anak yang debil dan rusak saraf di perkampungan nelayan Jakarta. Korban Minamata di Teluk Jakarta? Banyak orang tak yakin. Tapi Dokter Meizar B. Syafei -- tokoh paling aktif dalam kasus ini -- percaya betul: itu gejala peracunan laut. "Hentikan sumber polusi Teluk Jakarta sekarang juga," ujar Dokter Meizar. "Kalau tidak, kita akan menghadapi kasus Minamata di negeri kita." Boleh jadi, rasa khawatir itu berlebihan. Namun, mengabaikannya sama sekali sudah keterlaluan. Tingkat pencemaran industri selalu lebih besar dari yang terberitakan. Juga di Indonesia. Kita tak tahu persis, berapa tingkat pencemaran Kali Surabaya. Penggelontoran sungai itu beberapa waktu lalu sama sekali tidak memperbaiki kualitas air. Padahal, air itulah yang mengaliri rumah-rumah penduduk Surabaya. Yang didapat dari penggelontoran hanya efek politis. Yakni agar Bank Dunia bersedia meminjamkan dananya buat proyek penjernihan air minum di Surabaya. Lalu semua bangga: "kita punya proyek." Kita sudah terbiasa, tak peduli pada keganasan industri. Debu pabrik selalu membubung di kawasan udara Cakung -- menghalangi mata untuk melihat birunya langit. Di hari yang cerah sekalipun. Debu semacam itu juga yang telah memutihkan atap-atap rumah, kebun, jalanan, dan menyesaki napas di sekitar Cibinong di Jawa Barat dan Gresik di Jawa Timur. Pada sejumlah pabrik tekstil, serat-serat kapas lembut terisap masuk paru-paru buruhnya. Sedang di beberapa usaha pengawetan kayu, bahan-bahan kimia pun memperpendek usia pekerjanya. Kalaupun ada reaksi terhadap soal itu, paling hanya reaksi sesaat. Sedangkan polusi jalan terus. Tak ada penyelesaian. Repotnya, ada kecenderungan industri berbahaya dipindahkan ke negara Dunia Ketiga. Negara kaya tak hendak meracuni penduduknya sendiri. Namun, negara lain biar mampus saja seperti Union Carbide di Bhopal. Edan memang. Celakanya, yang memperparah keadaan justru sikap negara berkembang sendiri. Mereka -- tak terkecuali Indonesia -- berlomba-lomba untuk menarik investor asing ke dalam negerinya. Soal lingkungan sering menjadi nomor dua. Itu seperti memacu banyak penanam modal, lalu enggan mengeluarkan sedikit uang -- jika dibanding nilai total investasi -- untuk mengamankan lingkungan dari keganasan industrinya. Yang lebih mencemaskan, negara-negara maju punya cara baru meracuni Dunia Ketiga dengan industri. Mereka tidak lagi bersiasat: bikin pabrik di negara tertentu dan membuang limbahnya di negara itu juga. Mereka melakukan hal yang lebih langsung. Yakni, kirimkan saja limbah beracun, yang di negaranya sendiri ditolak, ke negara berkembang yang mau menerimanya dengan upah murah (lihat Kebusukan Bisnis Pembuangan Limbah). David Weir, Direktur Eksekutif Center for Investigative Reporting, San Francisco, pernah melacak soal ini. Ia dibantu rekannya, Andrew Porterfield. Dalam lacakannya, Weir dan Porterfield menemukan dua bersaudara Colbert di New York. Colbert menyimpan berbagai jenis limbah berbahaya, pestisida kedaluwarsa, cairan-cairan kimia yang sudah tak terpakai dari berbagai wilayah bagian timur Amerika Serikat. "Dalam sejumlah kasus," tulis Weir, "mereka mengubah label limbah itu seolah sebagai bahan kimia mumi." Bahan-bahan itu lalu dijual pada beberapa perusahaan -- dan bahkan pada pemerintah -- di negara Dunia Ketiga. Di antaranya ke India, Korea Selatan, dan Nigeria. Jejak Colbert baru terendus sewaktu mereka mengapalkan limbah ke sebuah perusahaan di Zimbabwe. Mereka mengatakan mengirim dry cleaning solvent ke sana. Dy cleaning mbahmu, itu limbah maut. International Organization of Consumers Unions (IOCU), yang berpangkalan di Penang, Malaysia, juga mengerdipkan alarem untuk kasus ini. Juni 1988, menurut siaran pers IOCU, pemerintah Muangthai mengumumkan: mereka menemukan barang haram, limbah beracun, dalam kontainer di pelabuhan Klong Toey. Barang-barang itu berasal dari pengirim "tak dikenal" di Singapura, AS, Jepang, Jemman Barat, dan Taiwan. Buangan limbah dari negara maju juga bakal tumpah di Indonesia. Ini menurut Zaim Saidi, staf peneliti Yayasan Lembaga Konsumen (YLK). Ia mengatakan itu ketika membahas soal iradiasi makanan -- hal yang dikampanyekan besar-besaran oleh negara maju. Teknik iradiasi, juga untuk makanan, membutuhkan cobalt atau radioisotop lain. Bila negara berkembang mengesahkan iradiasi makanan, maka negara itu membutuhkan cobalt. "Cobalt diperoleh dari limbah reaktor nuklir," kata Zaim. "Kalau mereka (negara maju) bisa mencari jalan keluar pembuangan limbahnya, mereka akan lebih mengembangkan reaktor nuklirnya." Hal itu berbahaya. Maka, YLK terus menentang makanan iradiasi -- masyarakat negara maju pun emoh menyantapnya. Membanjirnya limbah beracun ke negara berkembang ada beberapa sebab. Salah satunya, yang disebut David Weir, adalah biaya. Di AS, ongkos pembuangan limbah beracun naik tajam. Tahun 1976, ongkos itu cuma 10 dolar AS setiap ton limbah. Tapi sekarang ongkos itu melesat hingga 140 dolar "atau lebih". Padahal, tahun 1984 saja, Amerika menghasilkan 247 juta ton limbah beracun. Apalagi tempat penimbunan sampah di sana mulai penuh. Maka, ketika ada pemerintah -- atau perorangan secara sembunyi-sembunyi -- di negara berkembang mau menerima dengan biaya murah, tong limbah pur digelindingkan ke sana. Ada negara yang sengaja mengais rezeki dengan cara itu. Honduras, misalnya. Negara itu tak menandatangani Konvensi Hukum Laut Internasional. Padahal, konvensi itu melarang pembuangan limbah beracun dan berbahaya di perairan internasional. Berarti, mereka menyediakan lautnya buat pembuangan limbah. Tapi, dalam praktek, mereka pun tak ingin lautnya tercemar. Mereka-lalu memanfaatkan ketidakterikatannya pada konvensi itu dengan cara lain. Yakni menyewakan kapal. Bukankah negara-negara maju juga munafik: menolak keras membuang limbah yang terus diproduksinya -- di laut milik sendiri, tapi dengan senang hati melemparkannya ke laut orang lain. Maka, mereka, menurut istilah kelompok Jaringan Dunia Ketiga, "bermain mata dengan petualang-petualang dari negara seperti Honduras itu." Perlahan dan pasti, ancaman itu bakal mencekik Indonesia pula. Industri demi industri bertumbuhan. Mungkin dengan derajad kecerobohan yang tak lebih baik ketimbang Union Carbide di Bhopal. Lalu akan kita biarkan saja, kematian masal itu merayap diam-diam, membetoti nyawa kita. Akan kita biarkan sajakah "Bhopal dan Minamata kedua" terjadi? Kalau tidak, dengan cara bagaimana? Zaim Uchrowi
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini