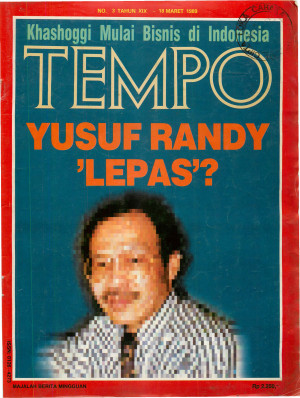INDONESIA nyaris menjadi kuburan. Kapal Felecia berbendera Honduras dengan muatan 14.000 ton limbah beracun buangan industri, tahun lalu, telah mengarahkan moncongnya ke Indonesia. Pemerintah diharap berlapang dada menerima kiriman racun dari sebuah pabrik kimia di Philadelphia, Amerika Serikat. Untung, tawaran itu ditolak mentah-mentah oleh Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup Emil Salim, kendati dijanjikan akan dibayar mahal. Memang baru satu kue kematian seperti itu yang dijajakan ke Indonesia. Namun, limbah-limbah beracun dari negara industri, sejenis yang diangkut kapal Felecia, sudah merupakan persoalan jamak. Jauh sebelumnya, kapal Karin B juga memuat limbah beracun berton-ton. Kapal ini pun sekitar setahun lamanya mencari sebuah negara yang mau dijadikan kuburan dengan bayaran tinggi. Akhirnya, ia kembali ke negara asalnya, karena tak satu pun negara yang bersedia menerimanya. Ketidakberhasilan membuang limbah beracun itu hanya sebagian kecil kegagalan bisnis jasa pembuangan. Banyak fakta pembuangan yang berhasil, dengan bayaran mahal, yang hanya diketahui oleh pelaku bisnisnya. Tapi sepandai-pandainya menyembunyikan bangkai, bau busuk tak bisa terbendung. Bisnis jahanam itu akhirnya mencuat juga ke permukaan. Misalnya, 15.000 ton abu sisa pembakaran limbah industri dari Philadelphia, Amerika Serikat, yang ditimbun di Pulau Kassa, Kepulauan Guinea. Sebuah perusahaan dari Norwegia menjadi perantara pembuangan itu. Penerima limbah memperoleh imbalan 40 dolar AS per ton abu yang mengandung bahaya tersebut. Padahal, limbah itu kalau dibuang di Amerika Serikat sendiri, perusahaan bersangkutan mesti mengeluarkan setidaknya 1.000 dolar AS per ton, sesuai dengan peraturan setempat. Limbah kimia dari Italia, yang diduga limbah radioaktif, pun dibuang dengan menggunakan perusahaan jasa pembuangan limbah. Sekitar 4.000 ton limbah itu ditimbun di pelabuhan Koko, Nigeria. Limbah yang di antaranya mengandung dioxin dan polychlorobiphenyl (PCB) itu dikemas dengan drum-drum. Sejak September 1987, drum-drum itu dikirim sedikit demi sedikit, secara bertahap. Pengusaha dari Italia, bekerja sama dengan pengusaha di Nigeria, membayar pemilik depot di pelabuhan sekitar 250 dolar per bulan. Penjaga depot hanya bertugas menyimpan drum-drum itu, tak lebih. Tampaknya, cara itu mulus. Dan Italia merencanakan mengekspor 100.000 ton lagi, limbah farmasi, industri, PCB, exhausted earths, serat asbes. Uni Soviet kabarnya juga sudah mengekspor limbah radioaktif ke Benin, Afrika Barat, antara tahun 1984 dan 1986. Buletin Afrika Newsfile, Juli 1988, yang berbasis di London, mengutarakan bahwa Soviet membuang limbahnya di bawah lapisan aspal lapangan udara militer yang dibangun pemerintah Soviet di Canna, sekitar 15 km sebelah selatan Abomey. Lalu ada pula limbah radioaktif yang dibuang Soviet di Dan, sekitar 25 km sebelah utara Abomey, di sebuah tambang batu bara yang telah ditinggalkan. Area itu kemudian dinyatakan tertutup, dengan dalih sebagi "zone militer". Berita-berita tentang "hadiah" limbah terkutuk tersebut cenderung cepat menguap begitu saja. Berbeda halnya dengan berita "kemuliaan hati" negara maju, berupa berbagai bantuan -- entah melalui IGGI, IMF -- kepada negara-negara Dunia Ketiga. Ini terdengar licik, tetapi begitulah kenyataannya. Syukurlah, banyak negara industri, dalam sepuluh tahun terakhir ini, mau sadar bahwa limbah yang beracun itu adalah ajal buat yang mereka terciprati. Untuk mengamankan, menetralkan sehingga tak menjadi bahaya lagi, butuh biaya tinggi. Limbah radioaktif dan limbah nuklir boleh dikata tak mungkin diolah jadi netral. Bagaimanapun kuat kemasannya, berlapis-lapis beton tempat pembuangannya, dua macam limbah itu tetap berbahaya. Seperti zat kimia beracun lainnya, dua jenis limbah itu pada umumnya memiliki daya tahan hidup lebih lama ketimbang tempat pembuangannya. Bayangkan apa yang bakal terjadi bila kemasan limbah bocor. Zat beracun itu akan menyatu dengan udara. Atau masuk ke bumi, dan tanah terkontaminasi. Tetumbuhan mampus atau tetap hidup tapi mengandung racun. Bila dibuang ke badan sungai atau laut, ekologi air pun rusak. Dan pada gilirannya manusia juga musnah. Di tahun 1940-an, perusahaan Hooker Chemical mulai menimbun beribu-ribu drum -- berisi eks macam-macam jenis bahan kimia maupun radioaktif -- di Love Canal, New York. Kuburan drum itu, 30 tahun kemudian, tumbuh menjadi tempat permukiman. Penduduk, yang tak tahu-menahu asal-muasal lokasi itu, tiba-tiba geger. Mereka mencium bau busuk. Lalu ketahuan, bau itu berasal dari cairan berlumpur yang merembes di lantai dasar rumah. Baru pada 1980, jelaslah akibatnya. Setelah kesehatan penduduk yang tinggal di atas diumumkan oleh pemerintah AS. Ternyata, banyak penduduk mengalami kerusakan kromosom (yang berpengaruh pada keturunan mereka), terkena kanker, kejang-kejang, keguguran. Pencemaran karena merkuti di Teluk Minamata, Jepang (lihat bagian pertama) telah menyebabkan beribu-ribu bayi lahir cacat atau didomplengi penyakit bawaan. Tak heran kalau industri yang menjadi biang kerok bencana itu harus membayar 200 juta dolar sebagai ganti rugi. Demikianlah, kendati tujuan industri semula adalah memproses bahan menjadi produk yang bermanfaat bagi manusia dan bernilai ekonomis, ia akhirnya buas. Sadar terhadap sulitnya mengelola limbah, negara-negara industri mengeluarkan peraturan ketat, yang memaksa industri harus mengolah limbahnya. Atau setidaknya menyimpan hasil samping industri yang beracun dan berbahaya seaman mungkin -- di samping harus membayar biaya pembersihan limbah yang dilakukan negara. Itu penting artinya dalam jangka panjang kalau tak ingin membuat terlalu repot generasi mendatang. Maka, perangkat teknologi negara industri makin berkembang untuk meminimkan limbah beracun berbahaya. Prancis, Inggris, Jerman Barat, misalnya, sudah dilengkapi dengan perangkat aturan pembuangan limbah yang amat ketat. Di Belanda, malahan hampir tak bisa membuang limbah karena sulit menghindari pengaruh limbah terhadap struktur air. Swedia dan Denmark pun menuntut teknologi pengelolaan limbah beracun yang cermat. Namun, industri yang mau memperhatikan sisa-sisa produksi berarti mengeluarkan biaya tambahan. Mahal. Badan Perlindungan Lingkungan di AS pernah mencatat, di antara 74.000 tempat pembuangan sampah, ternyata terdapat 32.000 yang keadaannya lebih buruk daripada Love Canal. Dan tak lebih dari 10 tempat yang memperoleh dukungan biaya besar -- menurut Presiden Dewan Kualitas Lingkungan AS, pada 1980, yakni antara 28 dan 55 milyar dolar AS. Pembersihan limbah di Love Canal saja cuma dipandu biaya 130 juta dolar. Dan jangan terkejut kalau ongkos buang sampah industri itu kemudian dibebankan pada harga produknya. Dengan kata lain, mesti dibayar konsumen. Sementara itu, persaingan dagang makin hari makin ketat. Maka, hitungan bisnis dengan orientasi untung -- tak peduli sampai keluar batasan moral -- ditekan ke tingkat paling praktis dan paling murah. Sesuai dengan kiat dagang: segalanya harus hemat. Dalam hal limbah pun sama saja. Mengolah limbah industri, menetralkan menjadi zat-zat yang tak berbahaya, itu mahal. Membuang limbah tanpa menetralkan terlebih dulu di negara sendiri pun memiliki risiko berat di masa depan. Orang lalu berpaling ke jalan lain: ekspor. Sasarannya, ya, siapa lagi, langganan tetap: negara-negara Dunia Ketiga, yang juga telah menjadi bulan-bulanan macam-macam bantuan itu. Bisnis empuk pun lahir. Menyediakan jasa membuang limbah beracun berbahaya ke negeri miskin. Tak semua usaha jasa itu terang-terangan. Malah kebanyakan berbentuk sindikat, seperti jaringan perdagangan narkotik dan sejenisnya. Masih mending kalau tampil sebagai industri yang mengolah limbah beracun supaya menjadi netral. Tapi industri seperti ini, di samping membutuhkan dana besar, teknologi canggih, pun harus tahan kritik dari kalangan pencinta lingkungan hidup. Mungkin karena sama-sama dikecamnya, akhirnya yang cenderung dilaksanakan justru membuang limbah dengan bantuan sindikat. Untung saja, hidung kelompok pencinta lingkungan hidup di Amerika Serikat, Greenpeace, cukup tajam. Pernah muncul semacam kesimpulan: "Limbah domestik dari AS diekspor ke Inggris dan dibuang di tambang-tambang tua secara sewenang-wenang." Seperti kata Ernst dari Greenpeace di Brussels. Ternyata, kendali usaha pembuangan limbah beracun cukup banyak yang bercokol di London. Termasuk perusahaan yang mesti bertanggung jawab atas ekspor limbah besar-besaran ke Guinea Bissau. Tapi bisnis limbah terbesar berpangkalan di New York, sebagaimana yang disinyalir oleh David Weir dan Andrew Porterfield (lihat Kematian Masal Mengancam Dunia). Wier dan Porterfield juga mengungkapkan cara pembuangan limbah lain yang lebih licik, atas nama pembangunan. Panama, misalnya, yang sedang punya proyek membangun jalan raya sepanjang pantai Panama, termasuk pembangunan hotel yang dibiayai sebuah perusahaan besar dari Norwegia. Untuk keperluan pembangunan itu, perusahaan dari Norwegia tersebut akan mendatangkan 250.000 ton abu asal Philadelphia, yang masih mengandung zat berbahaya, guna menimbun, sebelum landasan badan jalan dibangun. Pengusaha pembuang limbah diduga kongkalikong dengan pengusaha setempat, mungkin pula pemerintah. Negara-negara di Afrika, misalnya, cukup dikenal mau berembuk soal pembuangan limbah. Harga limbah bisa dirundingkan. Penawaran kebanyakan sekitar 40 dolar per ton. Di Eropa, biaya pembuangan limbah seperti itu 160 dolar sampai 1.000 dolar AS. Di Afrika Barat, seperti yang ditulis The Straits Times September 1988, hanya membutuhkan biaya 3 dolar AS per ton limbah. Itu bukan biaya menetralkan, tapi menimbun saja. Negara seperti Guinea Bissau setuju menyimpan sampah limbah kimia dari sekitar 12 negara di Eropa -- 3,5 juta ton setahunnya. Itu dijalin dalam kontrak selama 5 tahun, dengan imbalan 140 juta dolar AS per tahunnya. Untung, ada organisasi atau kelompok-kelompok yang siap menentang ulah yang merusakkan dunia itu. Misalnya Organisasi Kesatuan Afrika, yang Mei tahun lalu sudah mengecam penggunaan wilayah Afrika sebagai tong sampah. Mereka bikin resolusi. Di samping itu, mereka melakukan penyidikan. Hasilnya lumayan. Pada Juni 1988, sebulan setelah resolusi keluar, pemerintah Guinea Bissau mengakhiri perjanjiannya dengan tiga perusahaan di Eropa. Lalu sempat menangkap seorang pejabat Norwegia yang mengimpor abu beracun dari AS, dan memaksa agar Norwegia, yang mengirimi barang itu, memindahkan limbah tersebut dari Guinea. Kongo menangkap tiga pejabat yang -- seharusnya melarang semua usaha impor limbah beracun -- telah menyetujui menerima limbah beracun. Tapi jangan dikira bahwa penentangan terhadap pembuangan limbah beracun berbahaya itu selalu mulus. Ada korbannya. Misalnya yang terjadi di Benin, Afrika Barat. Presiden Benin, Mathleu Berekou, rupanya mengetahui persis bahwa ada pembuangan limbah radioaktif secara diam-diam di Benin. Tapatnya di bawah lapisan aspal lapangan udara yang dibangun pemerintah Soviet di Canna. Kepala Angkatan Udara Benin, Christophe Fandohan, yang getol berusaha menghentikan pembuangan radioaktif itu, tiba-tiba dipecat presidennya. Di samping itu, setidaknya ada dua orang pekerja -- pada pembangunan lapangan udara tersebut -- yang mati secara misterius dan tak pernah diungkapkan. Di tingkat internasional, perdagangan limbah beracun memang mendapat tantangan keras. PBB didesak untuk menyetujui suatu konvensi internasional tentang pengendalian limbah beracun berbahaya. Pertemuan untuk menggodok konvensi itu sudah terjadi dua kali, pada Februari dan Juni tahun lalu. Dan masih dilanjutkan, rencananya Maret ini, di Swiss. Para pakar lingkungan hidup Juli tahun lalu sudah menyepakati daftar limbah berbahaya yang mencakup 44 jenis. Kesepakatan pakar tersebut juga menyangkut soal ekspor-impornya. Misalnya, suatu negara yang mau impor harus memberi persetujuan secara tertis, sebelum dikapalkan. Pun harus menunjukkan bukti bahwa negara tersebut mampu mengatasi dan mengelola limbah yang diimpor -- bukan sekadar terima duit. Eksportirnya juga harus memberi keterangan jelas mengenai spesifikasi limbah yang dikirimnya. Maklum, limbah yang dihadirkan di negara Dunia Ketiga diperkirakan mencapai 300.000 ton sampah kimia per tahunnya. Parlemen Eropa sempat mengeluarkan resolusi yang melarang ekspor limbah dari Eropa ke negara Dunia Ketiga. Resolusi itu dipertimbangkan para menteri lingkungan hidup di MEE (Masyarakat Ekonomi Eropa). Namun, kemudian yang disetujui pertemuan para menteri itu, pada Juni 1988, ternyata justru menolak resolusi. Alasannya? Menteri lingkungan dari Jerman Barat dan Inggris berkilah, pelarangan itu tidak praktis dan tidak adil bagi negara yang mau menerimanya. Di Asia pun lantas muncul suara tentang limbah beracun. Pemerintah Muangthai, misalnya, telah menemukan limbah beracun yang ternyata berasal dari AS, Jerman Barat, Singapura, dan Taiwan. Limbah itu teronggok di pelabuhan Bangkok. Di Libanon (ini di Timur Tengah) juga ditemukan 2.411 ton limbah asal Italia yang dibuang sejak 1987. Filipina pun tak mau dengar ada limbah dari negara maju di wilayahnya. Maka, 8 departemen pemerintah Filipina, secara kompak, bersama-sama mengeluarkan peraturan larangan impor limbah beracun. Bagaimana Indonesia? Kita jelas unjuk sikap terhadap kapal Felecia. Juga sudah muncul perangkat Andal (Analisa Dampak Lingkungan), yang mewajibkan -- antara lain -- setiap industri memiliki studi kelayakan tentang efek sampingan produksinya. Tiap pendirian pabrik, investasi baru, tentu ditempel Andal. PT Chandra Sari dari lingkungan Ciba-Geigy, yang memperluas produksi -- zat pewarna reaktif pun mau tak mau membangun sistem pengolahan limbah, yang disebutnya sebagai zero polution. Andal tidak hanya gembar-gembor, tapi sampai memperkarakan. Hanya saja, sampai kini belum ada sebuah perusahaan pun yang keok di pengadilan, gara-gara pengelolaan limbah industri yang tak beres.Suhardjo Hs.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini