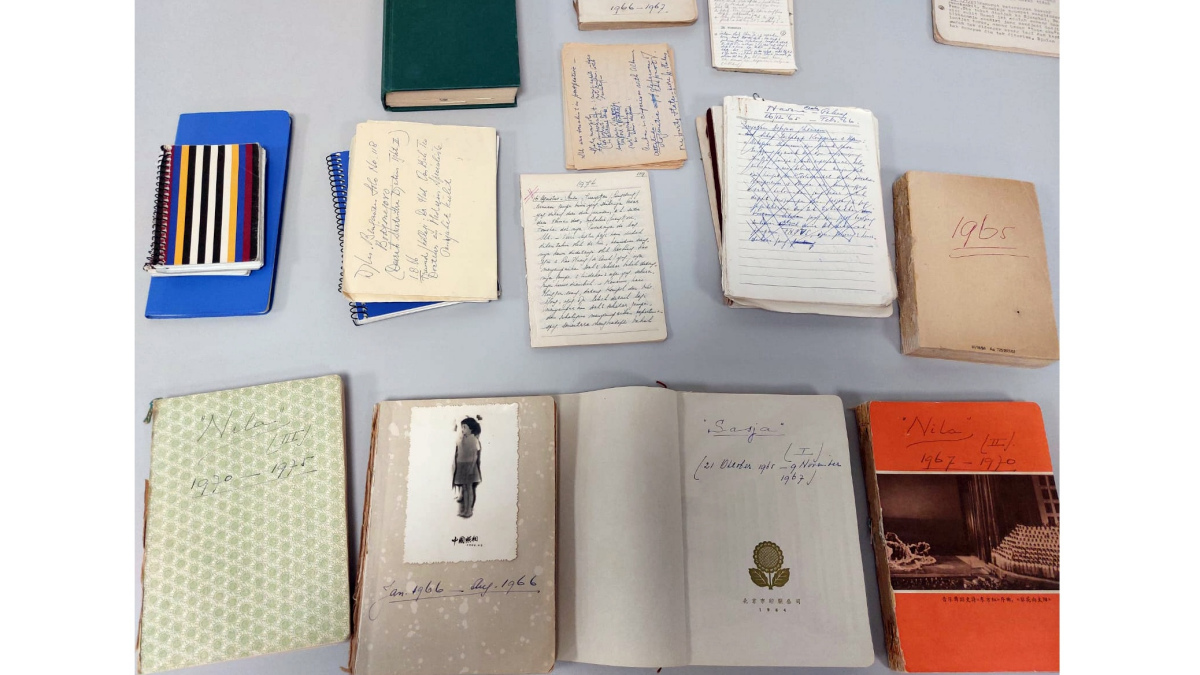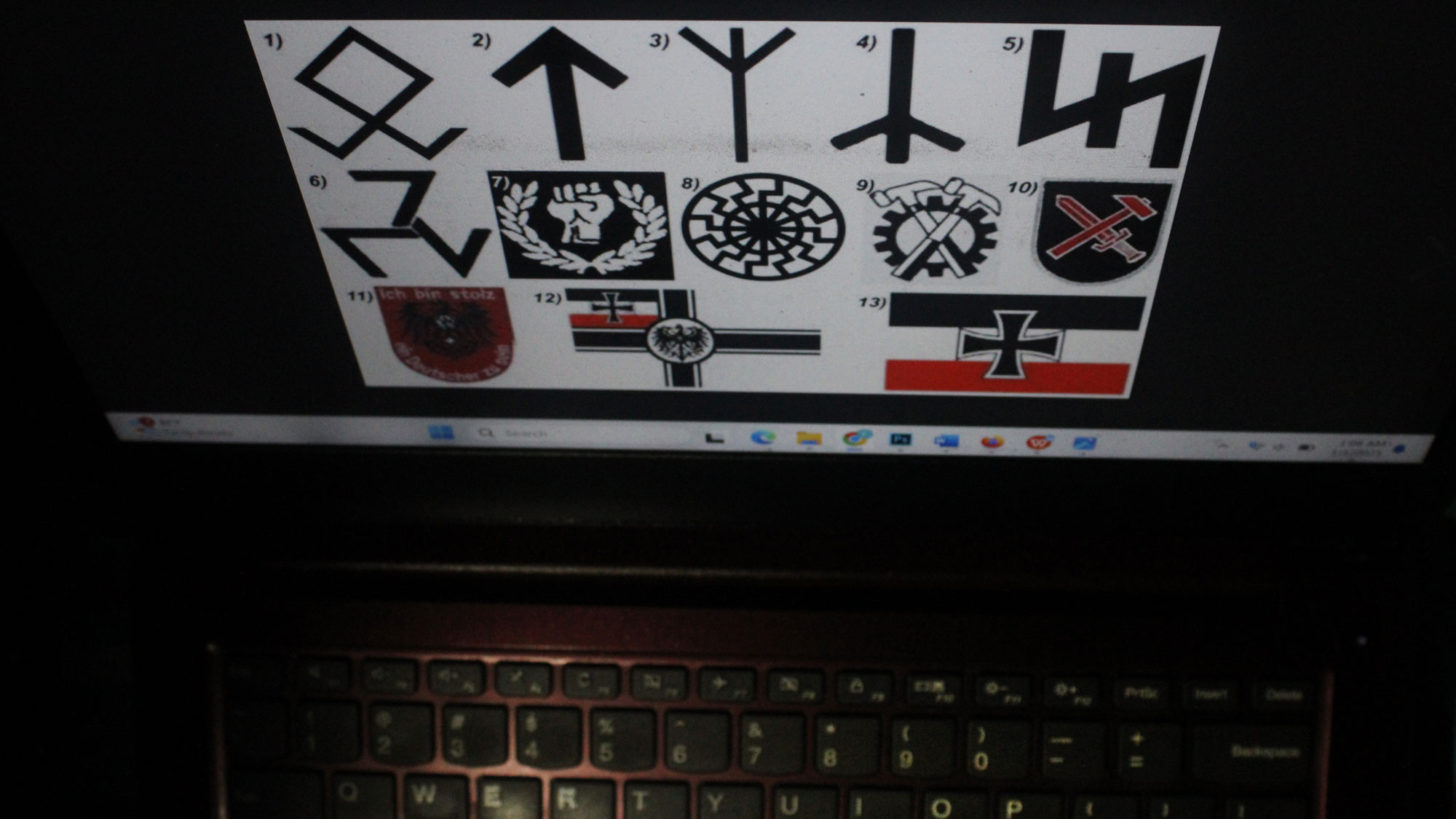Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Namun, sekitar tiga tahun belakangan, populasi rangkong gading terus menyusut. Pada 2015, sebuah lembaga konservasi internasional mengeluarkan status sangat terancam punah (critically endangered) untuk burung tersebut—satu tahap lagi menuju kepunahan. Tempo menelusuri habitat rangkong gading yang kian terancam dan memotret upaya pegiat lingkungan serta masyarakat setempat mencegah kepunahan burung enggang itu.

Kisah Rangkong Yang Terancam/shutterstock
CUACA cerah menemani Tempo, yang bersama beberapa peneliti, memulai penelusuran di kawasan hutan Desa Segitak, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, pada Ahad, 29 September lalu. Selama dua jam lebih perjalanan di dalam hutan itu, berbagai bunyi kicauan burung terdengar ramai bersahutan. Kicauan itu bagai konser paduan suara alam di hutan belantara pedalaman Kalimantan.
Namun, dari bermacam-macam bunyi burung itu, menurut para peneliti, tak terdengar sama sekali suara rangkong gading. Penelusuran di hutan untuk mengamati habitat rangkong gading hari itu rupanya tak berhasil. Hingga kami tiba di pondok grid B5—bangunan kayu yang menjadi tempat kami menginap—pada sore hari, suara rangkong itu tetap tak terdengar.
“Ada waktu tertentu suara rangkong gading bisa didengar,” kata Aryf Rahman dari organisasi nirlaba Rangkong Indonesia yang bertugas di Kapuas Hulu. “Meski demikian, waktu tertentu itu tak bisa pasti dijadikan ketentuan.”
Pada pertengahan September lalu, Aryf sudah sepekan lebih mengamati suasana hutan di kawasan Desa Segitak. Pada 16 September lalu, pukul 13.40, ia mendengar suara rangkong gading yang muncul dari arah dekat aliran Sungai Entibab, sekitar 300 meter dari pondok B5. Keesokan paginya, ia pun masih bisa mendengar kicauan tersebut, tapi terasa lebih jauh daripada sebelumnya.
Aryf mengungkapkan, pada 18 September, ketika asap kebakaran hutan yang diduga dari Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sintang terbawa angin dan melanda kawasan itu, ia sempat melihat rangkong gading sendirian bertengger di dahan pohon yang rendah. Padahal aktivitas burung ini biasanya hanya di pepohonan yang tinggi. Empat hari kemudian, saat asap tak ada lagi, Aryf juga mendengar suara rangkong gading dan enggang cula atau rangkong badak bersahutan pada siang hari.

Suasana hutan tempat pemantauan burung rangkong gading di Desa Segitak, Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, 30 September 2019./Tempo/Bram Setiawan
Setelah bermalam di pondok B5, menjelang siang esoknya, Tempo didampingi anggota Tropical Forest Conservation Act Kalimantan, Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia, dan Rangkong Indonesia menuju Bukit Belimbun. Bukit ini berjarak sekitar 15 menit berjalan kaki dari pondok. Aryf mengajak ke area itu karena di sana terdapat pohon ara, salah satu jenis tumbuhan Ficus yang buahnya menjadi pakan utama rangkong gading.
Selama satu jam pengamatan di area itu, tak ada rangkong gading yang hinggap. Demikian juga sampai siang, sebelum kami kembali ke kawasan permukiman Desa Segitak. Suara rangkong gading pun sama sekali tak terdengar sepanjang perjalanan ke luar hutan.
Meski mudah dikenali, rangkong gading boleh dibilang belakangan ini jarang bisa dijumpai, terutama sejak sekitar tiga tahun lalu. Pada 2015, International Union for Conservation of Nature mengeluarkan status sangat terancam punah (critically endangered) untuk rangkong gading—satu tahap lagi menuju kepunahan. Status tersebut dikeluarkan berdasarkan berbagai masukan yang bersumber dari data penelitian di Indonesia.
Populasi rangkong gading bisa ditinjau antara lain dari data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pada 2014, Kementerian Lingkungan Hidup menyebutkan luas total hutan di Kalimantan 26 juta hektare. Dari angka itu, potensi area yang diperkirakan menjadi habitat rangkong gading seluas 2,6 juta hektare.
Sumber penunjang data populasi juga dimuat dalam Strategi dan Rencana Aksi Konservasi (SRAK) Rangkong Gading. Dalam SRAK, tabel populasi menjelaskan estimasi pemetaan di Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah. Akumulasi estimasi temuan satwa menunjukkan angka 0,5-0,7 burung per kilometer persegi. “Artinya, kepadatan rangkong gading sangat rendah. Belum tentu ada satu burung rangkong gading per kilometer persegi,” ucap Yokyok Hadiprakarsa, pemimpin tim peneliti Rangkong Indonesia. Menurut Yok-yok, estimasi populasi rangkong itu diperoleh dari melihat langsung rangkong gading atau mendengar suaranya saja. “Faktanya, survei rangkong gading 80 persen berupa suara,” ujarnya. Ia menambahkan, bukti minimnya populasi rangkong gading di habitatnya juga didapatkan dari jumlah temuan kepala satwa tersebut yang hendak diselundupkan.

Rhinoplax vigil atau burung rangkong gading di Kalimantan./Rangkong Indonesia/Y Hadiprakarsa
RANGKONG gading adalah burung besar dengan bulu ekor bagian tengah memanjang. Dalam situs Rangkong.org disebutkan panjang burung bernama ilmiah Rhinoplax vigil ini, dari ujung paruh hingga ujung ekor, mencapai 180 sentimeter dengan bentang sayap 90 sentimeter dan berat tubuh 3 kilogram. Rangkong gading jantan memiliki kulit leher berwarna merah tanpa bulu, sementara kulit leher betina putih kebiruan.
Burung yang juga dikenal dengan nama enggang gading ini memiliki paruh simetris dan meruncing pada bagian ujungnya. Cula atau balung di bagian atas paruhnya padat berisi. Bobot cula itu sekitar 13 persen dari berat tubuhnya. Cula tersebut kerap digunakan dalam perkelahian memperebutkan buah ara, makanan utama burung jenis enggang ini. Yang menarik, suaranya yang mirip orang tertawa terpingkal-pingkal bisa didengar dari jarak hingga 2 kilometer.
Rangkong gading menghuni hutan tropis yang lebat dengan pohon-pohon besar dan tinggi di hutan dataran rendah serta hutan bawah pegunungan sampai ketinggian 1.500 meter di atas permukaan laut. Habitat rangkong gading bisa dijumpai di Semenanjung Malaya, Sumatera, Kalimantan, dan Thailand. Sejumlah populasi kecil terdapat di Myanmar.
Indonesia memiliki habitat rangkong gading terluas. Namun hanya pohon besar berlubang alami dengan bonggol khas di depannya yang dapat digunakan untuk bersarang. Bonggol tersebut dipakai sebagai pijakan induk rangkong gading saat memberi anaknya makanan di dalam sarang. Model sarang yang unik ini tidak ditemukan pada jenis rangkong lain.
Seperti semua jenis burung enggang, rangkong gading hanya memiliki satu pasangan selama hidupnya. Setelah menemukan lubang sarang yang tepat, burung betina akan masuk dan mengurung diri. Butuh sekitar 180 hari untuk menghasilkan satu anak. “Tahap bertelur, mengerami, menetas, sampai anak siap keluar dari sarang membutuhkan waktu selama enam bulan,” demikian dikutip dari situs Rangkong.org.
SEMUA jenis rangkong atau enggang dilindungi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Ada pula Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pun telah menetapkan Strategi dan Rencana Aksi Konservasi Rangkong Gading, yang berlaku selama sepuluh tahun.
Namun perdagangan gelap rangkong tetap saja berlangsung. Yokyok Hadiprakarsa menjelaskan, rangkong gading dianggap istimewa dibanding jenis enggang lain karena balung di bagian atas paruhnya. Materi pembentuk balung atau gading itu adalah keratin, seperti penyusun cula badak dan gading gajah. Dari penelusuran Rangkong Indonesia, ada kepala rangkong gading yang dijual utuh layaknya gading gajah. “Ada juga yang mengolah gading dari rangkong ini, digunakan sebagai medium ukiran,” kata Yokyok.
Yokyok menemukan rangkong gading sudah lama diperdagangkan ke Cina, yakni sejak era Dinasti Ming pada abad ke-14. Ia menjumpai sejumlah barang antik olahan dari kepala rangkong gading dijual lewat situs-situs lelang dunia. Gading rangkong diolah untuk dijadikan perhiasan, seperti gelang dan liontin. “Dulu hiasan itu kerap disukai kalangan bangsawan,” ujarnya.
Setelah lama tak muncul isu tentang perdagangan gelap kepala rangkong gading, pada 2011 upaya penyelundupan burung enggang itu banyak ditemukan di Indonesia. Berdasarkan data SRAK Rangkong Gading, diketahui ada upaya penyelundupan 1.368 kepala burung tersebut sepanjang 2011-2017. Menurut Yokyok, dari penyitaan diketahui kepala burung langka itu diselundupkan dari Pontianak ke Jakarta, juga ke Belanda, Hong Kong, Cina, dan Jepang.

Rumah betang di Dusun Sungai Utik, Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, 1 Oktober 2019./ Tempo/Bram Setiawan
ANCAMAN kepunahan rangkong gading menggugah kesadaran sejumlah kalangan untuk menjaga populasi burung enggang itu. Tak hanya dari lembaga yang punya perhatian terhadap konservasi, upaya mencegah kepunahan rangkong gading datang dari masyarakat adat setempat.
Bandi Anak Ragai alias Apai Janggut, misalnya. Tokoh masyarakat adat Dayak Iban di Dusun Sungai Utik, Desa Batu Lintang, Kecamatan Embaloh Hulu, Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, ini terus berjuang merawat hutan dan satwa di dalamnya. Bersama masyarakat, Apai Janggut menerapkan aturan adat larangan berburu semua jenis enggang, termasuk rangkong gading.
Apai Janggut menjelaskan, warga Dayak Iban di Sungai Utik menggunakan replika burung enggang cula sebagai simbol upacara adat untuk keperluan ritual, yakni gawai kenyalang. Dalam ritual gawai kenyalang, warga membuat tiang yang pada bagian atasnya dibentuk enggang cula menggunakan pahatan kayu. “Tidak ada kenyalang (enggang cula) sungguhan,” ujarnya. Ia menegaskan bahwa semua jenis burung enggang di hutan Sungai Utik dilindungi hukum adat. “Tidak boleh ditangkap, apalagi dibunuh.”
Hal serupa dilakukan warga di Desa Segitak. Meski belum ada kaidah resmi hukum adat ataupun peraturan desa seperti di Sungai Utik, warga setempat tak pernah berburu enggang. Mereka berpegang pada pengetahuan yang diwariskan leluhur.
Menurut Kepala Adat Desa Segitak, Vensensius Moksin, burung enggang cula dihormati warga keturunan Dayak Hulu Sungai di desa tersebut. Enggang cula dianggap sebagai pelindung roh leluhur. “Makanya enggang cula tidak boleh dibunuh, apalagi dimakan,” tuturnya. Warga Dayak Hulu Sungai menganggap segala hal sebagai penanda tentang kehidupan yang bersumber dari alam, termasuk suara enggang cula.

Serambi rumah betang di Dusun Sungai Utik, 1 Oktober 2019./Tempo/Bram Setiawan
Moksin mengungkapkan, warga setempat sedang berupaya memahami lagi pengetahuan adat warisan leluhur. Karena banyak orang tak dikenal berburu di kawasan hutan Desa Segitak, pengurus desa itu hendak menyusun hukum adat atau peraturan desa resmi. “Tidak hanya semua jenis enggang, tapi juga satwa lain yang dilindungi,” katanya.
Kawasan hutan di Desa Segitak memang tak begitu masyhur. Namun suasana alam hutan ini serta potensi keanekaragaman burung yang menghuninya boleh dibilang sangat memikat. Karena itu, Rangkong Indonesia menjadikan kawasan ini lokasi penelitian mereka. Organisasi nirlaba itu juga tengah mendorong potensi kawasan hutan di sana untuk ekoturisme yang menunjang kebutuhan konservasi lingkungan.
Menurut Yokyok Hadiprakarsa, ekoturisme bisa menjadi salah satu upaya masyarakat lokal untuk memantau populasi satwa di hutan. Ekoturisme juga dapat menjadi cara mengamati kehidupan rangkong gading. “Yang mengelola juga bisa menentukan tempat melihat burung tersebut,” ucapnya.
Peneliti burung dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Dewi Malia Prawiradilaga, menyebutkan ekoturisme bisa menjaga habitat rangkong gading. Keutamaan ekoturisme adalah keseimbangan ekosistem. “Bisa mempunyai manfaat ekonomi yang lestari untuk masyarakat setempat sekaligus menjaga hutannya,” ujar Dewi. “Pelaksanaan kegiatan ekoturisme sebaiknya mencakup pemantauan satwa.”
Boleh dibilang ekoturisme memang berbeda dengan watak pariwisata umum. Ada aturan yang benar bagi wisatawan untuk merasakan kealamian hutan yang ditelusuri. “Pendekatan alami yang tidak memanfaatkan pengubahan bentuk, misalnya pembangunan,” kata pelaku ekoturisme, Theodorus Libertus, dari Komunitas Pariwisata Kapuas Hulu.
BRAM SETIAWAN (KAPUAS HULU)
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo