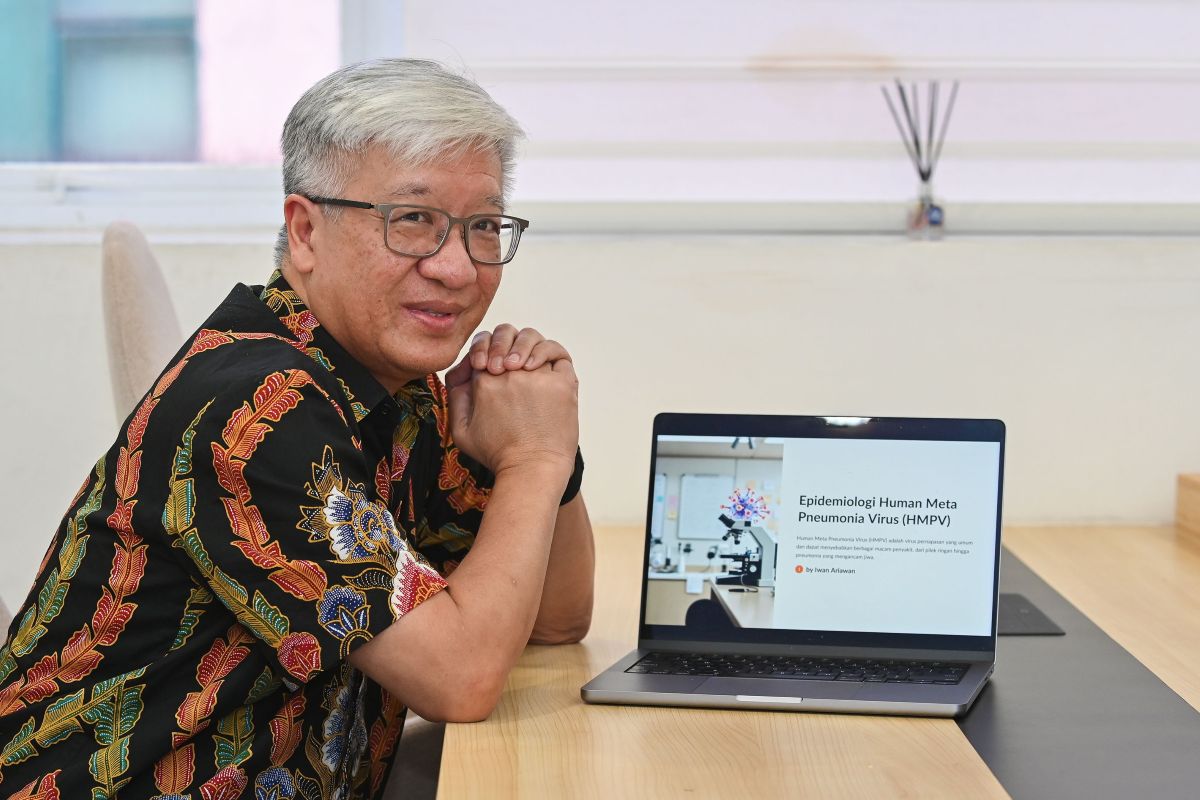Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
GELOMBANG demonstrasi mahasiswa September lalu memacu adrenalin Edward Aspinall. Indonesianis asal Australia yang memulai kariernya dari penelitian terhadap gerakan mahasiswa pada 1990-an tersebut tidak menduga gerakan semasif itu bisa muncul dalam hitungan bulan setelah pemilihan umum.
Aspinall, 51 tahun, mengatakan ada benang merah dalam semua gerakan mahasiswa Indonesia dari zaman ke zaman: kebebasan berekspresi dan pemberantasan korupsi. Pengajar Australian National University, Canberra, itu menuturkan, ada masa saat aspirasi tersebut bisa disalurkan lewat pemimpin dan wakil rakyat.
Namun politik identitas yang mengakar sejak pemilihan presiden 2014 dan politik uang yang terus dijalankan calon legislator membuat saluran itu tersumbat. Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat malah merevisi undang-undang yang dia nilai melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi, juga merevisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan sejumlah undang-undang lain. “Ada ketidaksinkronan antara apa yang dianggap penting oleh masyarakat dan apa yang terjadi di arena politik formal,” ujar Aspinall kepada wartawan Tempo, Aisha Shaidra, melalui sambungan telepon internasional, Jumat, 11 Oktober lalu.
Pertentangan antara elite politik dan masyakat itu antara lain tergambar dari perseteruan Arteria Dahlan, anggota DPR dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dan Emil Salim, guru besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Dalam program diskusi televisi Mata Najwa, Arteria naik pitam setelah Emil Salim menyampaikan pendapat berdasarkan sebuah buku yang menyinggung hubungan antara anggota legislatif dan politik uang. Buku itu adalah Democracy for Sale karya Aspinall dan rekannya asal Belanda, Ward Berenschot.
Dari penelitian terbarunya, Aspinall mendapati penurunan kualitas demokrasi ini tidak hanya terjadi di Indonesia. Tren yang sama terjadi di sejumlah negara yang masuk demokratisasi arus ketiga, yang beralih dari sistem monarki atau kediktatoran ke demokrasi pada 1970-an. “Dulu yang menumbangkan demokrasi adalah kelompok militer. Sekarang perongrongan justru dari pemimpin yang dipilih secara demokratis, seperti di Hungaria, Polandia, dan Filipina,” ujar Aspinall, yang pekan lalu dinobatkan majalah Research sebagai peneliti top dunia dalam studi Asia.
Fenomena apa yang Anda tangkap dari demonstrasi mahasiswa 2019?
Demonstrasi mahasiswa dan keributan yang menuntut pencabutan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi serta penundaan pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan rancangan undang-undang lain itu menunjukkan keanehan.
Keanehan seperti apa?
Gelombang demonstrasi masyarakat, dalam hal ini diwakili mahasiswa, terjadi hanya beberapa bulan setelah pemilihan umum. Ini ironi. Sesudah pemilihan umum, legitimasi dari masyarakat semestinya kuat. Seharusnya masalah terkait dengan kepentingan masyarakat yang berpotensi menimbulkan keresahan seperti ini dapat dibicarakan, didiskusikan melalui saluran pemilihan umum. Yang terjadi, hampir tidak tersentuh. Tampak ada ketidaksinkronan antara apa yang dianggap penting oleh sebagian masyarakat dan apa yang terjadi di arena formal politik perwakilan di Indonesia. Mahasiswa menginginkan pemberantasan korupsi dan kebebasan berekspresi.
Pemerintah dan DPR tidak mengakomodasi soal itu?
Gerakan mahasiswa adalah obyek penelitian saya sejak pertama kali melakukan penelitian di Indonesia pada 1990-an. Gerakan mahasiswa merupakan pelopor gerakan oposisi terhadap pemerintah Orde Baru. Saat itu, saluran formal yang disediakan pemerintah untuk aspirasi sangat terbatas. Jadi masuk akal gerakan mahasiswa menjadi oposisi paling vokal dan frontal terhadap pemerintah Indonesia sejak 1970-an (peristiwa 15 Januari 1974). Kalau konsolidasi demokrasi terbentuk dengan baik, gerakan mahasiswa tidak diperlukan. Kemunculan kembali gerakan mahasiswa yang masif setelah 20 tahun reformasi menunjukkan ada masalah dalam sistem perwakilan dan reformasi Indonesia.
Apa penyebabnya?
Di satu sisi, terjadi politik identitas yang besar sekali selama pemilihan presiden. Terbentuk koalisi islamis di belakang Prabowo Subianto dan koalisi pluralis di belakang Presiden Joko Widodo. Mungkin penyebutan islamis versus pluralis terlalu menyederhanakan, tapi kurang-lebih begitu perbedaannya. Dengan masuknya politik identitas sebagai faktor utama, masalah lain, seperti pengendalian korupsi, pembersihan institusi politik, tidak dimunculkan. Di sisi lain, dalam pemilihan legislatif, ada politik patronasi.
Seperti apa konkretnya?
Istilah yang sering dipakai di Indonesia adalah politik uang. Dalam ilmu politik, istilah ini mengacu pada pemberian bantuan atau materi dalam proses membangun pilihan politik. Bentuk yang paling vulgar di Indonesia adalah serangan fajar, yaitu calon legislator membagikan uang pada pagi hari pemilihan. Bentuk lain bisa berupa pembangunan rumah ibadah atau infrastruktur lain saat pemilihan. Logikanya, politik uang menyuburkan korupsi. Ketika politik identitas dan patronasi mendominasi, tidak ada ruang lagi untuk isu lain yang dituntut mahasiswa, yaitu pemberantasan korupsi dan kebebasan berekspresi.
Apakah besarnya gelombang demonstrasi mahasiswa menjadi indikator menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah?
Masalahnya ada di sistem perwakilan. Dengan politik identitas dan patronasi yang mendarah-daging, sistem demokrasi Indonesia menjadi tidak responsif terhadap masalah-masalah tertentu. Contohnya, jika masyarakat suatu desa menginginkan sesuatu, mereka bisa mendapatkannya lewat lobi kepada calon anggota DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada masa pemilu. Tapi tidak ada tempat untuk mengakomodasi tuntutan klasik sejak era reformasi, yaitu pemberantasan korupsi. Itulah yang akhir-akhir ini disuarakan mahasiswa. Dalam sistem demokrasi yang baik, jarang ada demonstrasi besar karena aspirasi masyarakat terwakili lewat lembaga legislatif.
Jadi demonstrasi besar bisa diartikan sebagai sesuatu yang positif atau negatif?
Kembali munculnya gerakan mahasiswa menjadi sebuah tanda harapan. Tanda proses reformasi bisa dihidupkan kembali. Indonesia bisa melakukan perbaikan terhadap mutu kualitas demokrasi. Demonstrasi ini terjadi begitu tiba-tiba, di luar dugaan. Saya, yang sudah lama meneliti sejarah gerakan mahasiswa Indonesia, tidak menduga gerakan akan kembali begitu cepat. Ini kekuatan yang harus dihitung dalam percaturan politik Indonesia untuk bisa keluar dari jebakan polarisasi yang begitu mengekang selama ini.
Gerakan mahasiswa dan masyarakat juga masif di media sosial. Bagaimana Anda melihat sikap pemerintah Indonesia?
Tak bisa dimungkiri, adanya media sosial membuat aspirasi atau ajakan bergerak dapat beredar dengan cepat. Pengaruh media sosial ada di mana-mana saat ini, di seluruh dunia. Di Indonesia, pola umum pemerintah makin represif terhadap reaksi media sosial. Terjadi penindakan hukum terhadap pihak yang mengkritik pemerintah. Itu pertanda kualitas demokrasi Indonesia makin turun.
Anda melihat gerakan mahasiswa 2019 bisa disamakan dengan gerakan 1998?
Saya melihat ada kemiripan, baik dari segi tuntutan maupun pola gerakan. Ada sebuah kesinambungan. Bahkan sebagian mahasiswa mengatakan ingin mengembalikan reformasi ke jalan yang benar. Itu sangat mirip dengan gerakan mahasiswa sebelumnya. Gerakan mahasiswa 1970-an menuntut Orde Baru kembali ke jati diri yang asli, yaitu pembersihan dari korupsi. Ada tradisi mobilisasi perjuangan yang sangat kuat.
Mana isu yang lebih dominan, pemberantasan korupsi atau kebebasan berekspresi?
Yang menjadi pemicu demonstrasi masif sekarang adalah Undang-Undang KPK, bukan Rancangan KUHP. Namun kebebasan berekspresi juga menjadi faktor kuat. Selama 50 tahun, selalu ada tuntutan terhadap kebebasan berekspresi. Itu menjadi bagian dari tradisi parlemen jalanan Indonesia.
Kebebasan seperti apa yang menjadi fokus mahasiswa?
Salah satu tuntutan mahasiswa adalah adanya revisi KUHP. Kalau dikaitkan dengan semangat gerakan mahasiswa era reformasi, dalam revisi KUHP ada beberapa pasal yang diduga menghidupkan kembali semangat Orde Baru. Salah satunya pasal penghinaan presiden. Itu contoh yang sangat terlihat. Sejak 1990-an, pasal penghinaan terhadap presiden sering digunakan untuk memenjarakan pengkritik. Kami sebagai pengamat tak heran melihat gerakan mahasiswa melawan pasal tersebut. Itu menjadi salah satu hakikat gerakan mahasiswa Indonesia sejak dulu, melawan atau mengkritik kebijakan pemerintah yang represif.
(Dalam draf Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden tercantum dalam Pasal 218 dan 219 tentang Penyerangan Kehormatan atau Harkat dan Martabat Presiden dan Wakil Presiden. Adapun Pasal 220 menyatakan perbuatan itu baru menjadi delik jika ada aduan dari presiden atau wakil presiden.)
Pemerintah dan DPR menolak tudingan revisi Undang-Undang KPK melemahkan pemberantasan korupsi. Tanggapan Anda?
Saya kira semua orang tahu tujuan utama revisi tersebut untuk melemahkan KPK. KPK menjadi satu-satunya institusi produk reformasi yang sangat efektif, secara umum atau spesifik, mengontrol tindak korupsi. Kalau para politikus menilai politik uang adalah hal yang hampir tak terhindarkan, tentu saja mereka akan melihat KPK sebagai sebuah ancaman. Tak harus menjadi pakar politik untuk bisa memahami itu.
Menurut Anda, KPK perlu diatur dalam undang-undang baru?
Kita melihat secara garis besar KPK sudah sangat efektif menindak banyak pejabat dan mereka diadili secara hukum. Saat KPK dibentuk pada 2002, banyak pihak memandang sinis. Mereka menganggap KPK akan menjadi macan ompong seperti banyak lembaga lain. Suaranya menakutkan, tapi tetap jinak. Kenyataannya tidak demikian. Sejak KPK melakukan operasi tangkap tangan pertama terhadap Gubernur Aceh Abdullah Puteh pada 2004, begitu panjang daftar pejabat tinggi sampai menteri yang diselidiki, kemudian ditindak. Masuk akal kalau mahasiswa dan masyarakat curiga ada landasan hukum yang hendak melemahkan institusi tersebut. Saya belum pernah membaca analisis yang memberikan landasan kuat untuk melakukan perubahan dalam tubuh KPK.
Presiden Joko Widodo menunda pengesahan revisi KUHP dan sejumlah rancangan undang-undang yang dianggap bermasalah. Apakah itu cukup menunjukkan sikap melindungi demokrasi?
Saya melihat itu respons yang tepat menanggapi tuntutan para demonstran. Tapi saya ragu soal penetapan Undang-Undang KPK, yang menjadi pemicu hadirnya demonstrasi masif. Upaya pelemahan KPK sejak era Susilo Bambang Yudhoyono selalu mengundang reaksi masif dari masyarakat. Sepertinya Joko Widodo agak dilematis saat ini. Di satu pihak, beberapa fraksi, terutama PDI Perjuangan, menolak jika Presiden menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang untuk membatalkan Undang-Undang KPK. Di pihak lain, jika Jokowi tak mengambil tindakan, masyarakat akan melabelinya sebagai Presiden lemah yang tak mendengarkan aspirasi rakyat.

Edward Aspinall (ketiga kiri) dalam Seminar Politik Uang Dalam Pemilu 2019 di Jakarta, April 2019. ANTARA/Muhammad Zulfikar
Artinya, Presiden Jokowi perlu mengambil tindakan terkait dengan Undang-Undang KPK?
Karena Rancangan KUHP belum disahkan, mengambil tindakan penundaan relatif lebih sederhana. Adapun masyarakat sangat prihatin terhadap masalah KPK.
Anda sependapat dengan pandangan yang menyebutkan sejumlah pasal dalam Rancangan KUHP bisa mengekang kebebasan sipil?
Poin itu selalu muncul dalam setiap gelombang mahasiswa sejak era Orde Baru. Kita tahu ada penangkapan terhadap beberapa orang yang mengkritik pemerintah. Itu menunjukkan kualitas demokrasi sedang menurun, walaupun electoral democracy tetap kuat. Dalam hal ini, Indonesia makin mirip dengan pola illiberal democracy yang terjadi di banyak negara sekarang, yaitu segi elektoral tetap jalan tapi demokrasi yang dijalankan tak liberal, dalam arti tak menjunjung tinggi prinsip kebebasan individual.
Ada juga yang menyebut pemerintah mengarah ke otoriter....
Ini menarik. Pemerintah Joko Widodo tidak sedang mengalami transformasi ke arah otoriter. Dalam beberapa hal, sistem demokrasi Indonesia cukup bagus. Terutama kalau kita lihat dari perspektif demokrasi elektoral. Terbukti, saat menargetkan 60 persen suara dalam pemilihan presiden, target itu tak tercapai. Padahal itu sudah mengerahkan kepala daerah dan ajakan kepada pegawai negeri sipil agar mendukung kerja pemerintah (inkumben). Ini patut dianggap salah satu kisah sukses dari demokratisasi arus ketiga, third wave democratization, secara global. Yang terjadi adalah illiberal democracy.
Artinya, demokrasi Indonesia mundur?
Ya. Banyak sekali kemajuan demokrasi pada awal era reformasi. Banyak perubahan politik yang sangat fundamental sampai 2004 atau 2005. Tapi, pada periode kedua Yudhoyono, demokrasi Indonesia mulai stagnan, lalu mengalami kemerosotan di era Joko Widodo. Tapi belum bisa dikatakan kemundurannya drastis. Penurunan kualitas demokrasi itu terlihat dari pembatasan kebebasan berekspresi.
Apa yang mendorong pembatasan berekspresi?
Banyak hal. Salah satunya polarisasi saat pemilihan presiden. Kasus Ahok (Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, yang terjerat kasus penistaan agama sebagai buntut demonstrasi besar yang mengatasnamakan Islam pada Desember 2016) membuat panas suhu politik yang membenarkan tindakan yang akan mengurangi kualitas demokrasi.
Polarisasi ini menguat pada masa Jokowi?
Betul. Polarisasi itu betul-betul dirasakan di era Jokowi. Di era Yudhoyono, masih berjalan proses koalisi pelangi, saat kelompok Islam semacam Partai Keadilan Sejahtera masih terwakili dalam pemerintahan. Sekarang polarisasi terjadi antara kelompok islamis dan pluralis. Itu baru satu faktor. Faktor lain adalah politik uang. Sejak diberlakukannya sistem pemilihan terbuka di legislatif pada 2009, fenomena ini makin berpengaruh kuat. Muara masalah korupsi ada di politik uang. Itu ada kaitannya. Seperti yang disampaikan Profesor Emil Salim dalam Mata Najwa beberapa waktu lalu.
Anda menyaksikan debat antara Arteria Dahlan dan Emil Salim?
Ya, tapi tidak seluruh acara.
Buku Anda, Democracy for Sale, dikutip Emil Salim….
Ya. Saya berterima kasih kalau memang ada kontribusi dalam diskusi itu.
Apa penelitian Anda berikutnya setelah buku itu rampung tahun ini?
Penurunan kualitas demokrasi tidak hanya terjadi di Indonesia. Banyak negara third wave democracy yang juga mengalaminya. Ini menjadi tema pokok pengamat politik belakangan. Saya berencana membandingkan penurunan kualitas demokrasi se-Asia Tenggara.
Dari premis awal Anda, apa penyebabnya?
Dulu demokrasi sering ditumbangkan oleh kelompok militer lewat kudeta. Tapi fenomena itu kini jarang terjadi, kecuali di Thailand. Yang terjadi sekarang, perongrongan terhadap kualitas demokrasi justru dari pemimpin yang dipilih secara demokratis, seperti di Hungaria dan Polandia, juga Filipina. Apakah akarnya di komunikasi politik? Atau media sosial yang dampaknya makin tajam dalam proses polarisasi? Atau ketimpangan ekonomi? Ini fenomena global yang menarik diteliti. Bahkan negara dengan demokrasi yang dianggap sudah baik juga mengalaminya, seperti Amerika Serikat.
Edward Aspinall | Tanggal Lahir: 17 Juni 1968 | Pendidikan: Doktor Ilmu Politik Research School of Pacific and Asian Studies, Australian National University (2000); Master Studi Indonesia dan Malaysia, Sydney University (1991); Sarjana di Adelaide University, Australia (1989) | Karier, di antaranya: Profesor di Australian National University; Senior Fellow di Department of Political and Social Change, Research School of Pacific and Asian Studies, ANU (2008-2011); Fellow di Department of Political and Social Change, Research School of Pacific and Asian Studies, ANU (2005-2008) | Buku, di antaranya: Democracy for Sale (2019), The State and Illegality in Indonesia (2011), Islam and Nation: Separatist Rebellion in Aceh, Indonesia (2009), Opposing Soeharto (2005).
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo