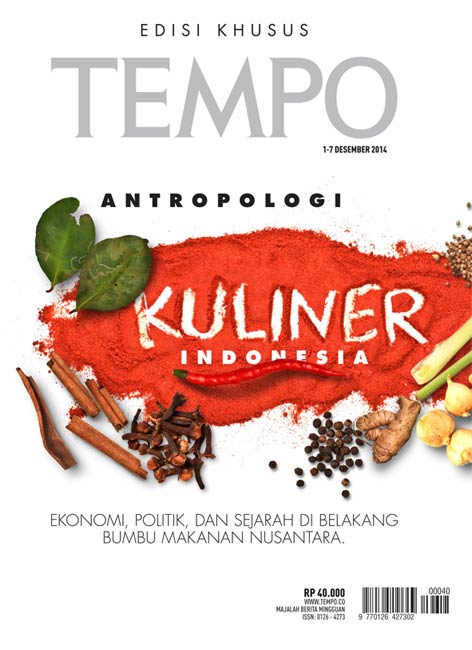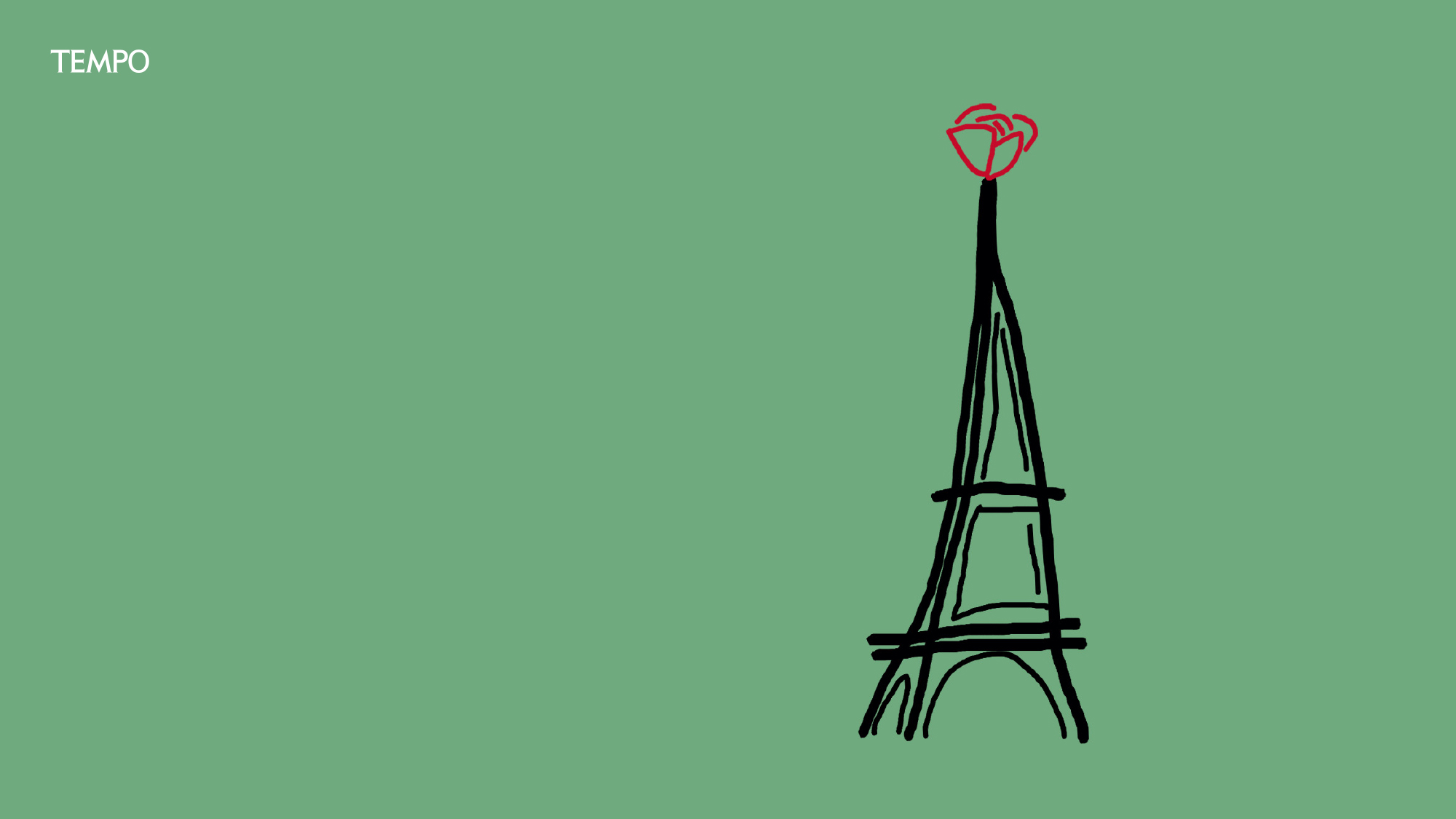Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Te kavo ala kojo vaqhe faicj, ubud ve, beke, blusut....Ngenj bulu ruqhu feza vaqhe re!"
SUARA melengking Agustin Fili memecah keheningan Desa Setulang, Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara. Dari atas teras lamin—rumah tradisional suku Dayak—dia meminta Samsyah Mekah dan Cik Usak, dua tetangga seberang rumah, pergi mencari pakis pahit, umbut rotan, daun bekai, blusut (kecombrang), dan bambu untuk memasak.
Siang itu, Sabtu kedua bulan lalu, jalanan Desa Setulang lengang. Sejauh mata memandang, dari teras rumah panggung Agustin, hanya tampak seorang inai alias ibu yang menjemur gabah di pelataran rumahnya. Sebagian lainnya duduk santai di langkan rumah panggung mereka, berlindung dari terik matahari yang kejam sambil menganyam tas rotan dan saung—caping warna-warni.
Tapi hari itu Agustin tak bisa ikut bersantai. Keponakannya, gadis remaja yang selama ini diasuhnya, besok siang dilamar seorang pria dari kota. "Masakan nasional sudah saya beli dari Malinau," kata Agustin, yang juga istri Kepala Desa Setulang. "Tapi bahan-bahan untuk masakan tradisional harus dicari di hutan."
Agustin merasa harus menyiapkan menu umum, seperti ayam dan ikan goreng, karena keluarga si pelamar bukan orang Dayak Kenyah Umaq Long, suku asli warga Desa Setulang. Tamu dari kota itu orang dari suku Dayak Bakung. Meski sama-sama Dayak, Agustin khawatir makanan khas Umaq Long yang diolah dari tumbuhan hutan tak cocok di lidah orang Bakung, apalagi yang lama tinggal di kota. Masakan khas warga Setulang tetap dia sajikan untuk pelawat dari tetangga di kiri-kanan rumahnya.
Seketika Samsyah, yang diminta bantuan oleh ibu kepala desa itu, turun menapaki tangga kayu ulin di depan rumahnya. Dengan saung melingkar di kepala dan tas rotan di punggung, perempuan paruh baya itu segera pergi mencari pakis di ladang.
Sedangkan Cik Usak, dengan perawakannya yang keras khas anak hutan Kalimantan, muncul dari samping rumah sambil memanggul seperangkat mesin perahu kecil atau ketinting.
Sesaat, Cik menghentikan langkahnya. Senyumnya mengembang sembari melambaikan tangan tanda mengajak kami, yang berdiri di samping Agustin. "Hutannya di seberang sungai, jadi harus naik ketinting," ujar Agustin.
Kami bergegas turun dari lamin Agustin, menyusul Cik menuju Sungai Setulang di belakang rumah. Di sana, ketinting merah bergaris biru miliknya sudah menunggu. Ikut serta bersama kami Amsal Kayang, sepupu Agustin yang datang dari Kota Malinau. "Beginilah kami ketika masih tinggal di kampung lama dulu di Long Saan," kata Amsal. "Pergi ke hutan cari makanan."
Bising mesin dan ketinting yang beralun kiri-kanan menyulitkan kami mengobrol. Tapi sebenarnya bukan juga karena mesin jika kami berhenti berbicara. Agaknya berdosa besar jika kami asyik mengobrol dan mengabaikan hijaunya pepohonan yang membentang di kiri-kanan sungai bening. Apalagi, ketika tak lama setelah lepas tambat, ketinting kami keluar dari anak Sungai Setulang yang kecil. Dan, blang…, Sungai Malinau menyambut kami.
Bak adegan film yang berganti, sungai kecil yang tadinya jernih berganti lebar kecokelatan. Arus landai yang tadi mengantar kami kini harus dilawan agak kuat. "Hati-hati, duduknya di tengah," kata Cik berteriak dari buritan.
SETULANG sebenarnya bukan perkampungan asli mereka. Desa ini baru terbentuk setengah abad lalu setelah mereka pindah dari Long Saan, tanah leluhur mereka di hulu Sungai Pujungan, sekitar 150 kilometer sebelah barat daya Setulang. Mereka pindah untuk kabur dari wabah penyakit.
Setelah mencari lahan baru, tetua memilih Setulang, yang kondisinya tak jauh berbeda dengan Long Saan. Berada di lembah Modong Meritem, Desa Setulang seolah-olah tersembunyi di balik kepekatan hutan. Ketika kami tiba sehari sebelumnya, dari kejauhan hanya tiang salib gereja yang bisa melawan pepohonan hijau nan rimbun. Itu pun karena Gereja Kemah Injil Indonesia tersebut bertengger di lereng tertinggi, dekat pintu masuk desa.
Seperti Dayak pedalaman lain, masyarakat Dayak Kenyah Umaq Long memandang hutan sebagai sumber kehidupan. Tinggal di tengah rimba, mereka memakan segala yang diberikan hutan, seperti umbut-umbutan, akar, biji, daun, bunga, dan satwa liar. Keterasingan mereka juga yang membuat Dayak di pedalaman tak mengenal rempah, komoditas yang membuat dunia hiruk-pikuk selama berabad-abad.
Menurut Roedy Haryo Widjono, antropolog STKP Keuskupan Samarinda, masyarakat Dayak di pedalaman Kalimantan memang tak begitu mengenal rempah-rempah yang umum diketahui di Indonesia. Bahkan garam diperoleh dari mata air gunung.
Tapi bukan berarti orang Dayak tak memiliki hubungan dengan bangsa lain. Penulis buku Masyarakat Dayak Menatap Hari Esok ini menjelaskan, bangsa India tiba di Kalimantan sekitar 250 sebelum Masehi. Kala itu, daratan yang semula dikenal Tanjung Negara ini telah ratusan tahun dihuni bangsa Austronesia dari Cina Selatan, yang diyakini sebagai asal-usul orang Dayak. Menurut Roedy, secara etnoantropologi, sebenarnya semua orang Kalimantan disebut Dayak—termasuk mereka yang selama ini populer disebut Melayu Kalimantan.
Ratusan tahun kemudian, kerajaan-kerajaan Hindu muncul di Kalimantan, hingga masuk ke era penaklukan oleh Kerajaan Sriwijaya pada abad ke-7 dan Kerajaan Majapahit pada abad ke-13. Pada masa pendudukan ini, berbagai suku bangsa ikut masuk, seperti Jawa dan Melayu.
Sebagian warga pendatang tersebut memulai penambangan intan. Ada juga yang membuka perdagangan hasil hutan, seperti getah, rotan, dan kayu. "Tapi semua hanya di daerah muara sungai, termasuk ketika bangsa Eropa masuk ke Kalimantan," ujar Roedy, yang juga Direktur Nomaden Institute for Cross-Cultural Studies.
Akulturasi budaya—termasuk di dalamnya bahasa, agama, dan kuliner—hanya terjadi di kalangan Dayak muara, yang nantinya dikenal sebagai Melayu Kalimantan. Adapun Dayak yang tinggal di hulu dan berpindah-pindah tak tersentuh "pertemuan budaya" itu. Akibatnya, mereka tetap memiliki bahasa, agama, budaya, dan cara memasak sendiri. Jauh berbeda dengan cara memasak dunia luar.
Amsal masih ingat masa kecilnya di hulu Sungai Saan. Di sebuah rumah panjang bernama Lamin Dadu, keluarganya tinggal bersama sembilan keluarga lain. Hampir saban hari mamaknya mencari berbagai macam tumbuhan di tengah hutan. "Saya biasa menemaninya," kata Amsal. Adapun bapaknya bertugas pergi berburu binatang di hutan atau menjala ikan di Sungai Saan. Di sungai itu pula Amsal dan Cik Usak kecil biasa bermain.
Pantas saja dua orang yang telah berumur lebih separuh abad itu masih sigap ketika ketinting merapat di tepi sungai. Sekelebat, mereka menaiki lereng tepi sungai yang rimbun. Kami—juru foto Frannoto dan saya—sempat sedikit kewalahan mengikuti mereka ketika menapaki jalan setapak, tanda lajur ini biasa dilalui orang yang akan meladang di tengah hutan.
Belum juga jauh meninggalkan tepian sungai, Amsal mencabut parang dari sarungnya yang terikat di pinggang. Sambil menuruni lereng, ditebasnya tanaman-tanaman yang menghalanginya menuju rumpun tanaman perdu. Di balik sana ada targetnya: rotan yang menjalar-jalar.
Dass... dass... dass.... Suara parang Amsal menebas bagian atas rotan muda. Rupanya, parangnya kurang tajam. Mungkin karena selama ini parang itu ikut Amsal tinggal di kota. Cik Usak pun mencabut parang miliknya, lalu menjangkau rotan lain. Blass.... Cukup sekali tebas, rotan itu menyerah. Ia hanya mengambil bagian teratas yang masih muda. Panjangnya sekitar semeter. Umbut adalah bagian dalam rotan yang paling enak dimakan.
Dua batang rotan dan bambu muda siap kami bawa pulang. Tapi pesanan lain Agustin, seperti blusut dan biji buah payang, harus dicari lebih jauh ke dalam hutan. "Semoga blusut sudah berkembang dan buah payang sudah matang," ujar Amsal.
Orang di Jawa mengenal biji payang dengan sebutan kluwek (Pangium edule), yang biasa dipakai untuk rawon. Untuk mendapatkannya, warga Dayak biasa menunggu payang sampai masak hingga jatuh ke tanah dan membiarkan buahnya membusuk sehingga bijinya mudah diambil.
Doa kami terwujud. Di tengah belantara, kami berpapasan dengan Laing Ngau dan istrinya. Keduanya akan kembali ke Setulang setelah meladang di tengah rimba. Di dalam tas rotan yang digendongnya, ada dua buah payang busuk. "Silakan ambil bijinya," kata Laing Ngau tersenyum.
Sempat malu kami rasanya karena pria yang sebaya dengan Cik Usak ini sebenarnya Ketua Adat Desa Setulang dan kami belum sempat berkunjung ke rumahnya. "Kalian coba cari blusut ke sana," ucap Laing Ngau sambil menunjuk ke lereng sebelah utara.
Benar saja. Setelah menapaki satu bukit, Cik Usak menghentikan langkahnya. Tangannya menunjuk ke cerukan di tepi jalan setapak. Sekitar lima meter arah bawah lereng itu, tampak serumpun tanaman pisang-pisangan dengan tangkai hijau langsing memanjang yang menopang bunga merah berbentuk gasing. Orang Dayak Kenyah Umaq Long menamainya blusut.
Masyarakat Jawa mengenalnya sebagai kecombrang. Orang Batak mengenalnya sebagai rias atau kincung. Adapun orang Betawi, yang menamainya honje, biasa memanfaatkan bunga ini untuk memandikan mayat. Orang Umaq Long memanfaatkan bunga, buah, dan tangkai tanaman tersebut untuk campuran lerek—semacam bubur berbahan nasi atau pati singkong.
Hari yang semakin sore membujuk kami untuk menyerah mencari bekai. Ini adalah daun penyedap rasa—bagian paling penting dari masakan Dayak mana pun. Seperti andaliman di masyarakat Batak, bekai merupakan benang merah di antara masakan suku Dayak yang beragam. Orang Dayak Lundaye dan Dayak Abai menyebutnya daun mekai atau apak. Kepada para pendatang, mereka mengatakan bahwa ini adalah daun micin karena dianggap bisa membuat gurih makanan.
Tapi lagi-lagi hutan Setulang memberkati kami. Atau mungkin juga karena Cik Usak dan Amsal menajamkan matanya ke sela-sela pepohonan di sepanjang perjalanan kembali ke tepi sungai. Mereka melihat bekai tumbuh liar di bawah pohon yang menjulang. Lima lembar daun kami petik, dan itu menutup perjalanan di hutan Setulang.
ALAM terasa lebih sepi di Setulang. Mungkin karena tak ada sinyal telekomunikasi dan televisi di sini. Tapi, di jayung (dapur) rumah Samsyah, kesibukan justru baru dimulai. Asap kayu bakar memenuhi ruangan. Asap yang bertahun-tahun mengepul melekatkan jelaga di seluruh dinding dapur.
Agustin meminta Samsyah memasakkan lerek leke fazang dao blusut, yang berarti lerek atau bubur payang campur daun blusut. Duduk di tepi bakaran, Samsyah menyiapkan bahan. Dua batang bambu yang kami ambil tadi siang sudah dipotong dan dibariskan mirip angklung. Di situlah nasi yang dicampur air secukupnya akan direbus. Uap pun mengepul dari lubang bambu.
Bulir bunga blusut yang telah dipisahkan dari tangkai dan buahnya dimasukkan bersama garam dan remasan daun bekai. Adapun batangnya, yang disebut nyating, direbus di dalam batang bambu yang lain.
Tapi itu semua belum pas, menurut Amsal, kalau tak diberi payang. Ternyata bukan biji payang tadi siang yang akan menjadi campuran. Biji payang itu harus lebih dulu dibuka kulitnya, diambil dagingnya, direndam, direbus, lalu difermentasi di dalam bambu. Keseluruhan prosesnya membutuhkan waktu paling cepat sebulan. "Lebih lama lebih enak," kata Amsal.
Beruntung, Samsyah sudah punya pasokan. Ditariknya bambu hitam di atas penjarangan kayu bakar. Payang yang difermentasi harus ditaruh di situ agar terkena panas asap kayu bakar. Samsyah mengeluarkan payang itu dari dalam bambu, yang ternyata seperti terasi. Diambilnya secuil, lalu dicampurkan ke dalam lerek sambil digejrot menggunakan ranting bambu.
Bubur panas dituang dari bambu ke mangkuk. Sekilas mirip nasi beras merah karena warna blusut memudar ke bubur ini. Adapun rebusan batang nyating ditempatkan di piring. Seluruhnya diangkut ke rumah Agustin.
Bersama Sale Uwang, Kepala Desa Setulang yang juga suami Agustin, kami makan malam bersama. Diam-diam Amsal membakar umbut rotan untuk melengkapi hidangan khas Umaq Long. Di atas meja makan sudah tersaji sebakul nasi putih, lerek payang daun blusut, rebusan nyating, dan sayur payang bercampur serai (leke fazang don balengla), yang dimasak paling akhir.
Daun bekai yang tadi diremat tak lagi berwujud. Bagi lidah yang telanjur biasa dimanjakan vetsin, memang agak sulit mencari fungsi bekai yang katanya penyedap rasa. Tapi, sesuap-dua suap, rasa itu muncul. Ada yang manis datang malu-malu di ujung lidah ketika mengecap lerek. Mungkin malam itu daun bekai sengaja membiarkan aroma khas payang yang agak-agak tengik, blusut yang semriwing, dan pahitnya potongan kecil umbut rotan. "Kalau lengkap seperti ini, saya jadi teringat masakan di Long Saan," ujar Amsal.
Malam berakhir, tapi benak ini tak bisa melupakan ucapan Laing Ngau, "Hutan ini adalah hidup kami." Kegembiraan melihat Setulang yang tenteram tak bisa menghapus kekhawatiran kami. Di belahan lain Kalimantan sana, mesin-mesin ekskavator sedang bergerak menggerus hutan tempat warga mencari makanan. Semoga mereka tidak datang ke sini.
Menuju Setulang
Setelah lebih sedekade berjuang mempertahankan hutannya dari gempuran korporasi, medio tahun lalu pemerintah akhirnya menetapkan Tane' Olen—yang berarti tanah larangan—seluas 5.300 hektare di Setulang sebagai hutan desa. Akhir tahun lalu, Pemerintah Kabupaten Malinau juga menetapkan kampung ini menjadi salah satu desa wisata daerah.
Menuju Kabupaten Malinau
Pesawat udara menuju Bandar Udara Robert Atty Bessing, Malinau (transit di Balikpapan atau Tarakan)
Feri Tarakan-Malinau
Destinasi Wisata di Malinau
- Taman Nasional Kayan Mentarang
- Air terjun Semolon
- Hutan Apau Ping
- Festival Irau Malinau (dua tahun sekali, terakhir Oktober 2014)
Menuju Kabupaten Setulang
Dari Malinau:
- Angkutan (mobil bak L-300 berkanopi) Rp 50 ribu per orang (pergi-pulang)
- Ojek kampung Rp 180 ribu per trip
- Taksi kota (carter) Rp 500 ribu per trip
- Sewa mobil (kurang-lebih satu jam perjalanan ke arah selatan) sekitar Rp 600 ribu per hari
Penginapan Setulang
Rumah warga Desa Setulang Rp 100 ribu per malam
Potensi Wisata Setulang
- Hutan Tane' Olen
- Arung sungai naik ketinting
- Selam sungai mencari ikan
- Pembuatan kerajinan tangan dari rotan dan parang
- Tarian adat Dayak Kenyah Umaq Long
Glosarium
Kecombrang (Etlingera elatior):
Blusut (Kenyah Umaq Long)
Sale (Lundaye)
Batang Kecombrang:
Nyating (Kenyah Umaq Long)
Baku (Lundaye)
Umbut Rotan:
Ubud ve (Kenyah Umaq Long)
Ubud fed (Lundaye)
Ruang Dapur:
Jayung (Kenyah Umaq Long)
Dafur (Lundaye)
Tempat Masak:
Atang (Kenyah Umaq Long)
Tetel (Lundaye)
Tungku:
Angnan (Kenyah Umaq Long)
Angan (Lundaye)
Daun Mekai/bekai (penyedap rasa):
Beke' (Kenyah Umaq Long)
Apa (Lundaye)
Sayur:
Leke (Kenyah Umaq Long)
Kikid (Lundaye)
Rumah:
Lamin
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo