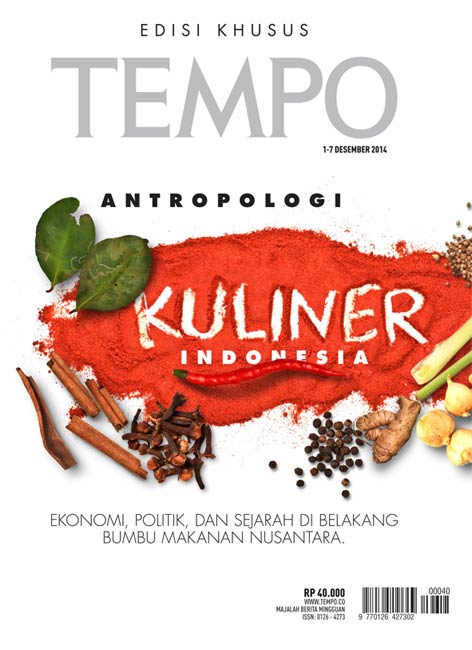Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
MATAHARI belum juga menunjukkan wajahnya di ufuk timur Kota Malinau ketika rombongan L-300 bak terbuka beriring merapat di tepi Jalan Raja Pandita, Desa Tanjung Belimbing. Mobil-mobil itu tampak kecil sekali. Bukan karena hari masih gelap, melainkan tumpukan sayur di dalamnya harus berebut tempat dengan belasan ibu-ibu yang berjubel sembari berpegangan pada besi tepian bak.
Mereka adalah rombongan warga Desa Setulang. Saban Selasa dan Jumat, mereka meninggalkan desa sejak pagi buta, menempuh satu jam perjalanan ke utara, untuk menggelar pasar tradisional. "Karena penjualnya kebanyakan ibu-ibu, pasar ini disebut Pasar Inai," ujar Kartini Yosef, warga Kampung Pelita, Kabupaten Malinau, yang telah menunggu pasar digelar. Inai adalah bahasa Dayak yang berarti ibu.
Kartini sebenarnya kelahiran Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Namun perempuan Dayak Ngaju ini sudah dua dekade tinggal di Malinau bersama suaminya yang berasal dari Dayak Lundaye. Bagi orang Dayak di kota, kata Kartini, Pasar Inai selalu ditunggu. "Pasar ini pelepas rindu jika kami kangen bahan-bahan dapur zaman dulu." Pantas saja hingga pasar yang hanya berupa jalanan kecil di tepi Sungai Malinau itu penuh dalam sekejap.
Warga Setulang rupanya tak hanya memanfaatkan hutan sebagai sumber pangan mereka sendiri. Sebagian hasil hutan mereka perdagangkan untuk menambah penghasilan. "Biasanya, sekali jualan, mereka bisa membawa pulang Rp 200 ribu," ucap Agustin. Kebetulan istri Kepala Desa Setulang itu ikut menumpang mobil bak miliknya yang digunakan warga pergi ke Malinau. Pagi itu, Agustin harus pergi bekerja di Dinas Pariwisata Kabupaten Malinau.
Karena yang dijual hasil hutan, lapak-lapak yang hanya berupa alas karung goni di pasar itu menyuguhkan bahan makanan yang aneh-aneh. Tentu saja bahan-bahan yang kami temukan seperti umbut rotan, blusut alias kecombrang, daun bekai, dan biji buah payang ada di sana. Semuanya telah dipisahkan dalam ikatan-ikatan tali dan dijual rata-rata Rp 10 ribu per bundel. Ada juga beraneka macam ikan sungai dan daging babi hutan yang telah dipotong-potong. Daging kijang dan kura-kura juga tersedia.
Pagi itu setidaknya ada tiga ekor kura-kura cangkang lunak yang dijual Rp 50 ribu per kilogram. Meski diam tak bergerak, kepalanya langsung bersembunyi seketika tangan menyentuhnya—tanda masih hidup. Masyarakat Dayak menyebutnya labi-labi. Mereka biasa memasaknya dengan sayur daun singkong mirip tumisan ikan.
Tapi, pagi itu, bukan labi-labi yang menjadi target Kartini. Setelah menyusuri pasar yang berderet sepanjang 50 meter, dia membawa pulang sekantong besar daun-daunan. Esok Minggu, dia akan memasak bitter, sejenis bubur khas Dayak Lundaye, yang dipesan seorang kolega.
Rupanya, sudah beberapa tahun terakhir Kartini dan ibu-ibu PKK Desa Pelita berbisnis katering spesialis masakan tradisional. Karena anggotanya berasal dari beraneka subsuku Dayak, kelompok ibu-ibu ini bisa melayani berbagai masakan tradisional Dayak. "Datang saja besok ke dapur kami," ujar Kartini.
Bagaimana bisa menolak ajakan tersebut. Inilah kesempatan kami setelah beberapa hari kecewa karena gagal menemukan rumah makan khas Dayak di Malinau. Apalagi yang mengundang orang Dayak Lundaye. Ketika baru tiba di Malinau tiga hari lalu, kami bertemu dengan Kosim, pegawai Taman Nasional Kayan Mentarang. Pria asli Sukabumi, Jawa Barat, ini menceritakan makanan kegemaran istrinya, perempuan Lundaye. "Namanya teluk. Kalian harus coba," kata Kosim. "Saya selalu ke luar rumah kalau istri saya memakannya."
DAPUR Kartini tak bisa dibandingkan dengan dapur-dapur di Setulang. Meski sama-sama masih menggunakan api kayu bakar, bentuk tungkunya semodern rumahnya yang terletak di tepi Jalan Raja Pandita, Kota Malinau. Berbeda dengan masyarakat Dayak Kenyah Umaq Long, yang menamai dapur sebagai jayung, Dayak Lundaye menyebutnya tetel.
Pagi itu, bukan Kartini yang memasak, melainkan tetangganya, Farida Sepiner, perempuan Dayak Lundaye. Cara masaknya hampir sama sederhana dengan cara memasak bubur khas Kenyah Umaq Long, yang disebut lerek, buatan Samsyah di Setulang. Air mendidih bercampur beras terus-menerus diaduk hingga akhirnya dicampur daun tengayen dan kicep atau jamur. Yang paling akhir, tepung ubi dimasukkan agar mengental.
Sama dengan di Setulang, bubur itu nanti tetap dimakan dengan nasi putih. "Itu sebabnya kami punya istilah ye telubak, ye tekiki. Nasi juga, sayur juga," ujar Farida. Bedanya hanya pada alat dan bumbu-bumbu yang digunakan. Karena tinggal di kota, Farida dan rekan-rekannya sudah jarang menggunakan bambu dan menggantinya dengan panci logam. Dan, yang paling utama, Dayak Lundaye juga tak terbiasa menggunakan fermentasi biji buah payang.
Tapi bukan berarti kebiasaan mengawetkan makanan tak ada di Lundaye. Setelah menuangkan bubur ke mangkuk besar, Farida menyajikan makanan yang paling kami tunggu-tunggu untuk membuktikan cerita Kosim: teluk. Wujud dua ekor ikan berukuran sejengkal tangan itu mirip bandeng presto. Mungkin bau asam ikan itu yang membuat Kosim selalu meninggalkan rumah ketika istrinya makan teluk. "Teluk memang makanan khas Dayak Lundaye," kata Farida.
Ikan yang dipakai Farida adalah ikan pelian, yang tergolong mahal karena hanya bisa diperoleh di derasnya air hulu sungai. Bintik putih di bagian sisiknya ternyata bukan tumpukan bumbu, melainkan kulit ikan yang telah melepuh karena fermentasi. Ya, sebulan lalu ikan itu mentah-mentah disimpan di dalam stoples bersama beras yang telah disangrai. Selain ikan, teluk bisa menggunakan bahan potongan babi hutan.
Menurut Roedy Haryo Widjono, antropolog STKP Keuskupan Samarinda, fermentasi makanan merupakan tradisi yang sudah ada ribuan tahun lalu sejak nenek moyang suku Dayak, yang diyakini dari Yunan, Cina Selatan. Kala itu pengawetan makanan diperlukan sebagai bekal bermigrasi ke Kalimantan.
Setelah tiba di Kalimantan dan membentuk komunal, mereka mempertahankan kebiasaan tersebut. Kali ini makanan yang diawetkan diperlukan untuk pergi berladang di tengah hutan. "Sekali meladang, mereka bisa berpekan bahkan berbulan-bulan meninggalkan rumahnya," ujar Roedy. Tak hanya sebagai bekal makanan, fermentasi juga diperlukan ketika hewan buruan harus tetap bisa dimakan ketika mereka pulang ke rumah. "Perjalanan pulang mereka juga bisa berminggu-minggu."
Maklum, Kosim tak kuat menahan baunya. Tapi, setelah mencicipinya, rasa teluk sebenarnya tak semengerikan yang kami kira. Setidaknya kami senang melihat tuan rumah sangat lahap menyantapnya. "Bagi kami, teluk seperti emas," kata Farida.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo