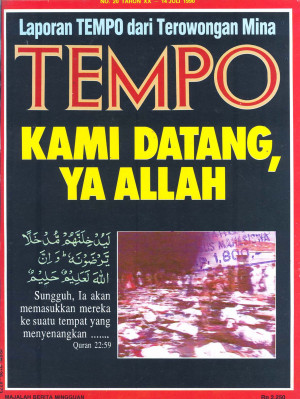Suku Bajo di Teluk Bone, Sulawesi Selatan, lebih kurang merupakan masyarakat "tertutup" yang khas. Mereka dikenal dengan julukan suku laut karena suka berkelana di lautan. Hidupnya tak bisa jauh dari ombak. Tapi kini mereka sudah mulai "mendarat" Generasi baru Bajo di BajoE tak mengenal kekayaan nenek moyangnya, "Seperti ada rantai putus yang menyebabkan kami tak tahu cerita mereka," kata seorang warga bernama Nadjamuddin. Untung, Bupati Bone berniat mencagarbudayakan kampung suku Bajo itu. Wartawan kami, Sri Pudyastuti R. menuliskan pengamatannya setelah tinggal beberapa hari di masyarakat yang menurut kesannya "ramah dan terbuka". HUJAN turun rintik-rintik. Sesekali terdengar kokok ayam bersahut-sahutan. Angin mengembus deras menembus celah-celah dinding papan. Dinginnya luar biasa. Ini saat yang paling nikmat sebenarnya untuk membungkus diri dalam sarung dan memasuki mimpi. Tapi di dalam rumah -- yang persis menghadap ke Teluk Bone itu -- tuntutan kehidupan sudah bangkit. Bengkok, laki-laki berumur 60-an itu, sibuk mondar-mandir keluar-masuk rumah. Diraihnya alat pancing, umpan ikan, dan ember berisi bongkah es. Lantai papan berderak-derak di bawah kakinya yang kukuh. Ia melakukan semuanya dengan membisu, sementara di mulutnya bertengger sebatang rokok yang terus mengepulkan asap. Sarungnya tersangkut sekenanya sebatas betis. Selembar kaus kutang tipis membungkus tubuhnya bagian atas. Ketika Bengkok turun menuju leppe -- sampan kecil khas suku Bajo yang cuma muat tiga orang -- di dapur terdengar bunyi gemericik. Ecce, anak sulungnya (sekitar 16 tahun), mengisi air tawar ke dalam jerigen. Darwati, adiknya yang berumur kira-kira 14 tahun, membantu memasukkan lauk-pauk dan beras ke kantung plastik. Kompor sudah diisi minyak tanah, tinggal diangkat. Bergantian mereka mengangkat segala perlengkapan. Rumah itu jadi sibuk seperti pasar. Suara-suara penghuninya -- sebagaimana ciri masyarakat pantai -- terdengar lantang dan berisik. Langkah-langkah kaki mereka dientakkan keras, membuat rumah panggung itu bergetar-getar. Bagi yang belum biasa, rasanya seperti berada di dalam gempa. Pelan-pelan mereka menurunkan perlengkapan tadi ke dalam leppe, yang ditambatkan persis di bawah tangga rumah. Air pasang menggenang sampai ke sekitar rumah. Leppe agak oleng, ketika Ngguro, istri Bengkok, menata barang-barang ke dalamnya. Hari itu, seperti juga hari-hari kemarin, ia ikut suaminya menangkap ikan. Tubuhnya dibalut training's pak yang sudah mati warna. Keriput di wajah wanita ini seperti mengisyaratkan usianya yang sudah mencapai kepala lima. Namun, sosoknya masih segesit suaminya. Itulah awal hari buat orang-orang Bajo. Kehidupan rutin suku yang dikenal dengan julukan suku laut (karena suka berkelana di lautan), yang kini sudah "mendarat". Laut menjadi ladang mata pencarian yang mesti disambangi setiap hari. Maka, cuaca dingin dan deras hujan telah menjadi sahabat. Bengkok didampingi istrinya mendayung leppe menuju Teluk Bone dipayungi selembar plastik. Seperti biasanya kedua anaknya menunggu di rumah. Tak ada lambaian tangan menyertai kepergian, seolah yakin semua akan berjalan aman. Sementara itu, tiga orang wanita pencari teripang berkain kebaya nampak mendayung leppe, tak lama setelah Bengkok melintas. Tubuh mereka yang kuyup disiram hujan tak meredam keinginan untuk melaut. Inilah sebagian potret ketangguhan suku laut yang masih tersisa. Kini ketangguhan orang Bajo cuma tinggal legenda. Setidaknya inilah yang terlihat di BajoE. Sebuah desa di Kabupaten Bone, sekitar 182 km dari Kota Ujungpandang, Provinsi Sulawesi Selatan. Jumlah orang Bajo di daerah ini kian memadat. Mereka tak lagi tinggal mengapung di tengah laut. Deretan rumah panggung sepanjang 1 km di pesisir Teluk Bone menjadi bukti. Mereka meninggalkan bidok -- perahu beratap, berfungsi sebagai rumah -- yang bertahun-tahun setia menemani mengarungi lautan, untuk menetap di sebuah rumah, secara berangsur-angsur sejak tahun '50-an. Dari tahun ke tahun jumlah pendatang ke BajoE terus bertambah. Menurut catatan kantor kepala desa, tahun ini di Dusun BajoE bermukim 997 jiwa (139 keluarga). Jumlah ini memang masih lebih kecil dibanding 3 dusun lain yang dihuni suku Bugis dan Mandar. Di Apasare, misalnya, ada 1.525 jiwa (237 kk), di Pao ditemui 2.922 jiwa (367 kk), dan Rompe berpenghuni 1.633 jiwa (252 kk). Hingga kemudian telah lahir generasi Bajo yang tak akrab dengan aroma laut. Daratan adalah dunia yang mereka gauli sejak lahir. Maka, tak heran jika hanya orang-orang tua saja yang piawai menggumuli laut. Anak-anak mudanya sudah mengenal deru mesin kapal dan alat tangkap modern, seperti jaring, pukat, dan alat selam. Bengkok dan istrinya mungkin bisa jadi contoh sisa-sisa masa lalu. Ia kuat mendayung sejauh 3 mil dari pantai. Leppe baru berhenti apabila mencapai gugusan karang yang sudah dikenal. Sebab, di situlah ikan-ikan karang seperti opo (tenggiri besar), baronang, titang, papaku, dan kalampeto bersembunyi. Kadang-kadang, ketika suaminya memancing, Ngguro menyelam. Memunguti teripang (sea cucumbers) yang gentayangan di kedalaman 50 depa (sekitar 40 meter). Teripang ini bertubuh lunak. Bentuknya seperti lintah tapi ukurannya lebih besar. Kalau dipegang, tak meronta-ronta seperti umumnya ikan. Ngguro tahan berada di bawah air sampai 10 menit. Tanpa alat selam. Ecce dan Darwati tak mewarisi bakat ibu dan bapaknya. "Waktu kecil aku pernah diajak Ibu memancing, tapi kepalaku pusing. Aku mabuk. Jadi, aku tak mau lagi ke sana. Lebih enak di darat, menunggu Bapak pulang," kata gadis berambut keriting ini, sambil menunjuk laut. Darwati apalagi. Gadis bertubuh bongsor dan berambut lurus ini lebih kenes ketimbang kakaknya. Wajahnya rajin diolesi bedak dingin buatannya sendiri. Tiap hari gincu merah tak lupa disapukan ke bibir. Dan tentu saja ia menolak berpanas-panas di tengah laut. Anak-anak generasi baru Bajo di BajoE tak mengenal kejayaan nenek moyangnya, "Seperti ada rantai putus yang menyebabkan kami tak tahu cerita mereka," kata seorang warga bernama Nadjamuddin. Mungkin ia benar karena hikayat itu memang tak pernah dihidupkan pada anak-anaknya. Bahkan seni budaya pun hampir tergusur punah. Dalam upacara-upacara tertentu, perkawinan misalnya, mereka sudah menyerap cara Bugis. Padahal, masyarakat Bajo, dulu, sangat bangga pada baong same. Itulah alat komunikasi yang mempersatukan mereka yang tinggal terpencar-pencar. H.A. Nimmo, seorang peneliti dari California, yang pernah datang ke BajoE, membuktikan adanya kesamaan bahasa antara suku laut di Pulau Zulu, Filipina Selatan, dan Bajo di BajoE. Sekarang orang Bajo di BajoE lebih banyak menggunakan bahasa Bugis daripada bahasa nenek moyangnya. Maka, bukan tak mungkin baong same akan punah. Sebab, umumnya mereka buta huruf. Tak tahu bagaimana menuliskan kalimat yang diucapkannya. Selain bahasa, tanda pengenal lain: ula-ula. Di lautan, ula-ula ini dipasang di depan kapal. Semacam "bendera" yang mengesankan sosok manusia. Tingginya sekitar 5,5 meter dan warnanya berubah-ubah mengikuti zaman. Hitam, lalu merah-putih-biru di zaman Belanda, dan kemudian merah-putih. Milik para bangsawan itu sekarang -- dianggap keramat -- sudah langka. Nasib tarian pun begitu pula. Dulu, pada setiap perayaan apa saja, suku Bajo selalu menampilkan tarian-tarian. Mulai dari tari kondo (tari burung bangau), tari nangaruak (tari pergaulan), tari sulwawane (tari madu), dan tari pukak-pukak (tari menangkap ikan). "Tarian itu cuma ditarikan laki-laki. Perempuan tidak bisa karena dulu perempuan tidak boleh bercampur dengan laki-laki. Jadi, mereka hanya boleh menonton," kata Jaelani, sambil mempertontonkan gerakan tari pukak-pukak. Tapi tarian ini tak dikenal lagi sekarang. Bahkan Jaelani, yang dulu pernah jadi penari, sudah lupa gerakan-gerakannya. Haji Jaelani adalah contoh Bajo yang tidak lahir di laut. Orangtuanya, setelah capek melaut, memilih tinggal di darat. Betul-betul di darat. Maka, meski keturunan bangsawan, Jaelani tak pernah melaut. Istrinya pun orang Bugis. Tapi tokoh ini disegani di kalangan Bajo, karena gelarnya itu. Ia fasih berbahasa Bajo, Bugis, dan Indonesia. Sehari-hari, ia adalah Kepala Bidang Kesejahteraan di Kantor Desa BajoE. Jaelani sendiri mengakui, tak ada seni Bajo yang diwariskan kepada anak-anak. Segala tata cara ritual maupun adat, kini, banyak terpengaruh adat Bugis. Termasuk adat perkawinan. Ia sendiri bingung, bagaimana membangkitkan budaya yang pernah ada itu. Tapi di tengah kebingungan Jaelani, ada angin segar datang dari Bupati Bone. Ia berniat mencagarbudayakan kampung suku Bajo itu. "Ini salah satu upaya menggali potensi yang ada di BajoE," ujar Andi Syamsoel Alam, 45 tahun. Suku Bajo, menurut dia, sangat potensial. Maka, ia ingin, "Unsur-unsur budaya yang hilang itu digali kembali. Sehingga tata cara kesukuan itu bisa disuguhkan kepada turis," katanya. Banyak hal ia persiapkan. Termasuk menyediakan kawasan di belakang tanggul, untuk pembangunan 45 rumah Bajo asli. Tentu dengan rancangan sedikit modern. Misalnya, dengan tiang-tiang yang dicor semen. Agar tetap berdiri kukuh. Dan tanggul itu akan dibongkar sedikit, untuk memberi jalan air laut. "Dengan demikian, orang Bajo merasakan kondisi rumah seperti dulu lagi. Ada genangan air di bawah rumahnya. Kalau seperti sekarang, apa bedanya dengan rumah darat," katanya menggebu-gebu. Ia pun berniat menata rumah di lingkungan kumuh itu. Di Sulawesi Selatan, suku Bajo tidak masuk kategori suku terasing. Karena itu, ia tidak mendapat dana dari Depsos. Ini ditegaskan oleh Kepala Bidang Bina Kesejahteraan Sosial Kantor Wilayah Departemen Sosial Provinsi Sulawesi Selatan. "Bajo tidak termasuk masyarakat terasing karena sudah berdomisili di daerah tertentu," kata H. Bahra Dafrid. Maka, dana Rp 74 juta untuk tahun anggaran 1990/1991 diprioritaskan untuk suku-suku di pedalaman.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini