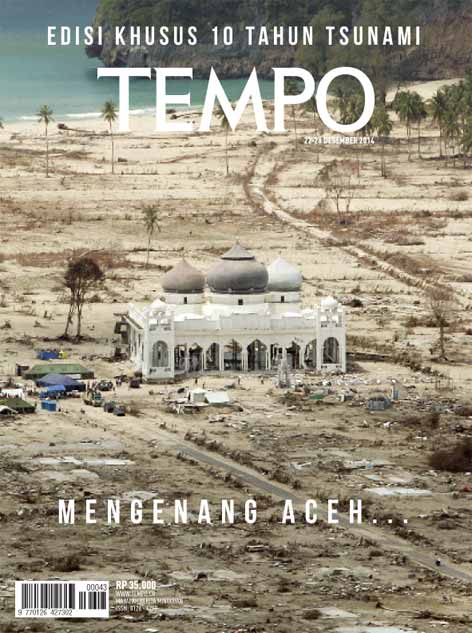Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Kafe itu menampakkan wajah mentereng dengan cat hijau menyala. Tapi ruangan di dalamnya ternyata kosong melompong. Hanya meja dan bangku berselimut debu yang mengisinya. Ayu Cafe Lhoknga di Gampong Mon Ikeun, Aceh Besar, itu ternyata sejak awal tahun lalu sudah tutup.
Padahal kafe ini sempat menjadi primadona di daerah itu. Hidangan mi Acehnya dikenal lezat. Sejumlah selebritas juga presenter kuliner pernah berkunjung ke sana. Seiring dengan berjalannya waktu, bukannya semakin maju, sebaliknya pamor kafe ini semakin redup. Pada 2011, pemiliknya, Ruslaili, meninggal—tatkala jumlah pengunjung kafenya menurun. Anak sulung Ruslaili, Wahyu Satria, hanya bisa menduga-duga penyebab kebangkrutan bisnis keluarganya itu. "Mungkin pelanggan tak mempercayai hasil racikan kami," kata pemuda 22 tahun itu. Kini Wahyu bekerja di Warkop Jubir Banda Aceh.
Ruslaili dan anaknya adalah salah satu korban tsunami Aceh. Air bah itu tak hanya melenyapkan harta benda Ruslaili, tapi juga istrinya, Sulasmi. Bersama tiga anaknya, Ruslaili sempat tinggal di sebuah barak pengungsian yang letaknya tak jauh dari bekas rumah mereka.
Duka Ruslaili menjadi-jadi lantaran ia kesulitan mendapatkan bantuan pembangunan rumah di tempatnya mendirikan kafe mi Aceh sebelum tsunami. Penyebabnya, sertifikat tanahnya—bukti bahwa lahan itu hak miliknya—ikut lenyap disapu tsunami. Masalah ini semakin pelik karena ada keluarganya yang lain ikut mengklaim tanah tersebut.
Persoalan yang dialami Ruslaili itu juga tercatat pada laporan Oxfam, lembaga nirlaba yang meneliti masalah pertanahan di Aceh dua tahun setelah tsunami. "Ilalang sudah mulai tumbuh di bekas rumah Ruslaili, sedangkan rumah-rumah lain sedang dibangun," tulis laporan yang diberikan Irwan Firdaus dari bagian advokasi Media Oxfam, awal Desember lalu.
Ruslaili sebenarnya tak perlu direpotkan oleh pengurusan sertifikat jika saja ia ikut program Reconstruction of Aceh Land Administration System (Laras). Didanai Bank Dunia US$ 28,5 juta, sebelumnya program ini menargetkan penyelesaian sekitar 600 ribu bidang tanah mulai 1 Juli 2005 sampai 31 Desember 2008.
Namun proyek di bawah kendali Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Aceh-Nias itu mandek. Oxfam mencatat, hingga 2006, program Laras hanya mampu mengeluarkan 2.608 sertifikat. "Karena keterlambatan proses administrasi di Jakarta," tulis Oxfam.
Pada 2009, program Laras disetop bersamaan dengan langkah Bank Dunia menarik sisa anggarannya. Sertifikat yang telah diterbitkan tak sampai setengah dari target semula. Bekas Wakil Gubernur Aceh Muhammad Nazar mengatakan penghentian proyek itu kemungkinan besar berkaitan dengan kebijakan pemerintah pusat. "Karena prosesnya berada di sana," katanya.
Kuntoro Mangkusubroto, bekas Kepala BRR, menyatakan sudah menggunakan berbagai cara untuk mempercepat penuntasan masalah tanah korban tsunami. Misalnya dengan memberikan sertifikat kepada janda korban tsunami yang tanahnya terancam dirampas keluarga pihak suami, begitupun sebaliknya seperti yang dialami Ruslaili.
Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral itu mengajari warga untuk mempermudah proses penerbitan sertifikat melalui pengukuran batas-batas tanah secara konvensional. Misalnya berpedoman pada bekas-bekas bangunan rumah yang tak hancur akibat tsunami, seperti kamar mandi dan jamban. "Bagian itulah yang paling kuat. Jadi, sisa bangunan itu masih ditemukan," kata Kuntoro kepada Tempo, akhir November lalu.
Cara cepat—juga sederhana—yang diajarkan Kuntoro itu cukup ampuh diterapkan warga di Desa Lambueng, Kecamatan Meuraxa, Banda Aceh. Wilayah pesisir Aceh itu bebas dari masalah penerbitan sertifikat baru ataupun batas tanah warga. Rumah bertingkat tumbuh di sana. Juga dilengkapi fasilitas umum yang teratur dan menganut konsep mitigasi bencana. Misalnya ruas jalan yang bisa dilewati dua mobil.
Padahal sebelumnya wilayah itu terhitung rawan sengketa lantaran sempat rata dengan tanah. Dari 1.900 penduduk, hanya 200-an yang selamat. "Kami menyelesaikan dengan mengukur tanah secara sederhana dan musyawarah antarwarga," kata Hardiansyah, Wakil Kepala Desa Lambueng. Menurut Kuntoro, ia tidak pernah mendengar, dari kebijakannya tentang tanah pasca-tsunami, ada sengketa atau tanah yang diserobot.
Sebenarnya, fakta di lapangan, persoalan tanah setelah tsunami ini masih menjadi masalah sendiri. Salah satunya banyaknya kasus tanah yang masuk Mahkamah Syar'iyah, lembaga peradilan yang menangani sengketa tanah pasca-tsunami.
Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Provinsi Aceh Jamil Ibrahim mengatakan jenis kasus yang ditangani lembaganya beragam, dari saling klaim batas, perebutan hak waris, hingga tanah yang tak lagi bertuan. Kasus yang terbanyak datang dari daerah yang disapu bersih air bah, seperti Banda Aceh, Aceh Besar, Aceh Barat, dan Aceh Tengah. "Mungkin ada ribuan kasus waktu itu," ujar hakim Jamil saat dijumpai di kantornya pada 19 November lalu.
Salah satu yang disidangkan Mahkamah adalah tanah Ruslaili si pengusaha kafe itu. Wahyu Satria, sang anak yang kala itu berusia 12 tahun, bercerita ketika itu ia kerap mendampingi ayahnya ke Mahkamah. Ia mengatakan ayahnya saat itu hendak mengubah kepemilikan tanah, dari yang sebelumnya atas nama "mendiang" istrinya menjadi namanya. Pihak keluarga sang istri keberatan karena tanah seluas 500 meter persegi itu warisan dari nenek moyang mereka.
Keluarga ibunya, kata Wahyu, khawatir pengubahan nama dokumen tanah tersebut akan menyulut persoalan di belakang hari. Apalagi Ruslaili sudah menikah lagi. Keluarga Sulasmi mengaku tak mengenal latar belakang perempuan yang dinikahi Ruslaili delapan bulan setelah tsunami itu.
Tapi belakangan keluarga Sulasmi luluh juga. Bukti dan kesaksian menguatkan alibi Ruslaili dan ia pun memenangi perkara itu. Sertifikat tanah pada 2010 beres. Tapi ada persoalan keluarga lain yang belum selesai. "Itu juga yang membuat kami menutup kafe ini," kata Wahyu.
Hakim Jamil mengakui memang kerap timbul persoalan setelah Mahkamah mengetukkan putusan. Menurut dia, saat proses peradilan, hal biasa jika ada pihak keluarga yang bersitegang. Jamil menolak menceritakan secara rinci penyebabnya. "Itu tak menonjol," kata pria yang kini mengikuti program doktor di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Aceh, itu.
Padahal Mahkamah, menurut hakim Jamil, berupaya menghasilkan putusan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan penggugat dan tergugat. Saksi-saksi dikumpulkan untuk mencari kebenaran status tanah, dari kerabat yang beperkara, perangkat desa, hingga tokoh masyarakat setempat. Untuk mendekatkan para saksi, proses peradilan kebanyakan dilakukan di lapangan.
Mahkamah, kata Jamil, juga segera akan mengamankan tanah yang tak jelas pemiliknya melalui Baitul Mal, sejenis Badan Amil Zakat, di Aceh. Tujuannya agar tak diserobot orang. Cara ini juga akan memudahkan ahli waris memproses kepemilikan tanah di kemudian hari.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo