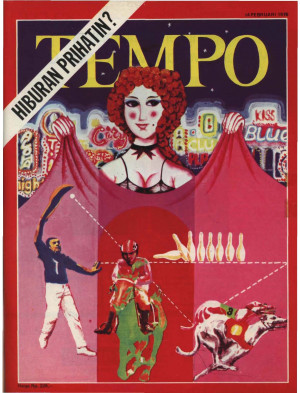DI Kecaman Kediri, laut terlalu ganas untuk dijadikan tumpuan
harapan. Karang yang menjulang tinggi tidak memungkinkan untuk
tempat mengalihkan usaha, membuat garam misalnya. Juga di Tanah
Lot, yang jadi obyek pariwisata, tidak terlalu menguntungkan
untuk obyek baru bagi petani desa sekitar itu. Cuma anak-anak
kecil semakin banyak beroperasi sebagai penjual barang-barang
kerajinan.
Maka beberapa desa di Kecamatan Kerambitan seperti Kelating,
Pasut atau Desa Yeh Ganggang Kecamatan Tabanan, boleh dibilang
laut tempat tumpuan terakhir dari kemelut serangan wereng ini.
Laut mulai diserbu para petani yang sebelumnya tak punya
keahlian apa-apa soal laut. Di Pantai Kelanting misalnya,
pondok-pondok darurat didirikan dan petani yang hijrah itu mulai
usaha baru, membuat garam. Penggaraman dengan alat-alat yang
keliwat tradisionil itu juga tak banyak menuntut tenaga, cuma
siram dan jemur pasir,dan karenanya tugas itu dilimpahkan pada
kaum wanita atau anak-anak. Sementara sang bapak mencebur ke
laut menangkap ikan, walaupun lebih sering sia-sia karena memang
tak punya keahlian dan alatnyapun cuma jala yang biasa dipakai
di sungai. "Ketimbang merenung, pekerjaan begini masih bisa
menghilangkan lapar,yang penting sibuk", kata Pan Sigra di
pantai Kelating.
Usaha untuk menyerbu laut juga mendatangkan problim yang tak
kalah ruwetnya. Di Kelating saja misalnya, ketika padi di sawah
masih dibanggakan hasilnya, 11 KK yang bergerak di bidang
penggaraman juga cukup berbangga. Tapi kini dengan makin
banyaknya petani berharap pada laut, terdapat 55 KK yang
mengusahakan penggaraman. Akibatnya pantai yang tidak begitu
luas karena ada muara sungai dan karang harus dibagi 55 petak
untuk menentukan batas penjemuran pasir. Praktis petak
penjemuran pasir terlalu kecil yang mengakibatkan pula
pengusaha-pengusaha garam ini kekurangan pasir. Padahal dalam
penggaraman tradisionil ini pasir adalah bahan baku utama di
samping air laut.
Datangnya penghuni baru di pantai tidak begitu saja disambut
dengan tangan terbuka oleh pendatang sebelumnya, sebab sangat
terasa mempengaruhi produksi garam per KK. Namun bagi Biyang
Sadikel yang anaknya berumur 2 1/2 tahun dan 1 1/2 tahun
menganggap biasa saja. "Waktu ada pembagian beras, saya juga
terima 7 kg", katanya, "walaupun saya tak punya sawah".
Barangkali dengan alasan seperti ini membuat 55 KK penghuni
pantai Kelating seperti hidup rukun, dan merasa bahwa mereka
seluruhnya -- termasuk yang 11 KK tadinya -- sebagai korban
utama keganasan wereng. Hingga seluruhnya merasa berhak menuntut
bagian kalau droping beras tiba.
Sementara sawah diserang wereng, lautpun tidak selalu jinak.
Dalam air pasang praktis pengusaha garam ini tak bisa berbuat
apa-apa. Pantai untuk menjemur pasir tertelan laut. Bukan itu
saja, kalau air surut, artinya pantai bisa dipergunakan, hujan
yang turunnya sering akhir-akhir ini juga rintangan utama. Maka
jangan heran kalau dalam seminggu, pengusaha garam di pantai
Kelating bekerja tak lebih dari 3 hari. Itupun kalau ada kayu
api kering untuk memasak air yang mengandung kadar garam untuk
dijadikan garam hingga siap diambil "tengkulak garam". Ni Lemog
bercerita, kalau dulu semasih 11 KK, kesempatan menjemur pasir 1
hari saja sudah bisa diproses 4 kali -- dengan jalan pasir yang
kering ditimbun dan ditutupi jerami. Sekarang tentu berbeda,
karena petak jemuran diperkecil, dibagi 55 buah. Sekali jemur
pasir untuk sekali proses. Dari sini didapat 2 belek --
sekitar 30 liter air yang siap dimasak. Mereka sebut air sari.
Mengetahui air sari ini dengan jalan memasukkan buah kemiri ke
air, kalau tenggelam mereka saring lagi -- namanya masih "air
kabar", kalau kemiri mengandung pertanda air sari yang
mengandung kadar garam. Air ari yang 2 blek itu dimasak 14 jam
non stop untuk mendapatkan 1 blek kecil garam, dijual dengan
harga Rp 200 sampai Rp 300. Kalau seminggu mereka kerja
rata-rata 3 kali -- dalam musim hujan ini -- maka
penghasilannya cuma Rp 600 per minggu untuk kehidupan paling
minim 4 perut tiap KK. Harga beras sudah mencapai Rp 155 per
kg, Maka bisa dibayangkan bagaimana pahitnya hidup mereka. "Kami
yang tua-tua 3 hari tak kena nasi tidak apa-apa, cukup ketela.
Tapi anak-anak nasinya dicampur ketela" ujar Biyang Sadikel.
Penghuni lain mengatakan, campuran nasi dan ketela termasuk
makanan hebat, dibanding bulung laut (agar-agar) tanpa nasi.
Sedangkan Pan Sigra yang punya 3 anak ketika ditanya tidak
berkomentar banyak. "Jangan tanya soal makanan kami, bapak kan
sudah tahu", katanya sambil menunjuk ke arah pohon pepaya yang
sudah dicercah untuk dicari "hatinya". Hari-hari lelakangan ini
hanya itu menu keluarganya.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini