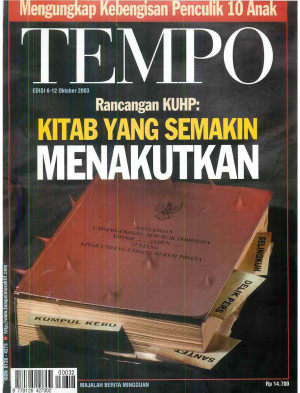Dari langit, hamparan luas itu tampak bagai festival. Gedung warna-warni, umbul-umbul, penjor Bali melambai-lambai ditiup angin. Kuta Galeria, kompleks pertokoan mewah yang dibuka beberapa pekan lalu, seperti tengah merayakan kembalinya Bali ke zaman normal: zaman ketika turis datang bergelombang seperti ombak yang tak pernah habis.
Setahun lumpuh disengat bom Legian, Bali kini mulai bernapas kembali. Denyut kehidupan itu bukan hanya tampak dari tumbuh suburnya mal dan kafe baru, tapi juga terisinya kembali kamar-kamar hotel mewah. Kursi restoran mulai penuh pengunjung dan dunia malam yang sempat mendingin kini menghangat lagi.
Napas kehidupan juga terasa di atas langit Bali. Selama beberapa bulan terakhir, sejumlah perusahaan penerbangan-baru mulai mendarat di Bandar Udara Ngurah Rai. Lion Air dan Star Air meramaikan penerbangan dari Jakarta, sedangkan Air Paradise bertarung di jalur Denpasar-Melbourne dan Perth.
Selain itu, musim semi industri wisata Bali juga tercatat dalam statistik. Riset bersama UNDP, Bank Dunia, dan USAID menunjukkan jumlah pelancong asing ke Bali sudah mulai mendekati angka normal (lihat Pesta untuk Kalangan Terbatas).
Kembalinya Bali akan menjadi kunci penting pulihnya industri wisata Indonesia, yang menjadi pencetak devisa kedua terbesar setelah ekspor migas. Selama ini, hampir sepertiga pelancong asing memasuki Nusantara melalui Bali. Tanah Nirwana ini pula yang menjadi pintu gerbang turis asing menuju daerah wisata lain seperti Yogyakarta dan Lombok.
Sayangnya, sukses Bali harus dilihat dengan sejumlah catatan. Setiap kabar baik rupanya punya sisi gelap: membeludaknya turis ke Bali tak lepas dari obral tarif perusahaan penerbangan dunia. Karena itu, pemulihan Bali dalam jangka panjang tergantung kemampuan industri penerbangan dunia menekan ongkos dan memperbaiki dirinya menjadi industri yang efisien.
Selain itu, isi kantong pelancong, setidaknya dalam beberapa tahun mendatang, tak setebal dulu. World Tourism Organization memperkirakan, muramnya perekonomian dunia selama tiga tahun terakhir akan memaksa para turis pintar-pintar mengatur pengeluaran. Demi penghematan, mereka tak akan pergi terlalu jauh dari rumahnya.
Dengan dua catatan itu, industri wisata Bali di masa depan tetap rentan gejolak. Bagi budayawan Bali, I Wayan Geriya, ancaman ini harus dijawab dengan mengurangi ketergantungan Bali pada pariwisata. Seperti kata pepatah "jangan letakkan telur dalam satu keranjang", Geriya mendesak agar lumbung uang pemerintah daerah juga dibagikan ke sektor-sektor yang lain.
Usulan Geriya sebenarnya sejalan dengan rekomendasi Bank Dunia. Persoalannya, sumber alam Bali sangat terbatas. Di luar ombak, terumbu karang, pasir pantai, hutan, dan danau yang indah-indah itu, Bali praktis tak punya apa-apa. Minyak bumi tidak ada, deposit tambang dan mineral juga tidak.
Selain itu, bagi Bali, small ternyata tak selalu beautiful. Luas provinsi yang mungil, cuma seperdelapan Jawa Barat, membatasi ruang gerak, terutama jika berkaitan dengan industri yang menuntut "skala ekonomi".
Mengalihkan ketergantungan Bali dari pariwisata ke pertanian, misalnya, akan kepentok ukuran lahan yang terbatas. Cengkeh, kopi, dan kelapa memang menjadi sumber kekayaan beberapa petani besar di Kabupaten Negara dan Buleleng. Namun, menjadikan komoditas pertanian sebagai soko guru ekonomi yang menghidupi seluruh penduduk bisa dibilang mustahil.
Begitu pula cita-cita pengembangan industri manufaktur, yang akan terbentur pasar yang terbatas. Jumlah penduduk Bali hanya 3 juta, sepertiga penduduk DKI. Selain itu, bahan baku tergolong langka dan biaya tenaga kerjanya lebih mahal (tingkat upah minimum regional di Bali setara dengan Jawa Timur, yang lebih banyak menyediakan tenaga kerja kasar).
Dengan pelbagai keterbatasan itu, apa boleh buat, nasib dan hari depan Bali akan tetap ditentukan oleh suram-tidaknya industri wisata yang rentan gejolak. "Yang bisa dilakukan," kata seorang konsultan pariwisata, "hanyalah mencari cara agar kerentanan itu bisa dikurangi."
Harus dipahami, karakter turis yang bulan-bulan ini mendarat ke Bali berbeda dengan pelanggan tradisional yang selama ini menjadi tamu Pulau Dewata. Selama beberapa tahun terakhir, adalah warga Jepang, Australia, dan Taiwan yang memadati hotel, restoran, dan kafe-kafe di Bali. Merakalah yang tercatat sebagai tiga besar pelancong yang membanjiri pulau seribu pura itu.
Selama enam bulan terakhir, posisi tradisional itu mulai bergeser. Data yang akurat memang tak tersedia. Namun, sejumlah keterangan para pengelola hotel menunjukkan posisi teratas tak lagi dimonopoli turis Jepang, tapi sudah ditempel ketat turis Taiwan.
Jumlah pelancong dari Australia juga terlihat melorot drastis, digantikan pendatang baru dari Singapura dan Korea Selatan. Hari-hari seputar tahun baru Cina, Februari lalu, semua penerbangan Singapura Airlines dari dan ke Denpasar sudah habis dipesan beberapa pekan sebelumnya.
Satu pendatang baru yang lain: turis lokal atau yang sering disebut dengan nada sedikit menyepelekan sebagai "wisnu" alias wisatawan Nusantara. Bagi para pecandu liburan di Jakarta, Bali saat ini dianggap sebagai tujuan terbaik. Selain karena sedang banyak diskon, juga dianggap lebih aman ketimbang Singapura atau Hong Kong, yang sedang terancam sindrom pernapasan, SARS.
Pergeseran ini bukan hanya menyangkut perbedaan geografi, asal-usul, kultur, bahasa, dan adat para tamu, tapi yang lebih penting: kesenangan, pola belanja, lama liburan, dan kemampuan kantongnya. Semua ini menuntut sejumlah perubahan besar dalam hal servis ataupun bentuk suguhan industri pariwisata Bali.
Selama ini, Bali dikenal sebagai surga nyaman di halaman depan Australia. Bagi warga Benua Kanguru itu, Bali ibarat Yunani bagi kebanyakan orang Eropa atau Hawaii bagi penduduk pantai barat Amerika dan Bahama bagi New Yorker. Sebelum bom Legian, setiap hari ribuan warga Australia terbang langsung dari jalanan di Perth, Melbourne, atau Darwin untuk membanjiri Kuta.
Akibatnya, terjadi semacam "Australianisasi" Bali. Kafe-kafe di Legian menjual bir Forster, yang bercap kanguru, jauh lebih kencang ketimbang Heineken, Corona, atau San Miguel. Lagu-lagu kelompok musik Men At Work, yang tak pernah mengudara di Jakarta, tiba-tiba begitu akrab di telinga.
Itu baru kafe. Masih ada suguhan khas Australia dan selera "Barat" yang lain: atraksi wisata petualangan seperti bungee-jumping, scuba-diving, dan arung jeram. Dalam lima tahun terakhir, pengelola wisata petualangan Bali tumbuh begitu subur.
Persoalannya, tamu-tamu baru Bali saat ini bukan mereka yang gandrung olahraga ruang luar alias outdoor. Itu sebabnya, lonjakan turis asing di Bandara Ngurah Rai dua bulan terakhir tak diikuti dengan tanda-tanda kehidupan wisata petualangan yang hampir setahun ini mati suri.
Sobek Bali Utama, pengelola arung jeram di Sungai Ayung, Karangasem, misalnya, sampai saat ini tetap pingsan. Sebelum bom Legian, pionir wisata petualangan di Bali itu kebanjiran 100-150 tamu sehari. Dengan pendapatan Rp 500 ribu yang dikutip dari tiap peserta, Sobek mampu menghidupi 300 karyawan. Tapi, dengan jumlah tamu hanya 25-50 orang saat ini, Sobek tak punya pilihan, sepertiga karyawan terpaksa dipensiun dini.
Selain tak menyukai wisata petualangan, isi kantong tamu-tamu Bali yang baru ini juga kurang tebal. Mereka membanjiri Tanah Nirwana itu lataran dorongan paket diskon (tarif penerbangan, hotel, dan akomodasi) yang besarnya bisa sampai 50 persen. Itu sebabnya, resor-resor ekstraluks di Nusa Dua sampai hari ini masih saja sepi, tak kebagian tamu. Jika ini terus berlanjut, para pemilik gubuk mewah itu agaknya harus bersiap-siap gulung tikar.
Dan satu lagi, turis asing yang kini menyerbu Bali bukanlah para backpackers seperti kebanyakan anak-anak muda Australia, yang pada masa jayanya sebelum bom Legian meletup sempat membuat Kuta seperti kampung gembel. Meskipun duitnya cekak, turis Singapura berlagak seperti nonik-nonik Jakarta yang pemilih: ogah tidur di losmen murahan yang penuh nyamuk dan bau got.
Turis domestik sebenarnya punya potensi untuk mengisi pasokan losmen yang ditinggalkan para backpackers. Namun, jumlah wisnu yang uang sakunya pas-pasan tak cukup banyak untuk menempati 20 ribu kamar penginapan tanpa bintang yang kini menjamur di seantero Kuta, Ubud, Bedugul, dan Candi Dasa. Dengan kata lain, jika para pengusaha losmen tidak segera berkemas, akan terjadi perang tarif losmen yang ganas.
Menghadapi pelbagai perubahan itu, pelaku industri pariwisata Bali di masa depan harus kreatif. Pasir, ombak, ngaben, dan tari kecak memang bisa menjadi modal yang besar untuk menjala pengunjung. Namun, kualitas dan keaslian surga yang empat dasawarsa lalu terasa alami bakal merosot seiring dengan ramainya turis. Pantai Kuta bisa saja menarik perhatian turis baru, tapi pelanggan lama akan pergi mencari surga lain yang belum terjamah. Karena itu, bentuk sajian maupun servis harus senantiasa disesuaikan dengan tuntutan pelanggan.
Wisata adalah "bisnis kaum sejahtera", konsumennya mereka yang kelebihan uang. Sejalan tuntutan kaum berduit yang ingin sehat dan kembali ke alam, sejumlah resor top di luar negeri kini menyajikan paket tiga-M: massage, mud, and medicine menggantikan ikon sand, sun, and smile yang sudah kehilangan peminat.
Pengelola wisata di Afrika Selatan juga punya menu istimewa yang kini banyak digandrungi New Yorker: "scalpel safaries". Ini adalah layanan terpadu yang terdiri dari perawatan bedah kecantikan di Johannesberg, disambung dengan petualangan ke Pantai Cape Town yang permai atau menelusuri hutan.
Di Bali, kita bisa menyediakan wisata budaya, misalnya, dengan mengajak para turis tinggal di rumah-rumah penduduk di desa. Mereka bisa mengikuti persiapan upacara adat atau menghadiri acara budaya di banjar. Pendeknya, bukan sekadar suguhan dasar seperti wisata seksual yang dijual Thailand—sebuah wisata yang menjamin Anda pulang ke rumah sebagai "orang lain".
Terakhir, dalam jangka panjang, industri wisata Bali harus menyesuaikan diri dengan tuntutan calon konsumen potensial di masa depan, yakni Cina dan para manula. Meskipun saat ini masih ada sejumlah hambatan izin dari pemerintahan di Beijing, warga Cina tampaknya akan menjadi calon-calon turis yang antusias di masa depan. Tahun lalu, lebih dari 16,5 juta orang Cina melanglang buana, setara dengan jumlah warga Prancis dan Italia yang ke luar negeri.
Calon konsumen potensial lain adalah mereka yang berumur 50 tahun ke atas. Manula masa depan diperkirakan bakal lebih sehat, lebih sejahtera, dan karena itu lebih banyak berlibur. Markus Deutsche, Direktur Pelaksana Cendant Vacation, sebuah konsultan industri wisata, memperkirakan bahwa dua tahun mendatang sepertiga pelancong yang memadati daerah wisata di seluruh jagat adalah para manula.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini