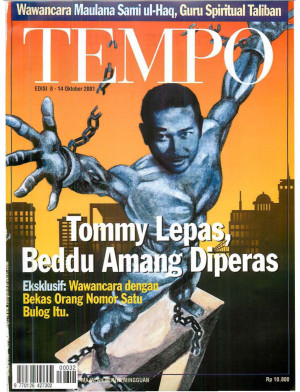Ruang-ruang perawatan Rumah Sakit Ibn Sina di Kabul ibarat kamp pengungsi. Pasien meluber tak tertampung. Tak ada lagi beda antara si sakit dan pengunjung. Dokter Amjad Hussein, ahli bedah kardiovaskuler dari Ohio, langsung syok melihat keadaan itu. Sekitar 30 tahun lalu dokter wanita itu magang teknik baru pembedahan jantung di Ibn Sina. Berdiri pada 1960, Ibn Sina adalah salah satu rumah sakit khusus paru-paru dan jantung terbaik di Asia pada masa itu. Kini, Hussein menyaksikan betapa kejayaan almamaternya betul-betul tak bersisa: obat-obatan begitu minim. Inkubator untuk bayi prematur sudah karatan atau pecah. Laboratorium memadai adalah barang langka.
Di bawah pemerintahan Taliban, rumah sakit adalah satu-satunya tempat perempuan boleh bekerja. Toh, Amjad Hussein merasa serba canggung. Aparat Taliban selalu mengawasi tindak-tanduk pegawai rumah sakit. Perawat yang tidak mengenakan burkak—pakaian hitam yang menutupi kepala sampai kaki kecuali secelah lubang mata—bakal disabet. ”Hampir tak bisa dipercaya bahwa dokter profesional di rumah sakit pun harus mengenakan burkak,” tulisnya dalam The Blade, empat bulan silam.
Apa yang ditulis Amjad Hussein adalah realitas muram Afganistan di bawah Taliban. Di satu pihak rezim itu ber-usaha menata kembali rumah sakit yang boyak, menghidupkan kembali listrik, memperbaiki sistem air bersih, sanitasi yang hancur. Tapi, di lain sisi, sang penguasa menerapkan aturan-aturan absurd: mengharamkan diagram dan gambar mengenai anatomi manusia, melarang perempuan kuliah. Alhasil, perawat dan dokter wanita yang dulu banyak dihasilkan Universitas Kabul kini tinggal cerita.
Taliban juga melarang dokter laki-laki merawat pasien perempuan, sehingga kematian kaum wanita Afganistan me-lejit sejak Taliban mulai berkuasa pada 1996. Tapi Wakil Menteri Kesehatan Taliban Abbas Stanikzai membantah hal itu. ”Apa yang ditulis media Barat itu salah semua,” ujarnya kepada Washington Post tahun silam. ”Kami punya banyak klinik perempuan. Kami juga memperbolehkan (untuk be-berapa kasus) dokter laki-laki merawat pasien perempuan,” ia melanjutkan. Bagaimana prakteknya di lapangan? Silakan simak catatan Human Right Watch berikut ini.
Suatu kali di ruang gawat darurat Rumah Sakit Kabul terbaring beberapa pasien perempuan korban luka bakar. Untuk menyelamatkan nyawa, dokter lelaki harus menyingkap kain yang mereka kenakan. Tapi penjaga Taliban tidak mengizinkan hal itu. ”Kematian adalah soal biasa,” hanya itu alasannya.
Dari Kandahar sampai Kabul—laporan itu menyebutkan—banyak pasien rawat inap perempuan dipulangkan pengawal, betapapun parah kondisinya. Mereka dianggap tak bisa menjaga ”kerapian burkak” di keramaian rumah sakit. Begitu parahkah nasib para pasien wanita? Nanti dulu!
Relawan sosial di Provinsi Badghis, Karine Zander, punya pengalaman bahwa kaum lelaki pun sama malangnya. Suatu hari, dokter asal Inggris ini mengantar seorang pria korban diare ke Kalinow—ibu kota provinsi. Perjalanan sudah makan waktu tiga jam ketika kondisi laki-laki itu memburuk. Sekitar 10 menit dari rumah sakit, azan magrib berkumandang. Mobil langsung berhenti. Aturan Taliban menetapkan, salat harus tepat waktu. Jadi, orang-orang Afganistan itu melakukan salat bersama selama 45 menit. Selesai salat, sang pasien telah mati.
Ancaman kesehatan juga terjadi karena sejak 1997 hampir 80 persen dokter spesialis dan dokter bedah lari meninggalkan Kabul. Mereka menghindari tugas mengerikan yang dibebankan penguasa Taliban: menjadi pelaksana hukuman potong tangan bagi para pencuri. Dengarlah apa yang disiarkan langsung Radio Kabul dari Kabul Sport Stadium ke seluruh Afganistan, suatu hari tahun 1998.
”… Para pendengar, kini dokter membubuhkan pemati rasa pada tangan Hamidullah. Hamidullah telah mencuri barang seharga US$ 313 (sekitar Rp 3,1 juta) di sebuah toko di Kabul…. ” Pelaksanaan acara ini seperti seremoni kenegaraan yang dihadiri banyak pejabat, antara lain Menteri Penerangan Taliban Mullah Amir Khan Muttaqi dan Menteri Dalam Negeri Taliban Mullah Khairulli Kahairkhwa. Upacara ini ”belum seberapa” dibandingkan dengan hukuman mati bagi mata-mata atau perusuh. Itulah yang terjadi suatu hari pada Maret 1998.
Sebuah pengeras suara besar di Kabul Sport Stadium berkoar-koar sejak pagi menyambut kedatangan 30 ribu pengunjung. Berduyun-duyun mereka datang untuk menyaksikan ”upacara” penggantungan Bahram Khan. Orang ini terbukti meledakkan salah satu instalasi militer di Kabul. ”Kami mengumpulkan kalian di sini bukan untuk piknik. Kami ingin memberikan sebuah pelajaran,” terdengar suara pidato seorang pejabat.
Sesuai dengan hukum Islam, sebelum melaksanakan eksekusi, petugas Taliban bertanya kepada ayah Bahram, apakah ia memaafkan anaknya. Sang ayah menjawab ”tidak”. Bahran pun menuai ajal dan tubuhnya diarak. Di Kota Spinboldak, dekat perbatasan Pakistan, Mullah Omar pernah memerintahkan hukuman gorok leher. Beberapa orang yang menonton pingsan melihat adegan ”teater barbarisme” itu.
Hukum Taliban itu memang ”sukses” membelalakkan mata masyarakat internasional. Menciptakan ketertiban adalah dalih untuk semua hukum yang superkeras ini. Sebelum naiknya Taliban, Afganistan memang diombang-ambingkan anarki dan perang antarlaskar (lihat Sebuah Negeri, tanpa Damai?). Penjarahan, perampokan, pemerkosaan adalah pemandangan sehari-hari. Pemerintahan Burhanuddin Rabbani yang korup tak bisa mengatasi ini. Bahkan terbukti, para aparat mujahidinnya adalah pelaku utama pemerkosaan.
Maka, begitu menumbangkan Rabbani pada 1996, Mullah Omar alias Ayatulah Taliban segera menerapkan hukum Islam secara kaku. Ia berpendapat, dalam keadaan genting, interpretasi tekstual Al-Quran adalah satu-satunya solusi. ”Harus diakui, setelah Taliban, ada jaminan keamanan. Sebelumnya, untuk pulang ke desa saja tidak mungkin,” ujar seorang petugas PBB asal Afganistan.
Apa yang diungkapkan petugas PBB ini bukan tanpa indikasi. Begitu Taliban menduduki Kabul, hampir sejuta pengungsi Afgan kembali ke Afganistan. Persoalannya, hidup seperti apa yang mereka temukan setelah itu? ”Selera humor warga lenyap. Masyarakat letih, bahkan sulit tertawa,” tutur Saira Shah. Wartawan CNN keturunan Afganistan ini melaporkan betapa dalam depresi psikologis yang melanda masyarakat.
Bayangkan, main layang-layang atau main catur adalah perbuatan haram. Lelaki yang tak berjanggut akan dibui 10 hari, karena dianggap tak meneladani Nabi. Sejumlah wartawan yang ”beruntung” masuk ke Kabul melaporkan bahwa warga Ibu Kota paling susah menyesuaikan diri dengan gagasan ”100 persen masyarakat Islam” ala Taliban. Dulu, Kabul adalah kosmopolitan yang penuh daya pikat (lihat Kabul Dalam Kenangan). Semuanya kemudian berubah secara radikal. Taliban merampas koleksi musik dan televisi di rumah penduduk—yang mereka cap sebagai kotak setan. Rentangan pita kaset dililitkan dari tiang listrik ke pepohonan atau jembatan.
Serdadu Taliban akan mengecek lagu yang disetel di setiap mobil. Musik pop Pashtoon tidak boleh. Dansa tradisional Afganistan dilenyapkan. Festival tradisional dilarang. Dan segala olahraga adalah haram. Jadi, jangan bermimpi melihat permainan polo atau hoki berkuda yang begitu digandrungi warga Afganistan zaman sebelum invasi Uni Soviet pada 1979.
Taliban juga mengatur soal perempuan dengan keras (lihat Perempuan Afganistan: Dari Bencana ke Bencana). Anak-anak Hawa tak boleh bersekolah sejak umur 8 tahun. Mereka dilarang memakai sepatu yang menimbulkan bunyi. Pupur wajah dan cat kuku, hukumnya haram. Nekat melanggar? Pada 1996, 10 wanita yang ketahuan mewarnai kuku dipenggal jarinya tanpa ampun. Wanita juga tak boleh memakai kaus kaki putih dan merah. ”Karena putih adalah warna bendera kita. Sedangkan warna merah merangsang libido kaum lelaki,” ujar seorang polisi Taliban.
Aturan Taliban mewajibkan perempuan harus bicara dengan nada berbisik. Kok, bisa? Polisi-polisi agama Taliban mengartikan suara keras perempuan sebagai ketidaksenonohan. Pendek kata, hal yang remeh-temeh dengan mudah mengundang ayunan pecut petugas. Washington Post pernah menulis: di jalanan Kabul pernah seorang wanita dihajar bertubi-tubi dengan antena mobil. Ia dianggap bersalah karena pergelangan kakinya terlihat sedikit tatkala ia kerepotan menggendong anaknya.
Taliban menganggap Afganistan sekarang masih berada dalam fase duka cita. Maka, warga diharapkan lebih banyak merenungkan kematian para pejuangnya, mengingat Tuhan, memohon ampun, mendoakan arwah dan keselamatan ketimbang terlena dalam kesukariaan. Taliban sebetulnya masih mengizinkan orang menyanyi. Tapi lagu yang boleh dilantukan hanya rap Taliban, semacam akapela tanpa iringan instrumen. Syairnya berisi doa-doa dan heroisme berani mati bernuansa Pashtoon. Contoh liriknya…, ”Jangan bunuh bunga di masjid, jangan bunuh kata-kata Quran, jangan bunuh Taliban….”
Sebuah hadis Nabi memang menganjurkan umat muslim terus-menerus mengingat kematian dalam kehidupan. Tapi Taliban tampaknya menafsirkan hal ini amat berlebihan. Dan para wartawan asing mencatat larangan Taliban banyak dilanggar dengan diam-diam. Hamayun Ahmed, seorang sopir taksi di Kabul, misalnya, mengaku sering mendengarkan Elvis Presley saat mengemudi.
Lagu rock’n roll itu ia setel dengan volume rendah dan segera ia ganti dengan rap Taliban bila tampak petugas polisi. ”Taliban terlalu religius bagi saya,” katanya. Adapun Mustafa, seorang pemilik studio foto di Hera, tetap diizinkan mencetak foto sebatas paspor. Tapi diam-diam ia berbisnis sebagai juru potret pesta pernikahan. ”Saya memang menyalahi peraturan,” ia mengaku. Sekali waktu, ia ketahuan. Kameranya dihancurkan. Taliban membuinya selama dua hari. ”Tapi saya tidak kapok,” katanya.
Semua wartawan asing ingin mencari jawab apa yang ada dalam benak petinggi Taliban yang menciptakan segala kemustahilan itu. ”Haruskah Tuhan melarang bunyi burung?” tulis seorang komponis, pemerhati musik Afganistan, dengan nada muram. Wartawan The New York Times, Barry Bearak, terus-menerus terusik oleh pertanyaan ini: apa yang sesungguhnya dicari Taliban? Ia berhasil menemui Menteri Agama Taliban Al-Haj Maulavi Qalamuddin.
Menurut Bearak, menteri itu mengaku lelah mendengar segala kritik dunia luar terhadap pelanggaran hak asasi di Afganistan. Untuk pelarangan bersekolah bagi anak perempuan, misalnya, ia memberi alasan. ”Negara dalam kondisi darurat. Kami hanya menunda, tidak melarang perempuan bersekolah,” ujarnya. Ulama ini berpendapat, kebijakan ketat itu justru melindungi perempuan dari pelecehan dan serangan.
Namun, Qalamuddin tak bisa menjelaskan mengapa se-telah lima tahun memerintah, hukum Taliban tak kunjung membawa perbaikan. Bahkan, 50 persen perempuan Afganistan pernah mencoba bunuh diri. Human Right Watch sampai menulis, pemerintah Taliban berwatak milisi. Peristiwa pada Februari tahun ini adalah contoh nyata. Mulah Mohammad Omar menitahkan serdadu Taliban meroket dua patung Buddha berumur lebih dari 1.500 tahun di Bamiyan. Patung Buddha tertinggi di dunia itu—53 meter dan 38 meter—menjadi remah dalam sekejap. Permintaan berbagai museum seni di Eropa dan kolektor Jepang untuk membeli patung itu dengan biaya mahal tak digubris oleh sang Mullah.
Taliban juga tak lupa menghancurkan patung-patung di dalam Museum Kabul. Museum itu mengoleksi lebih dari 60 ribu artifak pra-Islam, mulai dari inskripsi Yunani, barang pecah-belah Alexandria, ukiran-ukiran gading nan elok dari India, guci-guci Cina. Dengan lain kata, rezim itu meng-hilangkan sejarah Afganistan—yang pernah menjadi titik temu antaragama di masa silam. Sebelum Masehi negeri Sahara ini adalah jalan sutra antara Roma dan Cina.
Tragisnya, hukum yang diniatkan untuk menertibkan masyarakat itu justru menghancurkan jiwa anak negerinya. Sebuah penelitian menunjukkan, sejak Taliban berkuasa, tingkat stres meningkat pesat. Hampir 90 persen perempuan Afganistan mengalami depresi. Harapan hidup laki-laki wanita dan pria Afganistan kini mencatat angka terendah di dunia: 44 tahun.
Kebijakan Taliban sejatinya menimbulkan ekses memalukan dan sekarang mereka tutup-tutupi. Pelarangan wanita bekerja, misalnya, menyebabkan kaum wanita dan janda yang ditinggal perang menjadi kharabati atau pelacur. Seks itu mereka tawarkan kepada pemilik toko dan para pedagang Pakistan serta Iran. Pilihan lain adalah menjadi pengemis.
Dalam laporannya, Revolutionary Association of the Women of Afghanistan (RAWA), sebuah lembaga swadaya masyarakat perempuan Afganistan yang bergerak bawah tanah di Kabul, menuliskan hasil investigasi yang mengejutkan. Aparat Taliban ternyata tak sebersih klaim mereka. Dengarlah cerita Mariam, seorang janda di Herat yang terpaksa melacur. ”Tentara Taliban paling sering menjadi langganan saya. Tingkah laku mereka amat kasar terutama yang muda-muda. Mereka mau memberikan uang untuk jasa saya dengan syarat boleh merenggut kegadisan putri saya yang baru akil balig.”
Sistem Islam antigender yang dilansir Taliban memang telah menuai tuba. Contohnya jelas: janda-janda harus memilih melacur atau menyaksikan anak-anaknya kelaparan. Human Right Watch mencatat 85 ribu anak balita Afganistan meninggal setiap tahun karena diare. Sementara itu, lembaga Medicine Sans Frontier melaporkan 250 ribu anak mati akibat malnutrisi. Hampir 90 persen anak-anak Afganistan percaya bahwa mereka akan mati muda. Sebagian malah berharap agar mereka mati muda dan tak usah tumbuh dewasa.
Di bawah Taliban, Afganistan seperti menapaki labirin kepahitan, yang mengingatkan kita pada baris-baris puisi seorang penyair Arab: …”Di gurun-gurun pengasingan, hanya debu yang bersiut di wajah kami, maka mau apa lagi kami dengan cinta kami?....” Perselisihan rezim demi rezim, dari zaman Babrak Karmal sampai Taliban, membuat masyarakat Afganistan terus-menerus dipaksa lebih mencintai kematian daripada kehidupan.
Dan roket-roket Amerika yang berjatuhan di Afganistan pada hari-hari ini kian jelas mengabarkan kematian itu.
Seno Joko Suyono (The WP, The New Yorker, Guardian, NYR)
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini