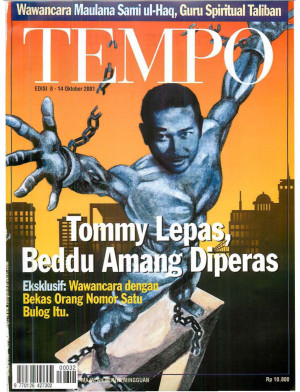MARET, hari ke-24, tahun 1997. Pasukan Taliban merebut Mazar-e-Sharif, kota di wilayah utara Afganistan. Sebelum mereka terusir oleh serangan balik Aliansi Utara, ke seluruh kota itu, dengan pengeras suara, diperintahkan kepada kaum perempuan agar tinggal di rumah. Perempuan boleh keluar rumah bila ber-sama muhrimnya, dan harus mengenakan burqa, jubah khas Afganistan yang menutup seluruh tubuh dari kepala sampai mata kaki kecuali secleret celah lubang untuk mata. Kaum perempuan dilarang bekerja, remaja wanita dilarang bersekolah. Melanggar perintah dan larangan ini berat hukumannya: teringan, dicambuk beberapa kali sampai seratus pukulan; terberat, hukuman rajam dan mati.
Pada mulanya itu terasa sebagai pembebasan. Sebab, sebelumnya, di negeri yang dilanda perang saudara sekitar 20 tahun itu, kelompok suku pemenang perang, suku mana pun, memperlakukan kaum perempuan lawan sebagai barang rampasan. Sang pemenang boleh melakukan apa pun terhadap mereka—nasib terbaik barangkali dijadikan istri kesekian, terburuk dijual ke pelacuran. Talibanlah yang membubarkan kompleks pelacuran, membebaskan perempuan-perempuan, lalu mengundangkan bahwa perempuan bukan barang rampasan perang, bukan untuk diperkosa dan disiksa.
Tapi pemandangan ini membuat pembebasan itu hanya ilusi.
Kabul, Jumat 28 Februari 1998. Sekitar 20 ribu orang memenuhi kursi stadion olahraga Kabul. Semua mata, lelaki-perempuan dan anak-anak, mengarah ke tengah lapangan saat seorang perempuan yang mengenakan burqa menggiring seorang perempuan remaja, Sohaila, ke tengah lapangan. Sohaila duduk di rumput, satu meter di belakangnya berdiri seorang laki-laki dengan cambuk di tangan. Kemudian, hukuman pun dijalankan: dera 100 kali untuk Sohaila. Entahlah kesakitan Sohalia sampai di mana—suara keras dari pengeras suara menenggelamkan kesakitannya.
Sohaila dilaporkan dan terbukti melakukan zina. Dan bukan hanya Sohaila. Seorang Nadia dicambuk di depan publik di stadion itu pada Mei silam, juga karena berzina. Di seluruh wilayah kekuasaan Taliban, pelaksanaan hukuman seperti itu bukannya jarang. Para aparat hukum Taliban mengintai di segala sudut. Dan bukan cuma pelaku utama. Bahkan orang tua yang tak melaporkan ke polisi agama bila anaknya me-lakukan hubungan seksual di luar nikah akan kebagian hukuman cambuk. Kesalahan orang tua itu: berperilaku tak bermoral.
Hukum zina lebih berat bagi perempuan yang sudah menikah, yakni dilempari dengan batu hingga mati, dan semuanya berlangsung di depan publik. ”Hasil penerapan hukuman semacam ini telah menekan tingkat kriminalitas,” tutur Abdul Manan Niyazi, Gubernur Kabul.
Sejak rezim Taliban berkuasa, 1996, hukum Islam diterapkan dengan sangat ketat. Mullah Muhammad Umar, pemimpin spiritual Taliban, membuat larangan buat perempuan: dari larangan menggunakan cat kuku sampai meng-”haram”-kan perempuan belajar dan bekerja. Tujuan larangan itu, selain untuk melindungi perempuan menjadi rampasan perang (seperti sudah disebutkan), juga untuk menjaga mereka dari keganasan para bandit yang merampok dan memerkosa perempuan.
Namun, ibarat terbebas dari mulut harimau jatuh ke cakar singa, kaum perempuan Afganistan tetap menjadi korban: kehilangan hak-hak asasi manusia yang mendasar, termasuk hak untuk mengembangkan diri, menyatakan pendapat, hak berorganisasi. Lalu, kehilangan hak terbebas dari rasa takut: bayang-bayang hukuman mengikut ke mana pun perempuan berada.
Lebih dari itu, larangan perempuan bekerja samalah maknanya dengan melaparkan mereka dan keluarganya. Ratusan ribu lelaki tewas, meninggalkan istri serta anak-anak yang tak bisa bekerja. Menurut catatan Amnesty International, tak sedikit anak-anak yang kelaparan dan meninggal di pangkuan ibu mereka yang bukannya tak mau bekerja, melainkan tak berani melanggar aturan Taliban.
Anehnya, mengemis tak termasuk dilarang. Menurut para wartawan yang melaporkan keadaan negeri, jangan kaget bila di antara pengemis-pengemis anak dan remaja yang memenuhi sudut-sudut Kabul, ibu kota Afganistan, adalah seorang dosen perempuan, janda, yang tak mungkin mencari nafkah selain mengajar. ”Perempuan pengemis di Kabul berbicara dengan saya dalam bahasa Inggris,” ujar Tariq Jamal Khattak, jurnalis Pakistan dari The Frontier Post, harian yang terbit di Peshawar, kota perbatasan Pakistan-Afganistan. Wartawan itu menelusuri Kabul selama lima hari pada 1999.
Tak mudah memperoleh angka pengangguran di negara yang dimiskinkan oleh perang saudara selama 20 tahun itu. Bahkan jumlah penduduk Afganistan kini hanya bisa diduga-duga, konon antara 15 juta dan 22 juta. Sebuah situs yang khusus meng-online-kan Afganistan memperkirakan bahwa dalam lima tahun pemerintahan Taliban, akibat perempuan dilarang bekerja, pengangguran meningkat hingga 70 persen.
Perang, di mana pun, adalah bencana. Banyak keluarga di Afganistan tak lagi punya rumah karena hancur akibat bom. Mereka menjadi penghuni liar di sekolah perempuan yang ditutup. Di sebuah bekas SMA khusus perempuan di Kabul, hidup 30 janda dan anak-anaknya. Mereka umumnya hidup dengan mengemis. Kadang kala mereka mendapat pekerjaan mencuci pakaian, dan itulah jasa yang menghasilkan upah paling besar, sekitar 20 ribu afghani. Tapi upah sebesar itu, yang diperoleh setelah mencuci banyak pakaian dari pagi hingga petang, tak lebih hanya senilai 20 sen dolar (Rp 500), yang hanya bisa dibelanjakan untuk roti tawar. Pekerjaan inilah yang kini dijalani seorang perempuan bekas dosen Universitas Kabul. ”Fundamentalis (Taliban) membunuh suami saya. Rumah kami hancur karena bom, dan saya punya tiga anak kecil,” tuturnya kepada wartawan Pakistan itu. ”Kalau tak mengingat anak, saya sudah bunuh diri.”
Laporan PBB menyebutkan kasus bunuh diri di Afganistan meningkat, dan sebagian besar pelakunya adalah perempuan. Cara bunuh diri itu sungguh menyakitkan: menenggak soda api, atau melompat dari jendela bangunan bertingkat. Yang tak sempat bunuh diri, yang dilindas tekanan hidup menjadi penghuni rumah sakit jiwa. Di Kabul, rumah sakit jiwa kewalahan menerima pasien—di akhir tahun 1990-an, rata-rata 35 orang, lebih dari dua kali lipat dari sebelumnya, masuk ke rumah sakit ini. Mereka umumnya menderita depresi berat.
Zina merupakan larangan berat. Karena itu, pelacuran sangat diharamkan. Pelacur yang tertangkap dipastikan bakal menjalani hukuman gantung. Februari lalu, di Kandahar, dua pelacur dihukum gantung di hadapan 1.000 orang.
Tapi menjadi pelacur merupakan pilihan lain daripada menjadi pengemis. Ancaman tiang gantungan tak menyebabkan mereka yang terimpit itu, yang tak ingin anak-anaknya mati kelaparan, menjauhi pekerjaan ini. Diva, 28 tahun, misalnya, terus terang mengaku kepada wartawan Pakistan itu bahwa ia pelacur. Hidup sarjana geofisika yang pernah bekerja sebagai pegawai negeri ini berubah drastis ketika sekelompok pria bersenjata memerkosanya pada 1995, dan ketika ia tak bisa kembali bekerja sewaktu Taliban berkuasa pada 1996. Padahal ia harus menanggung hidup ibunya, yang sudah renta, dan tiga saudara perempuannya.
Nasib Aqazat, 35 tahun, lebih buruk lagi. Suami Aqazat adalah tentara Afganistan yang tewas dalam pertempuran di Jalalabad pada 1989, meninggalkan tujuh anak. Perempuan suku Tajik ini pernah memiliki kedai bahan makanan. Tapi ketika Taliban berkuasa, semua kedai yang dikelola perempuan ditutup. Alhirnya Aqazat menawarkan tubuhnya di sekitar pertokoan Kabul.
”Ratusan pelacur berkeliaran di Kabul setiap hari, dan jumlahnya semakin bertambah,” ujar Zarghuna Hashemi, aktivis perempuan Revolutionary Association of Woman of Afghanistan (RAWA). Tentu mereka kucing-kucingan dengan polisi agama Taliban. Penampilan mereka yang terpaksa menjual tubuhnya itu bak pengemis—hal yang menyelamatkan mereka dari polisi. Keketatan Taliban menjalankan hukum Islam menjadi semacam berkah pula bagi para pelacur. Menurut hukum Islam, menuntut seseorang melakukan zina harus didukung empat saksi yang yakin tahu bahwa perbuatan itu terjadi. Rupanya mencari empat saksi yang bersedia angkat sumpah bahwa ia mengetahui perbuatan itu tak mudah.
Konon, ini hanya awal dari cara Taliban melindungi perempuan. Sedang dicari jalan keluar, katanya, bagaimana memberi kesempatan kepada perempuan untuk belajar dan bekerja tanpa menyalahi hukum Islam. Tapi pencarian itu, kalau benar ada, sudah berjalan setidaknya lima tahun. Dan menurut laporan para wartawan, yang terjadi bukan pengenduran aturan, melainkan sebaliknya. Bisa dimengerti, sebelum Amerika mengancam akan membombardir Afganistan (yang kemudian benar-benar dilakukan), sudah ribuah pengungsi mengalir ke Pakistan, Iran, dan negara lain. Di Pakistan, seorang doktor perempuan Afganistan bernama Zieba Shorish-Sahmley menulis puisi:
Aku masih ingat kalian ../ yang tanpa pilihan, tanpa suara, tanpa hak, tanpa kehadiran/ tak lagi punya tawa, kemerdekaan, perlawanan/ hanya kepedihan, kerinduan, kebisuan, kesepian....
Raihul Fadjri (AP, DAWN, Institute for Afghan Studies, RAWA)
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini