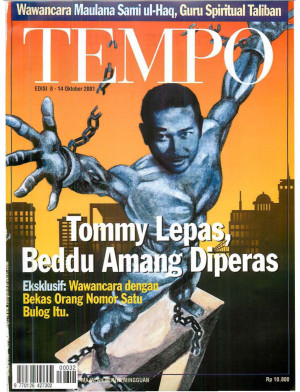Kematian di mana-mana, juga kehancuran, putus asa
Tapi kami masih peduli
Kami singkirkan jauh
tanah air, orang-orang, sejarah, kami simpan di dada
Penderitaan, kepedihan, mengalir
Tinggal harap, masih adakah esok?
(Afganistan, puisi Maria Momand)
PENDERITAAN dan kepedihan terus mengalir di Afganistan. Dari tahun ke tahun, dari perang ke perang. Penyair Maria Momand mencatat sejarah itu dalam puisi, dan berharap esok masih ada. Negeri sejumlah suku ini seperti tak pernah akur, bahkan ketika Amerika menggempur Kabul dua pekan lalu. Musuh dari luar ini tak membuat mereka bersatu. Pemeo klasik rupanya tak menembus Afganistan: musuh dari musuhku adalah kawanku tak berlaku.
Perang antarsuku di Afganistan bisa dirunut ketika bangsa Mongol menduduki wilayah ini pada abad ke-13. Kebengisan Mongol yang terkenal adalah memorak-porandakan irigasi. Tanah pun jadi kerontang, pertanian merana hingga kini, pada awal abad ke-21—hanya 12 persen tanah di Afganistan yang bisa ditanami. Selain pertanian, peternakan pun sering ke-sulitan air. Syahdan, penjarahan antarsuku jadi hal biasa. Kelompok yang kalah kuat dipastikan tumpas atau mati kelaparan. Bibit kebencian ratusan tahun inilah yang rupanya tumbuh subur di pegunungan berbatu di tanah nan tandus itu.
Sempat, Afganistan bersatu, di bawah kepemimpinan Ahmad Shah Badali yang karismatik. Pendiri Kerajaan Afganistan pada 1747 ini bisa menyatukan pasukan dari berbagai suku. Dengan kekuatan itu mereka menggempur tetangga: Punjab dan Kashmir yang subur. Rampasan perang rupanya mendatangkan kemakmuran, dan karena itu Shah Badali yang dipanggil Shah Baba oleh pengikutnya ini tak harus menghadapi perlawanan dari dalam. Pada zaman inilah kaum Pasthun berkembang, mendominasi Afganistan. Celakanya, setelah Shah Badali meninggal, bibit permusuhan itu kembali mengoyak persatuan, dan perang antarsuku pun berkobar.
Ketika Inggris cemas menghadapi perlawanan bersenjata di tanah jajahannya, India, ketika itulah Rusia tengah melebarkan sayapnya hingga ke Asia Tengah. Mengantisipasi Rusia membantu perlawanan di India, Inggris menengok ke Afganistan yang memiliki nilai strategis di kawasan ini.
Tapi tentara dan senjata tak bisa menaklukkan Afganistan, yang sudah terbiasa berperang saudara. Inggris, dalam perang Anglo-Afgan I (1839-1842), gagal total. Siasat lain pun ditempuh: Inggris menggerojoki penguasa Afganistan, Dost Mohammad, dengan bantuan militer dan keuangan. Imbalannya, Afganistan diminta bersikap netral terhadap aksi Inggris dalam menangani perlawanan di India. Dost dengan lihai memanfaatkan bantuan ini untuk memperkuat posisinya. Caranya, ia membiayai satu suku berperang dengan suku lain. Dengan begini, tak ada perlawanan berarti karena suku-suku itu sibuk berperang.
Baru dalam perang kedua, 1878-1880, Inggris menang. Amir Abdul Rehman Khan, penguasa Afganistan kala itu, harus puas dengan kewenangannya: mengurus dalam negeri. Urusan luar negeri jadi hak Inggris. Namun, sebagaimana Dost, Rehman pun mendapat bantuan militer dan keuangan dari Inggris.
Perebutan kekuasan pun silih berganti di Afganistan, sampai akhirnya Zahir Shah (yang kini hidup di Eropa dan konon didukung Amerika untuk kembali berkuasa) menggantikan Nadir pada 1933. Negara ini luput dari Perang Dunia II gara-gara Uni Soviet bersekutu dengan Inggris.
Namun, Perang Dingin membuat Uni Soviet memandang perlu menarik Afganistan berada di bawah panji Beruang Merah. Alhasil, pada 1973, Zahir Shah ditumbangkan oleh pamannya sendiri, Mohamad Daud Khan, yang didukung Soviet. Daud mengangkat dirinya sebagai presiden, sedangkan Zahir terpaksa lari ke Roma, Italia. Sekali lagi, Afganistan yang tandus itu mendapatkan bantuan keuangan dari luar untuk menyelenggarakan kehidupan bernegara.
Negeri yang lebih sering dalam keadaan perang daripada damai itu, di bawah panji-panji Soviet pun, tak bisa tenang. Perlawanan bersenjata melawan rezim boneka bentukan Soviet mulai mengkristal pada 1980. Perlawananan ini memang bukannya bersih dari campur tangan negara luar—maklum, zaman Perang Dingin. Pada periode 1980-1986, Amerika dan sekutunya memberikan bantuan senjata senilai US$ 5 miliar (Rp 50 triliun untuk kurs saat ini) kepada oposisi terhadap Daud Khan. Soviet tentu saja tak mau kalah: Kremlin menggerojok senjata senilai US$ 5,7 miliar (Rp 57 triliun) pada periode yang sama. Ribuan senjata inilah yang kini tersebar jadi milik kelompok-kelompok bersenjata di Afganistan.
Ketika Soviet tercerai-berai pada 1990, bantuan kepada negara-negara satelitnya pun berhenti. Ketika itu penguasa Kabul adalah rezim boneka Najibullah. Tanpa bantuan Soviet, Najibullah sulit bertahan lama. Dua tahun kemudian, 1992, Najib tumbang dan harus mati di tiang gantungan.
Afganistan terus bergolak. Para pejuang yang disebut sebagai mujahidin, yang melawan boneka Soviet, saling bertempur merebut kekuasaan. Sebenarnya, ketika mereka masih sama-sama melawan Najibulah pun, suku-suku itu tak pernah rukun benar. Pertempuran antarkelompok sering terjadi.
Kesepakatan mujahidin yang mengangkat Burhanuddin Rabbani dari etnis minoritas Tajik menjadi presiden hampir bisa dikatakan tak membawa perubahan: pertikaian antarsuku terus berlangsung. Rabbani berada di bawah bayang-bayang Menteri Pertahanan Ahmad Shah Mas’ud (yang bulan lalu tewas oleh serangan bom bunuh diri). Dan Mas’ud punya musuh, bekas kawan lama ketika masih bergerilya melawan kaki tangan Soviet: Gulbuddin Hekmatyar, yang adalah perdana menteri. Masih ada kelompok lain, Jenderal Dostum, yang pernah bergabung dalam rezim Najibullah. Pertempuran segi tiga ini bertujuan satu: menguasai Kabul.
Perang segi tiga itu membuat Afganistan seperti negara tanpa hukum. Semua pihak bisa berbuat semaunya. Yang menderita, rakyat sipil. Paling menderita, kaum perempuan (lihat Perempuan Afganistan: dari Bencana ke Bencana).
Rupanya, dari ketiga peserta perang itu, keluarlah pemenang. Unsur lain yang tak terduga ketika itu berhasil mencuri start. Ketika kekuatan militer ketiga kelompok itu melemah, muncul gerakan orang-orang muda, mahasiswa Afganistan yang sebagian belajar di Pakistan, membentuk Taliban. Segera, rakyat menyambut dan mendukung mereka, berharap perang berhenti, dan kehidupan normal berjalan.
Pada 1996, Taliban menguasai Kabul. Kelompok lain terusir ke Afganistan Utara, membentuk Aliansi Utara. Persekutuan itu terdiri dari faksi Rabbani, faksi Mas’ud (kini digantikan Jenderal Mohammad Qassem Fahim), dan—uniknya—Jenderal Dostum yang semula berseberangan. Sedangkan Hekmatyar lari ke Iran.
Lima tahun sudah Taliban berkuasa, meski tak sepenuh negeri. Pun dunia internasional belum mengkauinya. Hanya Uni Emirat Arab, Arab Saudi, dan Pakistan punya hubungan diplomatik dengan pemerintahan Taliban. Dengan dukungan ekonomi dari tiga negara itulah pemerintah Taliban mampu bertahan dari rongrongan Aliansi Utara.
Kini, setelah terjadi tragedi 11 September di Amerika, dan negara superkuat itu menuduh Taliban melindungi yang disangka mendalangi tragedi, Usamah bin Ladin, tinggal Pakistan yang punya hubungan diplomatik dengan Afganistan. Bisakah Taliban bertahan, di negara yang oleh Barnett R. Rubin dalam bukunya, The Fragmentation of Afghanistan: State Formation and Collapse in the International System, dijuluki ”The Rentier State” itu? Negara yang mengandalkan bantuan luar untuk bertahan sebagai negara karena tak punya sumber alam untuk menghidupi dirinya sendiri? Yang 85 persen warganya, kaum nomaden dan petani, sepeser pun tak membayar pajak? Dan kini, Taliban harus menghadapi gempuran Amerika yang tentulah mendukung Aliansi Utara.
Senjakala bagi Taliban tampaknya sudah dekat. Berbeda dengan saat di Irak, Amerika tak punya kawan yang bisa dibantu untuk menjatuhkan Saddam Hussein. Di Afganistan, ada Aliansi Utara yang punya peluang untuk mencuri kesempatan. Bekas raja Zahir Shah yang melarikan diri juga berkampanye untuk kembali ke negaranya. Ia sudah menyatakan tak keberatan bergabung dengan Aliansi Utara.
Tapi, menilik sejarah Afganistan yang sering tak terduga, sementara mudah menduga nasib Taliban, sulit menebak penguasa selanjutnya. Aliansi Utara bisa saja menang berkat dukungan Amerika dan Inggris. Namun, tak ada jaminan aliansi ini masih bisa terus bersatu begitu menguasai Kabul. Negara-negara sekitar negeri yang tak punya laut ini (Iran, India, Pakistan, Cina, Asia Tengah) bisa bersaing berebut pengaruh. Dan pertikaian antarsuku di Afganistan, sepertinya—melihat sejarah—mudah disulut menjadi perang antarsuku.
Dosa apa gerangan yang dipikul rakyat Afganistan? Mungkin epik Mahabharata adalah jawabannya? Sekitar tiga ribu tahun lalu, menurut epik besar itu, Afganistan ketika itu di-sebut Gandhara. Inilah kerajaan Sangkuni, mahapatih Astina yang dikenal dengki dan penyulut Bharatayuda, perang saudara keturunan Bharata. Tapi kenapa rakyat Afganistan kini yang harus menderita dosa sang penguasa ribuan tahun lalu? Pertanyaan yang juga harus dijawab Amerika: bisakah dihindarkan korban sipil, ketika bom dan rudal tak bisa membedakan siapa pengikut Taliban, pendukung Usamah, dan rakyat sipil yang ingin hidup damai. Yang pasti, puisi Maria Momand masih akan terus mengiang: Penderitaan, kepedihan, mengalir...
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini