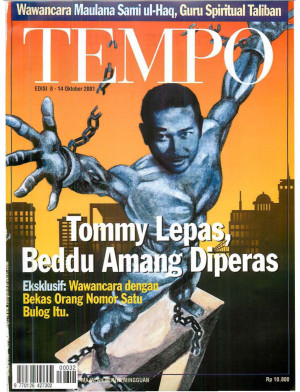SEBIDANG lantai berantakan, sebuah tenda di dalam ruangan, dan foto pegunungan di tembok. Di sudut lain, semacam maket rumah tingkat di-pajang di dekat seonggok besar keping-keping mainan yang dirangkai. Di samping instalasi keping mainan itu, semacam terap kayu, barangkali disusun dari kayu-kayu bekas kotak barang, terbujur. Di atasnya ditaruh berbagai "aksesori": beragam sobekan kain, lalu lembaran kardus bertulis kata-kata. Di seberang lantai berantakan, ada lima kubus kaca terbuka di atasnya, masing-masing ditaruh di kotak, sama tinggi, masing-masing disinari langsung lampu gantung. Di dalam kubus terlihat air kehijau-hijauan. Lalu sebuah meja biliar sebenar-benarnya meja biliar.
Itulah antara lain karya dalam pameran "Quobo, Seni Rupa di Berlin 1989-1999", yang berakhir Minggu, 14 Oktober. Karya-karya itu dipamerkan di ruang baru Museum Nasional, Jakarta, ruang yang belum se-penuhnya selesai dibangun. Entah disengaja atau tidak, terasa ruang yang belum selesai itu justru pas dengan karya-karya yang dipamerkan. Sebidang lantai berantakan itu, umpamanya, yang langsung menyambut penonton di pintu masuk, serasa bagian dari proses penyelesaian akhir gedung itu.
Awalnya, lebih-kurang, adalah gagasan dua kurator Jerman, Gabriele Knapstein dan Ingrid Buschmann: bagaimana sebenarnya pengaruh berdiri dan runtuhnya Tembok Berlin, dan melahirkan karya seperti apa bila para perupa meresponsnya.
Hasilnya adalah karya-karya yang ber-dialog dalam bahasa ruang, waktu, suara, dan cahaya. Tiga belas perupa itu, selain satu orang yang lahir pada 1952, semuanya kelahiran tahun 1960-an, tahun-tahun awal berdirinya sang Tembok. Ada yang lahir di wilayah Jerman Barat, beberapa di Jerman Timur. Tapi karya-karya itu tak mencerminkan dua Jerman. Bahkan, Tembok Berlin secara fisik tak hadir di ruang pameran; pun sesuatu yang langsung berasosiasi pada tembok tak ada.
Lihat saja karya Monica Bonvicini, lantai berantakan berjudul Plastered itu. Penonton, mau tak mau, harus menginjak karya ini, ikut andil makin memberantakkan "lantai" itu. Ketika seorang pengunjung keluar dari ruang pameran, ia akan menyadari bahwa kakinya telah mengubah karya itu—tak ada jalan masuk yang lain, hingga mau tak mau penonton harus menginjak karya ini. Sebuah karya terus berproses, dan hasil akhirnya entah akan seperti apa—nun di ujung sana terbayang: lantai ini bakal makin berantakan, hancur, untuk akhirnya musnah.
Albrecht Schäfer, perupa yang menyusun keping mainan itu, menciptakan karya instalasi penuh imaji. Dalam bangunan terdiri atas beratus keping putih itu, berongga-rongga, penonton bisa masuk berjalan di "lorong"-nya, terkandung banyak hal: dunia anak-anak, antara keseriusan dan main-main; suasana keterasingan; keterpisahan. Seperti Tembok Berlin, karya itu menyadarkan kita, ada batas yang membuat kita hanya bisa memandang dari celah-celah, tanpa bisa menyentuh. Berapa keluarga dipisahkan oleh tembok itu sejak didirikan pada 1961?
Lalu karya Carsten Nicolai, empat piringan hitam yang mendesah bercampur bunyi seperti kawah belerang meletup-letup. Ada sesuatu, entah di mana, di luar diri kita seperti menyapa, atau sekadar bersuara tidak untuk apa-apa. Dan suara itu tak mendikte: penonton bebas mengubah-ubah suara itu. Kemudian sebuah layar, putih, besar, di depan proyektor otofokus yang menyemprotkan gambar, bentuk-bentuk lingkaran bersinggungan. Gambar itu tak diam, kamera otofokus berputar: sebuah siklus, dari kabur ke jelas, dan sebaliknya. Tak ada yang tetap, semuanya berubah—hanya perubahan itu sendiri, rupanya, yang tetap. Inilah karya Fritz Balthaus.
Perlu kesabaran untuk menyaksikan karya Annette Bergerow, foto sebuah salon pada abad ke-19. Foto itu didigitalisasi, dan proses itulah yang diproyeksikan ke layar lebar. Lagi, karya ini menyuguhkan proses, bidang-bidang yang bergerak, membesar, mengecil, kemudian terpecah-pecah, sampai terbentuk foto salon itu.
Dua perupa, Nina Fischer dan Maroan el-Sani, memproyeksikan 21 potret wajah, masing-masing selama 10 detik, wajah-wajah yang bergeming, satu-dua ada yang mencoba tersenyum. Siapa mereka? Sahabat? Musuh? Tetangga? Atau famili kita?
Dan lihatlah karya Ulrike Grossarth. Ada meja, seonggok kabel konon sepanjang 500 meter, cermin, lampu-lampu. Di dinding, empat kaca hitam bulat, gambar tangan dan batu timbangan. Seperti barang bekas yang dicoba diatur. Barang bekas yang masih berfungsi: lampu itu menyala, terang. Ada cahaya, ada bentuk yang keras, ada yang lunak. Ada sesuatu yang penting, dan berakhir di tembok hanya berupa benda-benda sederhana yang menyimpan cerita. Pencerahan Kedua judul karya ini.
Pameran ini sesungguhnya menciptakan ruang, baik nyata maupun niskala. Liburan Seseorang, berupa kemah dengan aneka macam barang: boneka, meja kecil, bantal, dan di dua sisi diproyeksikan gambar-gambar slide mengesankan album keluarga—oma dan opa makan di meja, berfoto ber-sama di depan rumah, kala bercinta, dan seterusnya. Di dinding, gambar pegunungan.
Tiba-tiba, terasa bahwa hidup itu sendiri adalah sebuah karya seni rupa.
Bambang Bujono
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini