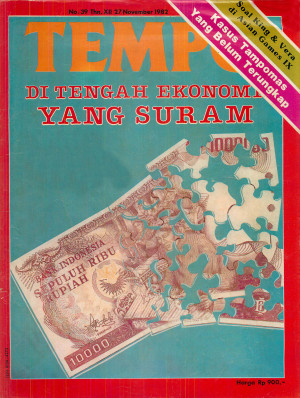TIGA ekor macan tutul mengendap-endap di atap rumah berjerami,
menggeram kepada saya. Enam yang lain mengepung saya di tanah.
Salah seekor mengaum, mengaiskan cakarnya pada kamera saya. Saya
jatuh ke belakang, tersandar di gubuk. Hati jadi kecut karena
teringat, bahwa sebelum datang ke sini saya sudah diberi banyak
peringatan: 'upacara macan tutul' itu penuh bahaya,
kadang-kadang fatal. Secara refleks saya lindungi muka dengan
tangan.
Bunyi cambuk menggeletar. Dan tiba-tiba saja beberapa orang
lain datang menyelamatkan saya. Mereka mengusir macan tutul ke
tanah berpagar rindang.Mereka berteriak: "Tak ada orang awam
boleh masuk sini!"
Cerita di atas, dimuat dalam National Geographic Magazine Juli
yang lalu, datang dari wartawan Michael Kirtley. Bersama
istrinya, Aubine, ia tinggal selama empat bulan di Pantai
Gading. Dan menghadiri 'upacara macan tutul' yang diadakan Suku
We.
"Beberapa saat kemudian," katanya, "manusia macan tutul itu
mengantari saya makanan. Mereka sudah ramah kini, tak lagi
mengenakan pakaian upacara yang penuh tutul. Tapi saya masih
gemetar. Saya tahu, masing-masing mereka harus tinggal tujuh
bulan di rimba belantara dalam usaha menghayati kehidupan
binatang buas. Untuk memuja macan tutul dan tinggal bersamanya.
Selagi saya mengajukan pertanyaan, seorang lelaki tiba-iba
terkapar di tanah. Menggeliat-geliat dan melolong iba seperti
binatang terluka. Sambil menggelepar dan merobek-robek bajunya,
ia melompat dalam keadaan telanjang. Yang tampak hanya putih
matanya. Bertelekan pada kedua tangan dan kakinya, ia merangkak
lari seperti seekor binatang masuk rimba. Saya terpana. "Anda
telah mengucapkan perkataan tabu," seseorang berteriak kepada
saya. Tapi ia tak memberi penjelasan lebih lanjut. Dan saya pun
tak pernah tahu apa perkataan itu."
Manusia-macan tutul itu tinggal di dataran tinggi sebelah barat
Pantai Gading Sebelum tiba di negeri kecil yang makmur di Afrika
Barat itu, Kirtley dan istrinya sudah diberi gambaran akan
menemukan suatu negara jajahan baru (neo koloni) yang korup,
yang merdeka tahun 1960 dari Prancis Di situ orang kulit putih
masih cukup besar kekuasaannya di belakang layar, 'tradisi'
cepat sekali jadi 'kesenian rakyat'. Mereka terkejut mendapatkan
ibukota Abidjan yang ultramodern itu hanya merupakan tiruan tak
sempurna dari Kota Paris.
DI seluruh negeri, kelompok-kelompok rahasia dan upacara ritual
seperti 'manusia-macan tutul' itu merupakan sesuatu yang lazim.
Kedua suami-istri itu mengunjungi para ahli sihir dan istana
kepala suku yang ternyata berlapis emas. Mereka ikut bernyanyi
dengan orang-orang Kristen fundamentalis dan menari bersama
dewa-dewa bertopeng. Terbengong-bengong mereka melihat seseorang
dalam suatu upacara ritual menikam perutnya sendiri, menarik .
keluar sebagian ususnya, lalu memasukkannya kembali. Luka di
perut disembuhkannya dengan menggosok dengan telur, jamu dan
kaolin.
"Siapa pun yang mencemoohkan atau tak percaya sihir di negeri
kami," kata Ambroise Agnero dari Perpustakaan Nasional yang
berpendidikan Prancis, "tak memahami apa-apa. Upacara-upacara
seperti itu merupakan landasan kehidupan kami sehari-hari."
Jiwa Pantai Gading memanglah kehidupan yang serba gaib dan hanya
dipahami orang-orang tertentu. Tapi jika seorang warga Pantai
Gading ditanya, apa yang diinginkannya dari hidup, jawabannya
bisa membuat geleng kepala. Yang dibayangkan adalah villa dengan
cir conditioning, dengan mobil Mercedes-Benz, televisi berwarna
dan kaset video, ditambah sofa, sampanye tiap kali makan, istri
kulit putih, klub eksklusif dan uang untuk dihambur-hamburkan.
"Kaki kami masih di Zaman Batu, sementara kepala kami sudah
melayang di zaman atom," kata Rene Rabbi, direktur urusan
pariwisata.
Dari namanya saja kita sudah tahu, Pantai Gading pernah punya
banyak gajah. Dan barangkali inilah satu-satunya negara Afrika
baru merdeka yang sampai kini belum pernah mengalami kudeta.
Juga tak pernah ada kerusuhan sosial atau perang antarsuku.
Tingkat hidup warganya paling tinggi di Benua Hitam Afrika. Juga
GNP-nya.
Manajemen yang sehat menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang sehat
pula, tiap tahun, sejak merdeka-dan prestasi ini tak ada taranya
di antara negara mana pun di Dunia Ketiga. Sekitar 2,5 juta
orang, atau lebih dari seperempat jumlah penduduk, datang ke
negara ini untuk bekerja. Dan ini terjadi sebelum ditemukannya
sumber minyak--belum lama ini--atau sumber tambang penting
lainnya, di tengah lebih dari 60 suku yang masingmasing punya
cara hidup sendiri.
Pantai Gading adalah produsen cokelat kelas satu di dunia, dan
produsen kopi dunia terbesar. Di antara bekas jajahan Prancis di
Afrika, ia paling banyak menyediakan lapangan kerja, paling
banyak menerima investasi asing dan paling maju perdagangannya.
TAPI di negara yang sudah tata tentrem kerta raharja seperti
ini toh masih saja ada yang mengeluh. Karena merosotnya harga
kopi dan cokelat di pasaran dunia, pemerintah terpaksa menghemat
anggaran secara drastis Seorang sopir menggerutu: untuk
buku-buku sekolah anaknya, ia harus mengorbankan dua bulan gaji.
Ke mana pun orang pergi di negeri itu, penduduk menyalahkan
nasib buruk mereka pada hantu la conjuncture atau resesi dunia
Hantu tersebut telah mengendurkan semangat, membuat bangkrut
banyak perusahaan. Dan untuk pertama kali penduduk mulai
menyuarakan kesangsiannya terhadap pemerintah.
"Kami memang tak melakukan pilihan yang hebat waktu memerdekakan
diri," kata seorang guru. "Kami meniru begitu saja masyarakat
konsumen model kolonial, dan kini kami jadi korban karena sangat
tergantung pada dunia luar. Kalau dunia menderita, kami pun
menderita."
Politik Pantai Gading memang condong ke Barat. Presiden Felix
Houphouet-Boigny, yang terpilih waktu kemerdekaan dan kini dalam
masa jabatannya yang kelima, sangat benci Soviet. Tahun 1969 ia
memutuskan hubungan diplomatik dengan Moskow. Di kalangan Dunia
Ketiga ia bersuara moderat. Sering disebut sahabat karib
Amerika, tapi kini negeri itu merasa tak banyak dapat imbalan
dari sikapnya itu. Dan resah akan masa depannya.
Rene Amany, Direktur Dana Stabilisasi Nasional, mengeluh.
Keuntungan perdagangan kopi yang lima tahun lalu mencapai satu
milyar dollar itu pada 1981 merosot hanya 100 juta dollar,
setelah terjadi kemerosotan 70% harga pasaran kopi.
"Amerika Serikat adalah rekan dagang kami terpenting," kata Rene
yang kini diangkat jadi Duta Besar untuk AS. "Celakanya AS
memperlakukan kami seperti perusahaan biasa saja. Bagi Amerika,
kalau kami bangkrut, tentunya salah kami sendiri, salah urus.
Padahal produksi kopi kami dua kali lebih banyak dari yang
diperkenankan persetujuan internasional untuk diekspor. Akhirnya
kami merasa juga, AS melindungi para petani kopi di Amerika
Tengah--yang berdasarkan persetujuan internasional mempunyai
kuota lebih tinggi. Sikap AS ini karena ingin menjaga stabilitas
politik di kawasannya. Apakah saya harus bilang pada jutaan
rakyat kami yang dirugikan, bahwa Paman Sam telah melupakan
sahabatnya di Afrika?"
Bersama istrinya, Kirtley mengunjungi Suku Senoutos yang tinggal
di savanna (padang rumput) sebelah utara-- sekitar Korhogo, kota
kelima terbesar di Pantai Gading. Waktu mcreka datang, musim
kemarau, sedang berlangsung upacara penguburan bagi orang-orang
yang mati selama tahun itu. Salah seorang adalah kepala suku,
yang diperkirakan berusia paling sedikit 114 tahun! Ini
diketahui, karena mendiang konon semasa hidup dapat mengingat
peristiwa-peristiwa yang terjadi di abad ke-19.
Di kalangan Suku Senoufos, hidup seorang lelaki dibagi dalam
tahap-tahap tujuh tahunan. Yang paling penting antara usia 121
tahun, dan paling ideal usia 126 tahun (6 kali 21 ) di saat
"semua ilmu dan kesucian di bumi" diperoleh.
WAKTU mereka datang petir menggelegar membelah angkasa. Dalam
suasana seperti itu Michael takut membuat foto. "Lihat saja
nanti," kata Ousman Coulaby, seorang pemuka setempat yang
mendampingi mereka. "Hujan mungkin akan turun, tapi doa pawang
hujan kami akan membuat upacara penguburan tak terganggu."
Desa itu memang kering. Debu mengambang di udara. Suasana
diributkan oleh bunyi petasan, sehingga membingungkan: upacara
penguburan atau pesta pora? Seorang wanita tua menyambut
kedatangan Kirtley dengan mmukul-mukul kaleng. Beberapa lelaki
memainkan alat musik tradisional di hadapan sekelompok wanita
yang sedang menggoyang-goyangkan tubuh, dengan bayi tertidur di
punggung mereka.
Sepanjang tengah hari petir menggelegar dan awan mendung.
"Ketika kami berlalu," tulis Kirtley, "angin kencang dan hujan
mengguyur kami. Tapi tak setetes pun yang jatuh di desa itu."
Suku Senoufos, seperti suku lainnya di Pantai Gading,
menjalankan hidup yang penuh disiplin dan mistik. Menurut
kepercayaan mereka sejak lahir sampai mati tingkah laku dan
pikiran manusia dikendalikan oleh serangkaian tata sosial dan
falsafah yang disebut Poro. Peraturannya yang keras dan upacara
inisiasinya yang berat hanya bertujuan satu: menciptakan dan
memelihara ketertiban.
Orang-orang tua dipuja sebagai guru. Membangkang tidak
diperbolehkan. "Ketaatan lebih berharga dari kekayaan," demikian
diajarkan. "Kalau perlu, persahabatan harus dihormati dengan
maut." Pendidikan seumur hidup mencakup seluruh pengetahuan
teori dan praktek, mulai dari agama, kosmologi, ilmu sihir,
sejarah, etiket, ilmu hitung dan bertani. Inisiasi (upacara
lelaki menjadi dewasa) mencakup penggunaan bahasa dan
peribadatan rahasia.
Michael yang hendak memotret upacara keagamaan yang menarik ini
hampir terbentur oleh "peraturan". Pendeta yang memimpin upacara
memintanya menghormati dewa-dewa dengan memberikan kurban.
"Apa yang mesti saya perbuat?" ia bertanya.
"Saya mau menerima 15.000 france (lebih kurang Rp 1,5 juta),"
jawab pendeta.
"Kok begitu mahal?"
"Monsieur, dewata kami pun ikut menderita karena 'la
conjuncture'."
Tapi dari lebih 60 swku yang kini mendiami Pantai Gading,
sebenarnya hanya sedikit yang benar-benar pribumi. Termasuk Suku
Senoufos dan Koulangos yang tinggal di utara dan timur sejak
kurang lebih seribu tahun lalu. Sekitar tahun 1600, Suku Manlike
yang suka berperang merembes kesclatan dari daerah yang kini
disebut Mali. Sekitar zaman inilah sekelompok penduduk dari
Kerajaan Askanti Besar pindah ke tenggara. Keturunan mereka,
kini dikenal sebagai Suku Baoule, merupakan suku terbesar di
Pantai Gading yang bertani di daerah padang rumput. Beberapa
suku lain juga mencoba hidup baru di daerah itu, sampai datang
orang kulit putih pertama yang berdagang, mencari gading, minyak
zaitun, dan budak belian.
Cote d'Ivoire (nama Prancis u ntu k Pantai Gading) secara resmi
dinyatakan sebagai jajahan Prancis tahun 1893.Hasil cokelat dan
kopi merangsang pertumbuhan ekonomi. Perkebunan yang dibuka
orang Prancis menghimpun tenaga kerja yang datang dari ratusan
mil jauhnya.
"Awal tahun 1940-an sebenarnya tak seorang pun menginginkan
kemerdekaan," kata Coffi Gadeau, Kanselir Besar Pantai Gading.
Yang diinginkan hanya diakhirinya ketidakadilan-- misalnya
undang-undang yang membolehkan kerja paksa.
Tahun 1944 dicapai kemajuan besar -- ketika Jenderal Charles de
Gaulle memberi hak kepada rakyat Pantai Gading menempatkan
wakilnya dalam Parlemen Prancis. Felix Houphouet terpilih ke
Majelis Nasional itu setelah mengadakan kampanye yang getir.
Selama 15 tahun berikutnya, bakal presiden dan partainya ikut
berusaha melenyapkan ketidakadilan.
Tapi setelah tercapai kemerdekaan, Houphouet tidak berusaha
mendepak bekas penjajah. Ia malah mendorong Prancis menanam
modal di sektor swasta, mendatangkan guru-guru Prancis, dan
minta bantuan teknisi Prancis mengurus negara baru itu. Kini
lebih 50.000 orang Prancis tinggal di sana--tiga kali lebih
hanyak dari sebelum kemerdekaan Houphout menyisihkan 30%
anggaran belanja untuk pendidikan, dalam usaha menggantikan
tenaga Prancis dengan pribumi.
Ke mana pun mereka pergi, tulis Michael, orang Prancis selalu
bisa ditemukan. Yang mengetik surat Michael sendiri sekretaris
Prancis. Yang memotong rambutnya tukangpangkas Prancis. Bahkan
yang bikin duplikat kuncinya orang Prancis juga.
KETIKA Michael hendak mewawancarai Emmanuel Dioullo, Walikota
Abidjan, ia disuruh menemui pembantunya--orang Prancis. Tak aneh
kalau banyak yang merasa, usaha membuka kesempatan bagi pribumi
sebenarnya mengalami jalan buntu. Sydou Coulibaly, seorang guru
pribumi, bahkan berpendapat: di negeri itu kini tumbuh suatu
anggapan, "kulit putih lebih unggul." Ini, pada gilirannya,
menumbuhkan penilaian di kalangan majikan, bahwa orang Pantai
Gading yang berpendidikan kurang disukai dibanding orang Prancis
yang bodoh.
Soalnya pemerintah sendiri memberi teladan begitu. Beberapa
tahun lalu AS menawarkan bantuan pertanian kepada beberapa
negara Afrika Barat, asalkan negara-negara itu mau mengajukan
usulan proyek yang bisa diterima. Presiden Houphouet mengirimkan
satu tim--terdiri dari orang-orang Prancis--untuk menjelaskan
proyek itu. Tentu saja pemerintah AS kaget. Karena Mali, tetang
ganya, mengirimkan tim yang terdiri atas pribuminya sendiri.
Demikian pula Volta Hulu. Tim Pantai Gading ditolak Nah.
Toh secara menyeluruh dapat dikatakan, rasa tidak senang
terhadap Prancis minim saja di negeri ini--meski ada keresahan
karena lapangan kerja diborong mereka semua, di samping mereka
lebih senang hidup menyendiri dan bermewah-mewah.
Seorang pejabat pemerintah di Abidjan mengatakan rakyat Pantai
Gading masih cukup bersyukur akan keadaan mereka yang lebih baik
dibandingkan dengan Ghana atau Guinea yang kacau. Presiden
Houphouet merasa, "boneka" (Pantai Gading) itu tak boleh
dipisahkan terlalu dini dari induknya.
"Kakek Afrika yang Bijak" itu, panggilan kesayangan Houphouet,
dalam usia 76 tahun memang punya kharisma yang melampaui batas
negaranya. Michael dan Aubine, beberapa waktu sebelum ke Pantai
Gading, sempat menonton film berita di bioskop Bamako, Mali.
Penonton tak sabaran mengikuti laporan berita konperensi puncak
Afrika ketika Presiden Mali sendiri berpidato. Tapi ketika
muncul Houphouet di layar, tepuk tangan penonton memekakkan
telinga.
"Ia seperti bapak kami," seorang penonton Mali berkomentar. "Ia
berhasil membuat kehidupan di negaranya berjalan lancar, dan
menunjukkan caranya pada kami. Kami bangga." Itu menurut si
wartawan.
Orang Pantai Gading pun konon ber pendapat sama, meski mereka
agak resah karena Houphouet belum juga menunjuk calon pengganti.
Mereka juga kurang senang, kenapa Presiden lebih suka
berpakaian seperti "orang kulit putih." Michael sendiri bertaruh
dengan seoran kawan: ia akan bisa memotret Presiden Houphouet
dalam pakaian tradisional.
Istana kepala negara itu terletak di kota kelahirannya,
Yamoussoukro, 27 kilometer barat laut Abidjan. Bunga adalah
tumbuhan paling menyolok di istana yang dihias modern itu,
karena Houphouet memang suka bunga. Orang juga menganggap
Houphouet semacam dewa. Meski tak diragukan kekuasaannya atau
sikapnya yang teguh mempertahankan wibawa, ia dikagumi juga
karena kemampuannya berkompromi. Ia bangga akan dirinya, karena
tak pernah menumpahkan darah. "Saya lebih suka mengampuni
musuh-musuh saya. Mengampuni musuh berarti merontokkan giginya
ia tak lagi bisa menggigit anda," demikian ia pernah berkata.
Tapi ketika Michael meminta memotretnya dalam pakaian
tradisional, Houphouet menolak secara halus. "Sebagai presiden,
saya menguasai semua rakyat saya, bukan hanya suku Baoule (suku
asalnya). Saya tak ingin mengbarkdn kedengkian, jika tampil
dalam pakaian tradisi saya," Presiden itu menjawab. Dan Michael
pun kecele.
Masalah mengganggu yang dihadapi presiden itu ialah pelestarian
alam. Dua puluh lima tahun yang lalu, sepertiga negeri itu
diliputi hutan yang padat. Lalu karena meluasnya daerah
pertanian dan pengusahaan kayu, kini hutan tinggal 10%.
Perburuan binatang tanpa izin dalam pada itu banyak sekali
memusnahkan satwa liar. Maka sejak 1975 pemerintah membatasi
perburuan, dan menyisihkan 18.500 kilometer persegi tanah untuk
taman nasional dan suaka alam.
Taman Nasional Tai seluas 3.500 kilometer persegi sudah
dicadangkan Unesco sebagai suaka alam. Ia merupakan satu-satunya
daerah hutan tropis di Afrika Barat, dan salah satu dari
beberapa yang masih tinggal di seluruh dunia. Yang lebih
penting: 10% dari species tanamannya tak bisa ditemukan lagi di
mana pun di dunia. Taman itu merupakan pula suaka bagi kuda nil
jenis kecil, dan beberapa jenis antelop.
Di taman itu pula, sejak 1979, sepasang suami-istri Swiss,
Christophe dan Hedwige Boesch, meneliti tingkah-laku simpanse.
Di situ ditemukan pula bangkai beberapa gajah, paling sedikit
lima ekor, termasuk tiga yang masih bayi. Gajah ini dibunuh para
pemburu gelap yang hendak - mengambil gadingnya. Pencurian kayu
juga merupakan masalah yang memusingkan penjaga kehutanan.
"Setiap kali saya memergoki pencuri kayu dan menyita alat-alat
mereka, tiga hari kemudian saya menerima perintah dari bos saya
untuk membebaskan tahanan saya itu," keluh seorang penjaga
hutan. Maklum: sogokan merupakan penyakit pula dalam
pemerintahan.
Di negeri yang masih muda ini, modernisme dan tardisionalisme
merupakan dua kutub yang saling bertentangan, seperti kata
seorang pengamat budaya setempat. Dan secara perlahan-lahan
Pantai Gading kehilangan landasan budayanya.
Di sebuah desa diselenggarakan pesta Dipri. Ini pesta tahun
baru, dan saat diadakannya perdamaian, dan dipulihkannya
kekuatan gaib. Bagi orang Barat, pesta seperti ini menakutkan-di
samping aneh dan menarik. Serombongan orang berbaris di jalan,
lalu salah seorang keluar dari barisan sambil berteriak
kesakitan. Seorang wanita mulutnya ternganga, matanya
berputar-putar, suaranya seperti mengerang, lalu jatuh ke tanah.
Seorang lelaki lain dengan pisau terhunus berteriak-teriak
kesurupan. "Dan tahu-tahu ia sudah berhadapan dengan saya.
Pisaunya diiming-imingkan ke udara, dan tiba-tiba ditikamkannya
ke perutnya. Darah yang mengucur membuat saya merasa sakit.
Kemudian dengan bangga orang itu mengeluarkan ususnya. Lalu
dimasukkannya kembali ke dalam perut. Lalu memecahkan telur.
Dengan jamu dan kaolin ia menutup lukanya. Dan, ajaib, luka itu
sembuh."
Tengah hari, suasana pesta yang terpimpin itu tinggal
sisa-sisanya. Yang kelihatan hanya orang berkerumun dalam
beberapa kelompok, kesurupan terengah-engah, terbata-bata tanpa
peduli dunia sekitar. Ini ujian terakhir untuk kekuatan. Tapi
ketegangan itu segera buyar: pesta selesai, suasana normal
kembali. Orang yang menusuk perutnya itu sekarang minum bir.
"Bir ini membakar semangat saya," katanya.
Orang pribumi merasa, misi Kristen telah banyak melemahkan
kekuatan pesta Dipri. "Anak-anak muda kami mulai banyak yang
menolak acara inisiasi. Mereka takut kesurupan waktu sedang
bekerja di kantor," kata seorang tua.
Tapi rasa nasionalisme kurang berkembang di sana. Orang rela
mati untuk membela kesebelasan sepakbola sukunya, tetapi segan
menghormati bendera nasional. Banyak yang beranggapan, kalau
Presiden Houphouet meninggal berarti Pantai Gading juga
meninggal. Berarti masih hanya mempercayai satu orang.
DI ibukota Abidjan, kehidupan bertolak-belakang dengan suasana
yang terdapat di desa. Di sini, seperti halnya di kota besar
mana pun, uang sama dengan hukum dan kebahagiaan.
Gedung-gedung pencakar langit menjulang tinggi. Lalu lintas
macet. Tukang copet ikut meramaikan pertumbuhan kota yang
modern. Hanya, meski sudah mulai banyak kaum wanita ikut
bekerja, kehidupan sehari-hari tetap dikuasai lelaki.
Ny. Alexise Gogoua, pegawai pemerintah, bercerita. Katanya, di
desa kaum wanita menghabiskan umur dalam kehidupan rutin
--mengambil air, menumbuk gandum, mengurus anak, memasak,
membersihkan rumah. Karena tak berpendidikan, mereka tak
mendapat tempat dalam masyarakat. Lelaki menguasai
segala-galanya. Di kota wanita sudah bisa bekerja.
"Tapi di kota kita jadi bukan apaapa," katanya. "Kita kehilangan
asal-usul kita." Dan, meski sama-sama bekerja, para istri tetap
harus pulang ke rumah untuk masak dan mengurus rumah. Tapi
memang ada beberapa perubahan. Ada suami yang rela bangun tengah
malam untuk memberi susu bayinya, karena tak sampai hati
mengganggu istrinya yang telah kerja berat di kantor dan di
rumah seharian. Seperti kata Ny. Gogoua, "perubahan memang
sedang terjadi, dan lambat laun akan meluas ke seluruh negara.
Satu ketika kaum wanita Pantai Gading pasti akan memperoleh
persamaan hak." Ukuran di sini memang ukuran Barat.
Yang dipusingkan kaum pria lain lagi. Edmond Kouakou, pegawai
Kantor Pariwisata, mengatakan: "Kehidupan di Abidjan tidak
mudah. Segalanya harus pakai duit, bahkan untuk makan kacang.
Saya pergi ke kantor dengan pikiran cemas. Apakah anak saya bisa
selamat menyeberangi jalan, di kota yang ramai ini? Apakah
mereka akan bisa memahami gaya ke hidupan orangtua saya di desa?
Apakah mereka akan bisa tetap ingat pada bahasa Baoule? Di desa
tak ada mobil. Tenang tenteram di sana. Saya sebenarnya ingin
jadi petani. Tinggal di pertanian, tapi memanfaatkan alat-alat
modern yang saya kenal."
Seminggu sebelum pulang, Michael dan istrinya diundang penyanyi
Pierre Amedee. Ia berkisah tentang salah satu baladanya yang
paling populer, mengenai reaksi seekor macan tutul yang
meninggalkan hutan tapi hanya jadi cemoohan dari kota.
Dengan mata berbinar, Pierre berkata: "Kami orang Pantai Gading
bagai macan tutul ketika memasuki peradaban Barat anda yang
modern. Tapi dalam kedunguan anda, anda memandang rendah pada
kami. Barangkali suatu ketika anda akan memahami kekuatan kami,
dan takut akan tindakan pembalasan kami yang adil.
"Berdoalah memohon rahmat Tuhan, orang putih!" katanya dengan
ketawa cekakakan. Lalu mengulurkan tangan persahabatan pada si
wartawan.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini