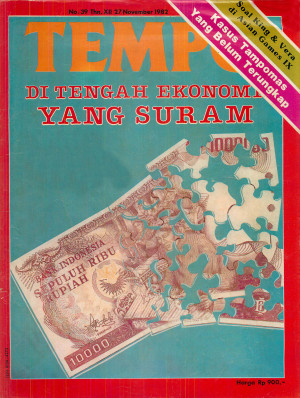MEMOTRET bukan pekerjaan sulit. Setidak-tidaknya begitulah yang
dikatakan Eddie Adams kepada Liz Nakahara, wartawan Washington
Post. Tidak percaya?
Hatta pada suatu ketika, seorang tahanan Vietcong sedang
digiring polisi di jalan raya Kota Saigon -- kini Ho Chi Minh.
Eddie Adams, jurupotret Associted Press, membuntuti dengan
sikap waspada. Tatkala Kepala Polisi Nasional Vietnam
Seiatan--Nguyen Noc Loan van kesohor itu--membidikkan
pistolnya ke jidat sang tahanan, Adams membidikkan kameranya.
Ngoc Loan menarik picu, Adams memen jet shutter. Sang tahanan
bergeming sedikit, kemudian terhempas ke jalanan berdebu, dengan
sebuah lubang menghiasi kepala. "Setiap orang bego yang hadir di
sana waktu itu dapat memotret adegan tersebut," ujar Adams
kemudian.
Tapi memenangkan sebuah hadiah penghargaan, apalagi' yang
bermutu internasional, bukan perkara gampang. Potret yang
diambil Eddie Adams itu menggondol hadiah hampir pada setiap
lomba foto jurnalistik 1969 --termasuk Hadiah Pulitzer. Dan,
anehnya, Adams tak sampai bersorak.
"Saya telah mengeduk rezeki dari menyaksikan pembunuhan antara
anak manusia," ujar Adams, setelah ia resmi dinyatakan berhak
menerima Pulitzer Itulah rupanya yang menjadi sebab. "Dua
manusia kehilangan nilai, dan aku dibayar untuk kesaksianku. Aku
telah menjadi 'pahlawan'," katanya pahit.
Tak ayal lagi, setiap jurupotret memendam cita-cita untuk sekali
waktu menggondol Pulitzer. Tapi beberapa di antara
mereka--rupanya termasuk Eddie Adams--tak mau diingatkan kembali
pada cara memperoleh hadiah itu, kata Liz Nakahara dalam
tulisannya yang dimuat International Herald Tribune. Mereka
mafhum, sebuah potret yang istimewa bisa terjadi oleh faktor
untung-untungan, atau oleh sentuhan seorang jenius. Ia bisa
hasil keringat tak kenal lelah seorang profesional, tapi mungkin
juga faktor kebetulan seorang amatir yang menekan shutter tanpa
perhitungan pelik.
Batas yang membedakannya memang sangat tipis--mungkin hanya bisa
diukur dalam mikrosekon. Begitu pula akibat yang ditimbulkan
sebuah potret terhadap kreatornya. Dengan sedikit guncangan)
sebuah potret dapat mengubah - - bahkan merusakkan--jalan hidup
si pembuat.
Dalam peristiwa Eddie Adams, dua tahun jurupotret profcsional
ini tak sanggup melihat foto pembunuhan di jalan raya Saigon
itu, yang telah dibuatnya sendiri. Malah secara terbuka ia
berusaha membela Nguyen Ngoc Loan, sang kepala polisi yang jadi
eksekutor itu. Lho? Alasannya, mungkin: sejak foto itu tersiar,
Ngoc Loan menjadi bulan-bulanan caci-maki seluruh dunia.
Itu membuat Eddie Adams tak betah tidur. Ia lalu minta maaf
kepada Ngoc Loan. Ia juga mencari kesempatan "menebus dosa"
dengan menampilkan potret Ngoc Loan yang manusiawi, yang
kira-kira bisa mengubah citra kepala polisi itu di mata dunia.
Susahnya, kesempatan tersebut tampaknya langka.
Perasaan yang hampir sama dirasakan pula oleh Dallas Kinney,
jurupotret The Polm Bech Post, Florida, yang memenangkan
Pulitzer 1970. Kinney merebut hadiah melalui sebuah foto yang
menggambarkan petani emigran, "yang semata-mata memuji era
liberal yang elok." Ia merasa berdosa karena "menerima hadiah
dari menjual kemelaratan dan penderitaan orang lain".
"Mengerikan," katanya, "betapa rasa sangsi dan bersalah telah
menghancurkan hidup saya."
Jerry Gay dalam pada itu memenangkan Pulitzer 1975.
Bertahun-tahun ia mengorbankan kehidupan pribadinya demi
mencapai "kemampuan psikis menciptakan imajinasi." Berulang kali
ia memenangkan lomba foto tingkat nasional. Tapi tatkala fotonya
tentang para pemadam kebakaran yang dimuat The Seottle Times
dinyatakan berhak menerima Pulitzer, ia malah bingung.
"Pulitzer mestinya lebih dari sekedar hadiah besar," katanya.
"Aku harus berbuat lebih banyak untuk memuaskan hatiku." Ia
dirasuk kegelisahan batin, dan menyangsikan pertanyaannya
sendiri. Kadang-kadang ia berkonsultasi dengan psikiater. Pada
saat yang lain ia memencilkan diri:
Pemenang Pulitzer 1971, John Filo, membidikkan kamera dan
memencet shutter-nya ke arah seorang wanita yang meratap di
samping mayat seorang mahasiswa Universitas Kent State, Ohio.
Belakangan ia sadar, dengan tindakan itu ia telah meledek
musibah yang menimpa sesamanya: si mahasiswa yang, tertembak
mati, dan wanita muda yang meratapi nasib. Tap apa lacur, foto
itu sempat tersebar-bahkan mendatangkan rezeki yang lumayan bagi
si pemotret. Sementara itu Filo tak kunjung selesai menjawab
pertanyaan hati nuraninya.
Keempat jurupotret di atas belakangan menarik perhatian, karera
mereka berbicara mengenai sisi lain Hadiah Pulitzer. Selama ini,
dengan menjanjikan uang US$ 1.000, Hadiah Pulitzer sering
dianggap "yang paling prestisius dalam dunia jurnalistik Amerika
Serikat." Agaknya kini banyak pertimbangan lain yang perlu
diambil, setelah empat dari pemenang hadiah yang menggiurkan itu
'buka kartu' lantaran tak tahan memendam rasa.
Cerita pertama datang dari Edward Thomas Adams, nama lengkap
pemount adegan maut di Saigon tadi. Konon, begitu
ceritanya,.Eddie tak menyangka Kepala Polisi Nguyen Ngoc Loan
itu mau menembak betulan. Ia menduga Ngoc Loan sekedar
menakut-nakuti si tahanan Vietcong yang kedua tangannya diikat
ke punggung. Masa' mau menembak betul--dari jarak begitu dekat!
Tidak dinyana, peluru berdentam. "Bayangkan," kata Eddie,
"bagaimana rasanya menyaksikan orang lain dipistol sampai mati."
Eddie sendiri tadinya tidak begitu peduli ketika menyerahkan
filmnya ke kantor AP di Saigon. Tapi 24 jam kemudian,
"berdatanganlah pesan dari seluruh penjuru dunia." Potret yang
satu itu saja membangkitkan kebencian dan amarah terhadap
perang. Masyarakat bersatu dalam opini, bahwa yang terjadi di
Vietnam adalah perang saudara, dan bahwa "Amerika sesungguhnya
tidak patut hadir di situ." Unt uk sebagian pembaca media massa,
Kepala Polisi Saigon itu langsung tampil sebagai monster
pembunuh. Para editor sendiri sih menerimanya sebagai bahan
berita yang sangat hangat, dan--tentu saja--sangat laku dijual.
Karena itulah, berlawanan dengan saran beberapa rekan, Eddie
Adams lantas datang ke kantor Ngoc Loan. Yang terakhir ini
menerimanya dengan sikap dingin. Si pejabat menceritakan, betapa
istrinya mengamuk karena ia tak berusaha merampas film adegan
yang menjijikkan itu. Setelah itu Eddie terus-menerus mengikuti
Ngoc Loan --selama dua minggu. Ternyata, kata si Mat Kodak,
"banyak juga yang mencintai orang ini."
Rasa bersalah Eddie terhadap Ngoc Loan tak pernah susut. "Aku
merasa bertanggung jawab, karena akulah yang membuat potret
itu." Jadi, kapokkah dia? "Kalau peristiwa seperti itu terjadi
lagi besok, umpamanya, mungkin aku akan memotretnya kembali "
Lho? "Aku terpaksa mengatakan ini, karena aku melakukan hal yang
menyebabkan aku dibayar. Tapi aku benci melihat penderitaan
orang lain yang diakibatkan perbuatanku." Pusing jadinya.
Ada saat-saat ketika rasa bersalah itu mcmberikan pukulan lebih
keras. Pada 1969, misalnya, Adams tiba di Negeri Belanda untuk
menghadiri Lomba Foto Pers Dunia. Di sana ia ditanya seorang
reporter Belanda: "Mengapa anda tak berusaha mencegah polisi itu
membunuh korbannya?"
Adams bergidik. "Aungkin ini pertanyaan paling bego yang pernah
kudengar," katanya kemudian. "Perang sedang hangat-hangatnya,
dan anda berusaha mencegah orang saling berbunuh?" Tapi ia
mengaku, pertanyaan itu membuat perasaannya haru-biru.
TAK kurang dari 10 hadiah lomba foto yang telah dimenangkan
Adams. "Tapi aku selalu dikenang dalam potret Saigon jahanam
itu," katanya kesal. "Aku merasa tertekan, dan berusaha
menampilkan hasil pemotretanku lainnya yang bisa mengubah citra
pembaca. Sebuah potret nonberita, barangkali, yang bisa membuat
orang ketawa atau menangis, pendeknya yang menggugah perasaan."
Kini, Eddie Adams, 49 tahun, bekerja sebagai jurupotret
freelance dan banyak membantu Time Inc. dan majalah Parade. Ia
senantiasa berusaha "membuat imbangan". Pada 1977, ia nyaris
mendapat peluang.
Tahun itu Eddie Adams mengikuti 48 pengungsi Vietnam di sebuah
perahu sepanjang sembilan meter, yang berlayar menuju Muangthai.
Terjadilah, Angkatan Laut Thai kemudian menghalau perahu itu
kembali ke tengah laut. "Kami mengirim gambar dan cerita orang
perahu itu ke Kongres AS," katanya. "Dan (kesaksian) itu
membantu meyakinkan Presiden Carter untuk menerima para
pengungsi Vietnam di Amerika." Adams kemudian menambahkan, "aku
sebenarnya ingin menerima Pulitzer untukhal-hal seperti itu, di
mana tak seorang pun merasa tersinggung."
Lain pula kisah Dallas Kinney, staf foto The Palm Beach Post.
Suatu ketika, bersama dua orang bosnya, Kinney pergi ke sebuah
pemukiman emigran --sekitar 64 km dari kantor mereka. Para
editor tadi menunjukkan kemiskinan keluarga emigran dalam
gubuk-gubuk mereka yang berdinding kertas. Mereka minta Kinney
menggali cerita yang laku dijual.
"Aku tak bisa mengungkapkan sebuah kisah tanpa terlibat di
dalamnya," kata Kinney mengenang. Sadar kalau kameranya akan
segera menarik perhatian dan mencurigakan para gembel itu,
Kinney bersikap pura-pura. Ia berusaha berbaik-baikan dengan
mereka, dan gerombolan orang melarat itu berhasil diyakinkan.
Pada 1970 Kinney dinyatakan berhak menerima Hadiah Pulitzer.
Untuk dia diselenggarakan sebuah pesta yang bersimbah sampanye.
Dan beberapa menit kemudian ia mulai dirasuk perasaan tertekan.
Bangun pagi esoknya, ia melirik halaman depan The Post. Tampak
dua foto besar berdampingan. Yang pertama memperlihatkan Kinney
diguyur sampanye dalam pesta semalam. Potret kedua, yang
memenangkan Pulitzer itu, mempertontonkan tiga anak emigran yang
compang-camping di samping gubuk mereka yang hampir tumbang.
Kinney terkesima. "Anak-anak itu tidak akan pernah punya
persediaan susu untuk hari berikutnya," kata Kinney. Sedang dia
bermandikan sampanye. "Ya, Tuhan. Apa yang akan dikatakan para
gembel itu mengenai diriku, yang telah mereka terima dengan
tangan dan hati terbuka?"
"Pulitzer," katanya belakangan, "adalah sebuah keputusasaan yang
aku tak kuat memikulnya. Aku harus lari, harus menghindar." Ia
meninggalkan The Palm Beach Post tak lama setelah kejadian
tersebut. Mencari ke sana ke mari, berusaha "menebus dosa"nya
dengan cerita lain--yang tak kunjung ketemu.
Di suatu hari libur, Kinney melakukan perjalanan bersama
keluarganya. Ia berusaha menulis serial kehidupan bangsa Indian
Amerika, dalam hubungan "menebus dosa" tadi. Toh ia sendiri
mengakui cerita itu tak terbilang berhasil. Ia kemudian bekerja
di The Philadelphia Inquirer. Tak sampai setahum Balik ke The
Palm Beach Post, empat tahun lamanya, lalu pindah ke dunia
komunikasi telepon. Pindah lagi ke Christian Broadcast Network.
Kini ia konsultan komunikasi padaMailers and Consultants,
perusahaan pemasaran yang berpusat di Richmond. Ia hampir tak
pernah lagi memotret.
Belakangan, Kinney, 45 tahun mencoba mengadaptasikan kembali
serial emigran itu, menambahkannya dengan beberapa film, dan
membubuhkan narasi. Ia agak terhibur. "Untuk pertama kalinya aku
melihat serial itu menurut seleraku," katanya.
Akan hal Gerald Gay, suatu hari Mat Kodak yang satu ini diutus
kanornya ke sebuah lokasi kebakaran. Assignment rutin," kata Gay
mengenang. Ketika ia tiba di sana, ia meyaksikan "suasana
surealistis". Asap dan halimun mengawang di atas puing rumah
yang sudah berubah menjadi conggok arang. Peristiwa itu terjadi
di sekitar pantai.
Para pemadam api menyiram ke ana ke mari dari sebuah tepian.
"Tiba-tiba mereka beristirahat, dan menyajian sebuah
pemandangan yang unik di depan mataku," tutur Gay. "Pemandangan
itu lebih bersifat adegan perang ketimbang suasana kebakaran."
Foto hasil pemotretan Gay, tentang aara pemadam kebakaran yang
sedang beristirahat itu, dimuat di halaman lepan The Seattle
Times. Kemudian segera beredar ke berbagai kantor berita.
"Naluriku mendorong memasukkan potret itu ke kontes Pulitzer,"
kata Gay meneruskan ceritanya. "Ketika itu kita sedang
menyongsong perayaan Bicentennial (ulang tahun ke-200 USA), dan
saya dengar para pembaca sudah bosan melihat hal-hal negatif.
Saya pikir, tentu para juri akan tertarik mendapatkan sesuatu
yang melambangkan 'Semangat Amerika'."
Perhitungan Gay tepat. Dia memperoleh hadiah impian itu. Tapi
yang terjadi kemudian sungguh di luar dugaan. Gay, yang tadinya
seorang Mat Kodak yang ulet dan rajin, mulai ogah-ogahan.
Sering ia menolak assignment, "karena saya tahu kelasnya bukan
Pulitzer." Ia takut memotret, karena merasa dibebani hadiah yang
sangat 'prestisius' itu. Ia khawatir potretnya tak cocok dengan
penghargaan yang sudah diberikan kepadanya. Ini lain lagi,
memang.
Gay terus-menerus berada di bawah bayangan 'kebesaran
'ulitzer'. Dan dua tahun lalu terjadilah sesuatu yang sangat
sulit diterangkan. Di depan sebuah jumpa pers di Seattle, Gay
mempermaklumkan dirinya sebagai "putra Tuhan". Benar. Dia
mencoba mcmbcritahu umat, katanya, "bahwa mereka memiliki
kemampuan untuk mencapai kekuatan seperti yang pernah
dianugerahkan kepada Kristus sekitar 20 abad lalu. '
Kini Gay hidup mengembara dan bekerja semaunya. "Saya percaya
pada kekuatan media " katanya suatu kali. Ia konon sedang
berusaha membangun sebuah centre, tempat mencari kemungkinan
peranan media massa menciptakan dunia yang lebih positif,
melalui cerita yang kita tulis." Tampaknya Gay belum sableng
betul.
Di kalangan jurnalistik Universitas Kent State, John Paul Filo
bukan nama asing. Mahasiswa tingkat empat ini bekerja 40 jam
seminggu.
Pada hari yang naas itu, ia sedang membidikkan kameranya ke
barisan Garda Nasional yang mengambil sikap siaga. Sasarannya:
seorang anggota Garda bersenjata yang, entah secara kebetulan,
juga sedang menatap tajam ke arah Filo.
Tiba-tiba senjata menyalak. Peluru menghantam sebuah patung
logam, kemudian bersarang di sebatang pohon. "Tuhan," desis
Filo, "mereka menggunakan peluru sungguhan."
Ketika tembakan berhenti, Filo melihat orang berbaring di
rumput. Tadinya ia menyangka tembakan diarahkan ke udara.
Kemudian ia sadar, dari kumpulan orang yang berada di lapangan
tersebut, hanya dia yang tidak tiarap.
"Seseorang luka di dekat saya," katanya kemudian, mengenang
peristiwa tersebut. "Ternyata Jeffrey Miller, tepat di
belakangku, agak ke kiri. Lehernya tertembak Darah memancur
deras."
Tatkala ia memotret jasad Millel yang tak bernyawa, Filo melihat
seorang perempuan berlari, kemudian berlutut di sisi jenasah.
"Ia memandang ke bawah," tutur Filo, "mulai tersedu dan
terisak." Sementara itu sang jurupotret bergerak lebih dekat,
membuat setengah lingkaran, "untuk mendapatkan efek tertentu."
Huru-hara itu terjadi 4 Mei 1970.
Khawatir kalau hasil pemotret itu akan dirampas para petugas di
Ohio, Filo mencuci dan mencetakkan foto tersebut ke
Pennsylvania. Setelah potret tersebut disiarkan berbagai kantor
berita, Filo segera dibanjiri pertanyaan. Ada surat yang bernada
mendakwa. Ia dicurigai ikut 'mengatur' adegan tersebut.
Hari-hari selanjutnya berlangsung dengan keresahan. "Aku tak
bisa tidur bermalam-malam," tutur Filo kemudian. Ia digoda
sejumlah pertanyaan. "Mengapa justru aku yang harus memotret
adegan tersebut? Mengapa bukan aku yang terluka, atau mati?" Ia
menjadi sangat peka, dan pemurung.
Dan, ketika suatu hari Filo kebetulan berada di kantor AP,
datanglah berita yang mengejutkan itu. Ia dinyatakan berhak
menerima Hadiah Pulitzer. "Di dalam hati aku sangat bergembira "
katanya. "Tapi aku tak memperlihatkannya. Kampus masih
diselimuti tragedi."
Lagi pula, ternyata, hadiah itu memmembawa buntut yang kurang
sedap. Apa? "Gaya hidup anda menjadi rusak," kata Filo. Segera
setelah menyelesaikan studinya, 1971, rumah tangga Filo yang
sudah berjalan tiga tahun berantakan. Ia berccrai dengan
istrinya.
Filo kerap menolak bila diajak bicara mengenai peristiwa di
Universitas Kent State itu. Ia menyebut kejadian itu "pengalaman
yang sangat emosional dan memilukan." Tapi ia dengan senang hati
bersedia tampil sebagai saksi, bila orang tua para korban
peristiwa tersebut menggugat pemerintah dan menuntut ganti rugi.
Meski demikian, penampilannya di pengadilan - yang kemudian
benarbenar dilakukannya--mengingatkannya kembali pada perasaan
bersalah yang tidak jelas. "Saya keluar dari situasi itu dalam
keadaan yang jauh berbeda dengan para mahasiswa yang terbunuh,"
katanya. Apalagi salah seorang teman karibnya, Bill Schroeder,
ikut menjadi korban.
"Aku datang ke pengadilan sehat walafiat. Para orang tua
almarhum itu memandang kepadaku, dan aku tak tahu apa yang ada
dalam pikiran mereka. Tuhan, apa yang bisa Kau katakan kepada
ayah bunda Schroeder? Mereka kehilangan seorang putra, dan aku
memperoleh kemasyhuran."
Rasa bersalah Filo tidak berakhir dengan selesainya
sidang-sidang pengadilan. Ia juga diresahkan oleh perasaan Mary
Ann Vecchio, perempuan muda dalam potret tersebut. aalam salah
satu wawancara, Hary mengatakan potret tersebut menghancurkan
hidupnya. "Sunguh mengerikan," kata Filo.
Jalan hidup perempuan itu kemudian memang tidak karuan.
Berdasarkan sebuah cerita pada Desember 1976, Mary Vecchio
menerima sejumlah surat berisi caci-maki dari orang tak dikenal.
Pada 1973 ia malah ditahan dengan tuduhan prostitusi.
Filo sendiri sementara itu tak lagi berani sembarang memotret.
Ia menimbang segala konsekuensi: Ia menyatakan keinginannya
untuk berbicara dengan Mary Vecchio suatu ketika. "Aku hanya
ingin tahu, berapa besar pengaruh foto tersebut atas jalan
hidupnya."
Kini Filo bekerja untuk Philodelphia Inquirer, masih sebagai
jurupotret. Entah apa kesan yang tinggal dalam dirinya mengenai
potret kampus yang memenangkan Pulitzer itu. "Tapi kalau
kesempatan seperti itu datang, aku tetap akan memotretnya
kembali." Tidak kapok?
Seperti berfilsafat ia menjawab: "Anda hanya perlu menaklukkan
diri sendiri. Orang lain tidak akan bisa memahami perasaan anda.
Kecuali Eddie Adams, yang pernah mengalaminya sendiri."
Akan halnya Eddie, orang ini mengirim surat ucapan selamat
tatkala Filo memenangkan Pulitzer. Pada baris terakhir surat itu
Eddie seperti berteka-teki: "Mari kita lihat apa yang akan anda
lakukan besok.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini