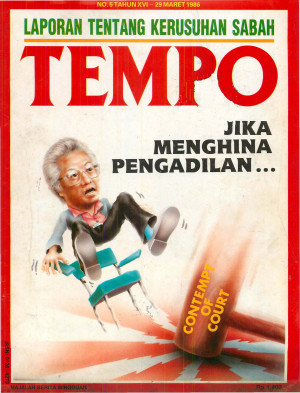Gajah? Hanya binatang masa lampau. Manfaatnya tak lebih dari cuma menjadi penghuni kebun binatang, kata sebagian orang. Di Muangthai, meski tenaga hewan-hewan raksasa itu (sebagai pengangkut kayu di proyek penebangan dan penggergajian) sudah sangat kalah efisien dibanding tenaga mesin, "masa lampau" itu dilestarikan -- sambil tetap membiarkan terbukanya lapangan kerja bagi ribuan pawang. Malah kini, tanpa perhitungan ekonomis sama sekali, orang di sana mendirikan sekolah gajah yang pelajarannya memakan waktu hampir sepuluh tahun. Amran Nasution dan Didi Prambadi dari TEMPO meninjau kompleks di pelosok pedalaman Muangthai Utara itu akhir Desember tahun lalu, selepas meliput acara SEA Games di Bangkok. Keduanya bukan hanya ingin merasakan empuknya leher gajah (untuk ditunggangi, bukan dimakan), tapi juga ingin membawa oleh-oleh buat kita semua. Dari bahan mereka berdua, Amran menuliskan laporan berikut ini bersama foto-fotonya. Barangkali ada manfaatnya: kita pun kini sudah mulai merintis sekolah gajah -- di Lampung, semacam yang di Lampang (Thai) itu. Daripada hanya menjadi pengganggu penduduk karena berebut habitat, barangkali saja. MASIH dipagut rasa malas, Chimun menyingkap kelambunya yang kumal. Dia singkirkan selimutnya yang tebal berwarna merah berkembang-kembang besar. Sebuah radio tua merk Wilco, yang selalu setia menemaninya di malam hari, dengan hati-hati dia taruh di sebuah pojok kamar. Kabut mulai menipis, tapi dingin pagi masih terasa mengigit. "Sebenarnya saya punya istri dan tiga anak. Tapi mereka tinggal di Ngao," ujarnya, menyebut sebuah desa yang terpaut belasan kilometer dari situ. Chimun sekarang sudah dalam seragam lengkap: baju tanpa kerah dan celana longgar, berwarna serba biru tua. Sehelai sarung kumal masih tampak melilit di pinggangnya, dan di situ terselip sebilah parang yang sarangnya terbuat dari kulit kayu. "Mari kita mencari gajah asuhan saya. Namanya Payau." Di tangan Chimun kini tergenggam gancu, sebilah besi setengah meter yang ujungnya bengkok dan tajam. Alat ini untuk mengendalikan gajah -- bagaimanapun besarnya binatang itu. Dengan sigap ia lalu menuruni tangga gubuknya yang terbuat dari kayu bulat, dua meter dari tanah. Di bawah, seorang temannya, Manith, sudah menunggu. Ia memakai topi pet tentara. Ketika itu jarum jam menunjuk pukul 06.00. Kami berjalan santai menyeberangi sungai kecil Huay Mae La. Sungai ini memisahkan gubuk yang tadi itu dengan hutan. Setelah meloncat-loncat di batu-batu besar di sungai, kami mulai mendaki Bukit Pang La yang memiliki keterjalan 30 derajat. Bagi orang yang belum biasa, perjalanan memanjat seperti itu cepat sekali menguras tenaga dan seakan merontokkan buah pinggang. Tapi Chimun, 34, dan Manith, 38, tampaknya tak merasakan itu: mereka maju dengan mantap, sesekali berhenti di depan rintangan tetumbuhan hutan -- dan dengan sigap parang di tangan Chimun segera bicara. Sesekali Chimun bernyanyi kecil, sembari di bibirnya terselip sebatang rokok putih lokal, Krong Thip. Kami berjalan sekitar 2 km memasuki hutan, ketika tiba-tiba Chimun menengadah. Sebelah telapak tangannya diletakkannya di belakang telinga. "Coba Anda dengar. Itu suara gajah ! " serunya. "Ke sana! Ke sana!" teriak Manith, menunjuk ke kanan bukit. Kami bergegas menyeruak di antara belukar dan semak ilalang. Telinga normal akan sulit menangkap suara itu. Tapi bagi Chimun dan teman-temannya, o, itu perkara mudah. Suara yang berasal dari kelontongan kayu (di sana disebut kadeng, mirip kelontongan di leher sapi di sini), bisa ditangkap telinga Chimun dalam jarak yang tidak dekat. Ternyata, betul. Setelah merayapi hutan sekitar 2 km, kami menemukan dua ekor gajah -- di sebuah lembah ilalang yang ditumbuhi pohon-pohon jati. Begitu sigap keduanya menuruni lembah itu, dengan suara mereka melengking tinggi. "Heh ! . . . Heh ! . . . Heh ! " yang segera disambut lenguhan kedua ekor kawan kita itu, yang tak lupa menaik-naikkan belalai mereka. "Ouuurgh ! . . . Ouuurgh! . . .," kata mereka. Manith mendekati Sadith, gajah enam tahun dengan bobot 500 kg. Perut Sadith ditepuk-tepuknya, diusap-usapnya, lalu kedua rantai yang terikat di kaki depan binatang itu dilepaskannya. Hal yang sama dilakukan Chimun terhadap gajah piaraannya, si Payau itu. Keduanya lalu mereka tuntun menaiki lembah, dengan cara menarik kuping mereka dengan tangan kanan, sementara gancu terpegang di tangan kiri. Sesampai di jalan setapak kedua gajah diperintahkan meniarap. Lalu kedua pawang membersihkan tubuh binatang peliharaan mereka dengan daun ilalang dan daun tebu yang mereka dapatkan di situ. Kemudian menggiring anak-anak asuhan itu ke pondokan. Dengan patuhnya kedua binatang itu menurut saja pada semua perintah -- meskipun, sesekali, ketika melintasi rimbunan tebu hutan, keduanya berhenti dan menggaetkan belalai ke pucuk daun tebu, lalu memasukkannya ke mulut. Yang menarik, bila bertemu lubang di jalan, gajah-gajah itu selalu berusaha menghindar, ke kiri atau ke kanan. "Itulah anehnya gajah: badannya kuat dan besar, tapi sangat takut lubang, lubang sekecil apa pun," Chimun mencoba menjelaskan duduk perkaranya. Sekitar pukul 07.00 kami sudah sampai di pondokan, yang tak lain kompleks sekolah gajah. Nama Inggris kompleks ini: The Young Elephant Training Centre, disingkat YEC -- yah, inilah pusdiklat pemuda gajah. Di sini sudah berkumpul sekitar 11 gajah lain, yang juga baru diturunkan dari hutan oleh pawang masing-masing. Selain itu masih ada lagi enam gajah yang masih kecil, para anggota kelas balita -- masih berumur 2-3 tahun dikandangkan di kurungan kayu bulat seluas 3 x 4 meter. Ini memang betul-betul sekolah, karena di lengkapi dengan kurikulum dan sejumlah guru yang dijuluki mahou alias pawang gajah. Istilah ini berasal dari India, tapi sudah melekat di sana. Padahal dalam dialek setempat pawang gajah disebut kuan chang. * * * Terletak di sebuah lembah landai yang dikelilingi bukit-bukit terjal, sekolah ini persisnya berada di kawasan Desa Pang La, Distrik Lampang, Muangthai Utara, kira-kira 700 km di utara Bangkok dan tak terlalu jauh dari tapal batas Laos. Tempat ini bisa dicapai melalui jalan raya yang menghubungkan Lampang dengan Distrik Ngao, hanya saja harus membelok melewati jalan tanah sejauh 2 km menuju kaki Bukit Pang La. Di situ berjejer gubuk-gubuk panggung, panjang 50 meter dengan lebar cuma dua meter, dengan dinding bambu pecah dan atap daun rumbia. Di gubuk-gubuk itulah berdiam (bukan para gajah, tapi) para guru gajah. Mereka, semua 33 orang, terdiri dari mahout (seperti Chimun dan Manith), asisten mahout, dan para pembantu yang bertugas memberi makan gajah dan mengerjakan hal-hal sejenis. Di depan gubuk panjang itu terhampar dataran seluas 8.000 m2, yang terasa amat teduh karena terlindung dari cahaya matahari oleh pohon-pohon besar yang tumbuh di sana-sini. Di lapangan terdapat kandang-kandang untuk anak-anak gajah anggota play group tadi. Ada pula beberapa kurungan segi empat -- semuanya dari kayu bulat sebesar betis dengan luas 2 x 3 meter atau 3 x 4 meter, digunakan para mahout untuk melatih para siswa. Lantas, di hampir tiap pohon besar ada rantai-rantai besi dipakai untuk menambatkan mereka. Gajah-gajah itu, seperti diterangkan dr. Preecha Phongkum, 36, pimpinan YETC, dididik sejak berumur tiga tahun, saat seekor anak mulai bisa diceraikan dari induknya. Biasanya anak gajah yang dipisahkan dari ibunya akan merana sekali -- akan terus menjerit sepanjang hari, sekalipun pawang memberinya susu. Tapi, menurut Preecha, pawang yang sudah piawai akan mampu memisahkan anak dan induk itu tanpa satu sama lain merasa sedih. Benar. "Dengan magic," ujar dokter hewan lulusan Universitas Kasetsart di Bangkok itu. "Sebagai orang yang berpendidikan, saya sulit mempercayai magic tapi di sini hal itu sudah terbukti," kata Preecha menyeringai, sambil memperlihatkan gigi-giginya yang jarang. Preecha lalu menunjuk Yien, 60, pawang paling senior. Yien sudah menjadi pawang sejak berumur 16, dan sekarang sebenarnya sudah harus pensiun tapi tetap saja giat mengabdi demi pembangunan gajah. Memang di sana kerjanya cukup ringan disesuaikan dengan keadaan fisiknya yang sudah renta -- yaitu mengawasi dan memberi pengarahan kepada mahout yang lebih muda. Tapi, sayang, "memisahkan anak gajah, di sini cuma bisa dilakukan Yien," ujar Preecha. Karena itu, hanya Yien yang dipakai. Dengan mantra-mantra yang dibacakannya, Yien seenaknya saja menangkap bocah yang sedang digandeng ibunya, tanpa mendapat perlawanan apa-apa. "Induk gajah itu pergi saja dengan sendirinya, seolah-olah dia membenci gajah kecil itu," tutur Preecha. Si bocah pun seperti tak pernah merasa kehilangan ibu -- tak pernah menangis, dan dengan lahap menenggak susu yang diberikan. Padahal, tak jarang anak gajah yang baru dipisahkan dari ibunya seharian hanya menangis melengking-lengking, tak mau meminum susu yang disuguhkan, kemudian -- lah-lah-lah -- mati. Sedih hati dibuatnya. Yien, yang total jenderal sudah melatih 200 gajah, pernah dicoba kemujaraban ilmunya. Suatu kali seekor anak gajah, yang baru beberapa hari dipisahkan Yien, dipertemukan dengan induknya. Mestinya akan terjadi sesuatu yang gawat: naluri sang ibu yang selalu ingin melindungi oroknya bisa mengakibatkan induk gajah itu marah dan menyerang orang-orang itu. Eh, nyatanya sebaliknya. "Induk dan anak itu seperti tidak saling mengenal," kata Preecha lagi. Di YETC, gajah kecil berumur 3-4 tahun akan diberi pelajaran pertama. Sungguh tak enak: dimasukkan ke dalam kandang yang pas-pasan dengan tubuhnya, sehingga tidak bebas bergerak. Kandang itu kandang yang terbuat dari kayu bulat sebesar betis tadi, yang cukup kuat dibanding kemampuan bocah-bocah itu untuk memberontak. Bagaimana mau memberontak: leher si bocah masih diikat lagi dengan rantai besi. Lalu, tugas mahout mula-mula membersihkan tubuhnya, dengan sapu yang terbuat dari daun tebu. Untuk pertama kalinya biasanya binatang kecil (tapi besar) itu akan memekik-mekik, meronta-ronta. Jangan dikira bahwa gajah, mentang-mentang tubuhnya segede gajah, akan baru merasakan rangsangan kalau digebuk. Gajah justru memiliki kepekaan luar biasa pada permukaan kulitnya sedikit elusan saja sudah cukup menimbulkan rasa aneh (mungkin geli, ya?) bagi binatang yang serba tebal itu. Kemudian, setelah puas meronta-ronta, si anak akan kecapekan, dan diam dengan sendirinya. Itu pada minggu pertama. Pada minggu kedua, tugas mahout tak cukup hanya mengelus-elus punggung si anak gajah dengan pucuk daun tebu. Mahout mulai melatihnya untuk merasakan pantat kita, alias menunggangi binatang itu. Pagi itu Plang Kot (Plang berarti nona, dan Kot nama sungai tempat gajah itu ditemukan. Kebiasaan di sana: gajah betina diembel-embeli nama sungai, gajah jantan nama gunung), seekor gajah empat tahun, dan baru 22 hari dipisahkan dari induknya, sedang sekolah. Terikat ketat di dalam jerejak kayu itu Plang Kot dicoba tunggangi oleh Num, sang pawang. Gajah kecil yang beratnya tak sampai setengah ton itu segera memberikan reaksi: belalainya turun naik, dan melenguh sekeras-kerasnya," Ouuurght! ... Ouuurght ...!" Kaki belakang menerjang-nerjang. Sampai beberapa belas menit ia tetap saja melawan, sekalipun seorang asisten Num sudah mulai menyakiti binatang itu. Dia menarik telinga gajah it keras-keras sambil berteriak, "Map! . . . Map! . . . Map! . . ." -- perintah menyuruh berbaring. Ketika si anak didik tak juga mau turut perintah, nah penyiksaan pun dilakukan. Sang asisten, yang rupanya sudah kehilangan kesabaran, mulai melecuti tubuh binatang itu dengan sebatang tebu, sampai betul-betul remuk redam (tebunya). Plang Kot terus saja menjerit-jerit: suaranya yang nyaring menggema di seluruh lembah. Sampai-sampai ia akhirnya terkencing dan terberak-berak. "Wah, dia sudah ketakutan," komentar Preecha. Penyiksaan segera dihentikan -- tampaknya untuk meredakan rasa takut anak itu. Ketika kemudian pelajaran diulang, si Plang Kot ternyata sudah bisa mengikutinya. Dia berusaha berbaring ketika disuruh berbaring, dan kembali berdiri ketika sang mahout mengeluarkan perintah, "Hek! . . . Hek!" Maka sang guru pun segera menghadiahkan sepotong tebu ke lilitan belalainya. Si murid segera memamah tebu itu. Seperti diungkapkan Preecha, dasar yang dipakai mendidik gajah di sana ialah prinsip "cambuk dan wortel". Binatang itu akan dihukum bila tak menuruti perintah, dan diberi hadiah bila patuh. Punishment and reward! Karena itu, jangan merasa mual dulu kalau suasana sehari-hari di sekolah gajah itu dipenuhi teriakan mahout yang marah dan suara lengking gajah yang ketakutan. Penyiksaan yang dilakukan para mahout kepada binatang-binatang itu tak cukup dengan hanya memukulnya dengan tebu atau kayu. Bahkan ada yang begitu tega, sampai-sampai membacok gajah dengan goloknya, kalau lagi kesetanan. Mungkin di sana memang banyak setan. "Karena itu lihat saja: gajah di sana pasti brocel-brocel, bekas kena golok," ujar M. Sugoto, 37, petugas kebun binatang Surabaya yang pernah belajar selama enam bulan di sekolah gajah YETC itu. Bukan itu saja: selama berada di negeri pagoda-pagoda itu, Maret-September 1979, Sugoto pernah pula melihat pawang yang marah lalu menyundut kaki gajahnya dengan besi yang sudah merah dibakar. "Semua itu mungkin karena temperamen orang Muangthai," kata Sugoto di Surabaya. Yang mengagumkan Sugoto: Bagaimana para pawang di sana begitu akrab dengan gajah-gajah itu. "Mereka tidur pun mau, bersama gajah itu," katanya. Itu dilakukan agar anak asuhan itu cepat mengenal bau tuannya melalui penciumannya yang juga peka. Karena itu pula, selama berada di kompleks itu, Sugoto baru mengganti pakian seragam biru-birunya seminggu sekali -- "agar gajah cepat hafal bau saya." Mungkin saja karena itu Campui, anak gajah tiga tahun yang ketika itu dipercayakan kepada Sugoto, cepat mengenali orang asing itu. "Bukan sombong: Campui itu kalau saya panggil segera datang dan menunduk kepalanya baru diangkat kalau sudah saya suruh.' Dari pengalaman enam bulan itu Sugoto berkesimpulan, untuk bisa menjadi mahout, selain punya rasa cinta kasih kepada binatang, juga harus punya .. "keberanian" istilahnya. Kemampuan para mahout mendidik gajah di sekolah itu memang sempat membuat orang Surabaya itu terkagum-kagum: gajah-gajah itu mampu menyusun rapi seonggokan kayu balok. "Saya sampai heran: kok bisa ya, balok-balok yang pada nongol itu mereka dorong sampai jadi rata?" Siang itu terjadi keributan kecil. Tiba-tiba saja Plang Kot, si gajah anak tadi, berhasil melepaskan diri dari ikatan dan berlari liar di sekitar kompleks. Beberapa mahout akhirnya bisa menyergapnya dan dia pun segera diikat lebih ketat di tempat semula. Untunglah. Mungkin karena usianya yang masih begitu sedikit, si gajah nakal lepas dari hukuman yang parah -- tak sampai mengalami diasingkan, misalnya, seperti yang terjadi dengan seekor gajah berumur 13 tahun yang diberi nama Plai Bok. Karena selalu membantah perintah mahout, sudah hampir dua bulan ini Plai Bok menjalani vonis penjara: ditambatkan di sebuah pohon besar, di seberang sungai, sekitar 500 m dari kompleks sekolah. Kedua kaki depannya diikat dengan rantai besi ke pohon besar itu. Masih syukur, para mahout memberinya makan setiap hari. Setiap makanan diantar, Plai Bok segera menyantapnya dengan lahap, seperti tanpa pernah merasa berdosa. Entah sampai kapan gajah nakal itu tertambat di sana, menunggu grasi. Yang berhak memberi grasi: Preecha. Tapi, tentu saja, bukan cuma gajah yang bisa jadi korban hukuman. Juga para mahout. Seperti diungkapkan Preecha, pada 1973 seekor gajah jantan yang bernama Plai Ngapot membunuh seorang mahout bernama Ton. "Gajah itu marah karena diperlakukan kurang sopan," kata Preecha, entah bagaimana. Ton, yang ketika itu berada di punggungnya, dilemparkan raksasa itu ke tanah, baru dengan ganas ditubruk dan diinjak-injak sampai luluh lantak -- dan mati. Sugoto pun sempat menyaksikan tragedi yang sama: seorang mahout asli Muangthai dilemparkan dari punggung gajah dan diinjak-injak sampai betul-betul remuk. "Begitu jadinya kalau raksasa itu sudah marah," katanya. Menurut pengetahuan Sugoto, kemarahan kawan kita itu terbit karena sang mahout memaksanya bekerja keras berlebihan, di bawah sengatan terik matahari. Padahal gajah adalah binatang yang tak tahan bekerja dalam panas. Karena itulah, di bulan-bulan yang sangat panas, Maret-Mei, sekolah gajah ditutup para siswa libur, meskipun tidak berpiknik. Menurut Preecha, gajah sudah kepanasan pada suhu 35 derajat Celcius padahal pada musim panas daerah itu bisa mencatat suhu sampai 37 derajat Celcius. Juga karena alasan panas pula bila jam pelajaran dimulai pukul 06.00 dan berakhir pukul 12.00. Setelah itu gajah-gajah kembali dilepaskan ke hutan, untuk ditangkap lagi esok paginya oleh para mahout dan kembali diberi pelajaran. Memang di situlah menariknya pemandangan kompleks itu. Persis di sekeliling sekolah terhampar -- seluas 5 sampai 7 km persegi --areal perbukitan Pang La, yang ditumbuhi hutan dan belukar serta menyediakan makanan alam buat saudara-saudara gajah, yaitu tebu, pisang, dan sebangsanya. Setelah pukul 12.00 siang, gajah-gajah itu pada datang main-main dan makan-makan di sini. Biasanya para mahout cuma menggantoli piaraan masing-masing dengan rantai besi di kaki, supaya binatang itu tak bisa pergi terlalu jauh ke tengah hutan. Juga mereka taruh kelontongan kayu di leher, untuk keperluan bunyi. * * * Muangthai, yang dijuluki Negeri Gajah Putih itu, memang memiliki banyak cerita tentang pergaulan manusia dan gajah. Ada berbagai legenda tentang para raja yang berperang dengan bangsa asing Burma, misalnya -- dengan mengandalkan bantuan binatang itu. Semua itu sampai kini masih bersisa: di desa-desa gajah masih akrab dengan penduduk, digunakan untuk membantu merambah hutan, misalnya, atau berbagai pekerjaan berat lain. Kecuali di belahan timur negeri itu, wilayah yang nyaris tak mengenal gajah. "Gajah jarang ditemukan di sebelah timur karena di daerah itu tak banyak hutan," ujar Preecha. Tapi munculnya sekolah gajah yang unik ini justru karena suatu kebetulan. Sekitar 1960, sebuah perusahaan di Burma mendapat konsesi dari pemerintah Thai untuk merambah hutan teakwood di kawasan utara negeri itu, di seputar daerah tempat sekolah gajah sekarang. Untuk melaksanakan proyek ini para kontraktor Burma ternyata menggotong 140-an gajah pekerja dari negeri mereka, dan kebanyakannya ditinggal begitu saja setelah proyek selesai. "Itu jadi problem bagi kami: mau diapakan anak-anak gajah pekerja itu?" kata Preecha. Dari sinilah. akhirnya muncul ide mendirikan sekolah gajah, yang direalisasikan pada 1969. YETC sebetulnya bukan milik pemerintah. Tapi hasil usaha Forest Industry Organization (FIO), sebuah perusahaan penebangan kayu dan pabrik kayu lapis yang sahamnya dimiliki swasta dan pemerintah. FIO sendiri terpilih sebagai pemegang konsesi penebangan hutan di kawasan utara, termasuk bekas konsesi orang Burma tadi. Untuk membiayai sekolah itu, setiap bulan perusahaan itu harus mengeluarkan 140.000 baht atau sekitar Rp 6,3 juta. Terus terang, Preecha mengakui, proyek ini sama sekali tidak ekonomis: gajah yang dihasilkannya, yang bisa dipakai sebagai tenaga kerja pengangkut kayu jati di HPH milik FIO, sungguh tak sebanding dengan dana yang dikeluarkan perusahaan itu. "Berapa besar biaya yang kami keluarkan setiap tahun, tentu tak seimbang dengan paling banyak dua ekor gajah yang sudah terdidik yang kami berikan kepada FIO," ujar Preecha, karyawan FIO itu . Gajah Muangthai, seperti gajah Asia lainnya, diketahui sebagai binatang pemakan rumput (mampu memakan 500 pon rumput plus minum air 60 galon setiap hari), pisang, pucuk bambu, dan dedaunan lain, dan dikenal sebagai pejalan lambat -- sekitar 2 km setiap jam. Sampai 1-2 umur tahun, seekor gajah betul-betul terikat dan menyusu pada induknya. Karena itu, baru mulai umur tiga tahunan anak gajah diambil dari sang ibu dan disekolahkan di YETC. Pelajaran pertama (dibersihkan tubuhnya, ditunggang, disuruh duduk, berdiri, dan berbagai gerakan dasar lain) akan diulangi terus-menerus sampai si murid berumur lima tahun -- "sampai betul-betul melekat pada mereka," kata Preecha. Setelah gajah berusia 6-10 tahun, pelajaran ditambah: mulai berlatih menarik dan mengangkat beban ringan, seperti balok-balok yang kecil-kecil, yang makin lama akan makin diperberat. Pada usia 11-15 tahun, mereka dianggap sudah menamatkan sekolah -- dan dikirimkan ke hutan-hutan konsesi FIO tadi. Jadi, bisa dihitung berapa tahun gajah harus mendekam dalam pesantren itu, dan berapa biayanya. Malahan sebetulnya pada usia 11-15 tahun itu gajah belum bisa diberi beban maksimal. "Masih harus yang lebih ringan," ujar Preecha. Sebab usia produktif seekor gajah, menurut Preecha, ialah 39 sampai 50 tahun. Waktu itulah binatang itu mampu menyeret balok seberat setengah bobot tubuhnya. "Lebih dari usia itu kemampuan gajah terus menurun, sampai dia mati dalam usia sekitar 70." Seperti kita saja. Seekor gajah berusia 26 tahun yang diberi nama Plai Nen, bobotnya mencapai 5 ton dan tinggi hampir 3 m, suatu siang memamerkan kebolehannya kepada TEMPO. Di bawah pengawasan seorang mahout kawakan bernama Sak Sakoe, 47, Plai Nen dengan mudahnya menggeret sebatang balok seberat lebih dari satu ton dari hutan pegunungan Pang La, 1 km dari kompleks sekolah. Gajah itu mengenakan nang keng, sejenis pelana dari kulit kayu hutan. Pada nangkeng diikatkan rantai besi, sepanjang 30 meter, yang ujungnya ditambatkan pada kayu balok. Ketika Sak Sakoe memberi aba-aba, "Hui! ... Hui! ... Hui! ...," Plai Nen dengan santai menggeret balok itu menuruni kaki bukit yang terjal, boleh dikatakan tanpa kesulitan kecuali kadang-kadang berhenti mendadak begitu bertemu rumpun tebu. Dan Sak Sakoe, yang menempel di leher Plai Nen, menggosok-gosok telinga binatang itu untuk membuatnya bergerak lagi. Sekitar setengah jam kayu balok itu sudah berada di kompleks YETC. Tapi hitung saja berapa tahun dihabiskan untuk memproduksi gajah seumur Plai Nen. Karena itu, menurut Preecha, perusahaannya tak berhitung dari segi laba-rugi -- bahkan tak terlalu mengharapkan gajah produksi sekolah itu. Dari 100 gajah lebih yang sekarang dipekerjakan di hutan-hutan konsesi FIO, di utara, hanya sebagian yang alumni YETC. Selebihnya dibeli dari para mahout di kampung-kampung. Maka, dengan tegas, Preecha mengumandangkan tujuan sekolah itu tak lain dari melestarikan budaya mahout -- dan mengembangkan "ilmu gajah". * * * Tak heran bila-di kota distrik Lampang, 54 km dari sekolah, FIO memiliki klinik pengobatan gajah. Sejauh ini, Preecha mengakui, mereka belum sampai menemukan penyakit gajah yang baru -- setelah adanya klinik itu. Yang menyerang gajah-gajah di sana masih penyakit yang biasa ditemukan, seperti perdarahan pembuluh darah, anthrax, infeksi jaringan dalam, hydrophobia (penyakit takut air), cacingan, berbagai penyakit kulit, sakit karena digigit ular, dan tetanus. Dari semua itu tetanus terbilang yang sering ditemukan -- "karena banyak terjadi pencurian gading," ujar Preecha. Sistem pemeliharaan yang dipakai FIO, yang melepaskan gajah-gajah di padang, memang bisa menguntungkan para pencuri gading. Harap dimaklumi, harga gading cukup merangsang: Menurut Preecha 1 kg bisa mencapai 20.000 baht atau sekitar Rp 1 juta. Biasanya para pencuri bergerak malam hari. "Mereka menggunakan ramuan kuno untuk membius gajah," tutur Preecha. Dengan ramuan itu biasanya gajah segera tertidur pulas, siap untuk dipotong kedua gadingnya dengan menggunakan gergaji biasa. Kata Preecha, maling tak mungkin menggunakan obat bius jenis modern karena pengendusan gajah terkenal sangat sensitif, terutama pada bau-bau yang asing seperti parfum dan alkohol. "Sedikit berbau lain saja, gajah tidak akan mau memakan umpan." Celakanya para maling itu terlalu serakah. Mereka biasanya memotong gading pada pangkalnya semestinya sekitar 20 cm dari pangkal. Itulah yang menimbulkan luka pada mulut gajah, yang akhirnya dijalari tetanus. Beberapa tahun lalu seekor gajah besar berumur 19 tahun, dengan bobot tiga ton lebih, ditemukan terperosok di Sungai Metip dalam keadaan sekarat. Mulutnya terkunci rapat oleh serangan "tetanus maling'' itu. Preecha dan anak buahnya mencoba mengangkat gajah malang itu dengan bantuan mobil derek. Sayang, sesampai di darat, binatang itu menemui ajal. Lebih sayang: setelah dilakukan autopsi, rupanya kematiannya disebabkan rantai baja mobil takal yang menjepit hati gajah kita ini. Preecha tak bersedia mengungkapkan data pencurian gading di sana. "Para pencuri itu bergerak dengan backing yang kuat," hanya itu katanya. Masih lumayan kalau pencurian bisa diketahui secepatnya -- sehingga gajah bisa diobati, tanpa menunggu tetanus. Misalnya, seperti yang dialami gajah bernama Plai Ling, 30 tahun, 20 Desember tahun lalu . Sekitar pukul 02.00 dinihari gadingnya dipotong maling - dan paginya diketahui oleh anak buah Preecha di kawasan Ngao, distrik yang berbatasan dengan Lampang. Siangnya Preecha segera berangkat menuju lokasi, membawa obat-obatan. Maka hewan yang bobotnya mencapai lima ton itu selamat -- minus sepasang gadingnya seberat 2 kg. Tapi kasus-kasus pencurian itu dilaporkan ke polisi, bukan? "Selalu," jawab Preecha. "Tapi tak ada hasilnya." Di atas segala-galanya, dokter itu tetap yakin akan satu hal: "Paling tidak proyek ini bisa menyadarkan masyarakat tentang gajah." Dan itu penting. Sekarang saja, sekalipun ribuan gajah di desa-desa dan hutan-hutan dimanfaatkan sebagai tenaga kerja, dan di daerah-daerah turis dipakai sebagai pembawa atraksi dan hiburan, belum sebuah pun universitas di negeri itu yang tertarik membuka jurusan gajah. Preecha, misalnya, tamat sebagai dokter hewan jurusan kuda. Jurusan itu memang terbilang favorit sekarang: dokter-dokter kuda tidak akan kekurangan pasien. "Sekarang 'kan orang-orang kaya senang memelihara kuda," tutur dokter kita ini. Untung, dokter-kuda-terpaksa ini sudah akrab dengan gajah: dia dilahirkan di Surin, kota kecil yang terkenal di kalangan turis karena atraksi-atraksi gajahnya. Sebab itu ketika perusahaan tempatnya bekerja, FIO, menugasinya empat tahun yang lampau untuk mengepalai sekolah binatang itu, sebagai pengganti pimpinan sebelumnya yang berangkat pensiun, Preecha berbesar hati. "Kebiasaan kecil saya bergaul dengan gajah. Sekarang kesampaian." Ia tertawa. Maka sepanjang minggu dia berada di kompleks sekolah itu -- dan hanya pulang pada hari Ahad untuk menemui istri dan tiga anaknya di Kota Lampang. Istrinya guru sekolah di kota itu - sekolah manusia, bukan gajah. * * * Seharian bergaul dengan gajah, di tengah hutan yang sepi, memang menyebabkan para mahout -- juga Preecha -- diusik sepi. Dan bagi rata-rata orang Thai, itu sudah suatu alasan untuk akrab dengan minuman keras. Preecha, misalnya, mampu menenggak sebotol kecil wiski lokal cap ayam jago seperti meminum sekaleng minuman buah saja. Juga, mungkin karena iseng, umumnya para mahout suka menggambari tubuh dengan tato. "Dan, satu lagi," Preecha menyela. "Mereka kebanyakan punya istri lebih dari satu." Preecha, sih, katanya, tetap bertahan dengan satu istri. Biasanya para mahout menyimpan istri-istri muda mereka di desa-desa sekitar, atau terkadang malah membawanya ke gubuk tinggal di kompleks sekolah. Selama sang suami mengirimkan gajinya secara rutin ke istri tua, tak ada soal. Yang bikin pusing -- dan yang bisa jadi urusan Preecha -- memang-bila anak buahnya yang berpoligami itu alpa mengirim uang belanja ke kampung. Maklumlah. Dan itu mengakibatkan istri tuanya datang melabrak sang suami dan istri mudanya sekalian. Ramai. Tampaknya dengan gaji Rp 70.000 sampai Rp 100.000 per bulan para mahout cukup laris di kalangan perawan desa. Teu Keoe, misalnya, yang sudah 57 tahun, mengaku masih mempunyai istri berusia dua puluhan. Dari sedikit mahout yang cuma beristri satu adalah Tib Tib Kam, 31, anggota suku pegunungan Karen. Pria berkulit putih dan baru punya dua anak itu, yang mengaku sejak kecil sudah bergaul dengan gajah di kampungnya, sudah 11 tahun bergabung di FIO. Jabatannya dulu cuma asisten mahout tugasnya merawat bayi gajah, memberi makanan gajah, atau palingpaling melatih gajah kecil. Baru tahun lalu dia diangkat menjadi mahout. Mengapa begitu lama orang Karen itu dilantik jadi mahout? "Kita tidak bisa memberhentikan begitu saja mahout-mahout senior, sedangkan kita sudah kelebihan mahout," jawab Preecha. Jadi, soal formasi. Sebagian mahout itu berasal dari orang-orang yang sudah jadi di desa. Sering, para mahout desa baru mendapat pekerjaan tetap bila gajah yang diasuhnya sejak kecil dibeli oleh sebuah perusahaan kayu. Karena itu, ada juga mahout yang nakal: sengaja melatih gajahnya untuk membunuh orang lain yang mendekatinya. Caranya mengajari gajah itu, sejak kecil, menginjak-injak orang-orangan yang diberi pakaian yang warnanya lain dari warna pakaian yang biasa dipakai si mahout. Dengan begitu, praktis si gajah tidak boleh berpisah dengan mahoutnya. "Mahout jahat seperti itu masih banyak di desa-desa," tutur Preecha. * * * Sebagai binatang yang memiliki inteligensia lumayan, gajah memang bisa dididik macam-macam. Bahkan, menurut Preecha, gajah yang sudah besar, yang baru ditangkap dari hutan, bisa saja dilatih. "Cuma, agak sulit." Karena itulah YETC mencari murid-muridnya dari antara anak-anak balita. Dan pada tahun terakhir, ketika seorang (seekor) siswa sudah menamatkan seluruh kurikulum, datanglah masa orientasi: Ia diperkenalkan dengan suara mobil, mesin, serta hiruk-pikuk manusia. Tentu, itu dimaksudkan agar setelah bekerja -- terutama sebagai penghela balok -- nanti ia tidak terkejut oleh suara-suara gergaji. Plai Din Dam kebetulan sedang mengalami pelajaran postgraduate itu. Dia lebih dulu dilatih para mahout mendengar deru mobil. Lalu diperintahkan naik ke sebuah truk, lewat tangga besi. Ternyata, melatih menaiki truk saja sulitnya bukan main. Seharian beberapa mahout hanya mengajarinya turun naik, dan selalu saja gajah itu seperti ketakutan melihat truk. Akibatnya, berbagai cambukan dan pukulan dideritanya, sampai dia terkencing-kencing. "Gajah ini memang dungu dan nakal," ujar Preecha. Kebetulan, menurut Preecha, Plai Din Dam keturunan gajah jahat itu bisa dilihat dari kuku kakinya yang kehitaman. "Berarti induk atau ayah gajah itu dulunya pernah membunuh orang," tambahnya, seakan mengutuk binatang yang memikul "dosa turunan" itu. Akhirnya Dim Dam berhasil juga: naik ke truk dengan mulus, lalu truk berjalan meninggalkan proyek, berputar-putar di jalan raya. "Dia akan diperkenalkan dengan suara mobil yang lalu lalang." Dari kurungan jeruji besi, di atas truk, Plai Din Dam melenguh-lenguh, "Ouuurgh . .. Ouuurgh! ..." Suaranya melengking, mengalahkan deru mesin mobil yang membawanya, meninggalkan jalan tanah berdebu di sekolah di hutan itu.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini