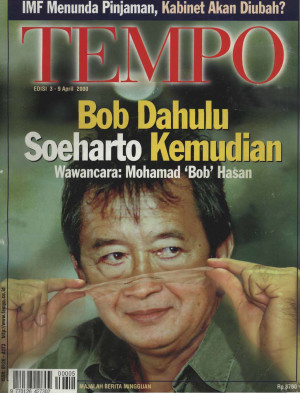Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Berdiri di Bukit Zaitun dan membelakangi matahari yang hampir tenggelam, kita bisa menyaksikan pemandangan paling khas dari Yerusalem. Setelah lembah yang curam, bertengger permukiman yang padat di lereng-lereng bukit seberangnya. Namun, di antara mosaik itu tampak mencolok sebuah blok dikelilingi tembok. Di dalam tembok, di atas sebuah dataran, berdiri sebuah bangunan dengan kubah emas yang mencorong, tak mungkin terlewatkan oleh mata.
Tembok itu membatasi Kota Tua Yerusalem. Dan bangunan berkubah emas itu adalah Masjid Batu Berkubah (Dome of the Rock)—landmark Yerusalem yang paling terkenal, sekaligus pula salah satu tempat paling suci bagi Islam. Dari batu di bawah kubah itulah diyakini Muhammad naik ke langit dalam perjalanan Isra’ Mikraj. Masjid itu dibangun oleh penguasa Dinasti Ummayah pada 691, lima belas tahun sebelum mereka membangun Masjid Al-Aqsa di dekatnya
Mereka menghancurkan kuil kami dan mendirikan masjid di atasnya,” kata David Shemesh, orang Yahudi yang menjadi sopir kami berkeliling Yerusalem dan Israel. Dome of the Rock dan Al-Aqsa berdiri di atas sebuah dataran seluas 35 akre yang dikenal dengan sebutan Haram Ash-Sharif. Orang Yahudi mengenalnya sebagai Temple Mount dan percaya bahwa di bawah dataran itulah Kuil Yahudi Kedua pernah dibangun oleh Herod, raja mereka, 20 tahun sebelum kelahiran Kristus.
Kami sekarang tak boleh memasukinya,” kata David. Kawasan ini memang terlarang bagi nonmuslim dan dikelola oleh sebuah komisi wakaf di bawah pengawasan Raja Yordania. Orang Yahudi hanya bisa mengunjungi dinding sebelah barat Hamam Ash-Sharif, dikenal sebagai Dinding Ratapan, yang kini merupakan wilayah paling suci bagi mereka. Sebagian orang Islam meyakini di dinding setinggi 18 meter itulah dulu Muhammad menambatkan Buraq, kuda sembrani yang membawanya ke langit.
Perjanjian Lama menyebut Temple Mount sebagai Bukit Moriah. Di bukit itulah Ibrahim mengorbankan anaknya. Meski dengan versi berbeda, baik Islam, Kristen, maupun Yahudi mempercayai pengorbanan itu dan menjadikan Ibrahim sebagai bapak ketiga agama monoteistis itu. Menurut Islam, yang belakangan merayakan peristiwa itu dalam Idul Adha, anak yang dikorbankan adalah Ismail, bukannya Ishak (Isaaq) seperti yang tercantum dalam Perjanjian Lama.
Mitos, legenda, dan manuskrip suci agama-agama bertabrakan di kawasan yang kecil itu. Tak hanya antara Yahudi dan Islam. Di situ pula berdiri Gereja Holy Sepulcher, di atas situs tempat Yesus disalib, dikuburkan, dan dibangkitkan—setelah menyeret salibnya sepanjang Via Dolorosa. Pada 335 Masehi, Kaisar Romawi Konstantin mendirikan gereja kecil di situ setelah sepuluh tahun sebelumnya memproklamasikan Katolik sebagai agama resmi kekaisarannya. Kelak, gereja ini menjadi salah satu tempat paling suci bagi umat Kristen selain Bethlehem, tempat Yesus lahir, dan Nazareth, tempat Yesus dibesarkan.
Tembok Kota Tua, dibangun oleh Sulaiman Agung dari Kekhalifahan Usmaniyah Turki pada 1542, mengemas gereja, sinagog, dan masjid dalam wilayah yang kelilingnya cuma empat kilometer. Ketika matahari menjelang tenggelam, bangunan-bangunan di situ, yang umumnya berdinding cadas putih, berubah keemasan. Kubah, pucuk gereja, dan menara-menara berdesakan dalam harmoni. Namun, Yerusalem tak selamanya tenang di bawah embusan angin sore seperti itu. Bangunan-bangunan Yerusalem menyimpan lumuran darah selama berabad-abad.
Menurut kepercayaan Yahudi, di kawasan kecil itulah dulu Nabi Sulaiman (berbeda dari Sulaiman Agung penguasa Turki) membangun Kuil Pertama hanya untuk dihancurkan oleh Nebukadnezar beberapa abad kemudian. Dan berbeda dari anggapan umum Yahudi seperti yang diungkapkan David Semesh, Kuil Kedua buatan Herod bukan diruntuhkan oleh muslim, melainkan oleh legiun Romawi pada 70 Sebelum Masehi—jauh sebelum Nabi Muhammad sendiri, dan bahkan Yesus, dilahirkan.
Pada masa kekuasaan Romawi pula, di bawah kekuasan Gubernur Pontius Pilate, tragedi lain berlangsung. Kali ini menjadi tragedi terbesar: Yesus disalib.
Pengusiran orang-orang Yahudi pada era Romawi dan penyaliban Yesus sudah menjadi klasik, tapi memiliki konsekuensi yang panjang hingga kini. Seribu tahun silam, perebutan terhadap Yerusalem—lokasi gereja dan masjid tersuci—telah memicu Perang Salib berkepanjangan Islam versus Kristen. Dan dalam setengah abad terakhir, dia menjadi ajang pertempuran dan konflik politik antara Arab Palestina dan Yahudi Israel, hingga kini.
Itulah salah satu ironi terbesar bagi Yerusalem, atau Yerushalaym dalam bahasa Ibrani, atau Al Quds dalam bahasa Arab, yang semuanya berarti ”damai” dan disimbolkan oleh dahan pohon zaitun.
Sebagai salah satu kota tertua di dunia, Yerusalem telah menjadi persimpangan budaya dan peradaban, para peziarah dari agama yang berbeda, dan para penakluk. Sudah sejak dulu kala, berbagai kelompok bertempur untuk menguasainya. Dan berbagai penguasa, Herod yang Agung, Kaisar Konstantin, dan Khalifah Ummayah Abdul Malik, menancapkan bangunan-bangunan besar, lapis demi lapis sejarah, yang sebenarnya memberi Yerusalem kekayaan tekstur budaya ataupun keagamaan. Dalam beberapa abad terakhir, Kekhalifahan Turki, Imperium Inggris, serta gerakan Zionis tak ketinggalan menorehkan jejaknya di situ.
Yerusalem, dan khususnya Kota Tua, merupakan masalah yang paling sensitif dalam negosiasi damai Arab-Israel sekarang ini. Kota Tua merupakan bagian dari Yerusalem Timur yang dikuasai Yordania, sampai Israel mencaploknya dalam perang 1967. Dan belakangan, pada 1980, setelah menguasai seutuhnya kota itu, Israel memproklamasikan ”Yerusalem, seluruhnya dan satu, sebagai ibu kota Israel” dan ingin kota itu ”tetap selamanya di bawah kedaulatan Israel”.
Sementara itu, orang-orang Arab Palestina di Tepi Barat dan Gaza berharap Yerusalem Timur menjadi ibu kota bagi negara mereka yang sampai kini belum berwujud.
Yerusalem, dan Palestina pada umumnya, telah menjadi obyek klaim Arab dan Yahudi hampir sepanjang abad ini, menambahkan nuansa politik di atas sentimen keagaman yang sudah menggelegak. Baik Arab maupun Yahudi menganggap Yerusalem saripati nasionalisme mereka dan simbol hak mereka atas negara.
Didesak oleh diskriminasi Yahudi di Eropa, nasionalisme Yahudi menyeruak pada 1897, ketika Theodore Herzl untuk mendirikan Organisasi Zionis Se-Dunia. Menurut Herzl, masyarakat Yahudi hanya akan nyaman hidup dan mampu mengembangkan identitasnya jika memiliki negeri sendiri. Pemerintah Inggris kala itu menawarkan Uganda, sebuah negeri Afrika, sebagai suaka bagi orang-orang Yahudi yang teraniaya di Eropa. Herzl menerima ide itu, tapi dia ditentang oleh tokoh-tokoh Yahudi lain, termasuk presiden pertama Israel, Chaim Weizmann, yang menginginkan negeri itu berdiri di Palestina. Argumen politik kini bertindihan dengan argumen agama, yakni ”kembali ke tanah yang dijanjikan”. Hezrl kalah.
Sejak saat itu, gelombang besar imigran Yahudi mengalir dari Eropa ke Palestina, yang kala itu berada di bawah mandat Inggris. Dan konflik dengan orang-orang Palestina yang bergenerasi mukim di situ tak terhindari. Sebagian tanah Palestina dibeli oleh orang-orang Yahudi secara legal atas biaya Dana Nasional Yahudi—lembaga pengumpulan dana dari seluruh dunia. Namun, tak jarang pula Palestina terusir secara paksa.
Pada 1944-1945, misalnya, kelompok Stern dan Irgun (yang dipimpin oleh Menachem Begin, kelak Perdana Menteri Israel), melakukan teror terhadap warga Palestina. Salah satu aksi mereka yang paling terkenal adalah membantai penduduk Desa Deir Yassin di pinggiran Yerusalem.
Puluhan tahun kemudian, dalam wawancara dengan koran Ha’aretz pada 4 April 1969, Moshe Dayan membuat pengakuan yang jujur. ”Tak satu pun tempat yang dibangun di negeri ini (Israel) yang tak ada penduduk Arab pada mulanya.”
Dalam upaya menemukan perdamaian permanen, pada 1947 Perserikatan Bangsa-Bangsa mengeluarkan sebuah resolusi yang membagi kawasan itu menjadi dua—Negeri Yahudi dan Negeri Palestina. Akan halnya Yerusalem, mengingat posisinya yang tak hanya penting bagi Arab ataupun Yahudi, diputuskan berada dalam pengawasan internasional di bawah kendali PBB.
Jewish Agency, badan yang mewakili orang-orang Yahudi, menyetujui resolusi pembagian itu. Sementara itu, Palestina, didukung negara-negara Arab, menolaknya karena resolusi itu tak mencakup pemecahan nasib bagi orang-orang Arab yang terusir dari tanahnya. Perang besar terjadi. Namun, Israel memenanginya dan menguasai lebih banyak Yerusalem Barat. Dan sebentar setelah Inggris melepaskan mandatnya pada 1948, Israel memproklamasikan kemerdekaan.
Setahun kemudian, perjanjian gencatan senjata yang dibuat Israel dan Yordania memformalkan pembagian kota itu menjadi dua, sektor barat dikuasai Israel dan sektor timur (termasuk Kota Tua) dikuasai Yordania. Dan belakangan, dalam perang yang lain pada 1967, Israel menguasai seluruh kota itu. ”Kami telah membebaskan Yerusalem,” kata Jenderal Moshe Dayan, Menteri Pertahanan kala itu. ”Kami menyatukan kembali kota yang terbelah itu, ibu kota Israel.”
Proklamasi itu mengingatkan orang pada Raja David (Daud dalam Islam), yang—setelah menundukkan bangsa Kanaan satu milenium sebelum Kristus—memproklamasikan Yerusalem sebagai ibu kota Kerajaan Yahudi.
Pencaplokan Yerusalem Timur lewat senjata itu tidak diakui oleh PBB. Demikian pula dengan klaim Israel atas Yerusalem sebagai ibu kota. Hingga kini, hanya ada dua negara yang memiliki kedutaan besar di Yerusalem, dan bahkan Amerika Serikat bukan termasuk di dalamnya. Banyak negara hanya mengakui Tel Aviv sebagai ibu kota Israel. Melalui berbagai resolusi yang sambung-menyambung, Dewan Keamanan dan Majelis Umum PBB, masyarakat internasional juga mengecam upaya ”Yahudinisasi”—dan karenanya ”de-Arabisasi”—Yerusalem.
Namun, itu semua tak menghalangi Israel. Seperti Herod, Konstantin dan Abdul Malik, penguasa baru Israel berupaya mengubah wajah kota. Perubahan untuk kesekian kalinya. Sepanjang sejarahnya, para penguasa kota berupaya membentuk dan membentuk-kembali wajah Yerusalem untuk mengantarkan pesan penting tentang kekuasaan ilahiah yang mereka wakili ataupun kekuasan mereka sendiri. Setiap perubahan di wajah kota, masing-masing maupun sebagai kolektif, dimaksudkan untuk membawa pesan agama ataupun politik. Itu semua adalah ekspresi. Itu semua dimaksudkan untuk dibaca.
Siapa saja yang mengunjungi Yerusalem dalam beberapa tahun terakhir akan akrab dengan banyak ekspresi itu, yang sekarang ini mendominasi wajah kota. Pada puncak-puncak bukit sekitar kota, dalam lingkaran konsentris yang mengelilingi Kota Tua, bangunan-bangunan baru—permukiman, gedung resmi pemerintah ataupun semi-resmi—muncul sebagai pernyataan politik: mereka ingin mendudukinya, mengklaimnya.
Dalam tingkatan yang praktis, bangunan-bangunan baru itu akan mempersulit Palestina melakukan klaim serupa. Langkah ini dibarengi dengan diskriminasi terselubung yang membuat orang-orang Arab terus terpinggirkan. Diskriminasi itu bahkan dikecam oleh para pembela hak-hak Arab-Palestina dari kalangan Yahudi sendiri, seperti yang tergabung dalam Gush Shalom atau Israeli Coalition against Home Demolitions (ICAHD).
Gush Shalom, yang mendukung kemerdekaan negara Palestina dengan ibu kota Yerusalem Timur, dibentuk pada 1992, menyusul pengusiran 415 orang Arab keluar Israel. Dan menurut data yang dikumpulkan ICAHD, setiap tahunnya wali kota Yerusalem memerintahkan penggusuran rata-rata 50 rumah dengan alasan dibangun secara ilegal. Banyak rumah Arab memang ilegal karena sulitnya mereka mendapat izin, sementara hampir semua permukiman baru Yahudi resmi karena dukungan pemerintah.
Hingga kini, pemerintah Israel terus mendatangkan imigran dari Eropa Timur di bawah prinsip ”law of return”—setiap Yahudi, di mana saja, bisa otomatis menjadi warga negara Israel jika mau datang. Kebijakan ini bersifat diskriminatif dan rasialistis karena meski ada juga yang menjadi warga negara Israel, orang Arab—yang bergenerasi mukim di situ—tidak otomatis memperoleh hak sama.
Akhir Maret ini, misalnya, orang-orang Arab melakukan demonstrasi tahunan untuk memperingati Land Day—peristiwa tewasnya enam orang Arab oleh pasukan Israel ketika mereka memprotes penyerobotan tanah Arab dan perluasan permukiman Yahudi pada 1976. Land Day diperingati oleh orang-orang Arab—sekitar satu juta dari enam juta warga negara Israel—untuk menuntut persamaan hak.
Ahmed Tibi, tokoh Arab dalam Knesset (parlemen Israel), mengatakan Land Day masih terus diperingati karena berlanjutnya kebijakan diskriminatif pemerintah. ”Ancaman terhadap eksistensi, identitas kolektif, hak-hak sipil minoritas Arab belum hilang,” kata Tibi seperti dikutip Radio Israel.
Dalam kasus Yerusalem, kebijakan diskriminatif itu sejalan dengan tekad semua pemerintah Israel sejak 1967, dan diungkapkan secara terbuka pada 1974, bahwa mereka menginginkan adanya ”keseimbangan demografik” di Yerusalem, yakni 75 persen Yahudi dan 25 persen Arab. Kini ”keseimbangan” belum tercapai, menurut sensus terakhir masih 70:30.
Di samping kebijakan diskriminatif itu, orang Arab—khususnya yang muslim—khawatir terhadap eksistensi Masjidil Aqsa. Dengan dukungan pemerintah sejak 1967, para arkeolog Israel membuat penggalian di bawah Haram Ash-Sharif dalam rangka menemukan reruntuhan Kuil Herod yang hilang. Penggalian itu memperlemah fondasi bangunan Islam tadi. Pada masa lalu, dengan fondasinya yang masih kokoh, beberapa gempa telah sempat merusakkan masjid.
Orang muslim menuduh pemerintah Israel sengaja melakukan itu untuk merobohkan Masjidil Aqsa dan membangun kembali kuil mereka. Meski gagasan seperti itu disokong oleh kaum Yahudi Ortodoks, tuduhan kesengajaan tadi mungkin berlebihan. Sebaliknya, pemerintah Israel kini tengah giat memasarkan Dome of the Rock melalui brosur-brosur wisatanya. Dalam perang persepsi, Israel mencoba mengambil alih simbol Islam dan nasionalisme Palestina itu menjadi miliknya.
Pemerintah Israel memberikan akses bagi semua agama untuk mengunjungi Kota Tua. Mereka juga memberikan otonomi pengelolaan situs-situs suci kepada badan agama masing-masing—termasuk terhadap kompleks Masjidil Aqsa. Israel tidak bodoh. Sepanjang ada dalam kekuasaannya, kelestarian situs-situs suci Kristen ataupun Islam justru berpotensi menyedot jutaan peziarah dari seluruh dunia.
Setelah simbol dan mitos, agama dan nasionalisme, kini kepentingan ekonomi menambahkan satu lagi elemen dalam konflik di Yerusalem. Konflik yang tampaknya belum akan reda di tengah seruan Paus Yohanes Paulus II—yang berkunjung ke sana dua pekan silam—untuk toleransi dan rekonsiliasi.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo