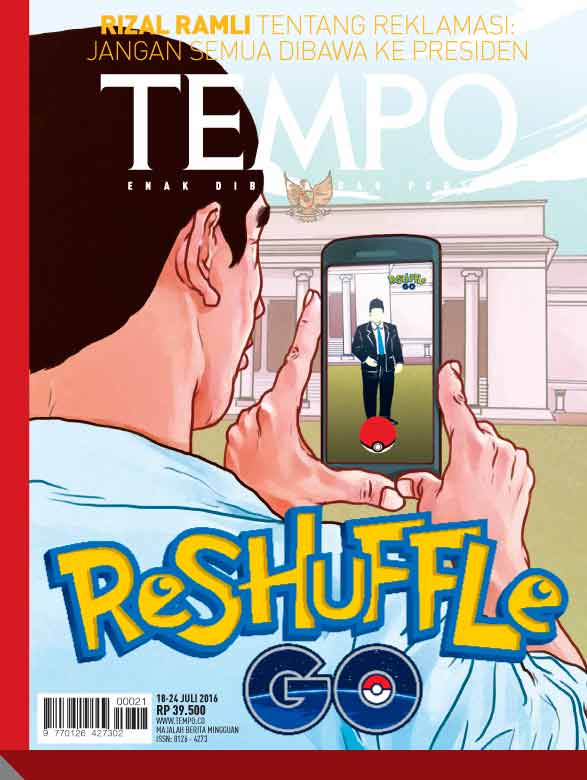Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
THE Algonquin Hotel yang terletak di 59 West 44th, di tengah Manhattan, New York, dikenal sebagai sebuah hotel yang identik dengan sejarah sastra. Di sanalah Tempo berjanji bertemu dengan sastrawan India, Amitav Ghosh, yang sudah menetap di New York bersama istrinya, sastrawan Deborah Baker, pada sebuah petang di pengujung April lalu. Ghosh membawa beberapa buku karyanya yang sudah ditandatangani, antara lain The Hungry Tide dan Sea of Poppies, lalu istrinya, esais Deborah Baker, juga membawa satu karyanya, The Convert.
"Tahukah Anda, ini tempat berkumpulnya para sastrawan di masa lalu?" kata Ghosh sambil memesankan minum.
Amitav Ghosh sedikit menceritakan sejarah hotel yang didirikan pada 1902 ini. Ia menuturkan bahwa hotel itu biasanya tempat berkumpulnya beberapa sastrawan terkemuka dan para pendiri majalah The New Yorker, antara lain Franklin P. Adams, Robert Benchley, Heywood Broun, Marc Connelly, Jane Grant, Ruth Hale, George S. Kaufman, Neysa McMein, Dorothy Parker, Harold Ross, Robert E. Sherwood, dan Alexander Woollcott. Kelompok ini menamakan diri Algonquin Round Table, karena setiap hari mereka akan mengadakan diskusi sembari menikmati makan siang.
Sastrawan yang telah menghasilkan delapan novel dan beberapa buku esai ini di Indonesia dikenal untuk karya berjudul The Glass Palace (2000), yang diterjemahkan menjadi Istana Kaca, yang diterbitkan kelompok penerbit Mizan, dan sudah diterjemahkan ke dalam 24 bahasa di dunia. Sedangkan dunia pembaca sastra umumnya menyukai trilogi Ibis, demikian sebutan bagi tiga bukunya yang berjudul Sea of Poppies (2008), River of Smoke (2011), dan Flood of Fire (2015), tentang perang opium pada abad ke-19. Sea of Poppies berhasil masuk nominasi shortlist Man Booker Prize pada 2008.
Berikut ini petikan wawancara Leila S. Chudori dengan Amitav Ghosh tentang novel The Glass Palace, yang mencakup kisah selama dua abad, tiga generasi, dan melampaui tiga negara Asia.
Beberapa kritikus sastra menyebut karya-karya Anda sebagai novel sejarah, apakah Anda setuju dengan terminologi ini? Atau seperti sastrawan Julian Barnes, yang menyatakan semua novel adalah novel sejarah?
Saya setuju bahwa pada dasarnya semua novel adalah novel sejarah. Itu adalah sebuah terminologi umum dalam arti, ketika kita menulis (dalam bahasa Inggris), selalu menggunakan past tense, tentang sesuatu yang sudah terjadi. Namun saya tak terlalu mempersoalkan bagaimana orang membuat kategori untuk karya-karya saya.
Anda pernah menyatakan bahwa perbedaan antara sejarah dan fiksi berlatar belakang sejarah adalah karena karya fiksi tak harus memandang sejarah dari satu sudut pandang. Mengapa?
Benar. Itulah daya tarik fiksi. Kita bisa menulis dari berbagai sudut pandang. Saya sangat berhati-hati saat menggunakan sejarah sebagai latar belakang. Untuk saya, dalam penciptaan novel, riset adalah bagian paling mengasyikkan dan paling mudah karena kita akan bertemu dengan berbagai dokumen atau hal baru. Dari dokumen inilah lantas tercipta tokoh dan cerita. Meski saya mencoba setia pada peristiwa sejarah, tak pernah sedetik pun saya mencoba menjadi seorang sejarawan, karena ini adalah karya fiksi dan saya adalah seorang penulis.
Novel The Glass Palace adalah karya yang luar biasa. Apa yang membuat Anda terinspirasi menulis novel yang melibatkan riset yang panjang dan dalam ini?
Saya memiliki hubungan historis yang panjang dengan Burma karena ayah dan paman saya pernah ditempatkan di sana dalam waktu yang lama. Saya sering mendengar berbagai cerita dan sudah lama saya selalu ingin menulis cerita tentang Burma. Di masa lalu, mendapatkan visa masuk ke Burma sungguh sulit. Akhirnya saya berhasil mengunjungi Burma pertama kali pada 1968. Dan belakangan, ketika akhirnya saya bertemu dengan Aung San Suu Kyi, saya ingat bagaimana polisi rahasia di mana-mana. Untuk melakukan riset novel ini, saya mengunjungi Burma dua kali. Riset dan penulisan itu seluruhnya lima tahun. Saya tak memisahkan proses riset dan penulisan. Saat menulis, saya tetap masih melakukan riset.
Ada beberapa tokoh sejarah nyata yang Anda jadikan tokoh dalam novel The Glass Palace, seperti Raja Thebaw, Ratu Supalayat, dan ketiga putrinya, yang berperan cukup besar dan Anda pertemukan dengan tokoh utama fiktif. Bagaimana cara Anda menciptakan dialog dan plot untuk mereka?
Sebagian adalah hasil imajinasi saya, sedangkan sebagian lain adalah hasil riset dari surat-surat, literatur, dan monograf tentang mereka. Harus saya akui, menulis tentang keluarga Raja bukan hal yang mudah.
Di masa muda, saya pernah membaca novel August 1914 karya Aleksandr Solzhenitsyn, yang bercerita tentang Perang Dunia I. Dalam novel ini, Solzhenitsyn menulis tentang apa yang dipikirkan Czar sepanjang 100 halaman. Novel inilah yang membuat saya jadi berani untuk menulis sebuah novel yang melibatkan tokoh sejarah. Bagi saya, jika Solzhenitsyn bisa menulis tentang pemikiran Czar sampai 100 halaman panjangnya, tentu saja juga bisa menulis tentang Raja Burma.
Bagaimana proses penciptaan tokoh utama seperti Rajkumar, Dolly, dan Uma dalam The Glass Palace seperti Deeti dalam Sea of Poppies?
Tidak ada proses penciptaan yang tunggal. Kadang-kadang seorang tokoh dimulai dari sebuah imaji atau wajah seseorang pada foto tokoh sejarah. Kadang-kadang tokoh saya bisa bermula dari salah satu bahan riset yang saya baca. Atau terkadang pula tokoh fiktif itu muncul setelah saya mewawancarai orang.
Bagaimana reaksi para keturunan Raja Thebaw dan permaisuri, dalam novel Anda, dan juga dalam sejarah?
Mereka senang sekali. Memang benar dalam novel The Glass Palace saya menulis Ratu Supalayat sebagai seorang yang keji, karena memang demikian yang tertulis dalam sejarah, berbagai literatur, dan monograf. Dia memang sangat kejam. Sebetulnya yang perlu diingat adalah Raja Thebaw dan keluarganya adalah bagian sejarah yang terlupakan. Saya selalu berusaha menulis dengan jujur sekaligus bersimpati saat saya menulis tentang mereka karena mereka tersingkir dari tanah airnya. Karena itu, para keturunannya tidak ada yang marah atau tersinggung oleh novel saya. Saya bahkan menerima Myanmar National Literature Award.
Tampaknya tokoh Uma adalah perwakilan suara anti-kolonialisme masa kini. Apakah Uma adalah perwakilan suara Anda?
Pandangan Uma, sikap anti-kolonialisme, adalah pandangan yang sangat umum bagi lelaki dan perempuan India saat itu. Ini bukan hanya pandangan kelas menengah, tapi juga kelas bawah.
The Glass Palace semula bercerita dengan fokus pada Rajkumar, Saya John, keluarga Raja Burma, dan sang dayang Dolly; kemudian belakangan fokus berpindah pada Uma dan para keponakannya, dan terjadi pernikahan antar-generasi kedua. Ini mengingatkan saya pada gaya penulisan novel Victoria abad ke-19 Inggris. Apakah Anda terpengaruh oleh sastrawan abad ke-19, katakanlah Thomas Hardy atau Charles Dickens atau nama-nama lain pada generasi itu?
Tentu saja saya sudah membaca karya-karya Hardy dan Dickens, tapi mungkin saya merasa terpengaruh langsung oleh Thomas Mann, terutama karyanya Buddenbrooks. Saya juga banyak dipengaruhi karya Herman Melville, Moby Dick.
Mengapa Anda menarik kembali novel The Glass Palace untuk bertanding dalam The Commonwealth Prize?
Novel ini bertema tentang bagaimana Kekaisaran Inggris Raya menjajah dan begitu banyak korban di India dan Burma. Ketika sedang dalam proses menulis, saya bertemu dengan begitu banyak orang yang menolak kekuasaan Kerajaan Britania Raya. Saya mewawancarai mereka, saya menetap bersama mereka. Sementara itu, The Commonwealth Prize adalah sebuah penghargaan yang merayakan kebesaran Kerajaan Britania Raya. Saya merasa, jika saya memasukkan novel ini ke lomba tersebut, akan terasa ironis. Jadi saya menarik kembali karena penerbit saya sudah telanjur mengikutsertakan. Mandat penghargaan itu, selain mempromosikan bahasa Inggris, penghargaan The Commonwealth Prize ini hanya diberikan kepada bekas jajahan Inggris. Penulis asal Inggris tidak masuk kategori ini. Jadi, dengan kata lain, penghargaan ini adalah hadiah dari kerajaan untuk penulis berkulit berwarna.
Berbeda dengan Prince Claus Award dari Belanda, yang bertujuan memberikan dukungan kepada kesenian dari negara berkembang dan karya-karya yang dinilai itu bisa dalam bahasa asli, sedangkan The Commonwealth Prize harus dalam bahasa Inggris. Tentu Man Booker Prize juga pernah dipersoalkan karena penghargaan itu hanya untuk karya yang ditulis dalam bahasa Inggris, tapi sekarang kan mereka sudah menciptakan Man Booker International Prize, yang menilai karya terjemahan ke dalam bahasa Inggris, meski memang harus dari penerbit Inggris. Memang penghargaan-penghargaan ini belum sempurna, tapi paling tidak mereka mencoba memperbaiki dari tahun ke tahun.
Anda pernah menyebutkan bahwa sastra India modern mulai bergetar sejak karya sastrawan V.S. Naipaul lahir. Mengapa?
Pada masa-masa awal kepenulisan saya, V.S. Naipaul adalah sosok sastra yang penting untuk saya, bukan hanya dia berhasil meraih Nobel Prize sejak dulu, tapi juga karena karyanya. Tapi tak berarti saya menyukai semua karya Naipaul. Buku esainya tentang Islam itu perlu dikritik. Tapi novel-novelnya sangat bagus, kalimatnya sangat berpengaruh.
Bisa ceritakan rencana riset dan penulisan di Indonesia bulan November nanti?
Saya sudah beberapa kali ke Indonesia. Terakhir saya ke Indonesia dua tahun lalu untuk ke Ubud, lalu ke Flores. Oh, saya sangat-sangat mencintai Flores. Saya rasa, dari semua tempat yang pernah saya kunjungi di dunia, Indonesia adalah tempat yang paling menarik untuk dikunjungi.
Bulan November nanti, pemerintah Indonesia memulai sebuah program penulis internasional di mana mereka mengundang penulis asing untuk menulis tentang Indonesia. Saya memilih pergi ke Maluku dan Papua menggunakan kapal. Saya menyukai kapal laut.
Saat ini, jika saya menulis tentang Indonesia, saya akan menulis artikel dulu. Saya selalu menikmati kunjungan saya ke sebuah negeri dan mempelajari kebudayaannya dan saya sangat tak sabar untuk menikmati perjalanan ini.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo