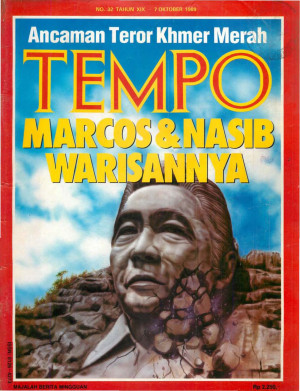PERMAINAN "petak umpet" antara P"tim" pedagang asongan dan tim tibum (ketertiban umum) DKI Jaya makin seru. Rabu dua pekan lalu, di perempatan Jalan Sisingamangaraja, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, para pengecer langsung "ngumpet" melihat petugas bersenjata pentungan mendekati wilayah operasi mereka di sekitar empat traffic light di kawasan Blok M. Sembari merangkul kotak rokok, koran, majalah, permen, lap atau rebana, mereka berpencar. Bagaikan kucing, sebagian mereka melompat ke mikrolet yang tengah melaju, ada yang menyelinap ke jalanan yang lebih sempit. Yang lainnya mengungsi ke Gelanggang Remaja Bulungan. Aman. Sementara itu, pedagang "modal besar" -- yang meskipun mampu menyewa gerobak dorong ternyata lamban menghadapi serangan petugas, penertiban. Gerobak bakso dan rak minuman dorong mereka diangkut petugas dengan pikup biru muda. Ketika para petugas pergi -- tinggal dua orang yang mengawasi perempatan -- satu per satu "kucing-kucing" asongan mendekat lagi ke wilayah operasinya. Bersiap-siap kembali merayu para penumpang kendaraan yang disergap lampu merah. Tak ada rasa cemas, apalagi kapok. Karena daerah itu telah menjadi sumber hidupnya. Begitu para petugas berlalu, bagaikan laron melihat lampu, mereka menyerbu. "Piks-piks, kopiko, kopiko!" Lalu terdengar suara rebana tanpa nada yang jelas. Tampak seorang anak menadahkan tangan. Segalanya berlangsung kembali seperti semula. seperti tak pernah ada "sapuan". Semenjak dikeluarkan peraturan di DKI, yang melarang pedagang asongan berjualan di tengah jalan, tugas tim kamtib jelas bertambah. Uniknya, para petugas ternyata punya "dilema". "Tugas di tibum itu berat. Sebetulnya kita kasihan sama mereka, karena ini kan masalah nafkah. Kita sama-sama orang kecil. Tapi kita harus melaksanakan tugas, walaupun di hati kontras," kata seorang petugas tibum, setelah bertugas membersihkan pedagang asongan di wilayah Jakarta Pusat. Ia maklum benar betapa susahnya mencari duit. Umumnya, hal itulah yang melemparkan anak-anak, pemuda-pemuda yang masih segar itu menjajakan penganan, minuman, atau surat kabar di "pasar" lampu merah. Sektor informal, termasuk pedagang asongan ini, akhirnya jadi pekerjaan yang dicintai, sekaligus dibenci. Dibenci karena menodai keindahan, ketertiban, dan keserasian kota. Disukai karena menjadi salah satu pilihan mengatasi pengangguran. Maklum, jenis pekerjaan ini bersifat free enter. "Siapa saja bisa masuk dalam lapangan kerja ini. Habis, yang dibutuhkan cuma tenaga dan keuletan," kata Sylvia Tjakrawati, peneliti dari LIPI. Plus kepandaian berhitung dalam tingkat yang paling dasar. Keluarga Memet dan Aris sudah 15 tahun menjadi sub-agen koran. Suami istri ini mangkal d bawah jembatan penyeberangan kawasan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Setiap hari, begitu tumpukan koran Terbit dan Suara Pembaruan diturunkan di emperan jalan, kontan para pedagang asongan menyerbu. "Setiap anak mengambil sekitar 15 sampai 60 lembar," kata Aris -- ibu dua anak asal Surabaya -- dengan bangga, "kalau sore bisa laku 2.000 eksemplar." Belum terhitung penghasilannya dari koran pagi. Untuk setiap koran, Memet dan Aris memungut keuntungan lima rupiah. "Tapi terhadap pengecer-pengecer itu, saya tidak pakai harga mati," katanya. Artinya, kalau cuma untung tiga rupiah satu koran, ia pun tak menolak. Yang jelas, nampaknya jumlahnya sangat pantas. Buktinya, di dekat tempat mereka berjualan, bertengger Vespa P 150. Itu salah satu hasil keringat koran. Mirip dengan Memet adalah keluarga Haji Harun. Di bawah tenda terpal di bilangan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Harun menggelar berbagai majalah, dibantu istri dan anaknya. Yang membeli boleh jadi tangan pertama, tapi yang terbanyak pengecer. Berdagang model begini sudah ditekuninya 30 tahun. "Siapa pun boleh beli asalkan bayarnya kontan," kata lelaki yang bertubuh subur dengan kulit hitam itu. Jelas, kalau yang mengambil banyak, untungnya -- sekitar 10-20 % dari harga majalah -- juga melonjak. Laba usahanya itulah yang menerbangkannya menunaikan ibadah haji. Bisa dimengerti kalau ada larangan berjualan di perempatan jalan, Harun cemas. "Akibat larangan itu, yang biasa ngambil 20 sekarang cuma 10," ujarnya sembari membetulkan letak kopiah hitamnya. Yang juga cemas adalah pedagang kecil macam Jayusman. Orang ini mengambil untung dari para pedagang asongan yang kehausan dibakar terik matahari. Bapak tiga anak yang berusia 31 tahun ini setiap pagi, pada saat anak sekolah berangkat sekolah, mulai mendorong gerobaknya. Ia membawa sekian ember berisi sirop warna-warni dan baskom bermuatan pisang goreng bikinan istrinya. Dari rumahnya di bilangan Pal Batu, Tebet, Jakarta Selatan, ia menuju pertigaan Jalan Tebet Raya dengan Jalan Dr. Saharjo dan Jalan Prof.Dr. Supomo. Jayus tak sendirian, dua asistennya ikut -- istri dan anaknya. Jayusman menawarkan dagangan, sementara istri dan anaknya menunggu dekat gerobak yang diparkir di trotoar. Konsumennya, selain para sopir bis dan bajaj, juga pedagang asongan. Untuk mereka, Jayus memberi "discount" khusus. "Sama mereka saya biasanya jual Rp 50," kata Jayus. "Tapi, sama sopir bis dan bajaj Rp 100," kata Jayus sembari tertawa. Penghasilan Jayus tidak jelek. Bisa Rp 4.000 sampai Rp 6.000 per hari. Tapi, kalau lagi apes, gerobaknya kena "razia" tim tibum. "Saya harus membayar sepuluh ribu untuk menebus gerobak," ujarnya. Tak jauh dari pangkalan Jayus, di muka bioskop Wira, Tebet, hidup seorang pemilik warung yang lain bemama Harun Lubis. Warungnya menyediakan berbagai macam merek rokok dan permen. Juga tisu seratusan. Dulunya, bapak enam anak ini guru SMP di Medan. Sejak tahun 1966, ia hijrah ke Jakarta. Kini hampir 20 tahun, ia menggantungkan nyawanya pada warung berukuran 1,5 meter x 3 meter, dibantu anak sulungnya yang duduk di kelas 11 SMA. Ia mengaku sudah kenal para pedagang asongan sejak tahun 1970. "Tapi, waktu itu mereka baru berjualan di depan bioskop Wira," katanya. Lima tahun belakangan barulah Harun tahu ada pengecer yang menjajakan barang di tengah jalan. Tak apa. Yang penting, para pengecer itu membeli dari warungnya. Harun tinggal melayaninya bersama anak sulungnya yang masih kelas 11 SMA. Harun memperkirakan langganannya sekitar 75 orang. Para "distributor" itulah yang menawarkan jualannya di sekitar Tebet, Pancoran, dan Kuningan, Jakarta Selatan. Sayangnya, kini, di dekat traffic light jalanjalan protokol ada papan pengumuman: "Dilarang melakukan kegiatan/melayani asongan, pengemis, pengamen, dan tukang lap mobil di jalan raya. Pemda DKI". Mengetahui larangan ini, ya, Harun ikut terpukul. "Kalau pedagang asongan dilarang berdagang, berarti setengah omset saya hilang," katanya 'berapi-api. Yang menarik, tampaknya para pedagang asongan telah membentuk komuniti tersendiri. Anak-anak yang kebanyakan asal rantau ini antara lain berusaha bersama-sama mengontrak rumah yang letaknya tak jauh dari "ladang" mereka. Sunarto, 15 tahun, dengan sekitar 15 pedagang asongan mengontrak rumah bersama di daerah Manggarai, sekitar 1,5 km dari lokasi kerjanya. Mereka bahu-membahu, misalnya, membantu pendatang baru yang ingin melakukan pekerjaan serupa. Memberikan modal awal bagi pedagang pemula. Suratman, 16 tahun -- yang ditemui TEMPO sedang belanja di warung Harun Lubis -- memberikan kesaksian. "Saya mencari modal dengan bekerja sebagai pembantu rumah tangga," katanya. Setelah uangnya terkumpul, pemuda belia kelahiran Wonosobo, Jawa Tengah, ini berhenti jadi kacung dan beralih profesi jadi pedagang asongan. Ternyata, modal pedagang asongan rokok dan permen ini lumayan juga besarnya. "Kira-kira Rp 70 ribu," ujar Suratman malu-malu. Kurang dari itu, ya bisa juga. Hanya saja, risikonya, jadi lebih sering mondar-mandir membeli barang. "Dalam sehari, bisa sampai tiga kali belanja." Yang tak punya modal pun masih siap ditampung dalam masyarakat pengecer ini. Caranya? Mereka jadi pedagang asongan "tembak", mirip taktik sopir gelap angkutan umum. Giliran pasukan tembak ini dimulai pada malam hari, menunggu jadwal pagi -- sore sang pemilik asli. Perjanjiar antara pemilik dan penggantinya hanya: harus mengembalikan utuh dagangan semula. Dihubungkan oleh tali bisnis ini, tak aneh kala pedagang minuman seperti Jayusman sering membela para pedagang asongan. Kalau bocah-bocah itu diperas oleh preman, misalnya, Jayus, yang lebih tua dari kebanyakan pengecer itu, tak segan menegur. "Saya bilang, masa nggak malu masih muda nggak bisa cari uang. Anak kecil saja bisa," kata Jayus, menirukan gertakannya pada premanpreman itu. Hampir terjadi keributan antara pedagang dan tibum, Kamis dua pekan lalu. Gara-gara di simpang empat Kuningan-Gatot Subroto, kepala seorang pedagang asongan berdarah dikepruk pentungan petugas tibum. Derita pedagang itu menggerakkan emosi. Serempak para pedagang asongan berkumpul untuk membuat aksi perlawanan. "Jumlahnya sekitar 200 orang," kata Suratman. Melihat kekuatan lawan yang begitu besar, petugas tibum yang cuma delapan orang mundur teratur. Terkadang pedagang asongan itu lupa bahwa pelarangan itu, selain untuk memperlancar lalu lintas, juga untuk keselamatan dirinya. Barangkali masih kita ingat nasib Tasrip, bocah 12 tahun, yang tewas Mei lalu. Anak kedua keluarga Rohana itu sehari-hari mengecer koran di sekitar Salemba Jakarta Pusat. Hari libur diselingnya dengan ngamen di bis kota. Anak yang menjadi yatim sejak usia tiga tahun itu betulbetul menjadi tulang punggung keluarga. "Hidup kami sekeluarga tergantung sepenuhnya pada dia," ujar Rohana -- ketika itu tengah mengandung anak kelima -- pada tabloid Noua. Bahkan, Tasrip sampai berhenti sekolah karena itu. Suatu hari, di awal Mei, Tasrip, yang sudah mengganggur dua hari karena modalnya habis untuk makan keluarga, ngotot ingin cari duit lagi. Tasrip merengek minta disediakan modal Rp 2.500 untuk menjaja koran. Akhirnya Rohana menggadaikan rantang susun miliknya ke seorang tetangga. Dan berangkatlah si kerempeng itu dari rumah petak 2 x 2 meter di Kampung Rawa Sawah, Jakarta Pusat, menuju Salemba. Sorenya, saat Tasrip bersama enam temannya menghitung hasil jualannya di pinggir Jalan Salemba Raya, sebuah mobil jip hitam yang ngebut menyambar kawanan pedagang asongan ini. Enam yang lainnya terseret sampai beberapa meter. Barangkali memang suratan nasib, hanya Tasrip yang tak tertolong. Ajal menjemputnya. Kisah Tasrip ini contoh betapa bahayanya berdagang di belantara lalu lintas. Tapi, orang boleh saja bertanya: Lalu apa lagi yang bisa dibuat Tasrip untuk memberi makan keluarganya? Problem kemiskinan bukanlah masalah yang sederhana. Ia bagaikan lingkaran setan. Demikianlah Jayusman. Suparman, dan Sunarto hanya memandang kosong atau bengong ketika ditanya mengapa tak mencoba melakukan pekerjaan lain. "Wah, kerja apa, ya?" gumam Jayus sembari menggaruk kepalanya yang tak gatal. Bunga Surawijaya, Ardian Taufik Gesuri, dan Tommy Tamtomo
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini