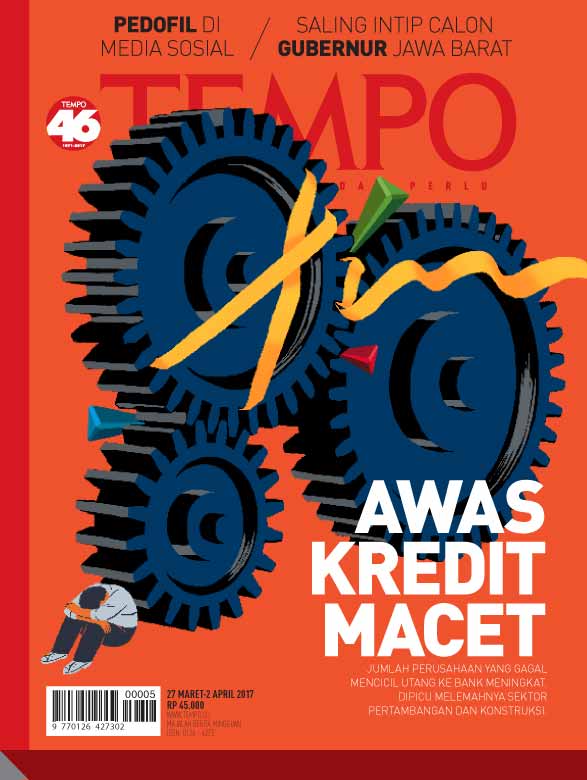Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
YOKOHAMA, kota pelabuhan di Jepang, sejak 2005 menggelar pertemuan seni penting. Setiap tahun, berbagai profesional dalam bidang seni pertunjukan, dari produser, direktur festival, sutradara, sampai dramaturg, berkumpul. Karya-karya utama disajikan. Para seniman diberi fasilitas bertemu dengan berbagai pengelola festival untuk membahas kemungkinan kerja sama.
Mulanya pergelaran ini bernama Tokyo Performing Art Market (TPAM), tapi pada 2011 berganti menjadi Tokyo Performing Art Meeting. Setelah berlokasi tetap di Yokohama, acara ini disebut Performing Arts Meeting in Yokohama. Kendati demikian, sebutannya masih TPAM. Tempo ikut meliput TPAM 2017 pada pertengahan Februari lalu. Apa saja pertunjukan yang menarik?
"Lukisan-lukisan Vermeer ini nanti akan dikembalikan setelah perang di Eropa selesai."
"Galeri ini terlalu kecil untuk menampung limpahan lukisan dari Eropa. Manajemen di sini kewalahan mengurusinya."
SETIAP Kamis, Museum Seni Rupa Yokohama, Jepang, tutup untuk pengunjung. Begitu juga Kamis, 16 Februari lalu. Yang menjadikannya berbeda, Kamis itu sebuah pertunjukan teater digelar di lobi museum. Berjudul Taipei Notes, karya ini disutradarai oleh Oriza Hirata, sutradara terkenal Jepang. Taipei Notes adalah adaptasi Hirata atas karyanya yang sudah diterjemahkan ke 15 bahasa: Tokyo Notes. Karya ini pada 1994 memperoleh penghargaan prestisius, Kishida Kunio Drama Award.
Oriza Hirata dikenal sebagai pencetus gerakan post-realism. Ini gerakan teater yang hendak mengembalikan akting senatural mungkin. Hirata mendidik para aktornya tampil di panggung dengan gaya percakapan biasa sehari-hari. Ia menghindari ekspresi dan emosi berlebihan sebagaimana kelompok teater realis pada umumnya.
Tokyo Notes berkisah tentang Tokyo tahun 2024. Pada saat itu terjadi perang besar di Eropa. Museum-museum Eropa berusaha melakukan evakuasi besar-besaran sejumlah lukisan maestro koleksi mereka. Salah satu lokasi yang dituju adalah Jepang, yang dianggap aman sebagai tempat penampungan sementara. Galeri dalam naskah Tokyo Notes dikisahkan mendapat kiriman karya maestro pelukis Belanda abad ke-17, Johannes Vermeer (1632-1675).
Naskah itu diadaptasi lokasinya ke Taipei, Taiwan, tahun 2024. Pertunjukan ini dimainkan oleh 20 aktor Taiwan. Oriza Hirata bekerja sama dengan Voleur du Feu Theatre, kelompok teater Taiwan, dengan produser Hsieh Tung-Ning. Aktornya diseleksi dari 250 pelamar oleh Voleur du feu Theatre. Seluruh dialog menggunakan bahasa Taiwan. Penonton bisa mengikuti pementasan lewat transliterasi bahasa Inggris di layar.
Dalam versi Taiwan, galeri itu dikelola oleh seorang kurator perempuan asal Jepang yang telah tinggal selama 10 tahun di Taipei. Pertunjukan ini terasa kontekstual karena diadakan di sebuah lokasi museum seni rupa. Seolah-olah di museum itu memang tengah dipamerkan lukisan Vermeer. Di tempat penjualan tiket di depan lobi dipajang katalog dengan sampul terkenal lukisan Vermeer: Girl with a Pearl Earring.
"Sekarang ini hanya 36 lukisan Vermeer yang tersisa di Eropa. Enam atau tujuh dibawa ke sini."
"Apakah benar Vermeer memiliki 11 anak?"
Para aktor menampilkan percakapan pengunjung yang hilir-mudik di lobi sebuah museum. Sepanjang pertunjukan, dialog sebagaimana adanya, seperti omongan pengunjung betulan. Percakapan tidak melulu membicarakan yang serius, tapi lebih pada obrolan selintas, dialog kecil yang sesekali membahas pameran. Misalnya mengapa Vermeer suka menggambar orang dengan posisi melihat jendela.
Menonton pertunjukan ini seperti menyaksikan percakapan ngalor-ngidul orang biasa yang memang barusan keluar dari melihat pameran atau menunggu masuk ke ruang pameran. Wajar, tidak ada ucapan dengan vokal keras atau "didrama-dramakan". Sekali ada adegan berbicara keras atau tertawa terbahak-bahak, sebagaimana dalam kenyataan sehari-hari, para "pengunjung" lain langsung menoleh. Kadang mereka berbicara bareng satu sama lain setengah berbisik. Ada yang diam saja membolak-balik katalog. Lalu beberapa dari mereka berfoto dengan kamera saku. Ke-20 aktor yang memerankan berbagai pengunjung itu keluar-masuk mengalir enak. Sangat alamiah.
"SETELAH membuat Taipei Notes, Oriza Hirata akan membuat Bangkok Notes, berkolaborasi dengan aktor teater Thailand," kata Kazumi Inami, Direktur Seni dan Kebudayaan Japan Foundation Asia Center, Tokyo. Japan Foundation, yang mendanai kolaborasi Hirata-kelompok teater Taiwan, tampaknya akan mendanai proyek selanjutnya. Dalam Bangkok Notes, para aktor nanti menggunakan bahasa Thailand.
Sesungguhnya Tokyo Notes pernah dipentaskan di GoetheHaus Jakarta atas prakarsa Japan Foundation Jakarta pada 2006. Karya itu dimainkan oleh Teater Seinendan, milik Oriza Hirata. Entah apakah Hirata berpikiran membuat Jakarta Notes dengan materi aktor Indonesia. Sebab, susah dibayangkan bila tujuan evakuasi lukisan maestro Eropa andai perang terjadi adalah Jakarta karena infrastruktur galeri dan museum kita kurang memadai.
Taiwan Notes adalah salah satu pertunjukan menarik di TPAM-Performing Arts Meeting in Yokohama 2017. Ada 15 pertunjukan utama dan lebih dari 50 pentas fringe dalam pergelaran ini. Selebihnya diisi dengan forum yang mempertemukan pekerja seni pertunjukan. Di forum ini, dari kurator, dramaturg, produser, direktur festival, sutradara, pengamat seni pertunjukan, pengelola gedung, sampai jurnalis seni pertunjukan diberi kesempatan melakukan presentasi.
Pusat kegiatan pergelaran ini adalah BankART. Gudang bekas milik perusahaan kargo perkapalan Nippon Yusen di kawasan Nihon Odori didesain menjadi art center. Yokohama adalah kota pelabuhan. Yokohama adalah salah satu pelabuhan Jepang pertama yang dibuka paksa oleh Commodore Perry. Dia mendarat di sana pada Maret 1854. Tak lama kemudian, Yokohama yang tadinya desa nelayan biasa menjadi permukiman pertama kaum Eropa di Jepang.
Kalau kita melihat topografi Yokohama, letak permukiman kolonial Eropa ada di daerah perbukitan bernama Motomachi. Mungkin saudagar dan serdadu Eropa saat itu lebih aman tinggal di perbukitan karena bisa mengawasi kapal yang datang dan pergi. Di Motomachi, kita bisa melihat kuburan tua Eropa dan taman yang dibangun pemukim pertama Eropa, seperti Yamate Park.
Kawasan China Town terletak di tengah. China Town Yokohama adalah salah satu pecinan terbesar di Jepang. Dulu para pekerja Cina dibutuhkan untuk pembangunan besar-besaran. Keluar dari kawasan China Town, berjalan kurang-lebih 1 kilometer, kita masuk ke kawasan Nihon Odori, yang letaknya di pinggir pelabuhan. Di kawasan inilah lokasi BankART berada. Di situ juga terdapat Zou Na Hana Park, taman di tepi pelabuhan. Zou Na Hana berarti belalai gajah--dinamakan demikian karena daratan yang menjorok ke lautan di situ menyerupai belalai. Konon di sekitar Zou Na Hana itulah dulu kapal-kapal hitam Laksamana Perry berlabuh.
Di depan Zou Na Hana, berdiri Yokohama Archive of History. Memasuki halaman gedung ini, kita langsung dihadapkan pada sebuah pohon besar. Syahdan, pohon itu merupakan anakan dari pohon asli yang ada sejak kedatangan Commodore Perry. Di gedung arsip, kita bisa melihat ukiyo-e (gambar grafis Jepang) yang menceritakan tentang kehidupan pertama orang Eropa dan Amerika di Yokohama. Dalam sebuah ukiyo-e digambarkan seorang samurai menaiki seekor kuda tunggang-langgang kebingungan melihat kapal Laksamana Perry datang.
BankART didirikan pada 1952. Luas bangunannya sekitar 3.000 meter persegi dan menghadap lautan. Pada 2003-2005, pemerintah Yokohama mengarahkan Yokohama sebagai creative city. Beberapa bangunan bersejarah dan gudang tua difungsikan menjadi tempat seni. Mula-mula gedung bekas bangunan Daiichi Bank dan Fuji Bank, yang didirikan pada 1929, dijadikan Yokohama Creative City Center. Pada 2005, bekas Nippon Yusen Warehouse kemudian dijadikan BankART.
Pembukaan Performing Arts Meeting in Yokohama 2017 dilakukan di Yokohama Creative City Center dengan sederhana. Wali Kota Yokohama mengajak bersulang ratusan undangan. Undangan dari Japan Foundation Asia Center sendiri lebih dari 60 orang, meliputi sutradara, produser, performer, sampai direktur festival dari Asia, Eropa, dan Amerika Latin. Belum puluhan hadirin lain.
"Saya dari The Katkatha Puppet Art Trust, New Delhi. Kami mengembangkan berbagai jenis wayang boneka. Saya pernah bertemu dengan Slamet Gundono. Dia jenius. Saya kaget mendengar dia meninggal," kata seorang perempuan bernama Anurupa Roy. Belum apa-apa, ia sudah menawarkan kerja sama. "Ayo, kita bisa bikin festival bersama. Nanti saya berencana melakukan riset ke Bali." Anurupa bercerita bahwa sekolah mendalang miliknya berada di pinggiran New Delhi. Dia mengangkat tema komedi Shakespeare sampai folklor India.
"Kami sampai main ke daerah konflik, seperti Kashmir, Manipur, dan Sri Lanka. Juga ke sejumlah perdesaan membawa tema seputar diskriminasi, kekerasan gender, dan stigma korban HIV," dia menambahkan. Namun bukan Anurupa saja yang blusukan. Seorang lelaki muda Jepang, di tengah hadirin yang berdesakan, tampak membagi-bagikan leaflet dan berusaha menerangkan kegiatan. "Saya Kanji Miura dari Teater Idiot Savant. Ini daftar pertunjukan kami. Kami pernah mementaskan Samuel Becket. Mungkin Anda tertarik."
Inti dari TPAM memang pertemuan dan pertukaran gagasan. Maka, pada 11-19 Februari, panitia menggelar berbagai lecture dan diskusi mengenai kondisi kesenian kontemporer terbaru, bagaimana membentuk jaringan manajemennya, artist talk, dan Asian Dramaturgs' Network Meeting atau pertemuan para dramaturg Asia. Salah satu sesi diskusi yang "hot" bertema "Is Performing Arts Critique Possible in the Age of Populism?". Pembicaranya adalah kritikus tari Keisuke Dakurai; profesor performance studies di The University of Tokyo, Tadashi Uchino; kritikus tari Daisuke Moto; dan sutradara Singapura, Ong Keng Sen.
Diskusi menjadi hangat tatkala Daisuke Moto menyatakan bahwa pada masa sekarang kritik kurang relevan. Baginya, lebih baik kritikus terjun langsung sebagai kurator dan melakukan lokakarya membenahi tari atau teater. Tapi Keisuke Dakurai dan Tadashi Uchino menolak habis-habisan pendapat Moto. Mereka melihat langkanya kritik justru membahayakan pertunjukan kontemporer. "Memang sekarang di Jepang teater sendiri pun jarang yang melakukan kritik politik. Semua cenderung mengangkat tema personal," ujar Chikara Fujiwara, penulis teater, yang ikut mendengarkan diskusi.
Tapi yang paling menarik adalah forum Exchange TPAM Exchange-Group Meeting Up Meeting. Di lantai 3 BankART, panitia menyediakan sejumlah meja. Satu meja ditata dengan jarak yang tak terlalu jauh dengan meja lain. Para direktur festival, produser, penata tari, sampai pengelola gedung silih berganti berbicara. Siapa saja boleh mendengarkan. Suasananya seperti rapat kecil. Di sini mereka bertukar pengalaman mengelola festival, mempromosikan karya terbaru, memaparkan kemungkinan membuat kolaborasi atau ko-produksi sekaligus alternatif sumber pendanaannya, sampai menawarkan grant dan residensi seniman.
Florian Malzacher, Direktur Artistik Impulse Theater Festival Jerman, misalnya, memaparkan serba-serbi festivalnya yang independen. Fu Ning, Direktur Dance Stages Shanghai Dance Festival, menjelaskan perihal pasar tari kontemporer Cina. Di meja lain, Lee Kyung-sung, Direktur Artistik Seoul Marginal Theater Festival, menerangkan festivalnya yang sangat eksperimental.
"Agustus nanti di Taiwan akan diresmikan gedung pertunjukan baru. Namanya Taipei Performing Arts Centre. Kami menyediakan tempat untuk kolaborasi pentas kontemporer," ucap Ying Wang dari bagian pemasaran Taipei Performing Arts Centre, berpromosi di meja lain. Dari Jepang sendiri banyak direktur festival yang menguraikan programnya. Chiaki Soma, mantan Direktur Festival Tokyo, misalnya, memperkenalkan platform barunya bernama Theater Commons Tokyo. "Saya juga berencana membikin program dengan seniman Indonesia. Saya akan melakukan riset di Jakarta," katanya. Suasana meeting sangat informal. Seseorang bisa loncat dari satu pertemuan ke pertemuan lain.
Panitia khusus menyediakan sebuah ruangan yang disebut Speed Networking. Di situ disediakan belasan meja dengan masing-masing dua kursi. Seniman yang telah membikin janji dengan direktur festival dan produser bisa serius melakukan "negosiasi" di Speed Networking. Negosiasi bisa terjadi dalam acara yang disebut 10 minutes one on one meeting itu. Di titik ini, TPAM tampak memfasilitasi terbentuknya pasar seni pertunjukan yang dikemas dalam suasana santai.
Di BankART juga beberapa pertunjukan utama dilaksanakan. Yumina Kato, dramawan Jepang, menghadirkan dua karya: Tower dan Layer. Lalu kurator asal Singapura, Tang Fu Kuen, membawa pameran instalasi sejumlah perupa Thailand bertajuk Samut Thai: Unfinished Histories. Pementasan Tower menggelitik. Di lantai 4 BankART, kita melihat sebuah kotak raksasa penuh lubang di sana-sini. Dari bolongan-bolongan itu kemudian muncrat cairan kental berwarna yang aneh. Juga keluar busa dan gelembung karet yang sepertinya lengket. Sekilas benda itu mengasosiasikan limbah. Dua aktor kelimpungan menahan muncratnya cairan itu.
LOKASI lain yang menjadi tempat pertunjukan utama TPAM adalah KAAT atau Kanagawa Arts Theatre, gedung pertunjukan besar di Yokohama. Di sini disajikan pemutaran film Fever Room karya sutradara Thailand, Apichatpong Weerasethakul; pertunjukan musik Ngoc Day dari Vietnam dan kelompok Senyawa Indonesia; serta pentas Solo Rites: Seven Breaths dari Jen Shyu, musikus berdarah blasteran Timor Leste dan Taiwan yang lama tinggal di Yogyakarta. Selain itu, pentas tari Balabala karya Eko Supriyanto (lihat tulisan "Bagian Kedua Trilogi Eko"), performance berjudul Be Careful oleh Malika Taneja dari New Delhi, pertunjukan Zan Yamashita asal Kyoto berjudul Road to Evil Spirit (lihat boks), dan karya Yasuko Yokoshi: Zero One.
Balabala tampaknya menjadi karya unggulan TPAM 2017. Foto penari Balabala menjadi poster resmi dan sampul katalog yang dibagikan kepada semua peserta. Di pintu masuk BankART dan Kanagawa Arts Theatre terpampang poster bergambar para penari Balabala. Tapi yang paling menjadi pembicaraan dari keseluruhan pementasan adalah film Fever Room karya Apichatpong Weerasethakul. Film ini bisa disebut merupakan bintang dari TPAM 2017.
Karya Apichatpong ini keluar dari batas-batas sebuah film. Karyanya bukan lagi tayangan sinema biasa, melainkan sebuah pertunjukan instalasi cahaya, pentas seni rupa, dan permainan ruang teater. Di hall utama KATT, kita mula-mula menyaksikan Fever Room seperti sebuah film dokumenter. Seorang lelaki digambarkan menyusuri sebuah sungai, mungkin Sungai Mekong. Tak ada gambar pantai yang indah. Mata lelaki itu kadang menatap air sungai cokelat yang terbelah oleh laju perahu motor. Lalu kemudian film menampilkan seorang perempuan yang terbaring lemah di sebuah dipan di rumah sakit.
Kita kemudian mendengar latar suara percakapan antara lelaki dan perempuan. Dari atas layar yang sudah ada kemudian turun layar lain. Layar menjadi dobel. Tiap layar menampilkan fragmen-fragmen sungai. Tiba-tiba di samping kanan-kiri penonton muncul layar besar yang juga menampilkan lanskap sungai. Suara angin terdengar jelas dari samping kanan dan kiri. Dengan empat layar mengitari, mulailah perlahan terasa kita dibawa ke suasana halusinatif.
Kita sadar bahwa sungai itu merupakan mimpi yang ada dalam benak perempuan yang tergeletak di rumah sakit tadi. Sungai tersebut penampakan bawah sadar atau ingatan-ingatannya yang direpresi. Kita melihat juga kemudian laki-laki di atas tidur tak berdaya. Lalu dua layar yang menampilkan sungai itu berganti menampilkan panorama gua gelap. Beberapa orang dengan senter menyusurinya. Kita dibawa ke suasana purba batu-batu. Alam arkaik yang lembap. Menyusuri stalagmit dan stalagtit.
Sekonyong-konyong, dari arah layar depan, muncul ke arah penonton sorot cahaya melingkar-lingkar. Berkas-berkas cahaya yang seperti kabut tipis turun dari atas meresap ke pendaran itu membentuk sebuah imaji lorong besar yang berputar-putar dan kemudian menelan seluruh penonton. Mereka kini seolah-olah berada dalam sebuah pusaran lorong. Penonton bak disedot masuk ke sebuah gua yang menakutkan. Gua yang di ujung tampak kabut hitam bergulung-gulung mengerikan. Dinding kabut mengimpit kanan-kiri penonton. Begitu nyata. Penonton seakan-akan dapat menyentuh kabut dari atas yang turun dekat sekali ke kepala.
Penonton juga seolah-olah diajak berkelana dalam halusinasi demam wanita atau pria di film tersebut, dibawa mengikuti perjalanan mimpi buruk dan penglihatan mereka tentang kematian. Inovasi ini luar biasa. "Kami sendiri tak pernah melihat film ini diputar di Thailand," tutur Pistakun Kuantalaeng, perupa dari Thailand. Namun ia menganggap teknik yang digunakan Apitchatpong Weerasethakul sesungguhnya biasa saja. "Itu video mapping biasa," ujarnya. Tapi penonton lain mengatakan apa yang dilakukan Apichatpong bukan video mapping, melainkan interaksi permainan cahaya dan asap yang sulit.
Dari Indonesia, yang tampil di KATT adalah duo Senyawa, dengan vokalis Rully Sabhara dan Wukir Suryadi. Pentas mereka sangat garang. Wukir dikenal sebagai musikus yang menciptakan berbagai instrumen petik dan gesek dengan bahan kawat yang dipasangkan pada bambu, kayu, dan gaharu--apa saja yang dengan bantuan amplifier mampu menghasilkan efek sound "kasar"dan "gahar" heavy metal. Sebanyak 14 lagu yang mereka bawakan terdengar tak melelahkan. Teknik jemari Wukir dalam setiap lagu variatif. Wukir semata-mata mengeksplorasi bunyi, bukan nada.
Sedangkan Jen Shyu tampaknya terinspirasi oleh Slamet Gundono. Sebagaimana Gundono yang menyanyi dan mendongeng dengan ukulele, Jen Shyu bersenandung dan berkisah seraya memainkan gitar bundar Taiwan. Ia menggabungkan teknik suara Kalimantan dan nyanyian Timor Leste sampai Korea Selatan. Dramaturg pertunjukan ini adalah Garin Nugroho.
Akan halnya Yasuko Yokoshi menampilkan sebuah duet tari dengan latar film dokumenter yang dibuatnya: Hangman Takuzo. Takuzo Kubikukuri dikenal sebagai performer Tokyo yang pentasnya selalu menampilkan aksi gantung diri. Ia memiliki teknik menggantung di rahang. Tiap hari, di halaman rumahnya, ia berlatih menggantung diri dan itu dilakukan lebih dari 20 tahun. Dia pernah menggelar pentas di Salihara, Jakarta. Dalam pertunjukan Yasuko Yokoshi, kita melihat ia sehari-hari menggantung dirinya bahkan di dekat dapur dalam rumah.
Yang sedikit kontroversial adalah pentas Malika Taneja. Perempuan ini mengkritik situasi ketimpangan gender di India. Begitu masuk, penonton melihat di panggung ada berbagai jenis selendang, kain, dan baju warna-warni tercantel rapi. Sepertinya itu bukan tontonan mengejutkan. Lalu lampu dimatikan. Tapi, begitu terang kembali, Malika berdiri tegak telanjang bulat di tengah cantelan. Ia diam tanpa bergerak lebih dari 10 menit.
Matanya menatap penonton. Hening. Tatkala berbicara, Malika bercerita tentang kondisi perempuan di India. Anak perempuan tidak boleh ini-tidak boleh itu. Dia bercerita tentang dirinya yang tiap hari harus mengenakan pakaian tradisional berlapis-lapis. "Saya tersiksa. Bayangkan bila siang New Delhi sangat panas dan saya ke mana-mana harus pakai baju tebal." Malika lalu mengambil kain di cantelan. Ia melilitkan kain di kemaluan dan payudaranya. Lalu selendang ia kerudungkan. Seluruh kain, baju, dan sweater yang tercantel akhirnya ia pakai berangkap-rangkap sampai tubuhnya menjadi tambun. Terakhir, Malika mengenakan helm.
DI samping pertunjukan utama, disajikan pentas fringe. Jumlahnya lebih dari 50 pentas, meliputi tari dan teater. Tempatnya terpencar-pencar dan berjauhan, bahkan sampai Tokyo. Pentas susah dipilih, selain tempatnya tidak seputar BankART, lantaran waktunya kerap bertabrakan. Namun, yang mencolok, banyak dari mereka yang tampil dalam seksi fringe tak menggunakan gedung pertunjukan konvensional. Mereka berpentas di lobi kantor sampai rumah toko.
Pentas Hiroshi Koike Bridge Project, The Restaurant of Many Orders, masih lumayan. Hiroshi Koike, sutradara yang sering melakukan pertunjukan di Indonesia, menggunakan auditorium sebuah perkantoran di dekat stasiun di Yokohama. Salah satu aktornya, Koyano, yang pernah belajar gamelan Bali, beberapa kali secara spontan menyerukan kosakata bahasa Indonesia. Tapi cobalah menghadiri pertunjukan kelompok Zeitaka Binbou, Everyone Fears the Night, di daerah Chojamachi, Yokohama. Lokasi pertunjukannya di lantai 2 sebuah ruko. Hanya ada 75 kursi. Lantai 2 itu sempit dan masih dijejali lemari es dan perabotan. Tapi tempat tidur disingkirkan. Para pemain meringkuk dalam tiga boks kecil. Kelompok ini tengah mempromosikan gerakan uchi-project. Uchi artinya rumah. Jadi ini gerakan pentas di rumah atau apartemen.
Yang lebih ekstrem adalah kelompok Fai-Fai. Pentas mereka berjudul Cat Fish di sebuah kamar hotel kecil bernama Claska yang luks. Sebanyak 25 penonton duduk di depan tempat tidur dan sofa kamar. "Kami menyewa kamar 402 ini tiga hari," kata seorang anggota panitia. Tiket pentasnya cukup mahal: 3.500 yen atau sekitar Rp 400 ribu. Tiga aktor, dua laki-laki dan satu perempuan, hilir-mudik. Seorang di antaranya menggunakan pakaian aneh. Di depan tertutup tapi bagian punggung sampai pantat terbuka. Akting mereka cenderung karikatural. Keluar dari kamar mandi, mereka berkejar-kejaran. Lalu mereka duduk berebut makan. Sesaat terlihat panik, kemudian tertawa bersama. Dialog mereka sepenuhnya menggunakan bahasa Jepang, yang sama sekali tak bisa dimengerti. Dari katalog yang diedarkan diketahui bahwa pembicaraan mereka tentang unidentified flying object (UFO).
Bagi yang menggunakan lobi kantor tentu saja tidak bisa berpentas pada sore atau pukul 8 malam. Pentas A Dance After Fukushima yang menggunakan ruang tunggu sebuah kantor bernama Kannai Future Centre, misalnya, dilaksanakan lewat pukul 10 malam. Dalam diskusi pentas ini, seorang penonton menyatakan, bagaimanapun, warga Jepang butuh listrik. "Pentas kami masih banyak yang tak menerima," ucap Kazuma Glen Motomura, sang penari.
Demikian laporan suasana Performing Arts Meeting in Yokohama 2017. Yokohama sendiri adalah kota dengan banyak museum. Di luar acara, kita bisa berkelana dari museum ke museum. Di Museum Seni Rupa Yokohama, misalnya, berlangsung pameran foto "The People" karya fotografer Kishin. Foto John Lennon berciuman dengan Yoko Ono di depan sungai karya Kishin menjadi poster yang banyak dipasang di jalanan Yokohama. Selain itu, ada Yokohama Doll Museum, Kanagawa Museum of Cultural History, dan Japan Newspaper Museum. Yang unik, ada Noodle Cup Museum yang memamerkan bungkus Indomie dari berbagai negara. Indomie kita dipamerkan hampir satu dinding penuh. "Bagi kami, orang Tokyo, Yokohama adalah tempat wisata, jalan-jalan," kata Chie Fukase, penerjemah bahasa Indonesia dan peniup suling Cianjuran.
Di Motomachi, di halaman Kanagawa Museum of Modern Literature, dipamerkan memorabilia novelis tenar Natsume Soseki. Duduk di bangku taman, kita bisa menyaksikan panorama Yokohama dari atas. Tampak laut, jembatan, dan kapal. Terasa tenang. Penutupan diadakan di teras Zou Na Hana. Teras ini dibuat untuk memperingati 150 tahun dibukanya pelabuhan sekitar Yokohama oleh Laksamana Perry. Laksamana itu dalam satire ukiyo-e digambarkan berhidung bengkak seperti buto.
Sama seperti pembukaan, penutupan pergelaran dilakukan secara sederhana. Tanpa seremonial apa pun. Semua menyalami Hiromi Maruoka, Direktur Performing Arts Meeting in Yokohama. Lalu, hurrah, terdengar tepuk tangan keakraban. TPAM-Performing Arts Meeting in Yokohama mengambil posisi bukan hanya sebagai festival biasa, tapi sebuah tempat rendezvous bagi para pekerja seni untuk membangun jaringan sekaligus meraba-raba pasar.
Seno Joko Suyono
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo