Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Ringkasan Berita
Banyak anak muda mengalami permasalahan psikologis kecemasan, trauma, dan depresi selama masa pandemi.
Tekanan dari lingkungan pekerjaan dan lingkungan keluarga kerap menjadi pemantik.
Perasaan tak berdaya dan sendirian dapat memicu persoalan yang lebih kompleks.
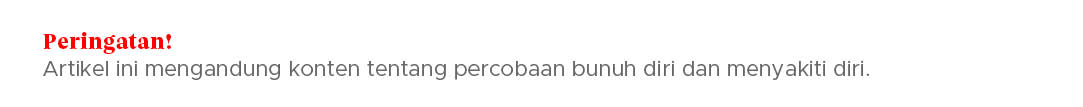
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo






















