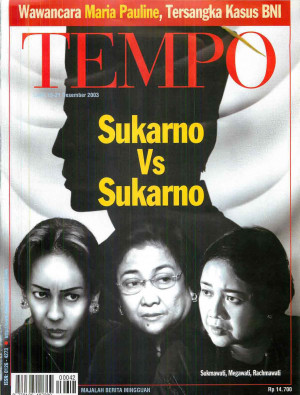DESA Sembungan, Kasihan, Bantul, Yogyakarta, yang senyap malam itu, terasa berbeda. Samar-samar alunan musik gamelan terdengar, timbul-tenggelam diterpa angin. Tapi masyarakat desa itu tidak heran, karena malam itu adalah malam Jumat Kliwon. Malam itu istimewa bagi keluarga seniman Joko Pekik, yang punya kebi- asaan membunyikan gamelan.
Kiai Lampor, nama gamelan itu, ditabuh perawit yang didatangkan dari Keraton Yogyakarta. Gusti Bendoro Pangeran Haryo Yudoningrat, pemimpin mereka, sering tampak hadir dalam kegiatan itu. Ditemani teh nasgithel (panas, legi, kenthel) dan nyamikan (snack) emping goreng, para tamu yang kebanyakan seniman, juga kerabat dekat Pekik, ngobrol di teras. Di belakangnya, di dalam sebuah pendapa kaca, para perawit dan pesinden asyik bercengkerama dengan gendhing-gendhing-nya. Selanjutnya mereka bersantap malam bersama dengan lauk khas kesukaan Pekik, gulai daging sapi.
Begitulah kebiasaan Pekik, yang memiliki koleksi dua gamelan. Satu lagi, Kiai Gleger, ditabuh setiap Selasa malam dan Sabtu Wage malam oleh warga kampung. Dan setiap Kamis atau Rabu malam dipakai latihan warga Gereja Katolik Pugeran. ”Kalau yang ini khusus dipakai latihan warga kampung. Kami sekeluarga juga sering main dan punya jadwal sendiri,” kata pelukis Berburu Celeng yang mulai mengoleksi gamelan sejak 1994 ini.
Menurut Pekik, gamelan itu dibeli dari perajin gamelan asal Solo. Harganya Rp 200 juta. Sedangkan Kiai Lampor dibeli setahun belakangan, dari pemilik gamelan di Malang, Jawa Timur. Umur Kiai Gleger relatif muda ketimbang Kiai Lampor yang buatan 1930-an. ”Sewaktu saya beli, umurnya sudah di atas 80 tahun,” ujarnya.
Konon, gamelan tua disukai jin atau sebangsanya. Namun Pekik mengaku tidak percaya begitu saja. Apalagi kebetulan gamelan miliknya yang usianya lebih muda justru lebih misterius daripada Kiai Lampor. ”Kiai Gleger ini sering bunyi sendiri meski tidak ada yang menabuh. Kadang gongnya saja yang berbunyi, atau kenongnya,” ujar Pekik, yang dibenarkan istrinya.
Sebagian orang Jawa memang punya kedekatan dan bahkan punya banyak kenangan khusus terhadap instrumen musik Jawa itu. Pada masa lalu gamelan hanya dimiliki seorang priayi atau orang yang berkedudukan tinggi. Kenyataan ini yang membuat Pekik kecil bercita-cita ingin memiliki gamelan. Kini, setelah sukses, Pekik berhasil mengaduk-aduk kenangan lamanya. ”Hati saya merasa tenteram dan damai kalau melihat gamelan tertata rapi dan bersih. Baru nyawang (melihat) saja saya sudah senang. Apalagi kalau dimainkan, saya jadi ingat masa kecil,” katanya.
Kini siapa saja bisa memiliki gamelan. Tapi yang namanya kolektor gamelan bisa dibilang masih eksklusif. Persoalannya adalah harga yang relatif mahal, minimal Rp 200 juta, belum termasuk perawatannya. ”Perawatan gamelan itu mahal. Setahun sekali saya membersihkan dan nglaras (menyetem) dua gamelan ini, bisa habis sekitar Rp 4 juta,” ujar Gusti Bendoro Raden Ayu Joyokusumo.
Berbeda dengan Pekik, Joyokusumo memiliki dua gamelan untuk mendukung usahanya. Rumah pesta dan restoran bernuansa etnik Jawa di rumah tinggalnya itu tidak lengkap tanpa hadirnya gamelan. Kerabat Keraton ini menempatkan koleksinya di pendapa depan dan belakang. Kiai Retno Puspo yang peninggalan Sultan Hamengku Buwono VII sengaja diletakkan di pendapa belakang. Sayangnya gamelan buatan 1916 ini tidak lengkap, hanya ada slendronya, karena bagian pelognya dibawa Belanda pada zaman penjajahan dulu.
Hingga kini kolektor gamelan terbanyak adalah keraton. Keraton Yogyakarta, misalnya, masih memiliki 18 pangkon (set) gamelan, tersebar di beberapa tempat. Ada gamelan Sekaten bernama Kiai Gunturmadu-Nagawilaga, gamelan Monggang yang disebut Kiai Kebonganggang. Juga gamelan Slendro-Pelog seperti Kiai Siratmadu-Madukentir, Kiai Surak-Kancilbelik, dan Kiai Harjamulya-Harjanegara.
Pada zaman dulu, sebagian orang Jawa menganggap benda peninggalan kuno memiliki jiwa karena dibuat dengan ritual khusus. Untuk itu, pemiliknya sering memberikan sesaji bila gamelan itu hendak dibunyikan. Kini hanya gamelan pusaka keraton yang biasa diberi sesaji. Kebanyakan kolektor tidak melakukannya. ”Saya tidak pernah pakai sesaji. Apalagi tiga gamelan saya semua baru, kok,” kata Sunyahni, penyanyi campursari asal Sragen, Jawa Tengah.
Sebagai penyanyi campursari, Sunyahni memang lekat dengan gamelan. Tak mengherankan bila ia punya tiga set gamelan. Satu di antaranya super, bahannya terbuat dari perunggu asli. Menurut dia, sekarang ini banyak gamelan yang kualitasnya kurang bagus karena terlalu banyak campurannya. Meski ia punya tiga pangkon gamelan, di rumahnya tak tampak ada gamelan. ”Gamelan saya tidak di sini. Ini kan pagupon (rumah burung dara). Semua gamelan saya simpan di Sragen,” ujarnya.
Seperti halnya Pekik, Sunyahni memiliki gamelan hanya untuk klangenan. Pada hari-hari tertentu, Sunyahni biasa membawa rombongannya ke Sragen, sekadar kumpul-kumpul sambil nabuh gamelan. Pada hari biasa, gamelan miliknya sering digunakan latihan para perawit di sekitar rumahnya di Sragen itu. ”Mereka kan lebih membutuhkan,” katanya.
L.N. Idayanie, Syaiful Amin, Heru C. Nugroho
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini